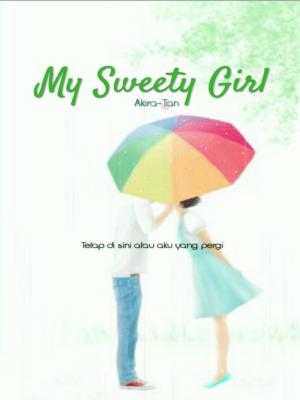Ada satu sisi dinding di ruang tengah yang tidak pernah dicat ulang. Dinding itu tidak mulus. Ada bekas coretan krayon, goresan spidol, dan yang paling khas sidik jari berwarna-warni, membentuk semacam mural liar yang hanya dimengerti oleh tangan-tangan kecil yang dulu membuatnya.
Itulah dinding kenangan kami.
Dinding tempat aku dan Dira berekspresi bebas. Tempat di mana kami merasa menjadi seniman hebat, walaupun karya kami lebih mirip peta buta daripada lukisan. Dinding itu juga saksi saat Ibu menyerah untuk marah dan hanya berkata, “Nanti kalian bersihkan sendiri ya,” padahal ia tahu kami akan lupa dalam waktu dua menit.
Hari itu, aku berdiri di depan dinding itu lagi. Menyentuh bekas sidik jari yang warnanya sudah pudar. Tapi jejaknya masih terasa nyata, seperti tangan masa kecil yang menyapa dari balik waktu.
"Masih ada ya," kataku pelan.
Aku menatap bentuk jari kecil berwarna ungu, menempel di atas gambar matahari yang dibuat dari jari telunjukku sendiri. Dira menempelkan warna oranye di sekitarnya, katanya biar mataharinya tampak “ramai”. Tapi sebenarnya, kami cuma kehabisan warna kuning.
Di pojok bawah, ada tulisan “Keluarga Bahagia” yang kutulis dengan huruf miring-miring tak rata, lengkap dengan gambar rumah berasap dan dua anak yang kepalanya lebih besar dari tubuhnya.
Lucu, ya. Dulu kita percaya semua bisa digambarkan dengan dua warna dan bentuk sederhana. Siang itu, Ibu ikut duduk di kursi di dekat dinding. Ia membawa kain lap dan botol semprot berisi air.
“Mau kamu bersihin?” tanyanya.
Aku menggeleng cepat. “Enggak, Bu. Jangan. Ini... ini peninggalan sejarah kita.”
Ibu tertawa. “Ibu juga enggak tega sebenarnya. Tapi kadang suka malu kalau ada tamu. Dikiranya rumah kita belum selesai renovasi.”
Aku tersenyum. Lalu duduk di lantai, menatap dinding itu dari sudut pandang yang sama seperti waktu kecil dulu dari bawah, dengan kepala miring dan mata penuh imajinasi.
Aku masih bisa mengingat hari-hari kami membuat “lukisan jari” itu. Hari Minggu, hujan turun deras. Ayah sedang di luar kota. Kami dilarang main hujan, jadi kami bermain warna. Ibu menggelar koran di lantai, menumpahkan cat air ke piring plastik bekas tutup toples, dan kami mulai mencelupkan jari kami satu per satu.
Awalnya di kertas. Lalu merembet ke tembok. Awalnya ragu-ragu, lalu makin berani. Sampai akhirnya... ya, dinding itu seperti galeri mini kami. Kami menyebutnya Tembok Bahagia.
Aku mendekatkan wajah ke salah satu bagian dinding. Ada sidik jari Dira dengan warna biru, membentuk bentuk seperti hati yang tidak simetris. Di atasnya, ada bekas tumpahan cat yang dulu membuat kami panik dan mencoba menutupinya dengan gambar kupu-kupu yang justru membuatnya makin aneh.
“Lihat ini, Bu,” kataku. “Ini waktu Dira jatuhin cat, terus kita pura-pura itu ‘proyek seni’ biar gak dimarahi.”
Ibu tertawa. “Iya. Ibu tahu itu bohong. Tapi pura-pura percaya biar kalian bangga.”
Kami bertiga tertawa, seperti dulu, seperti sore hari itu, seperti saat semua hal masih bisa dibereskan dengan teh manis dan pisang goreng.
Dira datang kemudian. Ia menatap dinding itu, diam. Matanya tampak lembap. Ia menyentuh sidik jari yang katanya milik anaknya kini—karena ukurannya hampir sama.
“Kalau rumah ini dijual, aku gak mau bagian dinding ini hilang,” katanya.
Aku mengangguk. “Mungkin nanti kita bisa bikin bingkai besar, khusus untuk bagian ini.”
“Enggak usah,” jawab Dira. “Biar tetap di sini aja. Rumah ini... ya, tempat semua ini dimulai.”
Kami duduk bertiga, memandang dinding yang sekarang tak hanya jadi tempat kami menggambar, tapi juga jadi tempat kami mengingat. Karena ternyata, yang paling sering kita lupakan bukan hal besar, tapi hal kecil yang dulu kita anggap biasa. Bekas tangan kecil itu... seperti pelukan dari masa lalu. Menyentuhnya seperti memeluk versi kita yang belum tahu dunia bisa menyakitkan, belum tahu bahwa rumah suatu hari bisa kehilangan suara tawa anak-anak.
Kami mengobrol lama di sana. Membahas bentuk-bentuk aneh yang kami gambar, membicarakan soal krayon yang patah, tentang bau cat yang menempel di kuku selama tiga hari. Dan kami tertawa, tertawa seperti dulu.
Malam harinya, aku kembali ke dinding itu sendiri. Lampu redup, bayangan lukisan jari itu terlihat samar, seolah mereka bergerak pelan mengikuti suara malam.
Aku menyentuh salah satu sidik jariku yang lama. Lalu, dengan pelan, kubisikkan:
“Terima kasih sudah tetap di sini,
meski waktu berlalu,
meski kita tumbuh,
meski tak ada lagi tangan kecil
yang melukis dengan riang.”
Aku menulis di catatan kecilku malam itu:
“Tembok itu tidak hanya menahan atap.
Ia menahan tawa,
juga kenangan yang tak bisa kita simpan di lemari.”
Dan sebelum tidur, aku berjanji:
Suatu hari nanti, anak-anakku akan kutunjukkan tembok ini. Biar mereka tahu, rumah lama ini pernah menjadi galeri kebahagiaan dua anak kecil yang percaya bahwa cinta bisa berbentuk sidik jari warna-warni.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_