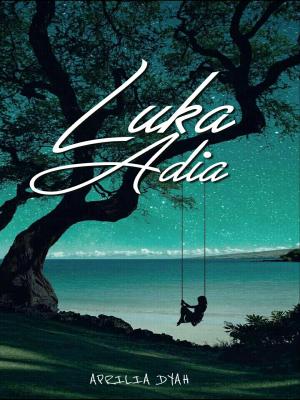Ada kotak kayu kecil di bawah meja kerja Ayah di ruang tengah. Warnanya sudah mulai pudar, dan salah satu sudutnya tergores seperti bekas cakaran waktu. Aku menemukannya saat sedang membersihkan ruangan itu, niat awalnya hanya ingin mengelap debu dan menyusun ulang buku-buku tua. Tapi seperti biasa, rumah ini tidak pernah kehabisan cara untuk membuatku berhenti, duduk, dan membuka kembali sesuatu yang lama.
Kotak itu tidak dikunci. Ketika aku membukanya, udara yang sedikit berdebu langsung menyeruak bau kertas tua, tinta lama, dan sedikit aroma kayu kering. Di dalamnya, tersusun rapi ratusan kertas yang dilipat menjadi bentuk amplop. Bukan amplop sungguhan, tapi kertas biasa yang dilipat dua dan diberi judul di pojok kanan atas. Semuanya ditulis tangan, dengan huruf yang kukenal betul: tulisan Ayah.
Aku mengambil satu.
"Untuk Ibu, 12 Juni 1997"
Jantungku langsung berdetak dua kali lebih cepat. Aku tahu hari itu—itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Tangan ini ragu untuk membuka. Tapi rumah ini punya caranya sendiri dalam mengundang kejujuran yang tak pernah sempat diucap.
Kubuka pelan-pelan.
“Sayang,
Hari ini hujan turun sejak pagi. Sama seperti hari kita menikah. Waktu itu kamu bilang, hujan pertanda rezeki. Tapi yang paling kuingat, kamu mengucapkannya sambil tersenyum, padahal bajumu kuyup dan sepatu kita belepotan lumpur.
Aku tak pernah menulis surat padamu, walau sudah sering niat. Tapi hari ini, aku ingin menuliskannya. Bukan untuk dikirim. Cukup untuk aku tahu bahwa aku masih bisa mencintaimu, dengan kata-kata, diam-diam.”
Tanganku gemetar saat membaca. Rasanya seperti sedang menguping suara hati yang tak pernah terdengar di ruang makan keluarga kami. Surat itu tidak panjang, hanya satu halaman. Tapi penuh dengan kehangatan yang tidak pernah kami lihat di permukaan.
Aku terus membuka satu per satu. Ada surat untuk kami, anak-anaknya, yang tak pernah dikirim. Ada surat saat Ayah marah padaku karena nilai jelek—tapi di surat itu, ia menulis:
“Aku tahu dia sudah berusaha. Tapi kadang mulut Ayah ini lebih dulu bicara dari hatinya. Maaf ya, Nak. Nanti Ayah peluk kamu waktu kamu tidur.”
Dan benar, aku ingat waktu itu. Ayah memang tidak bicara apa-apa malam itu, tapi aku bangun karena merasa ada tangan mengusap kepalaku. Kukira hanya mimpi. Ternyata, aku baru sadar sekarang: itu nyata.
Setiap surat yang kubaca seperti membuka potongan-potongan jiwa Ayah yang dulu kupikir terlalu kaku, terlalu diam, terlalu jauh. Ternyata, ia tidak jauh. Ia hanya menulis cinta dalam diam, dalam tinta, dalam surat-surat yang tak pernah dikirim.
“Lagi baca apa?” tanya Dira dari pintu. Ia datang membawa teh hangat.
Aku menatapnya dan menunjuk ke kotak surat. “Ayah nulis surat-surat. Banyak banget. Tapi nggak ada yang pernah dikasih.”
Dira ikut duduk, memandangi tumpukan surat. Ia mengambil satu dan membacanya diam-diam. Air matanya mengalir pelan, tapi senyum tetap tergurat di wajahnya.
“Selama ini kita pikir Ayah nggak pernah ngasih kejutan ya,” katanya sambil mengelap matanya. “Padahal ini... kejutan paling besar yang pernah ada.”
Kami membacanya bersama. Ada surat untuk Ibu saat mereka bertengkar soal hal kecil, seperti Ibu terlalu lama di warung. Tapi isinya lembut:
“Aku marah bukan karena kamu lama. Tapi karena aku takut kamu capek. Tapi lagi-lagi, aku salah cara bicara.”
Dan surat-surat tentang masa kecil kami. Tentang pertama kali aku bisa baca puisi di depan kelas. Tentang Dira yang main drama jadi pohon pisang. Semuanya tertulis.
Lucunya, Ayah bahkan menulis surat kepada seekor burung pipit yang pernah bertengger di jendela dapur:
“Kamu nggak tahu, tapi pagi itu kamu membuat istriku tertawa. Terima kasih ya, Pipit. Terima kasih sudah mampir.”
“Gila sih ini, Mbak,” kata Dira, masih terisak kecil. “Ayah kita romantisnya kebangetan. Cuma... diem-diem banget.”
Kami akhirnya memutuskan untuk menyusun surat-surat itu ke dalam map plastik, kami beri label: “Surat yang Tak Pernah Dikirim.” Bukan untuk dibagikan, bukan untuk dibacakan ke orang lain. Tapi untuk kami. Untuk hari-hari rindu, untuk malam yang kosong, untuk saat kami merasa kehilangan.
Satu hal yang membuat hatiku tercekat adalah surat terakhir, tertanggal dua minggu sebelum Ayah wafat. Di surat itu, ia menulis:
“Kalau suatu hari nanti kalian membaca ini, itu artinya Ayah sudah tak bisa peluk kalian langsung. Tapi percayalah, setiap kata ini Ayah tulis dengan cinta yang tak pernah pergi. Rumah ini mungkin akan sepi, tapi surat-surat ini... semoga cukup jadi suara Ayah yang masih ingin tinggal.”
Malam itu, aku tidur di kamar Ayah. Bukan karena takut sendirian, tapi karena rasanya hangat. Seolah surat-surat itu menjadi selimut baru. Dan aku merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, rumah ini tidak diam.
Rumah ini sedang bercerita. Pelan. Tapi tulus.
Keesokan harinya, aku dan Dira sepakat untuk membuat satu buku kecil. Bukan untuk dijual, bukan untuk dibaca publik. Hanya untuk keluarga kami. Kami beri judul sederhana:
“Ayah Menulis Diam-Diam”
Kami tahu, Ayah mungkin tidak akan suka jika semua orang tahu. Tapi kami percaya, kalau saja beliau tahu bahwa surat-surat itu membuat kami kembali dekat, beliau mungkin akan tersenyum dan bilang, “Akhirnya, surat ini menemukan alamatnya juga.”
Dan bukankah begitu, kadang cinta tidak harus dikirim lewat pos? Kadang ia cukup disimpan, tapi tetap terasa sampai jauh. Kadang surat yang tak pernah dikirim justru menyentuh lebih dalam, karena ditulis tanpa harap dibalas—hanya ingin didengar.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_