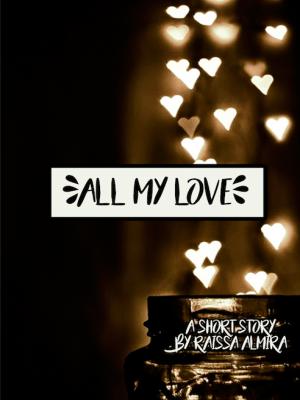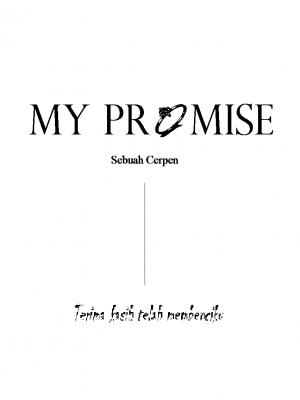Di Bawah Sadar yang Tak Mau Pergi
Ruang terapi itu sunyi. Dindingnya putih bersih, dan hanya diisi oleh satu sofa kulit cokelat, satu meja kecil, dan sebuah kursi kerja. Di sana, Nafa berbaring dengan mata terpejam, sementara Zac duduk di sebelahnya, memegang buku catatan dan alat perekam suara.
“Tarik napas dalam,” ujar Zac pelan. Suaranya lembut, mengalun seperti nyanyian tenang. “Lalu lepaskan perlahan…”
Nafa mengikuti.
“Kamu sekarang berada di tempat yang nyaman. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa sakit. Kamu bisa melihat semuanya dari kejauhan…”
Dahi Nafa sedikit berkerut. Zac memperhatikan gelombang napasnya.
“Coba ceritakan... tempat terakhir yang kamu lihat sebelum kamu koma.”
Hening. Lalu Nafa berbisik:
“…motor.”
Zac mencatat cepat.
“Motor siapa?”
“…Christian…”
Jantung Zac berdegup lebih cepat, tapi ia tetap tenang.
“Bagaimana kamu tahu itu Christian?”
Nafa mengernyit. Matanya tetap terpejam, tetapi bibirnya bergerak lirih.
“...jaket... tato... dia bilang... kita pergi…”
Zac menelan ludah. Ia tahu dari Adam, tidak ada bukti bahwa Christian yang benar-benar mengendarai motor itu. Tapi Nafa… begitu yakin.
“Kemudian apa yang terjadi?”
“Truk… truk besar... cahaya… kecelakaan…”
Tangan Nafa mulai mengepal. Tubuhnya sedikit gemetar.
“Baik… kamu sekarang menjauh dari adegan itu,” ucap Zac cepat, mencoba menstabilkan emosi bawah sadarnya. “Kamu berdiri dari kejauhan. Aman. Tidak ada yang menyakitimu.”
Nafas Nafa kembali tenang.
Zac mengganti pendekatan.
“Coba lihat… apakah kamu masih bisa merasakan Christian… dalam pikiranmu?”
Dan tanpa ragu, Nafa menjawab.
“Dia selalu ada.”
Zac terdiam.
“Dalam mimpi… di suara… bahkan ketika aku bangun. Rasanya seperti dia belum pergi.”
Zac menunduk.
Ia tahu tugasnya adalah menghapus trauma. Tapi yang dihadapinya bukan trauma biasa. Bukan luka, melainkan kenangan yang masih hidup.
---
Setelah sesi selesai, Nafa tertidur sejenak di sofa. Zac berdiri pelan, berjalan ke jendela. Hujan mulai turun.
Adam muncul di balik pintu kaca. “Gimana?” tanyanya, pelan tapi tegas.
Zac hanya menggeleng. “Dia tidak lupa.”
“Bisa dihapus?” suara Adam penuh harap.
Zac berpaling. “Saya bisa bantu dia berdamai… tapi saya nggak yakin bisa bikin dia melupakan seseorang yang begitu... dalam.”
Adam menarik napas panjang. “Saya cuma pengen dia hidup normal.”
“Saya juga,” kata Zac lirih, lalu menatap Nafa yang tertidur damai. “Mungkin… saya pengen lebih dari itu.”
Adam melirik tajam. Tapi tak berkata apa-apa. Hanya menatap Zac sejenak, lalu berbalik dan pergi.
Zac tetap berdiri di sana. Jiwanya bergulat. Di satu sisi, ia ingin menjadi pelindung Nafa. Di sisi lain, ia tahu—ada bagian dari hati perempuan itu… yang belum bisa ia sentuh.
Dan lebih buruk lagi…
Bagian itu masih milik orang lain.
Awal yang Tak Direncanakan
Pagi itu di ruang konseling klinik tempat Zac bekerja sebagai psikiater, Nafa duduk di bangku tunggu dengan mata sayu dan tangan gemetar.
Ia datang bukan untuk mencari cinta. Ia hanya ingin bisa tidur tanpa mimpi buruk. Bisa makan tanpa mual karena ingatan. Bisa hidup tanpa merasa bersalah karena masih bernapas sementara orang yang dicintainya hilang entah ke mana.
Zac telah memperhatikannya sejak pertama kali mereka bicara. Bukan karena wajah Nafa cantik, tapi karena ada keheningan dalam dirinya yang nyaring. Luka yang tidak pernah minta dimengerti, hanya butuh tempat untuk tidak merasa aneh.
Minggu demi minggu mereka bertemu. Awalnya formal. Konsultasi. Tanya jawab. Sampai suatu hari, hujan deras mengguyur kota dan Nafa masih duduk di ruang tunggu meski sesi mereka sudah selesai sejam lalu.
“Kamu gak pulang?” tanya Zac.
Nafa hanya menggeleng. “Gak pengen.”
Zac menatapnya, lalu mengambil dua cangkir kopi dari pantry kecil. Diberikannya satu ke Nafa.
“Kalau gak bisa pulang, kita diam bareng aja di sini. Gak usah bicara.”
Dan itulah awalnya.
---
Bukan Karena Jatuh Cinta, Tapi Dipeluk Diam-diam
Hari berganti. Mereka mulai berjalan kaki pulang bareng kadang-kadang, makan di warung ramen dekat taman, tertawa karena hal-hal kecil. Nafa belum bisa bilang ia bahagia. Tapi ia bisa bilang: dia tak lagi sendirian.
Zac tak pernah mendesaknya. Bahkan saat Nafa menangis di malam-malam tanpa alasan, saat ia tiba-tiba marah karena merasa bersalah tertawa—Zac hanya diam, menemaninya sampai reda.
“Kenapa kamu gak pernah tanya soal dia?” tanya Nafa suatu malam.
Zac menatapnya tenang. “Karena aku gak bisa bersaing dengan seseorang yang kamu cintai dari jauh. Tapi aku bisa berdiri di sini, dekat... kalau suatu hari kamu butuh tangan untuk digenggam.”
---
Pertama Kali Nafa Memegang Tangannya
Bukan saat Zac mengantar pulang, bukan saat makan malam pertama mereka, bukan saat diajak liburan ke luar kota. Tapi justru saat mereka sedang menunggu giliran laundry kering.
Nafa yang sedang membaca majalah tiba-tiba meletakkan tangannya di atas tangan Zac, yang bersandar di meja.
Tak berkata apa-apa. Hanya begitu.
Zac menoleh.
Nafa menatap lurus ke cucian yang berputar di mesin. “Aku capek membandingkan semua rasa. Jadi hari ini... aku berhenti menghitung dan mulai menerima. Apa pun bentuknya.”
Zac mengangguk. “Aku di sini, Naf. Selama kamu mau... aku tetap di sini.”
Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kehilangan, Nafa mencium seseorang karena ingin hidup, bukan karena ingin melupakan.
“Pelan, Tapi Jelas”
Sudah hampir setahun sejak pertemuan pertama mereka di ruang konseling itu. Hubungan mereka tumbuh dalam diam, dalam percakapan yang tidak diburu-buru, dalam pelukan yang hadir tanpa paksaan.
Suatu malam, di balkon apartemen kecil milik Nafa, mereka duduk berdampingan. Di bawah selimut tipis, dengan dua cangkir cokelat panas, dan radio kecil yang memutar lagu-lagu lawas lembut.
Angin dingin menyusup, tapi dada Nafa hangat.
Zac menoleh padanya. “Aku tahu kamu belum benar-benar selesai dengan semua itu. Dan mungkin gak akan pernah benar-benar selesai.”
Nafa tersenyum tipis. “Iya. Tapi kamu tahu, aku juga gak mau lari terus.”
“Kalau gitu,” kata Zac pelan, “boleh gak aku jadi tempat kamu belajar berhenti berlari?”
Nafa menatapnya lama.
Lalu, tanpa kata, ia memeluk Zac. Lama. Dalam. Diam-diam meneteskan air mata.
“Aku belum bisa janji akan sempurna,” katanya, suaranya gemetar.
“Gak usah sempurna. Cukup kamu gak sendirian lagi.”
Malam itu, mereka tidak saling menyatakan “aku cinta kamu” seperti di film-film. Tapi ketika Zac mencium kening Nafa sebelum tidur dan Nafa membiarkannya berbaring di sebelahnya untuk pertama kali, mereka tahu:
Mereka sudah memilih. Bukan karena sudah sembuh. Tapi karena ingin tumbuh. Bersama.
Aku Ingin Tahu yang Kau Sembunyikan
Ruang terapi sore itu tenang. Hanya suara jam dinding dan desah napas Nafa yang terdengar pelan. Ia duduk tegak di sofa, menatap Zac yang sedang menulis di jurnalnya.
“Zac,” ucap Nafa pelan.
Zac mendongak. “Ya?”
Nafa menarik napas dalam. “Kamu pernah bilang kamu pengen aku sembuh, bukan melupakan. Tapi… kamu gak pernah bilang, sebenarnya bagian mana dari masa lalu yang harus aku lupakan?”
Zac terdiam. Pertanyaan itu akhirnya muncul. Ia meletakkan pena pelan, menatap mata Nafa.
“Kamu merasa ada yang disembunyikan darimu?”
Nafa tersenyum miris. “Aku gak merasa. Aku tahu.”
Zac menunduk, jari-jarinya menggenggam lutut.
“Aku sering mimpi... laki-laki itu. Kadang cuma tatapannya. Kadang suara motornya. Aku tahu dia nyata, Zac. Aku tahu aku kehilangan sesuatu. Atau seseorang.”
Zac menelan ludah.
“Namanya… Christian.”
Nafa menggigit bibir bawahnya. Seperti nama itu memantik sesuatu yang familiar—nyeri, tapi hangat.
“Kamu kenal dia?”
Zac mengangguk. “Sedikit. Hanya dari cerita Ayahmu.”
“Jadi, kamu dan Papa sepakat untuk menghapus dia dari hidupku?”
Zac menghela napas panjang.
“Nafa... Christian sudah meninggal. Mereka temukan tubuh laki-laki yang membawa kamu malam itu. Wajahnya rusak parah karena kecelakaan. Dia memegang kalung dan ada tato segitiga kecil di jari tengahnnya. Motor, helm dan jaketnya pun di identifikasi milik Christian. Ayahmu yang mengurus pemakamannya..
Nafa memejamkan mata. Ia hampir bisa melihat kalung itu—pernah digenggamnya dengan cinta.
“Papa yang urus pemakamannya?” bisiknya.
Zac mengangguk. “Iya. Papa kamu yang urus semuanya. Tanpa memberitahumu karena… kamu koma waktu itu. Dan begitu kamu sadar, kamu seperti orang yang hilang arah. Menyebut nama Christian berkali-kali. Menangis, menjerit, kadang nggak mau makan. Papa kamu takut kamu nggak akan pernah kembali. Dia minta bantuanku—bukan untuk menipu kamu, tapi untuk menyelamatkan kamu dari rasa kehilangan yang terlalu dalam.”
Nafa menatapnya dengan mata memerah.
“Jadi dia benar-benar pergi"
“Iya,” kata Zac pelan. "Kamu terlihat mulai tenang. Mulai bisa tersenyum. Papa kamu bilang, mungkin itu jalan terbaik. Mungkin Tuhan sudah ambil Christian... dan kamu harus bisa lanjut hidup.”
Air matanya jatuh diam-diam.
“Aku masih mencintainya… meski aku gak tahu siapa dia.”
Zac bicara pelan, jujur, dengan luka yang ia simpan rapat.
“Aku jatuh cinta padamu, Naf. Tapi aku gak bisa bersaing dengan seseorang yang mungkin sudah meninggal… dan tetap tinggal di hatimu.”
Nafa menatap Zac. Tak ada kemarahan di sana. Hanya keheningan. Luka yang mulai berbentuk.
“Kalau dia masih hidup, Zac… dan suatu hari dia kembali?”
Zac tersenyum pahit. “Aku akan tetap di sini. Tapi kamu yang harus memilih.”
...
Rumah Baru Itu Bernama Kamu
Sudah lewat tengah malam ketika Nafa duduk sendirian di balkon. Udara dingin menyapa kulit, tapi hatinya terasa lebih hangat daripada beberapa malam sebelumnya.
Langkah kaki terdengar dari arah belakang.
“Belum tidur?” suara Zac pelan.
Nafa menoleh dan tersenyum tipis. “Belum. Lagi... ngerasa penuh.”
Zac duduk di kursi seberangnya, memandang ke arah langit gelap.
“Penuh… yang menyenangkan atau yang menyakitkan?”
“Campur,” Nafa menghela napas, “Aku sadar, Christian itu nyata. Cinta itu nyata. Tapi aku juga sadar... yang sudah berlalu gak harus selalu dilupakan.”
Zac hanya diam. Mendengarkan.
“Aku mau berdamai dengan itu semua, Zac. Aku gak mau lari dari rasa sakitnya lagi. Tapi aku juga gak mau tenggelam di dalamnya. Aku... mau hidup. Sekarang. Dengan semua kenangan itu tetap di sini,” ujarnya sambil menyentuh dadanya.
Zac menatapnya lama.
“Dan aku bukan Christian,” katanya akhirnya.
Nafa menoleh cepat, takut menyakiti.
“Tapi aku juga gak pengen jadi dia,” lanjut Zac. “Aku cuma pengen jadi seseorang yang bisa kamu ajak jalan bareng mulai sekarang. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk... melengkapi.”
Nafa terdiam. Kata-kata itu masuk seperti embun ke dalam pikirannya.
“Aku gak mau kamu harus berpura-pura melupakan dia. Atau merasa bersalah karena memilih bahagia. Kamu boleh tetap menyayanginya. Asal kamu tahu… kamu juga boleh mencintai lagi.”
Mata Nafa berkaca.
“Rumah... bukan cuma tempat pulang,” katanya pelan.
Zac mengangguk. “Rumah itu... tempat di mana kamu boleh menjadi dirimu sendiri. Dengan luka, dengan kenangan, dengan tawa barumu.”
Nafa tersenyum. “Rumah itu... kamu?”
Zac menarik napas lega, matanya menghangat. “Kalau kamu izinkan, iya.”
Malam itu, tanpa pelukan atau ciuman, mereka hanya saling menatap. Tapi dalam diam itu, dua hati akhirnya menemukan ruang.
Yang satu melepaskan.
Yang lain... menawarkan tempat baru untuk tinggal.
Beberapa saat berlalu dalam sunyi yang tidak canggung. Hanya suara angin menyentuh dedaunan, dan sesekali suara serangga malam.
Nafa menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, lalu menatap langit. “Aku pikir aku sudah rusak, Zac.”
Zac menoleh padanya. “Kenapa bilang begitu?”
“Karena hatiku seperti ruang tamu yang pernah kebakaran,” ia menghela napas. “Semua orang takut masuk. Bahkan aku sendiri pun takut duduk di dalamnya.”
Zac tidak langsung menjawab. Ia membiarkan jeda itu ada. Lalu dengan tenang, ia berkata, “Tapi aku lihat di ruang tamu itu masih ada jendela. Masih ada cahaya masuk. Mungkin tinggal diberesin sedikit. Dicat ulang. Dikasih bunga.”
Nafa tertawa kecil, tapi suaranya serak. Air matanya jatuh perlahan.
Zac menatapnya lekat. “Kamu gak rusak, Nafa. Kamu cuma... habis hujan besar. Dan aku gak keberatan bantu jemurin semuanya satu-satu.”
Nafa menutup matanya, membiarkan ucapan itu meresap. Ucapannya bukan janji kosong. Zac tidak pernah mencoba jadi pahlawan. Tapi ia selalu ada, bahkan saat Nafa tidak tahu bagaimana cara berdiri.
"Zac..." suaranya lirih. "Kalau suatu hari aku goyah lagi... kamu masih mau tungguin aku?"
Zac tersenyum lemah. "Aku gak mau nungguin kamu, Na. Aku maunya jalan bareng. Kalau kamu jatuh, aku bantu bangun. Kalau aku yang jatuh, kamu boleh marah dulu… tapi habis itu tolong tarik aku juga."
Untuk pertama kalinya, Nafa merasa tak perlu menggenggam masa lalu sekuat itu lagi.
“Kita mulai pelan-pelan ya, Zac?” bisiknya.
Zac mengangguk. “Satu hari, satu langkah.”
Langit mulai memudar. Warna biru gelap berubah menjadi ungu, lalu merah muda.
Fajar datang. Tak dramatis, tapi pasti.
Dan di antara dua orang yang telah saling menyimpan luka, ada satu hal yang akhirnya tumbuh: pengampunan—pada diri sendiri, pada masa lalu, dan pada cinta yang datang terlambat tapi tetap bermakna.


 choujie
choujie