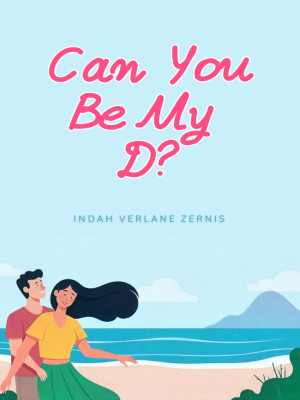Sorry, this chapter has been locked by the author!
Similar Tags
FaraDigma
1988
875
1
Romance
Digma, atlet taekwondo terbaik di sekolah, siap menghadapi segala risiko untuk membalas dendam sahabatnya. Dia rela menjadi korban bully Gery dan gengnya-dicaci maki, dihina, bahkan dipukuli di depan umum-semata-mata untuk mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Namun, misi Digma berubah total saat Fara, gadis pemalu yang juga Ketua Patroli Keamanan Sekolah, tiba-tiba membela dia. Kekacauan tak terh...
H : HATI SEMUA MAKHLUK MILIK ALLAH
47
45
0
Romance
Rasa suka dan cinta adalah fitrah setiap manusia.Perasaan itu tidak salah.namun,ia akan salah jika kau biarkan rasa itu tumbuh sesukanya dan memetiknya sebelum kuncupnya mekar.
Jadi,pesanku adalah kubur saja rasa itu dalam-dalam.Biarkan hanya Kau dan Allah yang tau.Maka,Kau akan temukan betapa indah skenario Allah.Perasaan yang Kau simpan itu bisa jadi telah merekah indah saat sabarmu Kau luaska...
The Best Gift
47
45
1
Inspirational
Tidak ada cinta, tidak ada keluarga yang selalu ada, tidak ada pekerjaan yang pasti, dan juga teman dekat. Nada Naira, gadis 20 tahun yang merasa tidak pernah beruntung dalam hal apapun. Hidupnya hanya dipenuhi dengan tokoh-tokoh fiksi dalam novel-novel dan drama kesukaannya. Tak seperti manusia yang lain, hidup Ara sangat monoton seakan tak punya mimpi dan ambisi.
Hingga pertemuan dengan ...
Can You Be My D?
132
117
1
Fan Fiction
Dania mempunyai misi untuk menemukan pacar sebelum umur 25. Di tengah-tengah kefrustasiannya dengan orang-orang kantor yang toxic, Dania bertemu dengan Darel. Sejak saat itu, kehidupan Dania berubah.
Apakah Darel adalah sosok idaman yang Dania cari selama ini? Ataukah Darel hanyalah pelajaran bagi Dania?
Taruhan
79
76
0
Humor
Sasha tahu dia malas. Tapi siapa sangka, sebuah taruhan konyol membuatnya ingin menembus PTN impian—sesuatu yang bahkan tak pernah masuk daftar mimpinya.
Riko terbiasa hidup dalam kekacauan. Label “bad boy madesu” melekat padanya. Tapi saat cewek malas penuh tekad itu menantangnya, Riko justru tergoda untuk berubah—bukan demi siapa-siapa, tapi demi membuktikan bahwa hidupnya belum tama...
My Private Driver Is My Ex
623
426
10
Romance
Neyra Amelia Dirgantara adalah seorang gadis cantik dengan mata Belo dan rambut pendek sebahu, serta paras cantiknya bak boneka jepang. Neyra adalah siswi pintar di kelas 12 IPA 1 dengan julukan si wanita bermulut pedas.
Wanita yang seperti singa betina itu dulunya adalah mantan Bagas yaitu ketua geng motor God riders, berandal-berandal yang paling sadis pada geng lawannya. Setelahnya neyra di...
Maju Terus Pantang Kurus
1970
928
3
Romance
Kalau bukan untuk menyelamatkan nilai mata pelajaran olahraganya yang jeblok, Griss tidak akan mau menjadi Teman Makan Juna, anak guru olahraganya yang kurus dan tidak bisa makan sendirian. Dasar bayi! Padahal Juna satu tahun lebih tua dari Griss.
Sejak saat itu, kehidupan sekolah Griss berubah. Cewek pemalu, tidak punya banyak teman, dan minderan itu tiba-tiba jadi incaran penggemar-penggemar...
Dalam Satu Ruang
189
131
2
Inspirational
Dalam Satu Ruang kita akan mengikuti cerita Kalila—Seorang gadis SMA yang ditugaskan oleh guru BKnya untuk menjalankan suatu program. Bersama ketiga temannya, Kalila akan melalui suka duka selama menjadi konselor sebaya dan juga kejadian-kejadian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Perahu Jumpa
373
300
0
Inspirational
Jevan hanya memiliki satu impian dalam hidupnya, yaitu membawa sang ayah kembali menghidupkan masa-masa bahagia dengan berlayar, memancing, dan berbahagia sambil menikmati angin laut yang menenangkan. Jevan bahkan tidak memikirkan apapun untuk hatinya sendiri karena baginya, ayahnya adalah yang penting.
Sampai pada suatu hari, sebuah kabar dari kampung halaman mengacaukan segala upayanya. Kea...
Perjalanan Tanpa Peta
75
70
1
Inspirational
Abayomi, aktif di sosial media dengan kata-kata mutiaranya dan memiliki cukup banyak penggemar. Setelah lulus sekolah, Abayomi tak mampu menentukan pilihan hidupnya, dia kehilangan arah.
Hingga sebuah event menggiurkan, berlalu lalang di sosial medianya. Abayomi tertarik dan pergi ke luar kota untuk mengikutinya.
Akan tetapi, ekspektasinya tak mampu menampung realita. Ada berbagai macam k...


 rosadewiita
rosadewiita