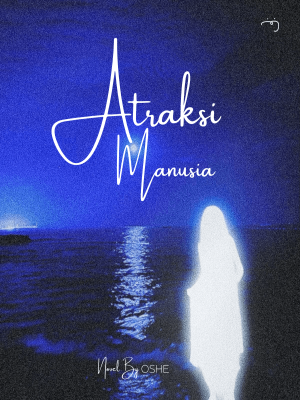Malam itu, setelah sekian hari hanya bertukar kabar secukupnya, Radit mengirim pesan.
“Besok sore, sempat ketemu bentar? Di taman deket kos kamu. Kalau kamu sempat.”
Pesan singkat yang nggak memaksa, tapi cukup bikin jantungku berdebar. Aku butuh waktu beberapa menit sebelum membalas, dan akhirnya hanya menjawab: “Iya, insyaAllah.”
Kami bertemu keesokan harinya. Taman itu masih sama—masih sepi, dengan suara motor sesekali lewat di jalan samping. Aku datang lebih dulu, duduk di bangku kayu di bawah pohon trembesi besar yang mulai menggugurkan daunnya.
Radit datang dengan kemeja lusuh dan wajah lelah yang tetap terasa hangat. Ia duduk di sampingku, cukup dekat untuk membuatku merasa tenang, tapi cukup berjarak agar aku bisa tetap berpikir.
“Kamu kelihatan capek,” kataku lebih dulu.
Dia tertawa pelan. “Iya. Lagi banyak kerjaan. Tapi lebih capek nunggu kabar kamu, sih.”
Aku tersenyum. “Maaf…”
“Enggak harus minta maaf.” Radit menoleh ke arahku, matanya jujur. “Aku ngerti kok. Kamu lagi butuh waktu.”
Aku mengangguk. Lalu kami diam sejenak. Tapi diam itu nggak canggung. Justru nyaman. Lalu dia mulai bicara lagi.
“Na, aku tuh dulu juga ragu waktu pertama kali bilang suka sama kamu.”
Aku menoleh, sedikit kaget.
“Aku takut kamu cuma lihat aku sebagai orang baik, bukan orang yang benar-benar kamu mau.”
Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tak menyangka dia punya keraguan yang sama.
“Aku juga gitu,” kataku jujur. “Aku takut nyakitin kamu. Takut belum bisa jadi pasangan yang utuh. Bahkan aku takut menikah hanya karena ‘sudah waktunya’, bukan karena benar-benar yakin.”
Radit mengangguk pelan. “Mungkin kita emang nggak akan pernah seratus persen yakin, Na. Tapi aku pikir… kalau kita sama-sama mau belajar, itu cukup.”
Aku menatapnya. “Belajar jadi pasangan?”
“Belajar jadi teman hidup. Belajar saling ngerti, bukan saling bener. Belajar ngobrol kayak gini terus, walaupun capek, walaupun nggak selalu sepakat.”
Obrolan itu nggak panjang, tapi terasa dalam. Ada ruang yang tiba-tiba terbuka di hatiku. Radit bukan orang yang selalu tahu jawabannya, tapi dia selalu siap mendengarkan. Dan entah kenapa, itu terasa cukup.
Sore itu, kami nggak membahas pernikahan. Kami cuma bicara tentang diri kami masing-masing. Tentang makanan favorit, mimpi masa kecil, alasan dia suka hujan, dan kenapa aku suka menulis hal random sebelum tidur.
Dan di sela semua itu, aku menyadari satu hal: mungkin proses ‘mengenal’ itu nggak berhenti di pelaminan. Tapi dimulai justru dari momen-momen seperti ini.
***
Beberapa hari setelah obrolan di taman, Radit mengajakku ke rumahnya.
“Bapak minta ketemu kamu,” ucapnya pelan saat kami makan siang di warung dekat kantor. “Nggak harus sekarang juga, tapi kalau kamu ada waktu akhir pekan…”
Aku sempat terdiam. Lalu mengangguk. “Aku bisa. Sabtu, ya?”
Sabtu siang, kami naik motor menyusuri jalan yang asing bagiku. Di sepanjang perjalanan, Radit tetap seperti biasanya—tenang, fokus pada jalanan. Tak banyak bicara, tapi sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan aku masih nyaman duduk di boncengannya.
Angin yang menerpa membuat perasaanku bercampur. Antara gugup, penasaran, dan entah—semacam perasaan yang belum kutemukan namanya. Tapi satu hal yang pasti, aku sedang diajak masuk ke dalam dunia yang lebih dalam dari Radit. Dunia yang belum pernah benar-benar aku sentuh.
Kami sampai di sebuah rumah tua sederhana dengan halaman luas. Di sampingnya ada bangunan kecil berlantai dua—di depannya terpampang papan kecil: Panti Asuhan Cahaya Kita.
Aku menelan ludah.
“Ini?” tanyaku pelan.
Radit mengangguk. “Ibu yang bangun panti ini. Dari uang pensiun dan donasi teman-temannya. Sekarang tinggal bareng anak-anak di sini.”
Kami masuk ke halaman, disambut tawa anak-anak kecil yang sedang main bola. Ada satu anak perempuan kecil yang langsung memeluk kaki Radit. “Kak Dit! Lihat gambarku!”
Radit jongkok, tertawa, dan mengelus kepala si kecil. Ia terlihat begitu hangat. Dan di saat itu, aku merasa melihat sisi dirinya yang selama ini belum sepenuhnya kutahu.
Bapaknya menerima kami dengan tenang dan ramah. Lelaki berambut putih dan senyum yang mengingatkanku pada Radit. Kami mengobrol di teras, dengan teh hangat dan biskuit yang rasanya seperti buatan rumah.
“Radit ini keras kepala. Tapi kalau sudah sayang, jarang lepas,” kata beliau sambil tertawa kecil. “Saya cuma ingin dia punya teman hidup yang juga sahabat. Bisa ngobrol, bisa diam bareng, dan bisa saling menguatkan.”
Aku tak sanggup menjawab, hanya bisa tersenyum dan mengangguk.
Sore hari, sebelum pulang, aku membantu membagikan makan malam pada anak-anak panti. Radit di sampingku, sesekali menggoda mereka dengan lelucon receh. Dunia kecil itu—penuh suara, tapi terasa damai—membuatku berpikir dalam.
Di motor dalam perjalanan pulang, aku bertanya pelan.
“Dit…”
“Hmm?”
“Kalau kita lamaran… kamu siap?”
Ia tertawa kecil. “Dari dulu juga siap. Tapi aku nunggu kamu mantap.”
Aku tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa mantap.
***
Beberapa minggu kemudian, dua keluarga bertemu. Bukan acara besar, hanya makan bersama di ruang tamu rumahku yang hangat. Tak ada hantaran berlebihan, tak ada perhiasan yang dipamerkan. Hanya niat baik dan rencana bersama. Ibuku menyiapkan nasi rawon, ayah Radit membawa oleh-oleh dari panti, dan kami hanya duduk, saling mengenal lebih dalam.
Itu bukan hari paling mewah dalam hidupku. Tapi mungkin, itu salah satu hari paling tenang. Seperti angin sore yang mengalir pelan. Sederhana, tapi cukup.


 rosadewiita
rosadewiita