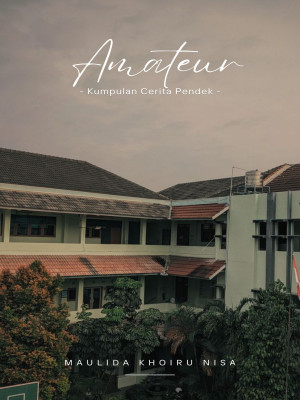Sudah tiga hari sejak terakhir aku dan Radit benar-benar ngobrol lama.
Bukan karena bertengkar. Bukan karena ada masalah besar. Justru karena... semuanya berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Terlalu sibuk. Terlalu banyak “nanti aku telepon ya” yang akhirnya tertidur tanpa sempat menelepon.
Dan aku pun tak berniat menuntut. Karena aku pun… sama sibuknya.
Pekerjaan di kantor sedang banyak-banyaknya. Proyek baru dari atasan membuatku lembur dua malam berturut-turut. Pekerjaan sebagai admin surat memang terdengar sederhana, tapi kalau urusan surat-menyurat macet di sistem, akulah yang dicari. Kadang aku bahkan lupa makan siang.
Aku buka WhatsApp, chat terakhir dari Radit masih bertengger di atas:
“Hari ini padet banget, Na. Maaf ya belum sempat ngabarin.”
Aku membacanya sambil tersenyum kecil. Radit tetap Radit. Jujur. Nggak sok romantis. Tapi ada jeda aneh di antara kami. Dulu, hal-hal seperti ini akan membuatku merasa kehilangan. Sekarang... hanya membuatku diam.
Dan dalam diam itu, ada rasa yang sulit dijelaskan: Aku rindu. Tapi tak tahu bagaimana mengatakannya tanpa terdengar menuntut.
***
Kami akhirnya bertemu hari Sabtu sore, di taman yang sama tempat Radit pernah bilang ia menyukaiku.
Tapi hari itu, tidak ada tawa lepas seperti dulu. Kami hanya duduk berdampingan, masing-masing dengan lelahnya sendiri. Dan aku sadar… hubungan kami mulai terasa seperti dua orang dewasa yang saling tahu harus bersama, tapi sedang lupa bagaimana caranya dekat.
“Aku mikir, kita kayak orang yang mau nikah, tapi… kayak belum ketemu lagi di tengah-tengah,” ucapku, pelan.
Radit menatapku. Lama. Lalu mengangguk.
“Iya… aku ngerasa juga.”
Aku menunduk. “Apa karena kita sibuk? Atau karena kita mulai jalan masing-masing?”
“Aku nggak tahu,” jawabnya jujur. “Mungkin karena kita sama-sama masih nyari cara untuk berdamai sama hidup kita sendiri.”
Dan aku tahu, kalimat itu bukan alasan. Itu kenyataan.
Kami berdua masih mencoba jadi versi terbaik dari diri masing-masing, tapi justru di situ... kami kadang kehilangan arah untuk saling merangkul.
***
Malamnya, aku kembali menulis di jurnal.
“Cinta dewasa bukan tentang seberapa sering bertemu, tapi seberapa sanggup saling memahami di tengah jarak. Tapi bagaimana jika aku sendiri belum selesai memahami diriku?”
Layar ponselku menyala. Pesan dari Radit.
“Maaf ya, hari ini rasanya hambar. Tapi aku masih mau kamu jadi temanku. Teman hidupku. Pelan-pelan, ya.”
Aku tak langsung membalas. Aku hanya menatap langit-langit kamar, dan membiarkan air mata jatuh diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rindu akan versi kami yang dulu—dan harapan pada versi kami yang nanti.
***
Hal paling menenangkan dari hari-hariku belakangan ini bukanlah waktu istirahat, bukan weekend, bukan juga momen jalan-jalan bareng Radit—yang makin jarang terjadi. Tapi… saat-saat di mana aku bisa membuka laptop, atau sekadar buku kecil bersampul biru di dekat bantal, lalu menulis. Apa saja.
Tentang rasa capek karena sistem kantor yang lambat, tentang Rina yang makin sering ngelucu di pantry, tentang makanan warteg yang rasanya makin hambar—atau kadang, tentang Radit, yang entah kenapa terasa makin jauh padahal masih sering mengucapkan, “hati-hati di jalan, ya.”
Aku mulai terbiasa menulis seolah sedang ngobrol. Bukan surat untuk seseorang, bukan juga catatan penting. Lebih seperti… aku bicara dengan versi kecil dari diriku yang mungkin masih bingung dan takut. Dan entah kenapa, aku merasa lebih lega setelahnya.
Hari ini aku bangun telat. Alarm berbunyi tiga kali, tapi aku tetap berguling di kasur. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya pengen jadi awan aja—nggak usah ngapa-ngapain kecuali mengambang di langit. Kadang hidup kayak terlalu rame buat hatiku yang senyap.
Tadi siang ada yang ngasih tahu soal seleksi CPNS lagi. Dulu aku akan semangat. Tapi sekarang aku malah bingung. Apakah itu masih keinginanku? Atau cuma keinginan versi lamaku?
Ada kenikmatan baru dalam menulis tanpa tujuan tertentu. Rasanya seperti menyapu lantai hati yang berdebu. Pelan-pelan. Menemukan bahwa di balik segala kelelahan dan pertanyaan, aku ternyata masih hidup. Masih bisa merasakan. Masih ingin bertumbuh.
Tuhan, kadang aku iri sama orang yang langkahnya kelihatan jelas. Tapi mungkin mereka juga punya malam-malam ragu yang tak pernah terlihat. Aku juga akan sampai, kan? Asal aku terus jalan?
Satu hal yang mulai kurasakan sejak rajin menulis: aku jadi lebih jujur.
Bukan pada orang lain—tapi pada diriku sendiri. Aku mulai bisa membedakan mana rasa takut, mana yang cuma belum siap, mana yang hanya ingin didengarkan. Menulis jadi caraku duduk bersama pikiran-pikiran itu tanpa harus merasa malu.
Dan anehnya, dari semua hal yang membuatku lelah, menulis justru membuatku kembali merasa hidup.
***
Sudah beberapa hari aku menulis setiap malam, dan entah kenapa—meski ada kelegaan—tetap saja ada ruang kosong di dada yang belum juga terisi. Malam ini, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk bekerja, bukan untuk menulis. Tapi untuk salat.
Sudah lama rasanya aku tidak benar-benar berbicara dengan-Nya dalam keadaan hati seberantakan ini.
Aku menggelar sajadah dengan pelan. Mengambil wudhu dengan langkah setengah gemetar. Hening kosan malam itu, suara air dari kamar mandi, detak jam dinding, dan nyala lampu kamar yang redup—semuanya terasa seperti saksi dari rasa lelah yang tak sempat kusampaikan ke siapa-siapa.
Salat malam itu bukan yang paling khusyuk, bukan yang paling panjang, tapi mungkin yang paling jujur dalam hidupku belakangan ini. Aku hanya bisa menangis. Membisikkan doa dalam hati yang bahkan tak sempat tersusun rapi.
“Ya Allah... Aku bingung. Aku sayang Radit, tapi aku juga belum yakin dengan diriku sendiri. Aku masih takut. Aku belum siap. Tapi aku juga tak ingin menyakitinya…"
Sesudahnya, aku duduk diam di ujung sajadah. Seperti anak kecil yang habis memeluk ibunya. Tak ada suara apa pun—kecuali hatiku sendiri, yang mulai terdengar lagi. Pelan-pelan.
Dan malam itu juga, aku mengangkat ponsel. Mengetik satu nama: Ibu.
Butuh beberapa detik sebelum aku benar-benar menekan tombol hijau. Tapi saat suara ibu terdengar di seberang, napasku langsung meluruh.
“Assalamu’alaikum, Bu...”
“Wa’alaikumussalam, Nak... kok tumben malam-malam telepon?”
Aku tak langsung menjawab. Tapi suara ibu, seperti biasa, membawa sesuatu yang menenangkan. Seolah cukup dengan mendengar suaranya, aku tahu bahwa aku tidak sendirian.
“Bu...” suaraku lirih, nyaris seperti bisikan, “Aku bingung. Aku capek. Aku... nggak tahu harus gimana.”
Ibu terdiam sebentar, lalu hanya menjawab dengan lembut, “Kalau kamu capek, jangan lari jauh-jauh, Nak. Pulang aja ke Allah. Nangis aja, nggak apa-apa.”
Tangisku pecah lagi. Tapi kali ini, tangis yang lebih ringan. Bukan karena sedih, tapi karena merasa diizinkan. Diizinkan untuk belum kuat. Diizinkan untuk belum yakin.
Dan mungkin... itu yang paling aku butuhkan saat ini.


 rosadewiita
rosadewiita