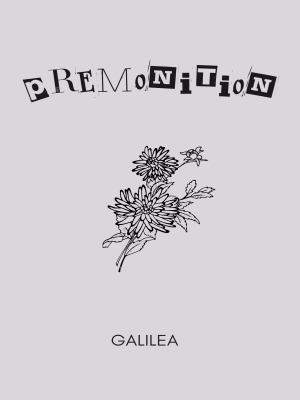Hari itu, sore mulai merayap. Cahaya matahari jingga masuk lewat jendela kaca café favorit kami, tempat di mana kami sering menghabiskan waktu bersama—ngobrol, tertawa, atau sekadar diam menikmati kopi.
Aku duduk di pojok meja, jari-jari main-main dengan gelas kopi hangat. Radit datang sambil membawa satu kotak kecil yang dibungkus rapi dengan pita merah.
Aku penasaran, “Eh, itu bawa apa sih? Kok kayaknya ada sesuatu yang mau kamu kasih?”
Dia duduk, senyumnya nggak biasa, ada getar-getar di matanya.
“Nara, aku mau bilang sesuatu. Tapi aku mikir, lebih enak kalau aku tunjukin aja.”
Aku melihat dia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada cincin kecil, simpel tapi cantik—batu kecil yang berkilau mengundang perhatian.
“Aku nggak jago ngomong panjang-panjang. Aku cuma mau kamu tahu, aku serius sama kamu,” kata Radit pelan. “Aku nggak janji bisa sempurna, tapi aku mau jalani hidup ini bareng kamu. Nara, mau nggak kamu jadi pendamping aku? Menikah sama aku?”
Aku menatap matanya, hatiku berdebar. Suasana hangat café, bau kopi, suara riuh pelan pengunjung lain, tiba-tiba jadi latar sempurna untuk momen ini.
Dengan suara yang sedikit bergetar, aku jawab, “Radit, aku... iya, aku mau.”
Dia langsung tersenyum lega, dan aku pun memasang cincin itu di jariku.
Kami tertawa kecil, saling bertatapan penuh makna.
Di sudut café itu, aku merasa dunia kami sejenak berhenti. Bukan karena kejutan, tapi karena rasa percaya yang tumbuh perlahan—tentang masa depan yang ingin kami jalani bersama.
Radit menatapku, berkata, “Ini bukan akhir cerita, Nara. Tapi awal bab baru yang kita tulis bareng.”
Aku tahu, perjalanan kami masih panjang. Tapi aku siap. Karena untuk pertama kali, aku merasa bukan cuma mulai lagi, tapi juga memulai sesuatu yang indah.
*
Setelah malam lamaran itu, aku duduk di balkon kamar kecil kosanku. Lampu kota berkelap-kelip seperti bintang-bintang kecil yang tak pernah lelah menunggu. Aku membuka buku jurnalku—tempat aku mencatat segala hal yang kadang terlalu berat untuk diucapkan.
Aku mulai menulis.
“Aku ingat betul bagaimana aku dulu merasa hancur saat segala rencana bersama Arya berantakan. Seolah jalan yang kupikir lurus, tiba-tiba penuh belokan tajam. Rasanya gagal itu seperti gelombang besar yang menggulung tanpa henti, membuat aku terseret tanpa pegangan. Tapi di dalam gelap itu, aku mulai belajar—bahwa hancur bukan berarti lenyap. Hancur adalah proses membuka ruang baru di dalam diri.”
Aku menulis tentang betapa sulitnya melepas masa lalu yang telah banyak mengajarkan luka, tapi juga kekuatan. Tentang betapa aku dulu sering bertanya, “Siapa aku sebenarnya? Apa arti semua ini?”
“Kadang aku merasa seperti terdampar di tengah samudra, menunggu sebuah kapal yang bisa membawa aku ke pantai. Tapi kapal itu ternyata bukan orang lain—itu aku sendiri yang harus jadi nakhodanya. Aku belajar pelan-pelan bahwa memulai ulang bukan berarti mengulang yang sama, tapi memberi kesempatan pada diriku untuk menemukan arah yang baru.”
Maka, ketika Radit datang dalam hidupku, bukan sebagai penyelamat yang datang tiba-tiba, tapi sebagai teman yang setia menemani prosesku, aku tahu aku mulai bisa membuka lembaran baru.
“Bertemu Radit adalah pengingat bahwa tidak ada yang salah dengan memulai lagi dari nol. Bahwa kita tidak harus sempurna untuk dicintai. Bahwa keberanian terbesar adalah menerima diri kita, dengan segala ketidaksempurnaan dan cerita yang belum usai.”
Aku menutup jurnalku dan menatap bintang malam yang sama dari tadi.
Aku sadar, perjalanan ini belum selesai.
Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap berjalan.
Karena aku belajar, “Kadang yang paling penting bukanlah tujuan, tapi seberapa berani kita melangkah meski belum tahu ke mana arah kaki ini akan membawa.”


 rosadewiita
rosadewiita