Malam sebelumnya, suara kentongan dua kali tidak lekas hilang dari telinga. Bunyi kayu beradu itu seperti seekor burung yang tak tahu di mana harus hinggap: melompat dari atap ke atap, menggelayut di lubang angin, merayap lewat sela anyaman dinding, lalu jatuh pelan ke bantal orang-orang yang memaksa matanya terpejam. Di antara jeda dua ketukan yang tetap, ada jarak hening yang anehnya justru lebih berisik: tempat khayal, cemas, dan ingatan lama muat berdesakan. Pagi datang setelahnya, namun cahaya matahari terasa lebih berat, seperti kain basah yang dibilas tergesa di sumur—matahari naik, tapi sinarnya memikul kabar yang tidak selesai diucapkan.
Di serambi villa, Roni membuka buku agenda peninggalan ayahnya. Sampulnya masih keras, sudut-sudutnya berlekuk karena sering dipegang. Halaman yang pernah ditempeli daun jambu—yang diselipkan ayahnya bertahun-tahun yang lalu—sudah menguning, uratnya retak halus. Roni menuliskan daftar kecil seperti biasa: pagar hidup, kelas Sabtu, gelas bekas. Goresan pensilnya rapi, tapi tak selincah biasanya. Baris-baris huruf itu terasa seperti pijakan di jembatan bambu yang menganga di beberapa tempat. Ia berhenti menulis, telapak tangannya ringan menyentuh daun jambu yang menua, seolah di situ ada cara untuk menambal jarak antara yang bisa ia catat dengan yang tak berani ia sebut.
Seorang anak kecil lewat di jalan tanah di depan serambi, kaki telanjangnya menabur debu halus. Ia menoleh, matanya bulat, suaranya serak karena baru bangun. “Mas, kenapa bunyinya dua kali?”
Roni menahan napas, lalu memasang senyum yang ingin hangat tapi basah oleh sisa cemas. Ia mengacak rambut anak itu. “Dua kali artinya kita harus lebih hati-hati. Kalau kamu lihat jalan retak, jangan diinjak. Kasih tahu bapakmu, ya?”
Anak itu mengangguk, lalu lari seperti biasa—hanya saja langkahnya kali ini lebih ringan, seperti sengaja menghindari bayangan sendiri. Senyum Roni padam, berganti gumam yang ia tujukan ke halaman kosong: “Kalau orang lain mundur, aku mesti mendorong.”
Ia menutup buku agenda lebih keras dari yang diperlukan. Suara kertas beradu tidak keras, namun terasa memantul ke dalam dadanya, menggelinding di sana, seperti batu kecil di dasar gentong.
Siang hari, balai kecil di tengah desa pelan-pelan terisi. Orang-orang datang tidak dengan panik, melainkan dengan cara yang telah dilatih oleh musim: ada yang membawa bambu panjang yang biasa dipakai mengukur dalam, ada yang menyelipkan obor tanpa menyalakannya—karena siang—ada pula yang menenteng tali rafia bekas karung beras. Mereka duduk melingkar dengan jarak yang dibiarkan bernapas, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, seolah di antara mereka ada kursi yang dipinjamkan untuk rasa takut agar tidak berdiri di tengah.
Pak Tarya berdiri di depan, rokok lintingan padam separuh di sela jari, suaranya serak namun tegap. “Kentongan dua kali bukan tanda untuk panik,” ujarnya, membuka rapat seperti membuka pintu. “Itu tanda untuk jaga mata. Malam ini ronda jangan kendor. Jembatan bambu dicek, jalan pasar jangan sampai ada lubang. Anak-anak jangan dibiarkan main jauh.”
Kepala-kepala mengangguk. Satu-dua orang menambahkan yang biasa, tapi penting: pagar hidup diperiksa, parit kecil yang suka meluap dibersihkan sebelum senja, sudut-sudut halaman disapu, bukan untuk rapi semata, melainkan supaya jejak-jejak yang tidak lazim gampang terlihat. Mereka menyebutkan hal-hal kecil dengan keseriusan yang tidak kecil—kebiasaan yang barangkali terdengar sederhana, tapi persis di situlah desa menyimpan kearifannya: cara menahan ketakutan adalah memberinya pekerjaan.
Di bagian belakang, Ahyi berdiri dengan caping di tangannya—dipegang, tidak dipakai. Ia mendengar semua, mengangguk pada beberapa poin, menatap tanah di sela kalimat. Suara rapat masuk ke telinganya seperti air masuk ke tanah: sebagiannya diserap, sebagian lagi mengalir ke tempat lebih rendah yang gelap. Tidak ada yang menyebut Tebing Cahaya. Jalur curam itu, yang berkelok di sisi bukit dan memantulkan cahaya matahari sore seperti sepenggal pisau, tabu disebut dalam pertemuan biasa. Terlalu banyak cerita lama yang berakhir tanpa kabar di situ. Namun justru karena sepi, anak-anak sering diam-diam menantang diri melewatinya—bukan karena berani, tetapi karena ingin diakui oleh bayangannya sendiri.
“Kalau tanah menagih, harus ada yang menjawab,” batin Ahyi, merasakan lidahnya kering. “Dan kalau bukan aku yang tahu jalannya, siapa?” Ia sangat paham, jika ia buka mulut di rapat, Pak Tarya akan melarang keras siapa pun menyentuh jalur itu. Larangan adalah cara melindungi, tapi kadang larangan juga membuat mata menghindar dari tempat yang seharusnya diperiksa. Di antara dua kemungkinan itu—melarang yang menyelamatkan dan melarang yang membutakan—Ahyi mengambil keputusan yang lahir bukan dari keberanian, melainkan dari pengalaman yang panjang dengan tanah: pergi sendiri dulu, lihat dengan mata sendiri. Ia mengangguk tipis ketika rapat bubar, seolah menerima keputusan bersama, padahal di dadanya keputusan lain sudah hidup, tumbuh akar dalam beberapa detik yang isi waktunya lebih padat daripada satu hari penuh.
Di kamar villa, Ridhan menutup laptop dengan gerakan tegas yang tidak mau disesali. Sisa bayangan wajah-wajah di layar—Tante Laila dengan blazer mengilap, pamannya yang selalu menimbang angka—tetap menempel pada kaca yang mendadak hitam. Suara mereka berbaur, menjadi satu suara panjang: jual—kelola—simpan—bagi hasil—branding—kawasan—prospek. Ia mengembuskan napas, mengusir satu per satu kata itu seperti mengusir laron yang nekat. Tapi yang pulang ke telinganya bukan kata dari kota; yang singgah justru bunyi kentongan dua kali, menyeberang dari malam kemarin, beradu di tulangnya sendiri.
Ia meraih kamera dan buku catatan. Bahunya kaku, tapi matanya mantap. Seperti tubuhnya memilih duluan sebelum pikirannya mengiyakan. Roni masuk, membawa agenda. “Kau dengar, Din? Kentongan semalam?”
“Dengar.”
“Warga sudah resah. Kalau ada data apa pun soal retakan tanah, keluarin.”
“Data tanpa bukti lengkap cuma menambah gosip,” jawab Ridhan, suaranya datar. “Aku butuh lihat langsung. Ke tebing.”
Roni menutup agendanya, napasnya ikut berat. “Sendirian ke tebing itu gila. Jalurnya rapuh. Kalau kau jatuh, siapa yang tahu?”
Ridhan memutar ring lensa perlahan, seperti menenangkan pikirannya sendiri. “Kalau kita pergi berdua, risikonya dobel. Jalurnya sempit, tanahnya mudah runtuh. Satu orang cukup.”
“Kau pikir aku bisa diam? Aku juga Amarfi. Kalau ada bahaya di tebing, aku ikut. Itu tanggung jawab kita berdua.”
“Justru karena kau Amarfi, kau harus tinggal,” kata Ridhan, menatap tajam bukan untuk menyakiti, melainkan supaya kata-katanya tidak kabur. “Kau jembatan satu-satunya ke warga. Kalau kau hilang, suara desa putus. Kalau aku hilang, council hanya kehilangan satu suara keras kepala.”
Keheningan setelah itu bukan jeda, melainkan ruang supaya alasan yang keras bisa turun derajat menjadi pengertian. Rahang Roni mengetat. Ia ingin menyebutkan berpuluh argumen lain, tapi ia tahu, di rapat-rapat desa, orang menunggu bahasanya, bukan angka Ridhan. Ada hal-hal yang hanya bisa ia lakukan jika ia tinggal. “Baik,” katanya akhirnya, “Tapi kalau kau tidak kembali, aku orang pertama yang membongkar council di depan warga.”
Sudut bibir Ridhan bergerak tipis—bukan senyum, lebih mirip pengakuan bahwa ancaman itu masuk akal. Ia mengangguk, mengangkat ranselnya, dan pergi.
Sore membentang seperti kain songket yang condong—benang-benang cahaya miring, menembus sela daun pisang dan petai cina. Ahyi berjalan sendirian di jalur Tebing Cahaya. Caping menutupi wajah, tangan kirinya membawa seutas rafia, tangan kanannya menggenggam tongkat bambu yang ujungnya dipangkas miring untuk menyelidiki tanah. Ia melangkah dengan cara orang yang mengenal tempat namun tetap menghormatinya: langkah pertama menjejak tanah yang tampak paling bosan diinjak, langkah kedua mencari suara, langkah ketiga baru percaya.
Jalur sepi, tapi sepi itu bukan sejuk. Sepi di sini terdengar, ada bunyinya. Serangga bersuara pendek-pendek, lalu berhenti bersamaan seperti ada aba-aba yang tidak terdengar manusia. Burung kecil melintas rendah, lalu meniadakan kicaunya seketika. Ahyi jongkok di tepi jalur. Jarinya menelusuri garis retak yang menjalar seperti saraf menuju perut bukit. Retakan ini bukan retak kering biasa. Bibirnya masih lembab, tanahnya hitam kecoklatan. Ada serbuk halus menempel di kulit jarinya; jika didekatkan ke hidung, baunya seperti arang yang pernah basah, ada getir yang singkat, hampir tidak terkatakan. “Tanah ini tidak diam,” gumamnya. Ia menempelkan telapak ke tanah, merasakan sesuatu yang samar—bukan gempa—lebih seperti rongga yang bernafas di bawah, pelan dan berat.
Ia menyingkirkan daun pisang yang melintang, masuk lebih dekat ke pancang bambu yang miring. Ketukan telapak pada pancang mengeluarkan suara hampa, bertolak belakang dengan pancang sebelahnya yang mantap. Simpul rafia di pangkalnya lapuk—air memakan simpul lebih cepat dari yang disadari orang. Ahyi memotong sisa tali dengan parang kecil, mengganti dengan simpul baru; jemarinya luwes, seperti seseorang yang menulis namanya sendiri di kertas yang bergerak. Namun saat ia menekan pancang dengan bahu, tanah di bawahnya tidak menahan—justru mengerut seperti kulit tua di atas luka yang ditarik. Pancang ikut bergerak, turun setengah jengkal. Ahyi mundur reflek, mata menyapu lereng. Di rerumputan yang tumbuh jarang, retakan halus seperti garis cacing merambat dari pangkal bambu ke arah jurang. Retakan itu baru; tanahnya masih lembab, serangga enggan menyilangkannya. Ia menempelkan telapak lagi, kini jelas terasa getar tipis—bukan dari atas, melainkan dari rongga yang menunggu di bawah.
Ia menimbang cepat: pulang memperingatkan warga—menutup jalur—menjaga anak-anak. Namun keputusan yang baik kadang kalah cepat satu detik dengan langkah yang buruk. Ujung sepatunya menekan bibir retakan yang ia kira padat. Tanah terbuka tidak seperti mulut yang ternganga, tapi seperti lembar kain yang tiba-tiba kehabisan tenunan di satu sisi. Tubuhnya terdorong, capingnya terlepas, pancang yang baru diikat ikut menarik dirinya ke bawah. Jeritannya tercekat, bukan karena takut, tapi karena tercepat oleh udara. Dunia berputar miring, tempat yang tadi ia pijak bergerak naik menggantikan langit. Dalam sepersekian detik yang lahir panjang, Ahyi anehnya sempat melihat detail: rusuk akar yang telanjang, semak berduri yang tak bergerak, satu batu kecil dengan lumut halus yang tetap menempel seolah masa kini tidak berlaku baginya.
Tong! Tong! Tong!
Di desa, suara kentongan tiga kali memecah udara seperti sobekan pada kain yang dipakai bersama. Tidak ada yang berteriak lebih dulu. Yang terdengar justru ketukan alu yang berhenti di udara, meninggalkan lesung sebagai wadah keheningan. Ayam-ayam yang biasa berlomba duluan ke remah nasi tiba-tiba memilih sisi teduh, memiringkan kepala. Anak-anak yang tadi berceloteh menadahkan telinga, lalu secara naluriah mencari pangkuan. Kentongan tiga kali di sini bukan informasi; ia adalah bahasa lain dari tanah yang semua orang tua paham tanpa perlu menerjemahkan.
Pak Tarya keluar ke halaman, wajahnya pucat seperti kain yang terlalu lama dijemur. Matanya menatap ke arah bukit meski yang terlihat hanya kabut. “Tebing Cahaya…” ucapnya, dan kata itu menyebar bukan lewat mulut, melainkan lewat dada ke dada, mengubah udara menjadi sesuatu yang lebih berat, seperti disiram minyak kelapa yang membeku.
Roni di serambi villa meraih agendanya, lalu berlari. Bukan jarak yang membuat napasnya sesak, melainkan nama yang berkali-kali menghantam kepalanya: Ridhan. Ia tahu kakaknya itu pergi dengan kamera, sendirian, bicara pendek tentang tebing. Jangan sampai… pikirnya, dan pikiran yang tidak selesai itu justru membuat langkahnya lebih kencang, untuk menyalip kalimat yang ia tak sanggup akhiri.
Di balai, warga berkumpul. Tidak ada ricuh. Kepanikan di desa ini tidak mengenakan suara keras; ia mengenakan kerja. Obor mulai dinyalakan—meski hari belum benar-benar runtuh—karena api adalah cara berbicara kepada yang tidak bisa dibaca mata. Bambu panjang diangkat, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai jari yang lebih panjang untuk menyentuh tanah sebelum kaki salah memilih. Ibu-ibu menimba air hangat, menyiapkan kain; bukan karena mereka yakin akan luka, tetapi karena mereka tak ingin kesiapan kalah cepat dari kabar.
Pak Tarya berdiri di depan, suaranya memikul umur orang-orang yang pernah hilang. “Kentongan tiga kali bukan sembarangan. Itu tanda tanah menelan, atau siap menelan.” Ia menatap jauh ke bukit, lalu merendahkan suara tanpa menurunkan wibawa. “Dulu, orang tua menyalakan obor di sudut-sudut jalan agar roh tidak tersesat pulang. Laki-laki muda membawa bambu untuk mengukur pijak, supaya tidak ada yang hilang dua kali di tempat yang sama. Perempuan menaruh kendi berisi air di serambi, untuk siapa pun yang haus—entah manusia, entah yang lain—supaya tidak meminta ke tempat yang tak bisa kita beri.” Beberapa orang mengangguk, tidak pada kalimat, melainkan pada ingatan yang dihidupkan kalimat itu.
Roni berdiri di antara mereka, dadanya naik turun, bukan karena lari. Ia memandang obor yang kecil tapi keras kepala, memandang tangan-tangan yang gemetar menggenggam bambu, memandang wajah-wajah yang setia menimbang antara pasrah dan ikhtiar. Ia mengangkat suara, tidak untuk menantang, tetapi untuk melengkapi bahasa yang sudah lama dipakai desa. “Kalau tanah menagih, jangan biarkan dia memilih sendirian,” katanya, membuat orang-orang menoleh bukan karena keras, tapi karena jelas. “Kita harus turun, mencari, memanggil, menolak menyerah. Kalau hanya diam, jurang itu akan selalu menang.”
Sebelum bergerak, Pak Tarya memulai cara desa memegang takut: absensi. Bukan sekadar menyebut nama—melainkan memanggil mereka kembali ke tengah lingkaran. Satu-satu, dua-dua. Suara jawab datang, kadang disusul “di rumah”, kadang “di kebun”.
“Ridhan.”
Hening satu tarikan napas. Terlalu panjang untuk dianggap lupa, terlalu singkat untuk disebut kehilangan. Lalu suara seorang lelaki dari sudut menyahut pelan, “Tadi kubilang dia ke arah tebing.” Kepala-kepala menoleh, pelan, seperti bambu yang serentak digoyang angin. Pandangan akhirnya bertumpu pada Roni.
Jantung Roni memukul-mukul dari dalam, menimbulkan rasa mual yang tidak ada hubungannya dengan lapar. Ia ingin menjawab, ingin menyangkal, tapi tidak ada kata yang bisa menyelamatkan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menahan wajahnya agar tidak menuduh siapa pun—selain waktu.
Absensi berlanjut. Satu nama, satu jawaban, suara-suara lirih yang terasa semakin berat.
“Ahyi.”
Kali ini hening yang datang lebih panjang. Sunyi yang menetes ke dada orang-orang seperti air dingin yang sengaja ditahan terlalu lama. Seseorang berdehem, seperti hendak menjawab, tapi tak jadi. Seorang ibu menutup mulutnya dengan punggung tangan, matanya membesar, air di sudutnya bergetar tapi belum jatuh.
Dari pojok, suara bocah muncul, tipis tapi tajam seperti bilah yang baru diasah. “Siang tadi aku lihat caping-nya, Bu. Di tangan.”
Kalimat pendek itu seperti meletakkan batu di telapak semua orang. Udara yang semula berat menjadi kental, membuat dada-dada sesak. Beberapa orang menoleh ke tanah, ada yang menggenggam bambu lebih erat, seakan kayu bisa meminjamkan keteguhan. Seorang lelaki muda menunduk, bibirnya bergetar tanpa suara.
Roni merasakan tubuhnya ditarik dua arah sekaligus: ke luar untuk berlari sendiri ke tebing, ke dalam untuk menahan dirinya agar tidak memecah barisan. Panik menyeruak seperti asap, mencari celah untuk menyalakan api ricuh. Ia tahu kalau ia membiarkan, desa akan pecah oleh takut. Maka ia paksa dirinya berbicara—keras bukan, jelas iya—untuk menahan semua orang agar tidak hancur lebih dulu oleh bayangan.
“Berarti dua,” kata seseorang, tidak berani menyebut siapa. Dua yang tidak ada selalu lebih berat daripada satu yang hilang.
Panik merayap, mencari celah. Roni melangkah setengah ke depan, menjaga suaranya agar jelas, tidak keras. “Kita tidak tahu menitnya. Tapi kita tahu jalannya.” Ia memandang obor, bambu, tali, dan wajah-wajah yang sudah setia bertahun-tahun pada kearifan yang menyelamatkan sebanyak yang tidak sempat diselamatkan. “Pasrah yang diam hanya memberi jurang pilihan. Pasrah yang bergerak memberi kita kemungkinan. Obor bukan hanya cahaya—dia doa yang berjalan. Bambu bukan hanya tongkat—dia jari yang lebih panjang untuk menakar pijakan. Air hangat bukan hanya untuk luka—dia undangan untuk pulang.”
Orang-orang menatap. Roni bukan orang lama, tidak tumbuh bersama mitos Tebing Cahaya. Tetapi justru karena itu, ia membawa kalimat yang diperlukan sekarang: kearifan lama bukan untuk menutup pintu baru.
Pak Tarya menurunkan bahu sedikit—gerak kecil yang artinya sama dengan “ya”. “Kita bagi baris,” katanya. “Dua jalur, satu tim menyisir dari atas, satu dari bawah lembah. Jangan satu-satu. Tali di pinggang. Bambu dulu kaki belakangan. Obor di tangan kanan, doa di mulut.”
Obor menyala satu per satu. Api kecil condong ke arah angin, tapi tidak padam. Ibu-ibu menabur garam di sudut halaman, menggantung daun sirih di pintu. Anak-anak duduk memeluk lutut, mata mereka sebesar matahari yang masih segan turun.
Orang-orang membagi tugas tanpa perintah panjang. Tiga orang di depan membawa bambu, dua orang membawa tali, satu orang membawa kain dan air di kendi. Rombongan bergerak. Roni berjalan di depan baris atas. Ia bukan pahlawan; ia hanya orang yang menolak membiarkan jurang memilih sendiri. Ia menatap obor di tangannya. Api kecil itu goyang, tapi tidak padam. Ia merasa aneh—api sekecil itu rasanya lebih berat dari bambu di bahu, karena yang ia bawa bukan nyala, melainkan harap.
Di sisi lain bukit, Ridhan berlutut di tanah. Kamera menggantung di dada, catatan hitam terbuka di lutut. Jemarinya meraup segenggam tanah dari celah retakan, menahannya sejenak sebelum diremas pelan. Butirannya kasar, cokelat kehitaman, lengket pada kulit dengan noda yang menyerupai jelaga. Ia gosokkan di antara jari—butiran itu hancur terlalu cepat, tidak seperti tanah liat atau pasir padat. “Lignite,” pikirnya. Batubara muda. Rapuh, jenuh air, menyimpan gas seperti paru-paru yang tidak mau berhenti bernafas meski tertutup tanah.
Pensilnya menari cepat: lapisan lignit bercampur lempung, jenuh air → rawan ambles; kemungkinan rongga udara/air di bawah. Ia menuliskan panah-panah kecil, lingkaran, tanda seru—tanda buru-buru orang yang tahu waktunya bisa lebih pendek dari yang ia kira.
Ingatan lama ikut duduk di lututnya. Sebuah laporan geoteknik dari Kalimantan Selatan: tambang tua runtuh setelah hujan, meninggalkan kawah selebar lapangan bola. Dua rumah hilang bersama jalan desa. Gas metana terperangkap di bawahnya pecah, membuat api biru menari semalam penuh. Ia bisa membayangkan cahaya itu—indah sekaligus mengerikan—api yang tidak lahir dari kayu atau minyak, melainkan dari perut bumi yang terlalu lama ditahan.
Di Sumatra, ia pernah membaca istilah yang masih membuat bulu kuduknya meremang: arang hidup. Lapisan batubara muda yang, meski tertutup tanah, tetap bernafas. Kadang melepaskan gelembung gas di permukaan air, kadang membuat pekerja tambang pingsan massal hanya karena runtuhan kecil membuka mulut bumi sepersekian inci. Nama itu—arang hidup—selalu terdengar baginya seperti doa terbalik: sesuatu yang seharusnya mati, tapi memilih tetap bernapas, dan napas itu beracun.
Ia menegakkan punggung sejenak, menatap kontur curam Tebing Cahaya. Retakan kecil berlari seperti garis samar di pipi orang tua. “Kalau di sini…” gumamnya. Ia mengangkat pandangan ke arah danau di atas. “Lapisan rapuh ini duduk tepat di bawah beban air. Air memberi tekanan. Gas menunggu celah. Retakan sekecil ini cukup jadi pintu.”
Pikirannya meloncat pada catatan lama—peta Belanda dengan garis-garis tipis yang seragam, semua berakhir di satu titik, seakan para juru ukur dulu pun sudah mengerti bahaya yang mereka tidak sempat tuliskan dengan kata. Ingatan laporan-laporan geoteknik kembali menimpa: foto kawah terbuka, garis retakan yang menjalar ke rumah, nyala biru yang menari sendirian di malam.
Ridhan merasakan telapak tangannya masih kotor, jemarinya dilapisi bubuk hitam. Ia menatap noda itu lama, seperti menatap sidik jari bumi. Di dadanya muncul kesadaran yang lebih dingin daripada angin sore: tanah ini bukan cuma rapuh—ia menyimpan janji lama, janji yang menunggu dipanggil oleh hujan, gempa, atau satu pijakan manusia yang salah.
Lalu suara itu pecah, menyalip catatannya.
Tong! Tong! Tong!
Tiga kali.
Suara itu merambat lewat batang pohon, lewat tanah yang diinjak, hingga ke tulang-tulang Ridhan. Ia berdiri membeku. Pandangannya menatap dua arah: ke desa di belakangnya, atau ke jurang yang di depannya. Di dalam dirinya, sebuah pertanyaan mendesak: apakah ia harus kembali ke balai desa untuk memberi tahu apa yang ia temukan, atau terus maju sendiri, menelusuri tanda-tanda yang mungkin mengarah ke seseorang yang terperangkap?
Kakinya melangkah setengah ke belakang, lalu berhenti. Ridhan berdiri kaku, menatap garis curam Tebing Cahaya.
Dengan hati-hati, ia memutuskan untuk mengikuti retakan.
Lereng itu memantulkan cahaya sore seperti pisau baru diasah: dingin, menyilaukan, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Angin dari bawah naik pelan, membawa bau tanah basah yang disusupi samar belerang, getir tipis yang hanya sebentar singgah di lidah. Kamera di dadanya berayun, lensa terbuka, seolah menunggu perintah. Tapi ia tahu, yang ia perlukan bukan gambar—melainkan mata yang mampu membaca tanah seperti membaca wajah sendiri.
Ia menempelkan bahu pada dinding batu. Dinginnya merayap ke tulang, membuat tubuhnya kaku sekaligus waspada. Setiap langkah mengikuti aturan yang ia buat sendiri: injak—tahan—dengar. Tanah sehat menjawab padat, tanah rapuh berbunyi kosong, seperti mengetuk peti kayu. Ia berhenti beberapa kali, menunduk, menimbang. Di sisi jalur, ada bekas geser panjang. Terlalu lebar untuk kambing, terlalu dalam untuk sekadar binatang kecil. Lebih mirip sesuatu yang berat kehilangan pijakan, menyeret tanah dalam sepersekian detik.
Ia jongkok, jemarinya meraba retakan kecil yang menjalar dari pijakan itu. Retakan tidak pernah berdusta. Dalam geoteknik yang pernah ia baca, retakan permukaan cenderung menuju pusat kelemahan—seperti benang tipis yang mengantar pada simpul utama. Kalau ada korban, jalannya pasti kesini, pikirnya. Naluri dan ilmu bertemu, membisikkan arah yang sama.
Tak jauh dari situ, sehelai rafia basah tergeletak, putus, ujungnya menghitam oleh lumpur bercampur arang. Ia mengangkatnya, mengendus bau lembab yang asing. Bukan bau gudang, bukan bau karung beras, melainkan bau perut tanah yang sempat bernafas lama. Setengah meter lebih dekat ke bibir jurang, sebuah caping. Anyamannya rapat, masih basah sisa hujan, satu sisinya patah. Di bawahnya, tapak tak sempurna—sisi kiri lebih dalam dari kanan, tanda pijakan terakhir yang goyah. Dari bekas itu, garis geser meluncur ke bawah, seperti anak panah yang tak sabar menunjukkan arah.
Ridhan merangkak, tubuhnya diperkecil agar angin tak semena-mena mendorong. Napasnya memburu, telapak tangannya lecet oleh batu kasar. Pandangannya menyapu ke bawah. Tebing itu jatuh dengan sombong—curam, tapi menyisakan ceruk-ceruk kecil yang tampak ramah padahal licik. Senja menajamkan warna, membuat tiap detail tampak lebih telanjang dari biasanya, seakan mata dipaksa membaca semua yang tersisa.
“Kalau tanah bicara,” gumamnya, “ia tak selalu pakai kata.”
Ia melangkah lagi, tetap mengikuti retakan. Dadanya bergetar antara panik dan doa. Kalau aku salah, aku hanya mengikuti tanah kosong. Tapi kalau benar…
Setiap cabang kecil ia abaikan, memilih retakan utama yang paling panjang, karena ia tahu: jalur utama selalu menunjuk inti kelemahan. Batu sebesar kepala kambing bergeser aneh di depannya; lumut di sisi bawah hancur, sisi atasnya bersih—baru saja berpindah. Di sampingnya, dedaunan kering membentuk kipas, seolah sesuatu jatuh melewati dan menyibaknya dari tengah.
Jalur itu semakin curam, memaksa tubuhnya menempel pada batu dingin. Kamera di dadanya bergesek pada kancing, bunyinya terlalu keras di telinganya sendiri, seperti pengingat bahwa ia tidak sendirian—ada saksi yang menunggu bukti.
Pikirannya berputar: Bagaimana kalau aku kembali sekarang? Aku bisa memberitahu warga. Mereka akan datang bersama obor, dengan bambu, dengan doa. Itu lebih aman. Tapi langkahnya tidak mau berhenti. Ada sesuatu yang lebih kuat dari keraguannya—naluri. Jantungnya berdegup seirama, antara panik dan doa, antara ilmu dan firasat. Kalau aku benar, di ujung retakan ini ada seseorang, setiap menit berarti.
Ia menunduk lagi, menajamkan mata. Retakan itu tidak hilang. Ia melengkung ke bawah, membelah semak, menuntunnya seperti benang halus yang tidak ingin putus.
Ridhan berhenti di bibir jalur, tubuhnya menempel pada batu yang dinginnya merayap ke tulang. Pandangannya jatuh ke ceruk di bawah, dan di sana, sesuatu yang aneh muncul—cahaya kecil, berkelip pelan, seperti bintang yang tersesat dan memilih singgah di jurang.
Semula ia ragu, tapi cahaya itu bertambah banyak. Satu, dua, lalu puluhan. Kunang-kunang. Mereka menyalakan udara, menari di sela semak basah, berputar di sekitar sosok yang terkulai, seakan sengaja menyorotinya.
Dadanya seketika penuh oleh rasa yang bertabrakan. Takut—jangan-jangan yang ia lihat hanyalah bayangan. Khawatir—karena tubuh itu pucat, bersandar pada akar seperti menunggu waktu. Panik—sebab setiap detik yang hilang bisa jadi tarikan nafas terakhir. Namun bersama itu, muncul juga lega—mata sosok itu terbuka, dada naik turun meski pendek dan berat. Hidup. Masih hidup.
Namun justru di balik lega, sesuatu yang getir menyelusup. Ingatan pada kata-kata lama, mitos yang pernah ia dengar sambil lalu: jika seorang laki-laki dan seorang perempuan menyaksikan kunang-kunang bersama, mereka tak akan bisa bersama. Waktu itu ia menganggapnya candaan belaka, tapi malam ini, di tepi jurang, cahaya mungil itu menjelma ironi yang menyala.
Ridhan tertegun. Kamera di dadanya berayun, lalu terangkat tanpa sadar. Jari menekan rana. Klik. Gambar muncul di layar: akar yang menjulur seperti tangan penolong, semak yang basah, senja yang meredup, puluhan cahaya kecil yang berkelip seperti doa, dan sosok manusia di tengahnya. Terlalu indah untuk bencana, terlalu pahit untuk disebut kebetulan.
Ia memotret lagi, refleks, seakan keindahan itu akan lenyap bila hanya disimpan mata. Klik. Foto kedua bergetar di layar, tapi ia hampir tak sanggup melihat.
Dadanya sesak. Udara senja yang dingin terasa berat, seperti ikut menekan kata-kata agar tidak keluar terburu-buru. Ia berdiri di sana, gemetar oleh rasa takut, panik, lega, dan getir yang saling berebut tempat.
Akhirnya, mulutnya terbuka. Dan dari semua kalimat yang mungkin ia ucapkan, hanya satu kata yang jatuh, lirih, menutup hari itu—
“Ahyi.”


 linschq
linschq

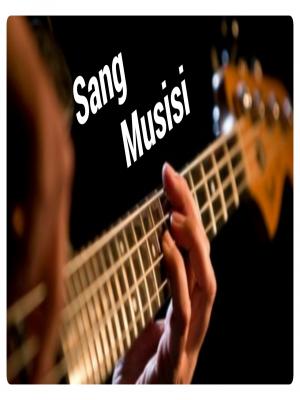








Roni sama Ahyi chemistrynya dapet banget berduaaa... Gaya bahasanya sukaa... puitis, tapi enggak yang terlalu mendayu-dayu. Ibaratnya dessert manisnya pas. Hehehehe...
Comment on chapter Chapter 1 Jejak Langkah di Desa Tanpo Arang