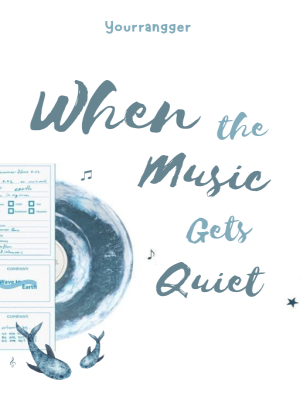Di sebuah sore yang tenang, angin meniup pelan tirai jendela rumah. Bau kayu, kopi, dan sedikit aroma kue pisang goreng yang baru diangkat dari penggorengan bercampur jadi satu. Suara burung gereja terdengar dari pohon jambu di samping rumah. Dan untuk sesaat, waktu terasa diam. Seolah dunia ingin memberi ruang bagi kenangan untuk muncul kembali—satu per satu. Aku duduk di ruang tamu. Di pangkuanku, sebuah album foto tua yang sampulnya mulai terkelupas. Sudut-sudutnya lusuh, dan lem di beberapa bagian tak lagi kuat menahan potret masa lalu.
Di halaman pertama, ada foto rumah kami dua puluh tahun lalu. Dindingnya masih papan, halamannya masih tanah merah. Di situ, ada Ibu, Bapak, dan dua anak kecil yang berdiri dengan senyum belum genap tumbuh gigi.
Itu aku. Dan Damar.
Dulu kami tinggal di rumah kecil di tepi kampung. Sekarang rumah itu sudah direnovasi. Tapi rasa yang tumbuh di dalamnya tetap sama: hangat, kadang riuh, dan seringkali penuh tawa yang dibungkus lelah.
Tapi... sore itu, aku tahu. Bahwa waktu tak akan selamanya sama. Dan pulang, tidak selalu berarti kembali ke tempat yang kita kenal.
Satu minggu lalu, Pak Yanto—tetangga lama kami—pulang ke kampung setelah 15 tahun merantau di Kalimantan. Tapi bukan untuk liburan, bukan untuk reuni, bukan untuk mengobati rindu. Ia pulang karena istrinya meninggal. Pak Yanto datang dengan wajah tua yang lebih tua dari usia aslinya. Langkahnya berat, matanya bengkak, dan senyumnya... tidak ada. Ia tidak membawa koper, hanya sebuah tas kecil dan dompet usang yang digenggam erat seakan di dalamnya ada satu-satunya yang masih bisa ia pertahankan. Ia duduk di beranda rumah kosong. Rumah yang dulu ditinggalnya waktu anak-anaknya masih kecil, dan istrinya masih rajin menjemur selimut di pagar depan.
Tetangga menyambut. Tapi ia lebih banyak diam. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan setelah sekian lama:
“Pulang nggak selalu bikin tenang.”
Aku mendengarnya sambil mengantar teh manis hangat. Dan kalimat itu menetap di pikiranku sampai sore ini. Aku pernah berpikir bahwa pulang adalah solusi dari semua lelah. Bahwa dengan pulang, semua luka akan sembuh, semua tanya akan terjawab, dan semua yang hilang akan kembali. Tapi ternyata... tidak selalu. Kadang kita pulang ke rumah yang sudah tak lagi utuh. Kadang kita pulang tapi orang yang ingin kita temui sudah tiada. Kadang kita pulang, tapi diri kita sendiri yang dulu... sudah tidak bisa ditemukan lagi.
Seperti Pak Yanto. Ia datang ke rumah yang kini hanya berisi gema. Istri yang dulu menanti di pintu, kini hanya tinggal bingkai foto di ruang tengah. Anak-anaknya sudah punya rumah sendiri. Dan ia... hanya duduk di kursi rotan yang pernah dibuatnya sendiri, memandang sepi yang mengendap di dinding rumah.
“Saya kira kalau saya balik, semuanya bisa saya perbaiki,” katanya pelan suatu malam saat duduk di warung kopi depan gang.
“Tapi ternyata saya terlalu lama pergi. Ada yang nggak bisa saya kejar lagi.”
Kata-katanya seperti cermin. Menyentuh hati, sekaligus bikin takut. Apakah kita semua sedang pelan-pelan menjauh dari rumah yang sebenarnya?
Beberapa hari setelahnya, aku memberanikan diri bertanya pada Ibu.
“Bu, menurut Ibu... pulang itu apa, sih?”
Ibu, yang sedang melipat baju sambil duduk di lantai, hanya tersenyum.
“Pulang itu... bukan tempat, tapi rasa. Bisa saja kamu nggak pulang ke rumah ini, tapi hatimu tetap pulang ke kami.”
Aku diam. Menimbang kalimat itu.
“Kadang kita merasa pulang itu harus kembali ke rumah, ke kampung, ke halaman lama. Padahal bisa jadi pulang justru ke diri sendiri. Ke versi kamu yang dulu bahagia, ke tujuan awal yang kamu lupa,” lanjut Ibu. “Dan kadang... pulang juga berarti melepaskan. Menerima bahwa yang dulu ada, sekarang sudah nggak bisa dipeluk lagi. Tapi kita tetap bisa menyimpan hangatnya.”
Tiga hari kemudian, Pak Yanto pamit kembali ke Kalimantan. Kali ini, ia membawa abu jenazah istrinya. Bukan untuk disimpan, tapi untuk ditaburkan di sungai belakang rumah mereka. Tempat istrinya dulu suka mencuci sambil bersenandung kecil.
“Saya mau dia pulang ke tempat yang dia suka,” ujarnya singkat.
Sore itu, kami ikut mengantar. Hanya beberapa tetangga dekat. Sungai kecil itu tenang, pepohonan melambai pelan, dan airnya mengalir seperti biasa—seperti tidak ada yang berubah. Tapi hati kami, terutama Pak Yanto, jelas tidak sama.
Ia melempar abu itu pelan ke aliran sungai. Tidak banyak kata-kata. Hanya mata yang sembab dan tangan yang bergetar. Dan di saat itu, aku belajar satu hal: Bahwa pulang tidak selalu harus kembali secara fisik. Kadang pulang hanyalah tentang menyelesaikan. Tentang merelakan. Tentang menerima bahwa beberapa hal memang hanya singgah sebentar.
Beberapa minggu setelah kepergian Pak Yanto, aku duduk di ruang tengah sambil menatap tumpukan foto. Lalu aku menemukan satu foto lama: foto Ibu duduk di sepeda butut warna biru, dengan aku kecil duduk di boncengan, memeluk erat dari belakang.Itu hari pertama aku masuk sekolah dasar. Aku terdiam lama melihatnya. Saat itu, aku tidak tahu apa-apa soal hidup. Tidak tahu tentang kehilangan, tentang perpisahan, tentang waktu yang diam-diam mencuri banyak hal. Yang aku tahu, selama ada Ibu, rumah, dan sore yang hangat—semuanya baik-baik saja.
Dan sekarang... aku paham. Bahwa perasaan aman itu adalah rumah. Dan selama aku bisa menjaga itu—untuk diri sendiri dan orang-orang yang kucintai—aku selalu bisa pulang. Meskipun tidak ke rumah yang dulu. Meskipun tidak ke tempat yang sama. Tapi aku bisa pulang ke rasa yang sama.
Pulang tak selalu berarti kembali.
Terkadang, justru saat kita pergi jauh, kita baru benar-benar bisa pulang. Pulang ke tujuan yang kita lupakan. Pulang ke nilai-nilai yang sempat kita anggap remeh. Pulang ke hati yang dulu kita abaikan. Dan ada kalanya, kita harus menerima bahwa tak semua tempat bisa kita datangi kembali. Tak semua orang bisa kita temui lagi. Tapi kita bisa menyimpan mereka dalam diri, dalam doa, dalam cerita yang kita teruskan.
Seperti yang Ibu ajarkan: pulang bukan hanya tentang pintu rumah yang terbuka, tapi juga tentang hati yang tidak menutup.
Sore ini, angin kembali berhembus pelan. Tirai jendela bergoyang pelan seperti melambai pada seseorang yang jauh. Aku menutup album foto perlahan, dan meletakkannya kembali di rak. Di sampingnya ada buku harian Ibu yang dulu sempat kutemukan, dengan tulisan kecil di halaman depan:
“Jangan takut jauh, selama kamu tahu jalan pulang. Dan kalau pun jalan itu hilang, jadilah seseorang yang membuat rumah baru—dengan cinta yang sama.”
Aku menarik napas pelan. Hati ini... terasa lebih penuh. Dan di saat itu, aku tahu.
Bahwa aku telah pulang.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_