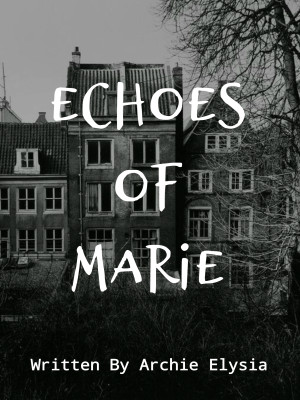Ada satu ruangan di rumah kami yang dulu sering terabaikan: ruang kecil di samping dapur yang dulunya adalah gudang, lalu disulap Ibu menjadi ruang jahit. Satu mesin jahit tua, tumpukan kain warna-warni, dan kaleng biskuit yang isinya benang, kancing, pita, serta jarum pentul. Ibu tidak pernah menyebut tempat itu "ruang kerjanya", tapi kami semua tahu—itulah tempat di mana Ibu menyelamatkan banyak hal. Dari baju robek, resleting rusak, sampai hati yang lelah. Karena anehnya, setiap kali Ibu duduk di depan mesin jahit itu, ia terlihat lebih tenang. Lebih hidup. Seolah dari balik setiap tusukan jarum dan derit pedal, ia sedang menata ulang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar potongan kain.
Pagi itu, aku menemuinya di sana.
“Ibu lagi buat apa?” tanyaku, duduk di bangku kayu kecil di sampingnya.
“Buat tas dari kain perca,” jawabnya sambil tetap fokus pada jahitannya. “Buat dijual minggu depan. Lumayan buat tambah-tambah beli gas.”
Aku tersenyum. “Masih kuat aja, Bu. Nggak capek?”
Ibu berhenti sejenak, menoleh dan berkata pelan, “Kalau ngerjain sesuatu yang disayang, capeknya beda. Kayak diselimuti sabar.”
Aku diam. Kalimat itu seperti menjahit langsung ke dalam dadaku.
Sore harinya, aku menemukan Damar berdiri di depan ruang jahit, memandangi Ibu yang tengah menata kain-kainnya.
“Kamu tahu nggak,” katanya, “Ibu dulu sempat punya cita-cita jadi desainer baju.”
Aku terkejut. “Serius?”
Damar mengangguk. “Aku pernah nggak sengaja baca tulisan lamanya. Katanya, waktu kecil dia suka gambar baju-baju pengantin. Tapi ya, hidup nggak pernah kasih ruang buat dia kejar itu.”
Aku terdiam.
Ibu, dengan semua ketekunan dan cinta yang ia curahkan di ruang kecil itu, ternyata pernah punya mimpi yang besar—yang ia simpan, lalu dijahit rapi-rapi jadi diam.
“Kenapa dia nggak cerita ya?” gumamku.
“Mungkin karena nggak sempat,” jawab Damar. “Atau karena... dia tahu nggak semua mimpi harus dicapai. Beberapa cukup jadi sumber kekuatan, supaya bisa hidup dengan hati penuh.”
Aku menatap Ibu dari balik pintu. Tangannya lincah, matanya fokus, mulutnya bersenandung pelan lagu keroncong yang entah dari mana datangnya.
Aku tiba-tiba merasa ingin menjahitkan sesuatu untuknya. Sesuatu yang bukan baju atau tas, tapi harapan—sebuah bentuk kecil balasan untuk hati yang tak pernah berhenti menyulam cinta.
Beberapa hari kemudian, aku mengajak Ibu ke toko kain di kota. Awalnya ia menolak, bilang kain-kain di rumah masih banyak. Tapi setelah aku membujuk dan menyebut bahwa aku ingin mulai belajar menjahit juga, wajahnya langsung bersinar.
“Beneran kamu mau belajar?”
Aku mengangguk. “Aku juga pengin ngerti rasanya menjahit. Bukan cuma kain, tapi juga... diri sendiri.”
Kami berdua tertawa. Tapi entah kenapa, tawa itu membawa rasa hangat yang lama tak datang. Seperti... aku akhirnya membuka pintu ke dunia kecil Ibu, dunia yang selama ini hanya kami lewati, tapi tak benar-benar kami pahami.
Di toko kain itu, Ibu seperti anak kecil di taman bermain. Ia menyentuh tiap lembar kain, membandingkan warna, menarik gulungan benang, dan mencoba pola-pola baru. Aku hanya mengikutinya, mengagumi bagaimana ia mengingat harga, tekstur, hingga asal-usul corak batik tertentu.
“Ibu ini kayak kamus berjalan,” kataku sambil tertawa.
“Namanya juga cinta lama,” jawabnya. “Susah dilupakan.”
Setelah belanja kain, kami mampir ke warung soto langganan. Di sana, di tengah semangkuk kuah panas dan sambal yang melebihi takaran, Ibu mulai bercerita. “Waktu muda, Ibu pernah ikut lomba desain baju. Nggak menang, tapi sempat masuk final. Hadiahnya cuma mesin jahit mini, yang akhirnya rusak karena kebanjiran.” Aku menatapnya, tak tahu harus bilang apa. Karena tak pernah terpikir Ibu juga punya masa-masa ingin terbang tinggi. “Tapi nggak apa-apa,” lanjutnya. “Mungkin Tuhan memang mau Ibu jadi penjahit di rumah ini. Bukan buat fashion show, tapi buat anak-anak yang baju sekolahnya sobek. Buat cucu nanti yang mau kostum karnaval. Buat diri Ibu sendiri, supaya tetap waras.”
Aku menggenggam tangannya. Ia tersenyum.
Tiba-tiba aku sadar: Ibu bukan tidak punya panggung. Ia hanya memilih panggung yang lebih kecil, tapi penuh cinta. Dan dari situ, ia menjahit ulang hidup kami satu per satu—tanpa pernah minta pujian. Hari-hari selanjutnya kami habiskan bersama di ruang jahit. Ibu mengajariku menjahit lurus, membuat pola dasar, bahkan memintaku menjahitkan sarung bantal. Hasilku belepotan, tapi Ibu tetap memuji.
“Lumayan lah. Nggak bisa buat dijual, tapi bisa buat kenangan,” katanya sambil tertawa.
Saat itu aku sadar, menjahit itu bukan soal rapi atau lurusnya benang. Tapi tentang sabar. Tentang membangun, tusuk demi tusuk, sesuatu yang sebelumnya hanya potongan tak bermakna. Seperti hidup. Seperti luka yang harus disulam pelan-pelan. Di malam yang sepi, saat hanya terdengar suara jangkrik dan derit kipas angin, Ibu berkata:
“Kita semua pernah robek, pernah sobek sana-sini. Tapi jangan buang kainnya. Karena kalau kita sabar menjahitnya kembali, bisa jadi lebih kuat dari sebelumnya.”
Dan aku tahu, kalimat itu bukan cuma tentang kain. Tapi tentang hati.
Beberapa minggu kemudian, Ibu mengikuti pameran kerajinan kecil di balai desa. Kami semua ikut mendampingi. Di sana, tas-tas kain buatan Ibu—yang selama ini hanya disimpan di lemari—dipajang rapi, diberi label harga, dan... dihargai. Ada seorang perempuan muda yang memegang salah satu tas Ibu dan berkata, “Ini bagus banget. Siapa yang buat?”
Ibu malu-malu menjawab, “Saya.”
Perempuan itu tersenyum. “Boleh pesen lagi, Bu? Saya suka motifnya. Jarang lho yang buat kayak gini.” Ibu hanya mengangguk, tapi matanya berbinar. Mungkin seperti itulah rasanya saat mimpi lama akhirnya mengetuk pintu.
Malam harinya, aku dan Damar membicarakan pameran itu sambil menyeruput teh di dapur.
“Kita pikir Ibu itu ‘cuma’ ibu rumah tangga. Padahal dia seniman,” kata Damar.
“Seniman benang dan harapan,” jawabku sambil tersenyum.
Kami tertawa kecil. Tapi rasanya... itu bukan candaan. Karena Ibu memang menjahit lebih dari sekadar kain. Ia menjahit ulang harapan kami yang sempat koyak oleh dunia. Ia menyulam keyakinan bahwa hidup mungkin berat, tapi tetap bisa indah... kalau kita tahu caranya menjahit kembali serpihan-serpihan kecil itu. Dan kini, aku hanya ingin belajar lebih banyak. Tentang menjahit, tentang sabar, tentang mencintai dalam diam, dan tentang menyulam harapan dari bahan-bahan sederhana—seperti yang telah Ibu lakukan seumur hidupnya.


 tumbuhbersamakata_
tumbuhbersamakata_