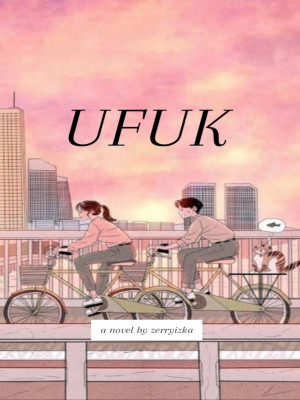Tempat itu tidak pernah berubah. Ketika mentari menggantung, sekitar pukul 10.00 pagi pada hari Sabtu, truk minimarket Minamigoto selalu singgah di samping taman dekat ceruk. Truk itu menjual beraneka ragam belanjaan. Beragam sayur mayur, makanan siap saji, dan aneka barang dapur dapat ditemukan berjejal menghias rak. Biasanya, ibu rumah tangga yang malas berjalan jauh ke jantung kota, atau tidak memiliki waktu luang, akan membeli segala keperluan di sini.
Aku ingat dulu bersama Ayah dan Ibu sering pergi ke taman itu. Sementara Ayah dan Ibu berbelanja, aku bermain bersama anak-anak seumuranku di taman. Jiwa anak-anakku kegirangan, terlebih ketika truk minimarket Minamigoto memutar lagu ikonik dari Disney yang berjudul "It's a Small World". Senandungnya merdu.
Lalu, tepat ketika pukul 11.00 tiba, selalu melintas sebuah kapal feri. Sinar kuningnya menyilaukan mata dan suara trompetnya menggemakan jiwa. Indah rasanya bila aku berada di atas dek kapal untuk memandangi kota kembar yang berada di dua pulau ini menjauh perlahan. Apalagi ketika festival kembang api. Beragam warna menghiasi langit di atas kota. Biru, oranye, merah, dan kuning.
Sudah lebih dari 10 tahun, aku sudah SMA sekarang dan tempat itu masih sama indahnya. Hanya saja bagiku, semua itu tinggal denging dan dunia berwarna abu-abu. Aku, kehilangan indra pendengaran dan mataku tak lagi bisa melihat warna selain warna abu-abu.
Duniaku berubah. Dunia tak Lagi sama. Batinku.
Selarik benda asing melintas di atas langit kota, tenggelam ke dalam cakrawala. Intuisiku mengatakan, kalau benda tersebut seharusnya indah dipandang kalau tidak berwarna abu-abu. Sebuah bintang jatuh ya? Warnanya seperti apa ya? pikirku dalam hati.
Seseorang mencuil bahuku, membuyarkan lamunan ini. Aku berbalik. Wajah wanita itu mengulas senyum lebar. Dia Ibu.
Ruri. Ayo kembali. Ibu mengatakannya lewat bahasa isyarat. Ibu sedikit mengangkat kantung plastik berisikan belanjaan hari ini.
Aku balas mengangguk.
Ibu membelikan makanan kesukaanmu. Katanya lagi menggunakan bahasa isyarat diiringi senyum menawan.
Aku kembali mengangguk, kini dengan seulas senyum kecil.
Kami melenggang menuju kompleks perumahan di lereng bukit.
Tadi. Ibu memulai percakapan lagi ketika kami sudah tiba di kompleks perumahan. Tukang pos tak sengaja berpas-pasan dengan Ibu. Beliau membawakan surat untukmu.
Pak Sanada? Surat untukku?
Ibu mengapit belanjaan, sementara tangan lainnya meraih sepucuk surat. Beasiswamu, mereka tetap memberikannya.
Langkahku terhenti. Beasiswaku? tanyaku lewat isyarat.
Benar. Selamat ya Ruri. Ibu tersenyum bahagia.
Meski aku, sudah berhenti bermain piano? tanyaku lagi ketika kami berdua sudah berada di depan rumah.
Benar, mereka tetap memberikannya. Tapi gantinya, kau harus mempertahankan prestasi akademikmu. Luar biasa baik bukan mereka? Mereka orang baik sekali. Ibu menaruh belanjaan di atas meja. Sementara aku masih berada di ambang pintu, memandang ke arah lain.
Sebuah TV LCD menampilkan berita terkini dalam keheningnya yang mendenging halus. Lalu taman hitam putih pun ditayangkan dengan takarir bertajuk ‘kejahatan akibat imigran meningkat’. Seorang reporter mewawancarai warga lokal.
Ibu menengok ke arah dapur sejenak, lalu memandangku yang sedari tadi diam.
Tidak ada kok Ibu, aku senang juga. Aku akan belajar dengan giat. Ungkapku lewat bahasa isyarat.
Senyum kaku yang Ibu tunjukkan berubah menjadi senyum hangat.
Entah bagaimana aku harus mengutarakan perasaanku. Senang dan sedih seolah bercampur satu. Apa tidak masalah demikian? Mereka rela membayarkan biaya sekolahku dengan beasiswa yang aku sekarang ini tidak layak mendapatkannya. Apa aku layak mendapatkannya? Pertanyaan yang aku tidak bisa tanyakan pada Ibu.
Malam pun datang. Sinar mentari mulai berganti dengan cahaya rembulan. Aku duduk menyangga dagu, memandangi suasana malam kota kembar melalui jendela kamar.
Kota ini memang tidak pernah berubah ya? Mereka indah dan juga baik, tapi kejam juga dalam lain sisi.
Di kota ini, distrik perumahan dan distrik publik terpisah dalam dua kota kembar yang terhubung oleh jembatan. Kota sebelah selatan dipenuhi oleh rumah-rumah penduduk. Beberapa ada berjejal toko kelontong dan ruko dan sebuah kuil, tapi pada umumnya dari tepi jembatan, yang terlihat hanya rumah-rumah sampai lereng bukit. Sementara kota sebelah utara, lebih didominasi oleh fasilitas publik. Sekolah yang berada di atas tanjakan curam, rumah sakit di perempatan, pelabuhan dan lain seterusnya menguasai kota utara. Rumahku berada di kota selatan, beberapa kilometer dari jembatan.
Kenangan itu pun bergulir merasuki pikiran. Penampilan pertamaku ketika bermain piano di atas panggung dekat jembatan. Sorak penonton membahana, tepuk tangan meriah mengisi sewaktu nada terakhir berhenti. Lalu terdengar bunyi ledakan memekakkan telinga. Penonton seolah menyaksikan penampilan spektakuler. Aku menghentikan permainanku, berpaling ke arah jembatan. Bunga api warna-warni menghiasi langit senja. Lalu, bunga api itu lenyap. Lenyap digantikan cahaya abu-abu yang mengerjap dan denging yang berkepanjangan.
Kenangan indah yang perlahan menjadi pahit, batinku.
Aku mendengus. Kembali pada realita. Pandanganku beralih kepada tumpukan dus karton di samping lemari baju. Di sana teronggok barang-barang yang sudah lama tidak kusentuh. Semua disatukan dalam dus berdebu. Tak jauh dari situ, di dekat jendela lain, sebuah piano Steinsway & Sons tampak kian kesepian di bawah temaram rembulan.
Perasaan aneh menggebu di dalam hatiku, kemudian merambat ke seluruh tubuh.
Bintang jatuh. Tadi pagi kusaksikan bintang jatuh. Bila aku memohon untuk indraku dikembalikan, apakah aku bisa menikmati musik lagi?
Aku menggeleng. Tidak... tidak... tidak boleh... Jangan beri aku Harapan. Aku tak bisa lagi melakukannya. Dokter sudah jelas mengatakan kalau aku sudah benar-benar kehilangan. Aku tidak lagi bisa.
Lanjut membaca buku. Kurasa ini yang bisa kulakukan sekarang. Membaca novel karya Rein-Sensei yang berjudul "Makhluk Pencuri Indra".
Andai saja, andaikan saja aku dulu tidak melakukannya. Duniaku tidak akan seperti ini. Tanpa rasa, tanpa warna, dan tanpa suara.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Sesuatu menekan-nekan pundakku. Aku menoleh.
Ruri, guru sudah datang. Gadis itu, Okuda, menunjuk ke arah depan kelas yang mana sudah berdiri sesosok pria baruh baya. Turunkan bukumu. Katanya lagi menggunakan bahasa isyarat, mengangkat buku catatannya.
Maaf, aku terlalu asyik membaca. Aku pun menurunkan buku novel Rein-sensei. Tatapanku beralih kepada guru wali di depan kelas.
Ini hari pertamaku duduk di bangku SMA Minamigoto. Jam pertama setelah upacara penerimaan, seperti biasa, dimulai dengan perkenalan.
Pak Suzuki memperkenalkan diri. Kemudian setelah beliau, satu persatu anak mulai memperkenalkan diri di depan kelas. Dimulai dari bangku ujung kanan depan. Aku tak terlalu mengingat semuanya. Lagi pula aku hanya mengetahui yang dibicarakan ketika Okuda menjelaskan ulang lewat bahasa tangan. Atau lewat pesan singkat di Line.
Lelaki tinggi dan berbahu lebar itu berjalan ke tempat duduknya yang berada dua bangku di sebelah kanan kursiku. Kelas memberikan tepuk tangan meriah. Meski aku tidak bisa mendengarnya, aku bisa tahu dari ekspresi para gadis. Lelaki tadi, Maehara, cowok populer. Dia memiliki bakat dalam olahraga. Semua cabang olahraga. Begitu kata Okuda di belakangku ketika menjelaskan ulang lewat ponselnya.
Sebuah notifikasi mencuat di layar ponsel. Pesan singkat dari Okuda lewat Line.
[Giliranmu].
Aku mengerling seantero kelas. Seisi kelas menaruh tatapan serius. Aku pun mengepalkan tangan di atas pangkuan, mengumpulkan keberanian lalu bangkit berdiri kemudian mulai menulis di papan tulis:
Takasaki Ruriko, seorang gadis SMA yang menyukai musik. Aku senang sekali bermain musik. Hampir semua alat musik bisa aku mainkan. Spesialisasiku adalah bermain piano. Aku pernah menjadi juara dalam ajang bermain piano ketika duduk di bangku SD. Berbagai lomba lain aku ikuti untuk mendukung musikku. Aku bermimpi ingin menjadi musisi terkenal. Seorang pemain piano hebat yang tampil dalam grup orkestra.
Hinggasanya, kejadian itu menimpaku dan mimpiku hanyalah mimpi belaka. Kejadiannya tepat ketika aku kelas dua SMP, duniaku menjadi seperti ini. Tanpa warna dan tanpa suara.
-Gadis SMA yang kehilangan warna dan suara.
Tanganku berhenti. Aku menarik napas dalam. kuturunkan kapur ini, lalu berputar. Salam kenal semuanya. Ungkapku menggunakan bahasa isyarat. Aku membungkuk hormat pada seisi kelas.
Tepuk tangan mengisi kelas. Pak Suzuki ikut memberi tepuk tangan.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Hari pertamaku sekolah telah usai. Aku dan Okuda pulang berbarengan. Jalan bersama keluar kompleks sekolah.
Sepanjang perjalanan, kami membicarakan klub apa yang cocok untukku. Tidak mungkin aku bergabung klub musik. Maka Okuda menyarankanku mendaftar klub memasak saja bersamanya. Tentu aku menolak, tanganku tidak pernah dilatih untuk memasak. Hal ini akan merepotkan sekali bila aku bergabung dalam klub memasak. Maka saran lain dari Okuda adalah mendaftar OSIS. Tentu aku yang saat ini hanya akan jadi beban pengurus lain. Jadi kutolak lagi sarannya. Dengan begini, tidak ada banyak pilihan menjanjikan untukku selain klub olahraga yang tidak memerlukan kerja sama tim atau klub membosankan seperti klub filmaker.
Tapi setidaknya, hari pertama sekolahku cukup menyenangkan. Teman-temanku banyak mendukung. Tidak terlalu pula menganggapku 'spesial'. Jujur aku benci ketika dibeda-bedakan sekali oleh orang banyak, apalagi sampai mendapat perlakuan 'spesial.
Maehara itu ternyata baik juga. Okuda berkata selepas melewati tanjakan menurun.
Biasa saja. Ungkapku lewat bahasa isyarat.
Dahi Okuda mengerucut. Jangan bohong kamu Ruri.
Okuda, aku bersungguh-sungguh.
Bersungguh-sungguh tidak menyukainya atau bersungguh-sungguh menyukainya? Okuda menghunjam pipiku menggunakan telunjuknya. Telunjuknya turun. Rona pipimu memerah ketika Maehara menghampiri mejamu. Tambahnya.
Berilah sedikit privasi jangan seenaknya menunjuk begitu. Kataku lewat bahasa isyarat. Yang lalu mengusap pipi kiriku. Aku cuman gugup banyak yang mengerubungi mejaku.
Okuda melotot padaku. Curiga. Tak lama kemudian dia mendesah ketika mendapatiku terus mengangguk-angguk. Baiklah aku percaya. Begitu jawabnya.
Kamu memang sahabatku. Okuda, terima kasih.
Terima kasih kembali. Okuda berhenti sejenak lalu melanjutkan kata-katanya isyaratnya itu. Dan selamat datang kembali di Minamigoto.
Warna lampu berganti dari abu terang ke putih. Okuda yang melangkah lebih dulu menyebrang jalan. Kami pun menyeberang jalan.
Oh ya. Okuda memulai obrolan. Gerak tangannya lumayan cepat. Dan entah kenapa wajah Okuda agak suram. Raut wajahnya tidak seperti biasa. Dia mencoba meraih sesuatu dari dalam kantong tasnya, lalu mengulurkan padaku.
Bawalah. Untuk jaga-jaga. Dia mencoba memberikanku sebuah taser.
Aku tidak memerlukannya.
Kamu memerlukannya Ruri. Belakangan terjadi terus tindak kriminal di dekat ceruk. Akan gawat kalau kamu bertemu dengan penjahat itu. Okuda menjelaskan lewat bahasa tangan. Dia juga mempraktikkan cara menyetrum orang menggunakan tasernya itu. Gunakan saja ini.
Aku menggeleng. Tanganku mendorong taser itu kembali pada pemilik aslinya.
Taser itu kembali padaku. Jangan menolak. Wajah Okuda kentara seriusnya.
Sepertinya aku tidak bisa menolak. Jadi kuputuskan mengambil taser itu dari tangannya agar semua segera selesai.
Setelah beberapa waktu, akhirnya kami sampai pada pertigaan yang biasa disinggahi truk minimarket Minamigoto. Taman dekat ceruk tidak hidup bila jam-jam segini. Sepi sekali.
Okuda berdiam diri.
Aku berpaling. Sampai jumpa besok. Melambai padanya.
Okuda balik melambai, beranjak pergi.
Rumahku berada sedikit jauh di kompleks perumahan di atas sana. Sementara tempat tinggal Okuda mengambil jalan ke kiri, turun sedikit lalu tiba di sebuah pelabuhan. Rumah Okuda berada tak jauh dari toko oleh-oleh di dekat pelabuhan. Kami terpaksa berpisah di pertigaan ini.
Agak gugup rasanya bila aku berjalan seorang diri tanpa Okuda di sisiku. Maksudku, bagaimana bila aku bertemu seorang turis di sini? Bagaimana caranya aku menghadapinya? Pemikiran semacam itu terkadang terlintas dalam benakku.
Wajar saja, aku berpikir demikian karena kota kembar tempat kelahiranku memang cukup banyak turis asing maupun lokal. Akan merepotkan bila menghadapi mereka dan mereka kebetulan tidak tahu bahasa isyarat. Tapi setelah menimang-nimang, kurasa skenario di atas masih lebih baik daripada yang sekarang menimpaku.
Mataku terbelalak. Di sana, seorang gadis tengah didatangi seorang pria berbahaya yang membawa pisau. Gadis itu memberontak. Meski tak bisa mendengar, aku tahu mereka tengah berdebat hebat.
Jantungku berayun. Napasku tersengal. Apa yang mesti aku lakukan? Karna sekarang jam kerja, perumahan masih sepi. Tidak ada siapa-siapa.
Pria itu menodong pisau pada wajah sang gadis. Sang gadis gemetaran.
Kakiku refleks berlari tanpa sepengetahuanku. Tanganku bergerak melawan kehendakku. Dan tak disangka aku berdiri tepat di hadapan pisau itu, menghadang pria itu.
Pria itu membentak. Murka. Raut wajahnya mengisyaratkan bahwa aku harus menyingkir dari hadapannya atau aku akan ikut mati bersama gadis di belakangku.
Aku teguh berdiam.
Dia makin murka. Pisau mengayun ke arahku. Dan—
Pria itu mendadak kejang, jatuh menggelepar tak berdaya mirip ikan yang dilempar ke tanah.
Jantungku seolah terhenti. Napasku memburu. Waktu yang sangat menentukan. Tepat waktu sekali aku menyambar leher pria itu menggunakan taser. Namun, kemudian peristiwa itu terjadi.
"Ka... kau... Gawat!!!"
Eh? Tunggu dulu! itu tidak mungkin bukan? Apa aku tidak salah? Itu suara bukan? Itu suara seorang gadis bukan? Jerit seorang gadis, ya kan? Bagaimana bisa? Mustahil.
Aku berpaling. Gadis itu menyambar tanganku. "Apa yang kamu lakukan, ayo lari!" Gadis itu menarikku ke mana kuasanya membawaku.
"Gadis jalang! Lari kema—arrgh!"
"Terima itu!" Sang gadis menghantam wajah penyamun dengan tas sekolahnya. Terdengar debam suara tubuh tergolek jatuh.
Tidak mungkin. Tidak mungkin.
"Cepat lari! Kantor polisi, oh tidak, tidak, kita ke rumah sakit saja," seru sang gadis histeris.
Apa ini mimpi? Apakah ini ilusi? Tidak mungkin ini nyata bukan?
"Hey, kau kenapa? Ayo gerakkan kakimu lebih cepat lagi!" serunya lagi, seraya membawaku menuju pertigaan sebelumnya. Menukik secepat kilat.
Langkah kaki terdengar berderap-derap. Tergesa-gesa. Aku dapat mendengar deru napasnya yang memburu, napas gadis itu. Kemudian, dari arah belakang dapat terdengar langkah kaki pengejar yang berderap cepat menuju kami.
"Celaka! Dia bangkit!" Gadis itu melirik ke balik bahu, napasnya makin terengah.
"Kemari kau sialan!"
"SIAPA SAJA TOLONG!!!!" Sang gadis melolong.
Apa ini artinya, pendengaranku kembali?


 ripley
ripley