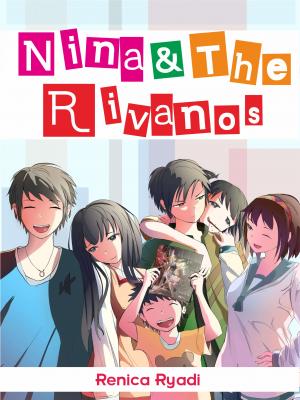"Mari menyerahkan semuanya pada takdir." --Ibu Fida.
∆∆∆∆∆
Halo, Hadi.
Apa kabar, Nak? Ini tulisan wali kelasmu; Ibu Fida. Katanya kamu pergi jauh dari rumah untuk bekerja ya?
Tidak apa-apa, itu mutlak keputusan kamu. Ibu, orangtua kamu, atau sahabatmu--Jelita, kami tidak bisa memaksa. Apapun yang menurut kamu itu penting, maka silakan lakukan.
Ibu menulis ini cuma untuk memberikan satu nasihat terakhir. Ibu tidak mau menyesal dengan melepaskan murid berprestasi seperti kamu.
Ingat kamu pernah menang olimpiade Matematika waktu kelas XI, kan? Wah, saat itu Ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Sejak saat itu Ibu sudah berjanji pada orangtua kamu untuk membantu supaya kamu bisa terus sekolah. Tetapi nyatanya itu hal yang sulit ya, lagi-lagi masalahnya adalah ekonomi keluarga. Maaf ya, Hadi, maaf... Ibu tidak bisa bantu kalau untuk masalah keuangan, namun kalau kamu berubah pikiran dan ingin berusaha melanjutkan sekolah lagi, Ibu seratus persen akan membantu. Ibu janji, Ibu bisa bantu!
Hadi, sekolah dan ijazah memang bukan penentu utama kesuksesan seseorang. Banyak orang sukses di luaran sana tanpa itu, banyak kok. Orang-orang itu termasuk orang beruntung. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah berusaha keras tapi masih seperti ini saja? Yang perlu dilakukan adalah usaha, salah satunya dengan sekolah. Menuntaskan pendidikan, itu menurut Ibu penting dan merupakan suatu usaha untuk mencapai kesuksesan. Walaupun tidak sekarang, tetapi Ibu sangat berharap kamu dapat menemukan pentingnya pendidikan itu, Nak.
Kalau kamu sudah ada keputusan, silakan datang ke sekolah ya, atau hubungi nomor Ibu.
087685900722 (Ibu Fida)
Hadi memejamkan matanya setelah selesai membaca secarik kertas yang berisi tulisan tangan Bu Fida. Ya Tuhan, ternyata Bu Fida dan Jelita begitu ingin dia lanjut sekolah karena itu bentuk kasih sayang mereka untuknya. Dan, Hadi dengan bodohnya baru menyadari itu.
Ia pergi dari kebun sawit dan akan kembali ke Pulau Jawa menaiki bus yang bisa memakan waktu tiga hari. Hadi tidak begitu yakin dia bisa sampai tepat waktu dan ikut ujian. Rasa cemas sejak tadi menyelimutinya.
Hadi tidak bisa tidur, dia was-was sepanjang jalan. Bus baru berjalan sekitar dua jam, masih sangat lama untuk sampai di tempat tujuan. Hari sudah sangat gelap, semua penumpang terlelap, hanya Hadi seorang yang masih mengerjap bingung harus melakukan apa kecuali melamun.
Keesokan harinya, dia masih tidak tertidur. Ketika orang-orang di dalam bus sibuk membuka bekal mereka untuk mengisi perut, justru ketika itu Hadi sarapan dengan rasa kantuk. Dia ditidurkan oleh suara kasak-kusuk orang.
Baru terlelap sekitar dua jam, Hadi sudah harus bangun karena masalah mendesak. Bus yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti. Orang-orang turun dari bus untuk ikut berkerumun bersama supir dan kondekturnya. Hadi menyusul setelah mengumpulkan kesadarannya. Dia melihat sekeliling, sejuk dan sepi. Mereka ada di tengah hutan dan bus berhenti berjalan.
"Kenapa ini, Pak?" Hadi bertanya pada salah seorang penumpang. Pria paruh baya dengan setelan jas dan memakai dasi. Orang itu baru saja kembali dari mengobrol dengan supir bus.
"Mesinnya bermasalah, entahlah."
"Waduh," desah Hadi.
Bus berjalan normal saja Hadi sudah tidak punya waktu, bagaimana dengan masalah seperti ini?
"Berapa lama busnya bisa jalan lagi, Pak?"
"Katanya sekitar dua jam, mereka harus nunggu bantuan datang dulu."
"Lama banget," lirih Hadi.
Hadi berdecak sebal menyesali nasibnya. Kalau sampai kampung halaman ia tetap tidak bisa ikut ujian, maka semuanya akan percuma saja.
"Halo sayang. Iya, aku mau ngabarin sesuatu."
Mendengar suara orang yang tadi mengobrol dengannya, Hadi praktis tersadarkan sesuatu. Dia segera menoleh pada bapak-bapak tadi dengan memasang senyum lebar. Duh, kenapa tidak terpikirkan sejak tadi ya. Hadi buru-buru membuka surat dari Bu Fida untuk menghapal nomor telepon gurunya itu.
"Iya, ya sudah, Mas tutup ya."
Ketika sambungan telepon bapak-bapak itu selesai, Hadi segera mendekatinya. "Pak, boleh saya minta bantuan, Bapak?"
"Bantuan apa?"
"Saya mau menghubungi guru saya Pak, penting."
"Oh, iya boleh, silakan."
"Terima kasih, Pak."
Dengan senang hati Hadi pun segera menerima ponsel bapak-bapak itu. Dia mendial nomor Bu Fida. Sambungan segera terhubung. Hadi menempelkan ponsel itu ke telinga kanannya.
"Halo, Assalamualaikum, Bu Fida."
"Waalaikumsalam, maaf ini siapa ya?" tanya Bu Fida di seberang sana.
"Saya Hadi, Ibu. Saya mau memberitahu Ibu kalau saya--"
Tut... Tut... Tut...
Mata Hadi membola, terkejut mendengar sambungan teleponnya terputus tiba-tiba. "Halo? Ibu? Ibu dengar saya? Bu Fida, ini Hadi mau bilang kalau Hadi mau ikut ujian!"
"Bu Fida?"
"Ibu?"
"Ibu dengar saya?"
Tepukan pada bahu kirinya menyadarkan Hadi untuk menyudari acara teriak-teriaknya tadi. Pemilik ponsel mendesah kemudian, "Sinyalnya hilang. Yang lain juga tidak dapat sinyal, tadi saya kayaknya beruntung."
"Saya memang selalu tidak beruntung dalam hidup," lirih Hadi.
"Tadi saya dengar ujian, kamu memangnya masih sekolah?"
Selalu saja, selalu saja semua orang menganggap penampilan Hadi terlampau dewasa. Memangnya dia terlihat setua itu ya untuk ukuran anak SMA?
Hadi terkekeh ringan. "Saya masih kelas dua belas, Pak."
"Aih, saya kira kamu sudah dewasa, lho. Maaf ya, soalnya kamu terlihat tinggi dan tegap, apalagi wajahmu itu, begitu tegas."
"Apalagi kulit saya, Pak. Beuh... cokelat begini, hehe..."
"Bukan saya yang bilang lho, ya."
Hadi dan bapak-bapak itu seketika akrab dan menjadi teman mengobrol selama di tengah hutan, bahkan hingga mereka kembali masuk ke dalam bus dan melanjutkan perjalanan.
Biarkan saja semua berjalan sesuai takdir. Hadi tidak bisa memaksa seperti apapun. Kalau seandainya sampai rumah dia tetap tertinggal, tidak masuk sebagai peserta ujian, dan tidak lulus sekolah, maka biarlah itu terjadi.
∆∆∆∆∆
Kala itu Bu Fida baru selesai mengikuti senam bersama seluruh warga sekolah di lapangan serbaguna. Dia berjalan di belakang murid-muridnya untuk keluar lapangan dan hendak menuju ruang guru.
Saat sampai di depan pintu ruang guru, ponselnya berdering keras. Merasa tidak enak menerima telepon di dalam ruang guru, maka ia pun keluar dan memilih mengangkat telepon di koridor.
Panggilan dari nomor tidak dikenal. Bu Fida sedikit tidak berniat mengangkat panggilan tersebut, namun takut juga kalau itu dari orang penting. Ya sudahlah, akhirnya Bu Fida menggeser ikon hijau dan menempelkan benda pipih itu ke telinga kanan.
"Halo?" sapanya.
"Halo, Assalamualaikum, Bu Fida."
Bu Fida terdiam mencerna suara yang ia dengar itu. Agak tidak jelas, tetapi seolah Bu Fida kenal sekali dengan suaranya.
"Waalaikumsalam, maaf ini siapa ya?" tanya Bu Fida memastikan.
"Saya--"
"Iya?"
Tut... Tut... Tut...
Sambungan terputus tiba-tiba. Bu Fida kembali melihat layar ponselnya. Dia tidak tahu itu nomor siapa, sepertinya cuma panggilan tidak jelas.
"Bu Fida." Seseorang memanggil. Bu Fida mendongak dengan segera.
"Iya, Pak?"
"Hari ini terakhir pengumpulan nama-nama peserta ujian. Cuma kelasnya Bu Fida yang belum laporan ke saya."
"Iya, Pak. Saya nanti ke meja Bapak untuk laporan."
"Baik, saya tunggu ya, Bu."
"Iya, Pak."
Bu Fida segera memasuki ruang guru dan berjalan ke mejanya. Dia mencari lembaran kertas yang telah ia print kemarin. Di atasnya sudah ada nama kelas dan jumlah siswa. Sebenarnya kemarin bisa dia laporkan pada Pak Januar langsung, tetapi Bu Fida ragu. Dia membuat dua laporan; satu tanpa nama Hadi, yang kedua dengan nama Hadi.
"Hadi... Duh, Ibu bingung."
Bu Fida nampak ragu beberapa saat, tetapi setelahnya dia meraih salah satu daftar hadir di kelasnya dan beranjak dari ruang guru.
"Mari menyerahkan semuanya pada takdir," monolognya seorang diri.
∆∆∆∆∆
Sabtu ini adalah hari Sabtu termenyebalkan bagi Jelita karena tidak ada Hadi. Hari ini juga tepat hari ke-12 pulang sekolah sendirian tanpa Hadi. Selain itu, ini juga hari terakhir dia merelakan Hadi untuk tidak lagi mengejar yang namanya mimpi.
"Awas saja kalau nanti aku sukses dan dia merengek karena tidak dapat kesempatan sepertiku, aku hanya akan menertawakannya." Jelita bersungut-sungut sebal sepanjang langkah.
Kepalanya menengadah ke atas, memperhatikan awan mendung yang menghiasi langit. Menyaksikan hal itu membuat hatinya jadi ikut mendung juga. Suram sekali tidak ada Hadi. Walaupun biasanya dia merasa kesal harus menceramahi Hadi, kini justru dia amat merindukan momen itu.
Seorang diri menyusuri bibir pantai, Jelita mengenang sahabatnya nun jauh di sana. Hadi sedang apa ya? Apa dia tidak rindu sekolah? Apa dia sudah berhenti mencari jati dirinya?
Jelita mampir sebentar di rumah Hadi, berharap dapat melihat sosok itu. Namun, dia hanya menemukan adik kecil Hadi yang tengah bermain boneka barbie di teras rumah seorang diri.
"Kak Lita!"
Niat awal hanya ingin sembunyi-sembunyi, nyatanya berakhir ketahuan. Jelita akhirnya mendekati rumah Hadi dan menemui Salsa.
"Kak Lita mau cari Abang Hadi ya?"
Jelita mengangguk. Dia gemas dan mencubit pipi Salsa.
"Abang kerja di tempat yang jauh, kata Ibu sih pulangnya lama. Kak Lita kangen Abang ya? Sama, Salsa juga. Kata Abang tidak apa-apa berjauhan asal Salsa bisa jajan banyak, padahal Salsa gak jajan banyak juga gak pa-pa yang penting ada Abang."
"Salsa doain aja Abang Hadi sehat selalu di sana ya." Jelita menenangkan seraya mengusap-usap lembut kepala Salsa.
"Hadi itu keras kepala, Lita." Tiba-tiba keluarlah ibunya Hadi dari dalam rumah sambil membawa ember berisi udang rebon. "Ngotot sekali mau ikut orang buat kerja di perkebunan kelapa sawit, jauh di Sumatera sana. Katanya lumayan bisa dapat gaji besar. Padahal Ibu tidak rela lho dia pergi. Sudah tidak bawa uang banyak, tidak punya handphone, susah sekali untuk komunikasi. Setiap hari Ibu merasa cemas kalau ingat Hadi."
"Eh, Ibu..." Jelita menyalami tangan ibunya Hadi.
"Aduh, maaf Lita, tangan Ibu bau amis."
"Gak apa-apa, Bu. Ibu mau bikin terasi ya?"
"Iya, lumayan. Sekarang bapaknya anak-anak juga sudah ikut melaut lagi. Alhamdulillah, pulang bawa banyak rebon, Ibu manfaatkan buat jualan terasi."
"Semoga lancar ya, Bu."
Ibunya Hadi tersenyum teduh memandang Jelita. Mengingat lagi soal kebohongan anak itu bersama putranya, Ibunya Hadi hanya bisa terheran-heran, lucunya anak itu.
"Ujiannya kapan, Lita?"
"Senin depan, Ibu."
"Wah, Hadi tidak bisa ikut ujian ya?"
Jelita terdiam, tidak bisa menjawab. Kalau saja laki-laki itu kembali secepat kilat, kemungkinan masih bisa. Tetapi, setahu Jelita peserta ujian sudah ditentukan hari ini.
"Ibu ingin sekali Hadi bisa lulus sekolah, tetapi Ibu tidak bisa memaksa. Kami tidak punya uang, tidak bisa memaksa Hadi untuk sekolah dan belajar tanpa uang saku. Jadi, ya terserah anaknya saja. Makanya, Ibu senang sekali kalau Lita bisa bantu Hadi menemukan mimpinya."
"Maaf ya, Bu. Jelita tidak sebaik itu buat ngeyakinin Hadi. Harusnya bisa, maaf... Jelita harus berhenti sekarang."
"Tidak apa-apa, Nak. Memang sudah nasibnya Hadi saja." Ibunya Hadi membalas tatapan sedih Jelita dengan senyum hangat yang begitu berarti dan Jelita dambakan bisa ia dapat dari kedua orangtuanya. "Semoga kamu bisa mencapai cita-cita kamu, dan jadi orang sukses ya, Jelita. Ibu juga berharap kamu sama Hadi selalu berteman baik."
Selesai berbincang dengan ibunya Hadi, Jelita lamit undur diri. Dia berjalan lebih cepat untuk sampai di rumah. Di sana, dia menemukan orangtuanya sedang berdiri di depan rumah dengan tampang yang begitu marah.
Ada apa?
"Assalamualaikum..." ucap Jelita.
Begitu melangkah sampai di depan kedua orangtuanya, hendak mencium tangan, Cawi malah mengangkat telapak tangan kanannya dan menampar keras pipi Jelita.
"Dasar anak tidak tau diri! Pembohong! Penyebar fitnah!" maki Cawi.
Selain Sabtu yang menyebalkan karena tidak adanya Hadi, hari itu juga Sabtu yang menyebalkan karena semua orang sudah tahu bahwa Jelita masih perawan dan semua yang dia katakan itu adalah kebohongan.


 indriyani
indriyani