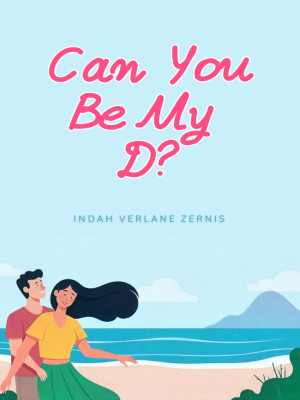"Tidak apa-apa tidak punya mimpi, asalkan adik-adikku bisa bebas bermimpi." --Hadi Ardian
∆∆∆∆∆
Suasana kelas 12 IPA 4 ramai oleh karena beberapa menit yang lalu ketua kelas mereka--Jelita, membagikan formulir peminatan. Selembar kertas tersebut harus diisi sesuai dengan tujuan siswa-siswi kelas dua belas setelah lulus sekolah.
"Kamu jadi daftar ke UGM, kan?"
"Ambil swasta aja langsung, aku sih gak pede ya daftar ke negeri."
"Kalian berdua mau ke mana habis lulus?"
"Oh, langsung daftar LPK ya. Cie... Bakal ke Jepang nih."
Semua orang sibuk bercengkerama, hanya Hadi yang tak tertarik untuk mengisinya. Dengan ogah-ogahan ia memegang bolpoin untuk mengisi bagian nama.
Bangkit dari kursinya, Hadi pun berjalan ke meja guru untuk mengumpulkannya pada Jelita. Gadis itu, sebagai ketua kelas, menjadi yang paling pertama selesai mengisi formulir peminatan.
Mata Jelita yang bulat terlihat seperti akan copot menemukan formulir peminatan milik Hadi kosong. "Heh, diisi dulu baru kumpulin!"
"Ya elah, justru kosong adalah jawabannya. Aku tidak akan lanjut kuliah, tidak akan masuk LPK dan bekerja di luar negeri juga, bahkan tidak mungkin sekali menjadi pengusaha."
Jelita menggaruk keningnya dengan menahan ledakan amarahnya yang naik ke ubun-ubun. Aduh, semenjak mereka masuk SMA, Hadi ini suka sekali membuat Jelita darah tinggi.
"Hadi, dengar ya, kamu hanya perlu isi impian kamu. Isi sesuai minat kamu, setelah lulus sekolah kamu akan jadi versi Hadi yang lebih dewasa. Kamu mau versi dewasa kamu seperti apa?"
"Punya banyak uang," singkat Hadi.
Jelita membeku di tempatnya. Ya, benar juga sih. Semua orang sukses juga ujung-ujungnya pasti ingin punya banyak uang.
Mengembuskan napas pelan-pelan lalu menghebuskannya, Jelita bangkit dari duduknya untuk memperlihatkan formulir peminatan miliknya. "Lihat nih punyaku, isi seperti ini. Nama, oke sudah di isi. Kelas dua belas IPA 4. Setelah lulus akan: melanjutkan pendidikan ke universitas. Atau, kalau kamu mau bekerja, silakan isi tujuanmu bekerja di perusahaan apa. Lalu terakhir, isi mimpi kamu. Contoh, punyaku; aku ingin kuliah di bidang kebidanan, lulus dengan predikat cumlaude, punya klinik sendiri, menikah dengan orang kaya."
Hadi tersenyum mendengarnya. Kalau Jelita sih sudah jelas, pantas dia hanya perlu 2 menit untuk menyelesaikan formulir peminatan itu. Bagaimana dengan Hadi, dia bahkan tidak pernah tahu bahwa dirinya harus punya mimpi.
"Gimana? Sudah mengerti bagaimana ngisinya, kan?" tanya Jelita.
"Memangnya tidak boleh kosong?"
"Di, ngarang aja udah." Seseorang mendekat sambil berkomentar setelah mengumpulkan formulirnya ke Jelita.
"Heh Raka, mana ada ngarang? Isi sesuai dengan tujuan kamu ya!" semprot Jelita.
"Udah sesuai kok itu, Ta."
"Kamu lanjut ke mana, Ka?" tanya Jelita.
"Aku mau masuk Akpol, melanjutkan perjuangan ayahku. Ikut aku aja yuk, Di. Badanmu bagus tau."
Hadi memperhatikan wajah Raka yang begitu antusias menyebutkan mimpi dan tujuan hidupnya. Miris sekali dengan dia, bukan? Jangankan punya tujuan, punya mimpi saja dia tidak.
"Nah, betul tuh. Tulis saja kalau kamu mau jadi polisi," Jelita menambahkan pendapat Raka.
Bukan hanya Raka dan Jelita, Hadi pun pernah mendapat pujian tersebut dari guru olahraganya. Badan Hadi itu bagus, tinggi dan tegap. Bukan karena dia rajin olahraga, tetapi itu terbentuk karena dirinya yang bekerja siang dan malam membantu orangtuanya.
"Memangnya berapa biaya sekolah kepolisian, Ka?"
Raka mengedikkan bahu. "Daftarnya gratis, paling kamu cuma butuh biaya makan saja."
"Gimana? Tertarik?"
"Gak, nanti kuisi sendiri saja!"
Jelita gemas ingin menempeleng wajah Hadi ketika dia seenaknya berlalu sambil merampas formulir kosong dari tangannya. Raka kembali ke tempat duduknya dan berbincang lagi dengan teman-teman yang lain, meninggalkan Jelita hingga kemudian gadis itu duduk kembali sambil menerima formulir milik teman-temannya yang sudah terisi.
Sekitar sepuluh menit kemudian Hadi kembali menghampiri Jelita. Dia menyerahkan formulir peminatan miliknya yang sudah terisi.
"Nah, sekarang sudah benar, kan?" ujar Hadi percaya diri.
"Setelah lulus akan; melaut dan mencari nafkah. Mimpi; menjadi orang kaya dan menyekolahkan adik-adikku sampai kuliah."
Selesai membaca formulir itu mendadak badan Jelita lemas. Ya Tuhan, bagaimana bisa seorang Hadi Ardian yang mendapat nilai Matematika lebih besar darinya tidak tahu bagaimana cara mengisi mimpi di formulir peminatan.
"Kenapa, Ta? Salah ya?"
"Hadi," panggil Jelita.
Hadi mengangguk dengan raut wajah tegas. Kulit wajahnya yang kusam dan bibir yang kering membuat pandangan Jelita pada laki-laki itu semakin berubah sendu.
"Bisa gak sih sekali saja kamu mikirin diri kamu sendiri? Bisa gak sekali saja kamu cari tau tujuan kamu hidup?"
Jawabannya; tidak bisa. Hadi hidup untuk kedua adiknya. Azka, anak kedua dari orangtuanya, adik pertamanya yang kini sudah duduk di bangku kelas 2 SMP. Salsa, si bungsu, dia masih duduk di bangku kelas 2 SD. Kalau Hadi tidak ikut bekerja, kedua adiknya tidak bisa jajan seperti anak-anak yang lain. Kedua orangtuanya memang bekerja semua, tetapi tetap saja tidak cukup untuk menghidupi keluarga tanpa bantuan Hadi.
Bohong kalau Hadi tidak pernah mengeluh iri dengan teman-teman yang lain. Bukannya angkuh tidak peduli, melainkan tidak layak untuk mendengki. Hadi sudah cukup bersyukur bisa sekolah pagi-pagi setelah semalaman melaut mencari ikan bersama Bapak. Tidak ada ruang baginya untuk cemburu dengan teman-teman lain yang waktu luangnya digunakan untuk bermain ponsel. Tidur cukup di siang hari saja dia sudah mengucap syukur berkali-kali.
Pertanyaan Jelita memang berhasil membungkam Hadi. Meskipun jelas jawabannya tidak bisa, Hadi tetap tidak tahu apa itu mimpi.
Sampai mereka pulang sekolah pun, Jelita dan Hadi masih tidak saling bicara. Biasanya Jelita bawel bertanya ini-itu pada Hadi, sepertinya gadis itu masih sungkan. Sepanjang jalan menyusuri tepi pantai, gadis itu hanya mencuri-curi pandang pada anak laki-laki berkulit tan di sebelahnya.
"Kulitku memang hitam, tak usah dipandangi begitu."
"Kamu ada waktu luang ba'da ashar?" Bukannya merespons pernyataan Hadi, Jelita justru melemparinya dengan sebuah pertanyaan.
"Aku selalu sibuk, Ta. Sampai rumah aku keliling jualan tahu bulat, sekitar satu jam kemudian aku menjaga toko kelontong Pak Dun."
"Keliling tahu bulatnya lewat rumahku, ya?"
"Kenapa?"
Jelita mengulum bibirnya demi menghilangkan raut wajah cemas. "Turuti saja kataku, Di. Sampai di depan rumahku nanti, kalau suasananya ramai, berhenti dan cari aku."
"Ta, jangan bilang--"
"Ya, sama pemilik kapal besar yang umurnya sudah tiga puluh tahun. Bulan lalu istrinya meninggal, statusnya duda."
"Tidak bisa, Ta!" bantah Hadi.
"Kenapa?"
"Aku dan Bapak bekerja di salah satu kapal milik orang itu."
"Tidak mau tau, pokoknya kamu harus bantu aku!"
"Caranya?"
"Bilang kalau kita pacaran."
"Orangtuamu tidak akan peduli," kekeh Hadi.
"Aku akan bilang kamu menghamiliku."
"Sinting!" bentak Hadi.
Jelita semakin tantrum. Dia mengentak kakinya keras-keras sambil merengek bagai anak-anak. Hadi terus berjalan melewati pantai, membiarkan Jelita di belakangnya menyusul sambil menangis.
"Di..."
"Gak mau! Hidupku saja sudah pusing, kamu tidak boleh menambah bebanku lagi."
"Sepertinya aku punya ide!"
Praktis Hadi memutar tubuhnya jadi menghadap Jelita. Gadis itu mengusap kasar kedua pipinya yang baru saja dilintasi air mata. Kunciran kuda poninya tertiup angin, terayun lucu ke sana-kemari.
"Ide apa?"
"Aku kasih tau nanti, pokoknya jangan lupa untuk keliling jualan tahu bulatnya di depan rumahku ba'da ashar. Aku tunggu, dah, duluan!"
Selama 17 tahun dia menjadi sahabat Jelita, Hadi tidak pernah setakut saat ini. Jelita memang gadis pintar dan ceria, tetapi kelakuannya tidak bisa dibilang wajar kalau mimpinya terhalang.
Tidak mau ambil pusing urusan perjodohan Jelita, Hadi kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Itu bukan rumah milik keluarganya, melainkan rumah kontrakan. Itulah kenapa keluarganya selalu kekurangan, karena uang pas-pasan mereka kadang hanya cukup untuk membayar kontrakan saja.
Maka dari itu Hadi bekerja. Maka dari itu Hadi rela bolos sekolah untuk tidur, lalu siangnya bekerja lagi. Maka dari itu Hadi rela tidak bermimpi apapun demi menukarnya dengan kebahagiaan Azka dan Salsa.
"Abang!"
"Assalamualaikum..." sapa Hadi.
Salsa tersenyum lebar. "Waalaikumsalam, Abang!"
Hadi buru-buru merogoh saku celananya dan mengeluarkan lembaran uang dari upahnya melaut semalam. Dia menyisihkan satu lembar uang lima ribuan kepada Salsa.
"Salsa tunggu dari pulang sekolah. Abang ada uang? Kalau gak ada gak usah kasih Salsa."
Hadi gemas dan mengelus lembut kepala Salsa. "Ada kok, semalam Abang dapat banyak ikan. Ini buat Salsa jajan di tempat ngaji."
"Makasih, Abang!" pekik Salsa girang seraya mengambil uang dari tangan Hadi.
"Ngajinya yang fokus ya, doain Abang dapat banyak ikan juga nanti malam."
"Iya, Abang."
"Kak Azka belum pulang?"
"Udah, tapi berangkat lagi. Katanya mau latihan Pramuka."
"Salsa udah makan?"
"Sudah tadi sebelum Ibu ke rumah Bu Cucun. Kata Ibu, Abang makan dulu sebelum jualan."
"Yuk, Salsa temenin Abang makan ya, nanti Abang antar ke tempat ngaji."
"Oke, Abang!"
Hadi menggandeng lengan Salsa untuk mengajak gadis kecil itu masuk ke rumah mereka. Salsa mengekori Hadi yang masuk ke kamar untuk berganti pakaian, setelahnya ikut juga ke dapur untuk menemani sang kakak makan. Walaupun dengan lauk tempe dan sambal terasi saja, makanan itu terasa mewah karena dilengkapi senyuman manis Salsa.
"Abang, di sekolah tadi Bu Guru tanya soal cita-cita Salsa."
"Oh ya? Terus Salsa jawab apa?"
"Salsa bilang kalau sudah besar nanti Salsa mau jadi dokter. Salsa mau bantu obatin luka Bapak sama Abang, Salsa juga mau merawat Ibu biar kalian semua panjang umur."
Padahal Hadi baru menelan tiga suapan, namun rasanya perutnya sudah kenyang. Tiba-tiba saja dia semakin bersemangat untuk terus mendapatkan banyak uang. Tidak apa-apa dia tidak punya mimpi, asalkan adik-adiknya bisa bebas bermimpi.
"Kalau Abang, cita-cita Abang apa?"
Hadi tidak menjawab, dia hanya tersenyum dan lanjut makan.
Cita-cita ya?
Cita-cita itu... apa sih? Kok rasanya Hadi tidak pantas ya punya cita-cita?


 indriyani
indriyani