Tidak semua langkah terdengar saat dijatuhkan. Kadang, langkah paling berat justru terjadi dalam diam—saat seseorang akhirnya memilih untuk menghadapi yang selama ini ditinggalkan. Hari itu, aku tidak pergi untuk menyelesaikan semuanya. Aku hanya ingin mulai… berjalan.
**
Pagi itu, udara masih dingin saat aku duduk di belakang motor Nata, menggenggam tas kecilku dengan jari-jari yang sedikit gemetar. Hati aku campur aduk antara antusias, takut, dan malu sekaligus.
“Gak apa-apa kalau kamu deg-degan,” kata Nata pelan, sesekali menoleh ke belakang. “Aku di sini kok.”
Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini bukan sekadar janji bertemu orang baru, ini adalah langkah pertama yang aku ambil untuk menghadapi perasaanku yang selama ini tertahan dan bergejolak.
“Terima kasih ya sudah mau ngantarin aku,” bisikku.
Nata tersenyum hangat. “Aku gak akan ninggalin kamu. Kita jalan bareng sampai kamu nyaman.”
Motor berhenti di depan sebuah gedung kecil berwarna putih bersih dengan papan bertuliskan Klinik Psikologi Sejahtera.
Aku menatap pintu masuk, lalu menoleh ke Nata sekali lagi. “Aku siap.”
Nata mengangguk, membuka helmnya, lalu membantu aku turun. Bersama-sama, kami melangkah masuk, memulai babak baru dalam perjalanan penyembuhanku. Ruang tunggu klinik terasa tenang, dengan warna-warna lembut yang membuatku sedikit lebih rileks. Nata duduk di sampingku, masih memberi senyum semangat. Setelah beberapa menit menunggu, seorang perempuan paruh baya dengan wajah ramah memanggil namaku.
“Silakan masuk, Nara,” ucapnya lembut.
Aku mengangguk dan melangkah masuk. Ruangan itu kecil tapi nyaman, dihiasi tanaman hijau dan lukisan-lukisan sederhana di dinding. Aku duduk di kursi yang disediakan, berhadapan dengan perempuan itu.
“Perkenalkan, aku Bu Rina, psikolog yang akan menemani perjalanan kamu,” katanya sambil tersenyum.
“Senang bertemu dengan Ibu,” jawabku pelan.
“Ceritakan, apa yang membuat kamu memutuskan untuk datang ke sini?” tanyanya sambil membuka buku catatan.
Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita tentang semua yang aku rasakan selama ini: perasaan cemas yang sering datang tiba-tiba, kebiasaan-kebiasaan yang sulit kuhentikan, rasa hampa yang kadang menyergap, dan betapa sulitnya menjalani hari tanpa rasa senang seperti dulu.
Bu Rina mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan memberi pertanyaan yang membuat aku bisa lebih memahami diri sendiri.
“Dari cerita kamu, aku bisa lihat ada tanda-tanda Obsessive Compulsive Disorder atau yang sering dikenal dengan OCD dan ini juga sudah menunjukkan adanya gejala anhedonia,” ujarnya lembut. “Tapi jangan khawatir, ini bisa ditangani dengan terapi yang tepat dan dukungan dari orang-orang terdekat.”
Aku mengernyit sedikit, “Tapi... apakah aku bisa sembuh? Apakah aku akan merasa normal lagi?”
“Prosesnya memang tidak instan, dan setiap orang berbeda. Tapi banyak yang berhasil menemukan cara untuk mengelola dan bahkan mengurangi gejala mereka,” jawab Bu Rina. “Yang penting, kamu sudah berani melangkah ke sini. Itu langkah besar.”
Sesi itu berlanjut dengan penjelasan tentang terapi perilaku kognitif (CBT) yang akan membantuku menghadapi obsesi dan kompulsiku secara bertahap. Aku merasa campuran lega dan cemas, tapi setidaknya aku tidak lagi sendirian. Ketika sesi berakhir, Bu Rina memberi jadwal terapi berikutnya dan beberapa tugas kecil untuk kulakukan di rumah.
Di luar ruangan, Nata menunggu dengan senyum yang membuatku merasa aman.
“Gimana?” tanyanya lembut.
“Aku... merasa ada harapan,” jawabku pelan. “Meski jalannya panjang, aku mau coba.”
Nata meraih tanganku, “Aku akan selalu ada di sini, ya.”
Aku tersenyum, menatap ke depan dengan tekad baru. Ini baru permulaan, tapi aku siap melangkah.
Beberapa minggu berikutnya, aku mulai menjalani terapi secara rutin. Setiap pertemuan dengan Bu Rina selalu membuka pintu baru untuk memahami diriku sendiri. Tapi jalan ini nggak mudah. Ada hari-hari ketika obsesiku kembali menyerang, membuatku ingin mundur. Aku harus melawan dorongan untuk menghindari tugas-tugas kecil yang terasa berat.
Suatu sore, aku duduk bersama Nata di perpustakaan, tanganku terus merapikan buku yang berantakan berulang kali, ritual yang hampir menguras energi dan waktu. Nata memandangku dengan mata penuh perhatian, lalu menghentikanku dengan genggaman tangan yang hangat.
“Kamu nggak perlu sempurna, Nara,” katanya lembut. “Aku tahu ini sulit, tapi kamu nggak sendiri.”
Aku menahan air mata, merasa rintangan berat yang akan aku hadapi, tapi juga diberi kekuatan oleh kehadirannya. Di antara perjalanan berat itu, aku juga mulai belajar untuk menerima ketidaksempurnaan, pelan-pelan membuka diri pada hal-hal yang dulu terasa mustahil.
Aku tahu, penyembuhan bukan seperti jalan mulus yang mudah dilewati. Tapi aku siap berjalan, selangkah demi selangkah, dengan Nata dan Bu Rina di sampingku. Aku juga bisa bangun dengan perasaan yang sedikit lega. Bukan bahagia yang meledak-ledak, tapi ada kedamaian kecil yang merayap masuk ke dalam hatiku.
Hari itu, aku berhasil melewati ritual cuci tangan yang biasanya berulang kali kujalani. Aku tahu ini hal kecil, tapi bagiku, itu kemenangan besar. Saat aku membereskan meja belajar, aku nggak merasakan dorongan kuat untuk menyusun ulang barang-barang secara berlebihan. Aku bisa fokus mengerjakan tugas tanpa harus berhenti berkali-kali.
Setiap sesi terapiku usai, Bu Rina selalu berkata bahwa kemajuan sekecil apa pun adalah tanda bahwa aku sedang melangkah maju. Aku mengangguk dan tersenyum, meski di dalam diri, rasa takut dan cemas masih kerap datang tanpa aba-aba. Tapi ada yang tak pernah berubah—Nata. Ia tetap setia di sisiku, memperhatikan setiap perubahan kecil itu dengan mata yang penuh keyakinan. Sesekali, ia akan menggenggam tanganku dan berkata pelan, “Lihat, kamu bisa, Nara.”
Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan kadang berat, tapi aku tetap berterima kasih pada diriku sendiri. Aku mulai percaya, aku bisa melewati ini.
Hari-hari berlalu, dan aku mulai belajar untuk tidak lari dari kecemasan. Salah satu latihan dari Bu Rina terdengar sederhana—membiarkan pintu ruang tamu terbuka sedikit. Tapi untukku, itu seperti menantang bencana. Tanganku gemetar saat kusengaja tidak menutup rapat pintu. Pikiran buruk berdatangan, satu per satu. Tapi aku mencoba mengingat kata Bu Rina, “Rasakan kecemasan itu, tapi jangan biarkan ia mengendalikanmu.”
Aku duduk di sofa. Tidak menolak rasa takut, hanya membiarkannya lewat. Dan perlahan, rasa itu memudar. Saat Nata datang malam itu, dia mendapati aku duduk santai dengan pintu terbuka.
“Kamu berhasil, ya?” tanyanya sambil tersenyum bangga.
Aku mengangguk. “Iya, aku belajar untuk gak lari dari rasa takutku.”
Nata mengangguk, “Aku bangga sama kamu, Nara. Terus semangat ya.”
Malam itu, aku tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Walau aku tahu masih banyak tantangan di depan, aku mulai percaya bahwa aku bisa menghadapinya. Tapi penyembuhan, seperti kata Bu Rina, bukan jalan lurus yang tanpa kelokan. Kadang, setelah satu kemenangan kecil, bayangan lama datang menyelinap, mencari celah saat aku mulai lengah.
Di suatu malam, aku terbangun mendadak. Napasku pendek, dan keringat dingin membasahi pelipis. Rasanya seperti ada yang meneriakkan sesuatu di kepalaku: tugasnya belum sempurna. Masih ada yang salah. Harus dicek lagi. Harus dicek lagi.
Aku turun dari tempat tidur dan menyalakan laptop. Jam menunjukkan pukul 02.14. Di layar, file tugas yang sudah kukirim siang tadi kembali kubuka. Kutelusuri satu per satu, detail demi detail. Garisnya terlalu tebal. Font-nya tidak konsisten. Komposisi warnanya salah.
Tanganku mulai gemetar. Aku membuka software lain, mencoba membenahi, lalu menghapusnya lagi, lalu kembali mengulang dari awal. Keringat dingin semakin deras, sementara dadaku terasa kosong. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku melakukannya lagi. Yang kutahu hanya satu: apa pun yang kulakukan terasa salah.
Saat itu juga, muncul lagi rasa familiar yang mengerikan: ketidakmampuan merasakan apa pun. Tidak senang. Tidak sedih. Tidak marah. Hanya kosong. Hampa. Seperti berjalan di ruang tanpa suara dan udara. Air mataku mengalir tanpa sebab yang jelas. Kepalaku sakit. Aku berhenti di tengah-tengah proses, lalu hanya duduk diam, menatap layar. Tak ada suara, tak ada harapan. Hanya bisikan kecil: semua ini percuma. Kamu nggak akan pernah sembuh.
Teleponku tiba-tiba berdering. Nata. Lalu aku mengangkat dengan ragu.
“Halo?” suaraku parau.
“Nara? Kamu belum tidur?” tanyanya. Lalu jeda. “Kamu kenapa?”
Aku ingin menjawab jujur, tapi tenggorokanku terasa terkunci. Yang keluar hanya, “Aku ngerasa semuanya percuma, Nat.”
“Kenapa kamu ngomong gitu? Kamu udah jauh banget, udah hebat banget…” suaranya terdengar panik, tapi tetap pelan.
“Nggak. Kamu nggak ngerti,” potongku cepat. “Kamu pikir ini gampang? Aku capek banget. Aku udah coba, tapi tetap saja, aku balik lagi ke awal. Semuanya sia-sia.”
“Nara, tolong jangan ngomong kayak gitu. Aku ngerti kamu lagi drop, tapi—”
“Berhenti bilang kamu ngerti, Nata!” suaraku naik, membuatku kaget sendiri. “Kamu cuma lihat dari luar. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Gimana rasanya bangun dan tidur dengan pikiran yang terus menghancurkan diri sendiri!”
Di ujung sana, Nata terdiam. Lama. Sampai akhirnya ia berkata pelan, “Oke. Aku salah. Maaf. Tapi kamu gak boleh nyerah, aku selalu ada buat kamu Ra.”
Aku menutup telepon tanpa menjawab. Untuk pertama kalinya sejak terapi itu kujalani, aku merasa gagal. Bukan karena aku belum sembuh, tapi karena aku mulai kehilangan kepercayaan diri bahwa aku bisa.
Ponselku terus bergetar di atas meja. Nata menelepon lagi. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Aku membiarkannya begitu saja. Tapi pada dering keempat, aku tidak tahan lagi. Setengah karena kesal, setengah karena… aku ingin didengar. Jadi aku angkat.
“Nara, please, jangan tutup lagi,” suara Nata terdengar terburu-buru, penuh kecemasan.
“Apa lagi sih, Nat? Mau denger aku ngeluh lagi? Mau denger aku bilang aku capek lagi? Bosan, ya?” suaraku tajam, dingin.
“Enggak, aku cuma… aku khawatir. Aku tahu semua ini berat banget. Aku nggak akan sok ngerti, aku cuma mau nemenin—”
“Berhenti, Nata,” potongku. Nafasku berat. “Kamu pikir nemenin orang kayak aku itu gampang? Aku bahkan gak tahan sama diriku sendiri!”
“Nara…”
“Kamu malu, kan? Pacaran sama orang kayak aku. Yang tiap malam nangis, nyalahin diri sendiri, bolak-balik ngecek pintu, ngerasa kosong. Kamu malu kan kalau temen-temenmu tahu cewekmu hampir gila?”
“Apa? Enggak, Nara, aku—”
“Kita putus aja, Nat. Gak usah pacaran sama cewek macam aku. Kamu gak harus pura-pura kuat atau pura-pura ngerti.”
“Nara, jangan kayak gini…”
“Gak usah kasihan. Aku gak butuh dikasihani!”
“Nara, aku sayang sama kamu. Aku—”
“Kalau kamu sayang, lepasin. Aku capek.”
Aku tutup telepon tanpa menunggu dia menyelesaikan kalimatnya. Tanganku masih gemetar, dan air mata jatuh satu-satu tanpa suara. Aku bersandar ke tembok, membiarkan kepalaku terantuk pelan ke dinding dingin. Saat itu, aku merasa benar-benar sendirian. Dan sejujurnya… mungkin itu yang pantas untuk orang sepertiku.


 bunca_piyong
bunca_piyong











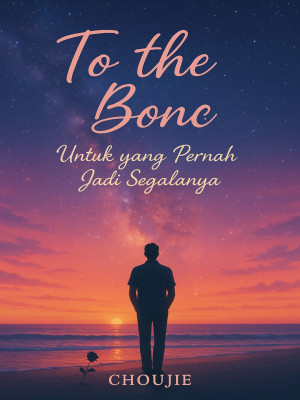
ga ada typo, bahasanya puitis tapi ringan, setiap bab yang di baca dengan mudah membawa masuk ke cerita. ceritannya juga unik, jarang banget orang mengedukasi tentang KESEHATAN MENTAL berbalut romance. dari bab awal sampe bab yang udah di unggah banyak kejutannya (tadinya nebak gini taunya gini). ini cerita bagus. penulisnya pintar. pintar bawa masuk pembaca ke suasananya. pintar ngemas cerita dengan sebaik mungkin. pintar memilih kata dan majas. kayaknya ini bukan penulis yang penuh pengalaman...
Comment on chapter PROLOG