Ketika kata-kata yang tertahan akhirnya menemukan jalan, hati yang terluka mulai perlahan merajut kembali benang-benang harapan yang hampir putus.
**
Siang ini cerah, dengan langit yang berwarna biru lembut. Awan putih tipis tersebar di langit, seperti kapas yang mengambang santai. Matahari bersinar hangat, memantul lembut di permukaan jalan yang kering setelah hujan. Udara segar dan hangat menyapa, mengisi paru-paru dengan nyaman, tanpa beban yang menggantung di tenggorokan. Hari ini kami akan menuju lapas, membawa rindu di tengah hari yang tenang.
Mobil melaju pelan di jalanan sempit, lalu berbelok melewati gerbang tinggi yang dihiasi kawat berduri. Aku duduk di kursi depan, jari-jariku saling menggenggam erat di pangkuan. Di sampingku, Nata menyetir dalam diam. Tak ada percakapan sepanjang perjalanan. Tapi bukan karena kami canggung. Justru karena terlalu banyak hal yang belum sempat dibicarakan, dan aku tahu, akan ada waktunya nanti.
Saat mobil berhenti di area parkir yang padat, aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti sesuatu mengencang di dadaku. Kunjungan ini bukan cuma tentang melepas rindu. Ada bagian dari diriku yang masih takut, takut akan hal-hal yang dulu kami tinggalkan begitu saja di balik sekat kaca dan bangku plastik warna pucat.
“Udah siap ketemu Bara?” tanya Nata pelan, matanya tak lepas dari kemudi.
Aku menoleh padanya, mencoba tersenyum meski tak sepenuhnya berhasil. “Ya, siap gak siap sih. Kalau nggak sekarang, entah kapan lagi.”
Kami turun dari mobil dan berjalan menuju gedung utama. Langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Di depan kami, bangunan itu tetap sama seperti yang kuingat: tembok tinggi, bau logam, suasana yang memaksa semua suara mengecil. Dan entah kenapa, aku malah teringat kunjungan pertamaku ke sini, bertahun-tahun lalu.
Saat melewati pos pemeriksaan dan menyebutkan nama Bara, petugas yang berjaga mengarahkan kami ke ruang tunggu. Ruangan yang sama. Dingin, senyap, dan penuh gema yang seakan masih tertinggal.
Aku berhenti sejenak di ambang pintu. Dinding-dinding pucat itu tak berubah. Bau disinfektan menyengat seperti dulu. Bangku-bangku plastik berbaris rapi, dan di seberangnya, kaca pembatas besar, dengan lubang kecil tempat suara bisa lewat.
Lalu, mataku menangkapnya lagi. Lukisan itu. Masih tergantung di tempat yang sama. Warna-warna lembut yang menggambarkan senja yang belum selesai. Sosok kecil yang duduk membelakangi dunia, menghadap danau yang tenang seperti cermin. Pohon-pohon ramping di sekelilingnya, berdiri diam dalam sunyi. Dan entah kenapa, kali ini, lukisan itu terasa lebih dekat dari sebelumnya.
Aku melangkah pelan mendekat. Hatiku bergemuruh. Bukan karena suasananya. Tapi karena aku tahu, tanpa sadar, aku pernah berdiri di tempat ini dan merasa seperti melihat bayangan diriku sendiri di dalam lukisan itu.
“Dulu waktu pertama ke sini, aku sempat berhenti lama di depan lukisan ini…” bisikku, tanpa menoleh.
Aku tahu Nata berdiri di belakangku. Kudengar napasnya menahan sesuatu.
“Aku nggak tahu kenapa,” lanjutku. “Tapi rasanya… kayak lukisan ini ngerti aku, dan aku ngerasa… aku ada di sana.”
Lukisan itu masih sama, warna senja yang belum selesai, dan sosok kecil yang membelakangi dunia. Diam, tapi tidak menyerah. Sunyi, tapi tidak kalah.
Nata melangkah ke sisiku. Lama dia tidak bicara. Lalu akhirnya, dengan suara pelan, dia berkata, “Aku yang gambar.”
Aku menoleh cepat. “Apa?”
“Lukisan ini,” ujarnya, matanya masih tertuju ke kanvas yang terpajang. “Aku yang lukis itu, beberapa tahun lalu. Waktu ikut sayembara lukis untuk komunitas difabel. Nggak nyangka bakal sampai ke tempat ini.”
Aku menatapnya lekat-lekat. Jantungku serasa berhenti sebentar.
“Serius?”
Dia mengangguk. “Aku sendiri nggak tahu gimana lukisan ini bisa sampai ke sini. Mungkin ada yang menyumbang dari komunitas difabel tempat aku dulu ikut berkegiatan, atau dari galeri yang pernah aku ikuti. Aku juga kurang tahu pasti.”
Aku kembali menatap lukisan itu. Dunia rasanya runtuh pelan-pelan, lalu membangun ulang dirinya dalam bentuk baru. Semua jadi masuk akal. Semua perasaan yang dulu sulit dijelaskan, mengapa aku bisa begitu tenggelam dalam lukisan ini, ternyata karena hatiku sudah mengenal lama goresan tangan itu. Tanpa aku sadari.
“Mungkin…” kataku perlahan. “Mungkin dari awal, tanpa sadar, aku memang sedang berjalan ke arah kamu lewat lukisan ini.”
Aku masih terpaku di depan lukisan itu saat suara pintu terbuka di ujung ruangan. Suara langkah kaki berat menyusul, diiringi bunyi kunci dan sepatu dinas.
Aku menoleh.
Bara berdiri di balik kaca, mengenakan seragam lapas berwarna kelabu. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali, tapi posturnya masih sama: tinggi, tenang, seperti seseorang yang belajar bertahan di tengah kekacauan. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti padaku. Sekejap saja. Tapi cukup untuk membuat tenggorokanku tercekat.
Aku melangkah pelan ke bangku yang disediakan, duduk tepat di depan kacanya. Nata menyusul, ragu-ragu, lalu duduk di sebelahku.
“Bang,” bisikku, hampir tak terdengar.
Bara menyentuh permukaan kaca seolah ingin menjangkau, lalu tersenyum tipis. “Nara... udah lama, ya.”
Aku mengangguk. Air mata sudah menggenang, tapi aku tahan. Aku nggak datang ke sini untuk menangis. Aku datang untuk memberitahu bahwa aku masih di sini. Bahwa meski dunia berubah, kami tetap satu darah, satu cerita.
“Ini Nata,” ujarku sambil menoleh ke samping. “Temanku.”
Nata mengangguk pelan, mencoba tersenyum. “Halo, Bang.”
Bara mengamati Nata sejenak, lalu mengangguk. “Makasih udah nemenin dia ke sini.”
Mereka berdua tak saling mengenal. Tapi ada pemahaman diam yang tiba-tiba mengalir di antara mereka. Mungkin karena keduanya tahu, aku tidak mudah membuka diri. Dan ketika aku memilih membawa seseorang ke tempat seperti ini, artinya orang itu penting.
Aku melirik Bara sebentar. Ada kerutan halus di dahinya yang tidak ada tiga tahun lalu, tapi tatapannya masih sama, tajam tapi tulus. Seolah dia selalu bisa melihatku, bahkan ketika aku sendiri tidak yakin sedang jadi apa.
“Gimana kabarmu di sini, Bang?” tanyaku pelan. Suaraku nyaris patah di ujungnya.
Dia mengangkat bahu, senyum tipis masih bertahan di wajahnya. “Hari-hari ya gitu-gitu aja. Bangun, olahraga, maka, baca, tidur. Kadang mimpiin rumah.”
Aku tertawa kecil, kecut. “Mimpiin Mama masak nasi goreng?”
“Selalu,” katanya. “Tapi pas bangun, yang ada cuma nasi dingin dan kuah entah apa.”
Nata ikut tersenyum. “Yang penting masih bisa ngerasain mimpi.”
Bara tersenyum, lalu matanya menyapu dinding ruang kunjungan. Pandangannya tiba-tiba berhenti pada sebuah lukisan di belakangku. “Aku senang kamu datang, Ra,” ucapnya pelan. “Aku juga selalu suka saat ada yang ngunjungin aku di sini... karena aku bisa lihat lukisan itu. Rasanya bukan sekadar karya biasa, itu seperti ruang lain untuk merasakan tenang.”
Aku mengangguk pelan. “Itu... Nata yang buat.”
Bara terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. “Iya? Keren banget sih kamu Nat.”
Aku dan Nata saling berpandangan. Dari raut wajahnya, aku bisa menangkap ada rasa bangga sekaligus bahagia di sana.
“Dari dulu, aku ngerasa seperti lihat bayangan diri sendiri di sana.” kataku
Bara menatapku. “Mungkin karena lukisan yang jujur... bisa kayak cermin. Nggak ngasih jawaban, tapi bikin kita diem.”
Nata tertawa, sedikit malu. “Waktu bikin lukisan itu dulu, aku nggak mikir sejauh atau sepuitis itu, kok.”
Bara ikut tertawa. Aku menyukai suara itu. Bukan karena lucu, tapi karena suara itu terdengar... hidup. Setelah sekian lama, aku merasa duduk bersama Bara, seperti dulu. Seperti sebelum semua runtuh.
“Senang kamu udah punya temen yang baik, Ra,” kata Bara, menatapku.
Aku mengangguk. “Dia lebih dari baik.”
Mata Bara berpindah ke Nata. “Aku titip Nara ya. Jagain dia.”
Nata mengangguk mantap. “Pasti aku jaga Bang... kayak rahasia negara. Bahkan debunya aja bakal aku lindungi dengan nyawa.”
Kami tertawa lalu mengobrol selama sisa waktu yang diberikan. Obrolan ringan. Tentang makanan kantin yang makin hambar. Tentang kabar Mama dan Papa. Tentang pameran kampusku yang kemarin. Tentang langit yang katanya bisa terlihat lebih luas dari balik jeruji, justru karena nggak ada hal lain yang bisa dilihat terlalu dekat. Tapi yang paling penting, tidak ada yang terasa canggung.
Ketika waktu kunjungan habis, Bara berdiri dan menyentuh kaca lagi.
“Nara,” katanya. “Hidup itu berat, ya. Tapi kamu kuat. Dari dulu juga gitu. Jangan lupa itu.”
Aku menggigit bibir, menahan air mata. “Iya. Kamu juga.”
Kami berjalan keluar dalam diam. Seperti tenggelam dalam pikiran masing-masing.
“Nara,” suara Nata memecah keheningan. “Setelah ketemu Bara. Kamu udah ngerasa sedikit lega sekarang?”.”
Aku berhenti sejenak. Lalu mengangguk.
“Makasih ya Nat, udah nemenin aku ke sini,” ucapku.
Dia menggeleng. “Harusnnya aku yang makasih karena udah di ajak ke sini.”
Matahari mulai condong ke barat saat kami keluar dari lapas, udara terasa segar tapi ada beban di dadaku yang tak mudah hilang. Nata membuka pintu mobil dan mengajak ku masuk. Mesin menyala pelan, lalu mobil melaju menyusuri jalanan kota yang ramai. Kami melewati gedung-gedung tinggi dan pohon-pohon rindang, suara radio yang lembut mengisi ruang di antara kami. Di sampingku, Nata mengemudi dengan santai, sesekali melirik ke arahku.
Aku mengamati pemandangan di luar jendela dengan mata yang terus bergerak, tak pernah diam. Jariku tanpa sadar mengecek ulang kancing baju, lalu menyentuh gagang pintu, memastikan semuanya benar. Namun di balik gerakan itu, ada rasa hampa yang terus menggerogoti, segala warna dan suara seperti kehilangan arti, seperti dunia di luar sana menjauh perlahan, tak mampu kupegang.
“Jadi... mau ke mana nih?” tanyaku akhirnya, suaraku sedikit serak.
Nata tersenyum tipis. “Aku cuma ingin kita jalan-jalan aja. Santai. Gak usah mikirin apa-apa dulu.”
Aku mengangguk pelan. Ada ketenangan aneh di udara, seolah kami sedang menunda waktu, melangkah perlahan tanpa harus buru-buru menghadapi masalah.
Setelah beberapa menit diam, Nata mengalihkan pembicaraan, “Ra, aku lihat belakangan ini kamu kayak.., berubah. Bukan cuma karena rindu sama Bara, tapi aku ngerasa kamu kayak lagi banyak masalah, kayak.. banyak beban gitu, dan akalo boleh, aku pengen bantu.”
Aku menoleh, menatap matanya. “Aku juga ngerasa begitu, Nat. Tapi aku nggak yakin gimana cara ceritanya. Aku takut kamu nggak ngerti.”
Nata menarik napas dalam, lalu berkata lembut, “Aku nggak janji bisa ngerti semuanya, tapi aku mau dengerin kalo kamu mau cerita.”
Aku menarik napas dalam, mencoba merangkai kata yang selama ini kupendam.
“Nat, aku... selama ini aku merasa kayak ada sesuatu yang nggak beres di dalam diri aku. Aku capek, tapi bukan capek biasa. Aku susah senang, susah merasa bahagia. Bahkan hal-hal yang biasanya aku suka, sekarang terasa hambar,” suaraku pelan, agak bergetar.
Nata tetap diam, matanya fokus ke jalan di depan. Perlahan, tangannya meraih tanganku, menggenggam erat seolah ingin memberiku kekuatan tanpa perlu kata-kata. Aku merasakan hangatnya genggaman itu, sedikit menenangkan hati yang sedang gelisah.
“Aku juga sering merasa harus melakukan hal-hal tertentu berulang-ulang... Kayak, kalau nggak, aku nggak bisa tenang. Tapi aku nggak ngerti kenapa aku harus begitu. Kadang aku merasa terjebak sama pikiran sendiri, dan itu bikin aku takut,” aku melanjutkan, mencoba membuka satu per satu lapisan perasaanku.
Nata mengangguk pelan, memberi ruang bagiku untuk bicara.
“Aku nggak tahu kapan semuanya mulai, tapi sebenarnya aku nggak mau ini terus berlarut. Aku takut kehilangan diri aku sendiri, tapi aku juga nggak tahu caranya buat berhenti” aku menghela napas, menatap matanya lewat kaca spion, berharap dia mengerti.
Nata menoleh sebentar, tersenyum lembut, “Ra, aku nggak bisa janjikan semuanya akan langsung mudah. Tapi aku percaya kamu kuat, dan aku bakal ada buat kamu. Kita bisa cari bantuan, bareng-bareng.”
Hatiku sedikit lega mendengar kata-katanya. Mungkin ini awal yang aku butuhkan.
Setelah beberapa detik hening, Nata melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, “Ngomong-ngomong soal itu... Aku pernah baca kalau ngobrol sama psikolog itu bukan berarti kamu ‘gila’ atau lemah. Justru itu langkah berani buat nyelametin diri sendiri.”
Aku menunduk, menghela napas panjang. “Aku... aku takut, Nat. Takut nanti dibilang aneh, atau malah dibilang nggak waras. Aku juga nggak tahu apa yang bakal aku omongin di sana. Kalau aku buka semuanya, apa aku bisa terima kenyataan itu?”
Tangan Nata menggenggam tanganku lebih erat. “Aku nggak bakal maksa kamu, Ra. Tapi aku janji, aku bakal nemenin kamu kalau kamu mau coba. Kamu nggak sendiri.”
Aku menatapnya lama. Ada campuran takut dan harapan di mataku.
“Boleh aku pikir-pikir dulu, ya?”
Nata tersenyum hangat. “Tentu. Gak perlu buru-buru. Aku di sini, kapan pun kamu siap.”
Mobil terus melanju, lalu kemudian berhenti di sebuah kafe kecil yang terang di pinggir jalan. Nata mengajak aku keluar, menghirup udara sore yang segar.
“Kita makan dulu ya, biar kamu nggak kepikiran terus,” katanya sambil membuka pintu mobil untukku.
Kami duduk di pojok kafe, suasana hangat dan sederhana membuat jantungku sedikit lebih tenang. Nata memesan dua cangkir cokelat panas dan sepiring kue kecil.
“Kamu nggak harus langsung cerita semuanya sekarang,” ujarnya sambil menyendok kue, “Aku cuma mau kamu tahu, aku ada buat kamu.”
Aku tersenyum tipis. Aku merasa lega karena tidak sendirian dalam kebingungan ini.
Setelah selesai dari kafe, Nata mengajakku berjalan-jalan di taman kota tak jauh dari situ. Lampu jalan baru menyala perlahan, udara sore mulai beranjak ke senja dengan warna langit yang hangat.
“Kamu suka tempat kayak gini?” tanya Nata sambil tersenyum kecil.
Aku mengangguk pelan. “Iya. Tenang... dan nyaman.”
Kami duduk di bangku taman, menghadap kolam kecil yang memantulkan warna jingga dari langit senja. Suasana sunyi, hanya terdengar desir angin dan suara langkah kaki kami.
Nata menoleh padaku, “Ra, aku tahu ini nggak mudah. Tapi aku tahu kamu kuat.”
Aku tersenyum, berusaha mengusir rasa takut yang masih menggelayut.
“Kadang aku takut... takut nggak bisa berubah, atau malah jadi beban buat orang-orang yang sayang sama aku,” suaraku pelan.
Nata menatapku lama. “Kamu bukan beban, Ra. Kamu berharga. Aku yakin kamu bisa lewati ini.”
Senja berganti malam tanpa terasa, kami duduk berdua, berbagi tawa kecil dan keheningan yang nyaman.
Saat aku diantar pulang, di depan rumah Nata menatapku hangat, “Jangan banyak pikiran ya cantik. Cukup mikir aku aja yang cinta banget sama kamu”
Aku menatapnya, lalu tersenyum.
Dia membalas senyumku dengan lembut, lalu melambaikan tangan sembari melaju dengan pelan.
Setelah Nata pergi, aku melangkah masuk ke kamar dengan hati yang masih berdebar. Di depan pintu, aku berhenti dan menggenggam gagangnya, lalu melepasnya, ulangi lagi, pastikan posisi tanganku tepat, pastikan kunci benar-benar terkunci. Aku cek sekali, dua kali, bahkan tiga kali, walau tahu aku sudah melakukannya dengan benar. Tapi kalau aku tidak memastikan, rasa cemas itu datang menyerang dengan lebih ganas. Tanganku gemetar tanpa henti, napasku jadi cepat dan pendek. Aku berusaha menenangkan diri, mengalihkan pikiran, tapi tubuh ini seperti terjebak dalam lingkaran yang sulit kutinggalkan.
Di sudut kamar, semuanya terasa hampa. Hal-hal yang dulu memberi aku rasa nyaman kini berubah jadi beban berat yang susah dijelaskan. Pikiran tentang ke psikolog terus menghantui. Aku ingin sembuh, tapi juga takut. Takut kalau aku benar-benar berbeda, takut kalau aku tak bisa menerima kenyataan itu. Keraguan menyelimuti, membuat ku bimbang menentukan langkah.
Namun, ada suara kecil di dalam hatiku yang berkata, mungkin ini saatnya aku mencoba. Aku menutup mata, menarik napas dalam, dan berbisik pelan, “Aku harus berani.”


 bunca_piyong
bunca_piyong
















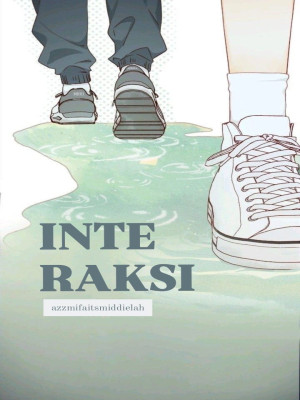

Eh eh eh eh bab selanjutnya kapan ini? Lagi seru serunya padahal.. kira-kira Nara suka Nata juga ga ya??? Soalnya kan dia anhedonia🧐 .