Ada cara-cara tertentu yang membuat seseorang bicara tanpa suara. Lewat cara ia memanggil namamu. Lewat jeda sebelum berpaling. Atau lewat perhatian kecil yang terlalu sering untuk disebut kebetulan. Dan saat semua itu datang dalam diam—kau mulai sadar: seseorang tak sedang lewat, ia sedang mengetuk pelan-pelan.
**
Pagi datang terlalu cepat. Sudah jam delapan lewat dua belas menit ketika akhirnya aku selesai menggantungkan handuk di kamar mandi. Gantungan barunya memang sudah aku pasang semalam, tapi posisi handuk yang miring, walau hanya satu atau dua derajat bikin dadaku terasa ganjil. Tiga kali aku lepas, lipat ulang, lalu gantung lagi. Tetap saja seperti tak ada yang benar. Sampai akhirnya aku menyerah dan memutuskan berangkat, perasaan itu belum pergi. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang harusnya pas, tapi tidak pas.
Kampus sudah mulai ramai ketika aku sampai di gerbang. Di sana, Nata berdiri menyender santai di tiang pagar, satu tangan dimasukkan ke saku jaket, sementara tangan lainnya memegang botol minum yang sudah tinggal separuh.
“Tumben datangnya telat? Aku udah nunggu 15 menitan nih” tanyanya sambil mengatur langkah di sebelahku.
Aku sedikit mengatur napas sebelum menjawab. “Tumben banget nungguin aku… Emang ada apa?”
Nata nyengir. “Emangnya gak boleh?”
Aku menatapnya sekilas, agak bingung. “Biasanya enggak pernah nunggu…”
Dia tertawa pelan. “Iya, biasanya. Tapi kamu kan bukan ‘biasanya’.”
Aku diam. Gak tahu harus menjawab apa. Kalimatnya ringan, tapi entah kenapa terdengar serius.
Kami jalan menuju ruang panitia, melewati koridor panjang dengan bayangan pohon di sisi kaca. Udara mulai hangat, tapi tidak terlalu pengap.
“Nara,” katanya tiba-tiba, membuatku menoleh pelan. Ia mengangkat botol minum di tangannya. “Kamu udah minum belum? Beli minuman bentar ya”
Aku hanya terdiam. Tidak mengangguk tidak juga menggeleng.
Dia berhenti di depan vending machine dan tanpa tanya, langsung memasukkan uang. “Kamu lebih suka teh dingin atau kopi?”
Aku diam sebentar. “Teh.”
“Manis atau tawar?”
“Sedang.”
Nata tersenyum. “Nggak ada pilihan ‘sedang’ di mesin ini, tapi aku pilih yang manis tipis, ya?”
Aku mengangguk. Lalu memperhatikan tangannya saat menekan tombol, memperhatikan caranya berdiri sedikit miring agar tidak menutupi lubang keluarnya botol. Hal-hal kecil seperti itu yang harusnya tidak penting, akhir-akhir ini terasa seperti jeda di tengah keramaian pikiranku sendiri.
Dia menyerahkan botol teh itu padaku. Tutupnya masih berembun, dingin menempel di ujung jariku saat aku menerimanya.
“Makasih ya,” ujarku pelan.
Nata hanya mengangguk kecil, lalu kembali melangkah di sebelahku. Ia sedikit memiringkan badannya, seolah memberi ruang agar langkahku tak terganggu. Map gambar di tangannya tampak mulai terlipat di bagian ujung, terbawa gerakan yang terus ia ayun pelan-pelan.
“Eh, kamu tau gak,” katanya sambil melirikku, “aku semalam ngecek ulang layout poster acara. Trus keinget kamu pernah bilang warnanya terlalu rame.”
Aku menatapnya sebentar. “Terus kamu ganti?”
“Ganti,” jawabnya cepat. “Aku pakai palet abu dan biru muda. Lebih kalem. Ala-ala kamu gitu lah.”
Aku mengernyit tipis. “Ala aku?”
“Ya, desain kamu kan rapi, bersih, nggak neko-neko. Kayak... kamu juga sih,” katanya, suaranya agak merendah di akhir.
Aku tidak menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena aku belum tahu harus bereaksi seperti apa.
“Eh, jangan marah ya,” tambahnya cepat. “Aku nggak maksud nyamain kamu sama poster.”
Aku menggeleng. “Aku nggak marah.”
Dia tertawa pelan. “Ya siapa tau kamu tersinggung. Soalnya kamu tipe orang yang susah ditebak.”
Aku menatap ke depan. “Aku juga susah nebak diriku sendiri.”
Nata tidak menjawab. Tapi dari sudut mataku, aku melihat dia tersenyum. Bukan senyum karena lucu, lebih kesenyum yang... puas, atau mungkin lega.
Kami melewati taman kecil sebelum belok ke koridor ruang panitia. Angin pagi berhembus pelan, menerbangkan beberapa lembar kertas bekas di lantai.
“Kalau tiap pagi kamu berangkat naik angkot, boleh nggak... besok aku jemput?” tanyanya tiba-tiba.
Aku hampir berhenti melangkah. Tapi aku tetap berjalan. Perlahan.
“Buat apa?” tanyaku datar.
“Kan sayang.,” jawabnya. Kalimatnya terputus. Dia diam sejenak, lalu melanjutkan, “Kan sayang waktunya kebuang sia-sia nungguin angkot” sambungnya sambil tertawa.
Aku menoleh sebentar padanya, lalu kembali menatap jalan.
“Aku nggak masalah nunggu,” kataku pelan. “Lagipula… aku biasa sendiri.”
Kalimat itu terdengar lebih jujur daripada defensif, tapi aku sendiri tak yakin apa maksudnya. Rasanya seperti kalimat yang keluar begitu saja, tanpa filter, tanpa rencana.
Nata tak langsung menjawab. Langkahnya sempat melambat, lalu ia tersenyum kecil.
“Ya... tapi kan kadang sendiri itu capek juga,” katanya santai. “Bukan maksain sih, Cuma.. kalau ada yang bisa nemenin, kenapa nggak?”
Dia tidak menatapku saat mengatakan itu. Matanya lurus ke depan, seperti takut kalau pandangannya ketahuan terlalu serius.
Kami masuk ke ruang panitia, tempat yang sudah terasa familiar sekaligus kacau. Meja-meja berantakan dengan tumpukan kertas dan makanan ringan berserakan di sana-sini. Di pojok ruangan, beberapa teman tertawa lepas sambil mengedit foto di laptop, sementara yang lain sibuk membahas rundown acara dengan penuh semangat. Suasana itu hidup, penuh dengan energi yang beragam, kontras dengan perasaan yang aku bawa saat ini.
Aku dan Nata duduk berdampingan di sisi kiri ruangan, dekat jendela yang terbuka separuh. Cahaya matahari masuk miring, mengenai layar laptopku. Kami sama-sama sibuk. Nata tenggelam dalam file desain spanduk utama, sesekali menarik napas panjang saat harus me-nye-croll ulang dari awal. Aku juga fokus menatap lekat ke layar laptop, tanganku bolak-balik klik shortcut keyboard untuk merapikan tabel peserta. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Hanya bunyi ketikan, kipas angin yang berdecit pelan, dan obrolan jauh di sudut ruangan.
“Nata,” kataku akhirnya, tanpa menoleh. “Bisa bantu cek ini gak? Aku takut ada baris yang loncat.”
“Hmm.. yang mana?,” jawabnya cepat. Kursinya bergeser ke arahku.
Aku tetap duduk di tempatku, pikiranku masih sibuk memeriksa angka-angka. Aku baru sadar ketika bahunya nyaris menempel di bahuku. Nafasnya terasa sangat dekat membuatku reflek menahan napas. Aku lupa mundur. Nata juga nggak buru-buru menjauh. Dia mencondongkan tubuhnya, menatap layar laptopku dari jarak yang... terlalu dekat.
“Ini.....,” suaranya pelan, nyaris berbisik, “baris ke dua puluh lima agak ngegeser. Tapi sisanya rapi banget.”
Aku mengangguk, tanpa menoleh. Tapi aku bisa mendengar degup jantungku sendiri. Atau... itu degup jantungnya? Aku nggak tahu. Yang pasti, ruang ini terasa sunyi sejenak, meski orang-orang di belakang kami masih bercanda.
Aku mencoba bicara. “Oh. Oke. Thanks.” Tapi suaraku terdengar pelan, nyaris tenggelam.
Nata masih belum menjauh. Tangannya bergerak, menunjuk sel kosong di layar. “Ini juga perlu diisi, kayaknya.”
Aku mengangguk lagi. Terlalu cepat.
Beberapa detik kemudian, dia pelan-pelan bersandar mundur. Kursinya bunyi sedikit. Jarak kami kembali aman. Tapi detaknya masih tertinggal.
Kami masih duduk berdampingan. Aku kembali menatap layar, membetulkan beberapa baris dan mengetik ulang nama-nama yang typo. Nata sibuk lagi dengan desain. Tak ada lagi obrolan.
Tanganku bergerak ke touchpad. Di saat yang sama, tangan Nata juga bergerak, entah untuk meraih kertas atau ngetik shortcut di keyboard-ku. Kelingking kami bersentuhan. Kecil. Sepintas. Tapi cukup untuk membuatku berhenti mengetik.
Aku menarik tanganku pelan. Tapi Nata tidak langsung bergerak. Mataku masih menatap layar, pura-pura sibuk, pura-pura gak terasa apa-apa.
“Nara,” panggilnya pelan.
Aku menoleh sedikit. Dia sedang menatapku. Bukan seperti biasa. Bukan sekadar tatapan ngobrol. Bukan tatapan kerja tim. Tatapannya penuh. Diam. Tapi jelas.
“Aku suka cara kamu kerja.”
Aku berkedip. “Maksudnya?”
Dia tersenyum tipis. “Kamu teliti. Rapih. Nggak neko-neko. Semuanya terasa pas. Tenang.”
Aku menunduk sedikit. “Itu biasa aja, kayaknya.”
“Nggak buat aku,” katanya pelan.
Aku tidak tahu harus menjawab apa. Di kepalaku, kalimat itu berputar-putar. “Nggak buat aku.”
Dia menatapku sebentar lagi, lalu berpaling, pura-pura melihat ke layar. Tapi tangannya tidak bergerak. Dia seperti masih memikirkan sesuatu. Atau mungkin, masih menunggu jawaban dari ku. Tapi aku hanya diam. Karena sejujurnya... aku belum bisa merasakan apa-apa.
Nata menarik napas pelan, lalu mencondongkan tubuh sedikit. “Aku tau kamu mungkin bakal nganggep aku sok deket atau malah nganggap aku kelewat batas.”
Dia menatapku lagi, kali ini tatapannya tidak selembut tadi. Ada gugup di sana. Tapi juga tekad.
“Tapi aku pengen kamu tahu. Aku suka ada di dekat kamu Ra.”
Aku langsung menoleh. “Nata...”
“Aku tahu kamu nggak bakal langsung bales perasaan aku. Aku nggak maksa. Aku cuma pengen kamu tahu aja,” katanya buru-buru. “Biar kamu ngerti kenapa aku kadang terlalu banyak bantuin kamu, atau terlalu sering nyari alasan buat ngobrol.”
Dia tertawa pelan, lebih ke arah dirinya sendiri. “Kedengeran bodoh ya?”
Aku menggeleng pelan. “Enggak.”
Dia mengusap tengkuknya. “Kamu tuh... nggak kayak orang lain. Kamu tenang, kamu nggak berisik, tapi kamu... ada. Dan aku suka itu.”
Aku menatapnya. “Aku nggak ngerti, Nat” kata-kataku tergantung, lalu aku terdiam berusaha memikirkan kalimat yang pas untuk menjelaskan “Maksudnya... aku ngerti apa yang kamu bilang, tapi aku nggak ngerti apa yang aku rasain.” Sambungku.
Dia mengangguk. “Itu gak apa-apa. Serius. Aku cuma pengen kamu tahu. Dan kalau nanti kamu udah bisa ngerasa, apa pun itu, aku masih di sini.”
Kami saling diam beberapa detik.
Lalu dia berdiri. “Mau lanjut kerja lagi?”
Aku mengangguk. “Lanjut deh kayaknya.”
Dia tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya lebih ringan. Seperti beban yang baru saja dia lepas.
Waktu istirahat siang, ruang panitia mulai kosong satu per satu. Beberapa anak nyelonong keluar sambil bawa totebag, ada juga yang langsung turun ke bawah karena katanya ada booth makanan baru yang enak.
Aku masih duduk di kursi. Masih tenggelam dalam layar yang menampilkan layout dihadapanku.
“Ra,” suara Nata muncul dari belakang laptopnya. “Kamu belum makan, kan?”
Aku menggeleng. “Nggak lapar.”
Dia berdiri sambil menggantungkan lanyard di leher. “ada booth makanan yang baru buka. Katanya siomaynya enak. Yuk, temenin aku.”
Aku ragu sebentar. “Nemenin doang?”
“Kalau kamu gak lapar, ya nemenin. Tapi kalau kamu kepincut siomaynya, itu bukan salah aku,” katanya sambil nyengir.
Akhirnya aku berdiri juga. Kami jalan berdua melewati lorong menuju halaman samping gedung, tempat booth makanan berderet. Udara siang panas, tapi semilir angin membawa sejuk yang menenangkan.
Di booth ketiga, Nata berhenti. “Kamu lebih suka yang goreng apa yang kukus?”
“Eh?” aku bingung.
“Siomay. Aku beliin.”
Aku mengernyit. “Katanya aku nemenin doang.”
“Yaudah, anggap aja kamu aku gaji karena udah nemenin,” katanya, melirikku sekilas. “Tapi gajinya cuma berlaku buat kamu: satu porsi somay spesial plus senyum manis dari bosnya.”
Aku tertawa kecil, tidak tahu kenapa. “Goreng, deh.”
Nata langsung memesan dua porsi: satu kukus, satu goreng. Waktu nunggu, dia melirik ke arahku.
“Kamu tuh selalu bilang nggak lapar, tapi kamu juga harus ingat manusia butuh makan biar hidup.”
Aku nyengir. “Iya... iya”
“Makanya harus ada yang selalu ngingetin, biar nggak kelupaan makan.”
Aku mendelik tipis. “Emangnya siapa?”
“Ya akulah, calon pengingat harianmu?” Dia mengangkat alis, ekspresinya setengah bercanda, setengah serius.
Aku tidak menjawab. Tapi wajahku terasa sedikit menghangat.
Saat makanan datang, kami duduk di bangku plastik di dekat pohon, cukup teduh. Nata membuka saus, memilih bagian yang garing, dan memberikannya padaku.
“Nih, yang ini kelihatan paling enak.”
Aku mengambilnya pelan. “Makasih.”
Dia mengangguk kecil. “Sama-sama. Aku suka lihat kamu makan.”
Aku mendongak. “Hah?”
“Iya, maksudnya... kamu kelihatan lebih hidup aja. Waktu kamu diem, kamu tuh kayak... ngilang.”
Aku menggigit siomay, menunduk, tak tahu harus bilang apa.
Kami makan dalam diam beberapa menit. Tapi diam yang tidak bikin canggung. Malah... nyaman. Selesai makan, kami duduk sebentar, menikmati sisa angin dan suara riuh pameran yang makin ramai.
“Eh, aku ke sana bentar ya,” kata Nata sambil berdiri.
“Mau ke mana?”
“Temen SMA aku dateng. Mau nyapa aja bentar.”
“Oke,” jawabku singkat.
Dia ngangguk. Tapi sebelum pergi, dia ragu sebentar. “Kamu di sini aja ya? Nanti aku balik lagi.”
Aku mengernyit. “Kenapa gak ngajak aku sekalian?”
Nata terdiam, lalu senyum nakal muncul di bibirnya. “Gak usah kamu tunggu di sini aja. Soalnya cantik. Nanti di taksir lagi sama temenku”
Aku langsung melipat tangan di dada. “Cih. Gak penting.”
Dia ketawa, lalu pergi sambil dadah-dadah. Aku masih duduk di tempat tadi, mengalihkan pikiranku dengan menatap layar ponsel.
“Lah, kamu di sini juga?” Suara yang familiar tiba-tiba muncul dari samping.
Aku menoleh. “Dita.”
Dia duduk tanpa diundang, “Sendiri?” Tanya Dita.
“Enggak, tadi sih bareng kakak tingkat kita, anak seni”
“Ooh.. Siapa?” Dita manggut-manggut dengan ekspresi yang tidak peduli.
“Nata.” Jawabku singkat.
Dita langsung menoleh ke arahku, matanya membulat seperti tidak percaya. “Hah? Nata??”
“Iya,” jawabku singkat tanpa menoleh ke arahnya.
“Di mana dia sekarang?,” Jawab Dita sambil membetulkan posisi duduknya.
“Lagi keluar bentar, katanya ketemu teman SMA.” Jelasku sambil menatap layar ponsel yang menampilkan percakapan grup.
“Kok kamu bisa sama dia sih? Kok bisa ke sini sama Nata? Kalian kenal di mana?” tanya Dita bertubi-tubi.
“Lah..., kan kami satu divisi, Bu Ratih yang atur”. Jawabku sambil nyengir.
“Ihhh.. beruntung banget sih kamu, tukaran divisi yuk..”
Aku melongo, “Beruntung? Kenapa?”
Dita langsung nyerocos. “Lah, kamu gak tahu? Nata tuh ganteng, pinter, keren, humble, tajir, gaul, terkenal dan... well, semua cewek di kampus ini minimal pernah suka dia dalam hati. Termasuk aku, dulu.”
Aku kaget. “Kamu pernah suka Nata?”
“Dikit doang. Cuma kagum, gitu. Tapi terus sadar dia terlalu perfect buat aku,” katanya sambil ketawa. “Makanya pas tahu kamu satu divisi sama dia, aku langsung mikir... beruntung banget sih kamu bisa deket sama dia, bisa mandangin dia dari deket, bisa cium harumnya dia.” Jelasnya setengah tertawa.
Aku belum sempat menjawab.
Dita langsung melanjutkan kalimatnya, “Kamu gak naksir dia?.”
Aku semakin diam. “Kalo aku jadi kamu sih, udah aku ajak nikah kali ya,” sambung Dita sambil tertawa.
Belum sempat aku merespons candaan terakhirnya, seseorang memanggil Dita dari arah seberang booth. Suaranya cukup kencang, disertai lambaian tangan.
“Eh, itu aku dipanggil. Kayaknya disuruh bantuin ngangkut barang,” katanya cepat sambil bangkit. “Nanti cerita lagi, ya!”
Aku mengangguk pelan, dan Dita langsung berlari kecil meninggalkan tempat duduk.
Aku kembali sendiri. Sumpit sudah tergeletak di atas mangkuk kosong. Siomaynya habis sejak beberapa menit lalu, tapi aku masih duduk di tempat yang sama, menatap meja tanpa fokus. Ucapan Dita tadi terus terngiang. Beruntung banget bisa deket sama dia… bisa cium harumnya dia…
Aku menarik napas, lalu menghela pelan. Ada sesuatu yang berbeda di dada, sedikit hangat, mungkin juga gugup. Tapi saat aku mencoba mengenalinya, sensasi itu langsung menguap, seperti embun yang hilang sebelum sempat disentuh. Tidak ada yang benar-benar menetap. Hanya samar. Dan sunyi. Seperti sesuatu yang seharusnya bisa membuatku tersenyum, tapi tidak tahu bagaimana caranya.
Seketika itu juga, langkah kaki yang familiar terdengar mendekat. Nata kembali dengan membawa dua botol air minum dingin di tangannya. Dia memberikannya satu kepadaku, lalu duduk di sampingku lagi.
“Maaf lama. Dia cerita panjang banget.”
Aku mengangguk pelan. “Gak apa-apa.”
Beberapa saat kami duduk dalam diam, menikmati sisa udara sore yang perlahan mulai dingin. Tapi pekerjaan belum selesai, dan waktu terus berjalan. Akhirnya, Nata berdiri lebih dulu, menepuk celana dan merentangkan tubuh. “Yuk, balik. Panitia lain pasti udah mulai nyariin.”
Aku ikut berdiri, membenarkan ujung bajuku yang sedikit tergulung. Langkah kami kembali mengarah ke gedung panitia, melewati jejak-jejak kaki dan sisa kabel di lapangan yang mulai sepi. Sesampainya di ruang panitia, suara obrolan, bunyi ponsel, dan denting logam dari alat-alat logistik langsung menyambut kami. Meja-meja penuh kertas, snack, dan alat tulis kembali jadi pusat kesibukan.
Aku langsung duduk di kursiku, membuka kembali laptop yang tadi kutinggal, sementara Nata sudah sibuk berdiskusi dengan divisi perlengkapan. Seolah tak pernah ada jeda, kami kembali jadi dua roda dalam mesin besar bernama persiapan malam puncak.
Langit mulai berubah warna saat kami beranjak dari lokasi pameran. Matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung kampus, meninggalkan semburat jingga di langit yang perlahan menggelap. Nata berjalan di sampingku, tangannya merogoh saku jaket lalu mengusap tengkuknya pelan, seperti menimbang sesuatu. Lalu ia bersuara, ringan tapi tak membuka ruang bantahan.
“Aku anter, ya?” kata Nata tiba-tiba. Suaranya ringan, tapi nadanya tidak membiarkan ada penolakan.
Aku menoleh. “Naik angkot juga nggak apa-apa, kok.”
“Enggak bisa,” jawabnya cepat. “Udah malam. Aku nggak tenang ngelepas kamu pulang sendiri.”
Aku sempat diam beberapa detik. Tapi Nata sudah berjalan ke arah parkiran, tidak menoleh lagi. Mau nggak mau, aku menyusul.
Di dalam mobil, sunyi terasa nyaman. Jendela sedikit terbuka, membiarkan udara malam masuk bersama bau aspal panas yang masih belum benar-benar hilang dari tadi siang. Nata menyalakan playlist-nya. Lagu-lagu akustik lembut mengalun, persis seperti yang dulu sering aku dengar saat masih senang mengurung diri di kamar dengan lampu remang dan headset. Aku kenal lagu ini, bahkan terdengar sangat akrab di telinga. Dulu, nada-nada itu seperti pelukan. Tapi sekarang… hanya suara. Tanpa rasa.
Aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan seperti garis-garis cahaya yang lewat cepat di sisi kami. “Playlist-nya, kamu yang pilih sendiri?” tanyaku pelan, sekadar basa-basi.
Dia mengangguk. “Aku inget kamu pernah cerita soal lagu-lagu kayak gini waktu awal-awal jadi panitia.”
Aku diam. Ada sedikit hangat yang muncul, atau mungkin hanya pikiranku yang berharap bisa merasakannya lagi.
Mobil melaju ke arah timur, membelah kota yang mulai redup. Beberapa kali berbelok melewati perempatan yang makin lengang, lalu akhirnya berhenti perlahan di depan rumahku.
Aku membuka pintu, tapi sempat menoleh. “Mau mampir dulu nggak?”
Kupikir dia akan menolak. Tapi dia justru mematikan mesin mobil. “Mau kalo boleh.”
Aku hampir menyesal sudah menawari. Tapi bibirku hanya menarik senyum tipis sambil masuk lebih dulu.
Di dalam rumah, Mama sedang menyiram tanaman kecil di teras belakang. Nata ikut masuk sambil membawa map gambarnya. Dia memperhatikan sekeliling dengan senyum kecil, seolah mencatat detail ruangan. Aku menaruh tasku di kursi dan buru-buru merapikan rak sepatu yang tadi pagi sempat sedikit miring. Sudut-sudutnya harus lurus. Harus sejajar.
“Bentar ya,” ujarku sambil membenarkan posisi gelas-gelas di meja, ada yang agak serong. Tangan ini belum bisa tenang sebelum semuanya pas.
Nata menatapku, tapi tidak berkomentar apa-apa.
Mama masuk ke ruang tamu, sedikit kaget melihat Nata. “Eh, temennya Nara?”
“Iya, Tante. Saya Nata,” ucapnya cepat, lalu berdiri sopan.
“Oh, yang sering disebut-sebut itu ya?” Mama tersenyum, ramah.
Aku menatap Mama tajam. “Aku enggak pernah nyebut-nyebut juga.”
Nata hanya terkekeh. “Saya minta izin, ya, Tante. Kayaknya... saya mulai suka main ke rumah ini.”
Mama tertawa pelan. “Izin diterima, asal jangan ganggu kuliahnya Nara.”
“Enggak akan,” jawab Nata cepat, lalu menoleh padaku. “Justru pengen bantu dia biar makin semangat.”
Setelah cukup basa-basi, Nata pamit. Aku mengantarkannya sampai ke pagar.
Dia berhenti sejenak sebelum masuk mobil. “Eh, Ra...”
“Hm?”
“Jaga diri, ya.” Dia tersenyum. “Soalnya... kamu berharga.”
Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya, dan dia langsung masuk ke mobil dan pergi.
Aku berdiri beberapa saat di depan pagar. Malam mulai dingin. Lampu jalan menyala redup di kejauhan, cahayanya membentuk bayangan tipis di lantai teras. Ucapan Nata tadi terus berputar di kepalaku.
Kamu berharga.
Kalimat sederhana. Tidak dramatis. Tidak seperti baris puisi atau kutipan novel. Tapi justru karena itu… terasa nyata. Aku menatap langit. Awan sudah habis tersapu angin. Bintang-bintang mulai muncul malu-malu. Malam ini, rasa sepi itu masih ada dan aku merasa tidak takut padanya.


 bunca_piyong
bunca_piyong


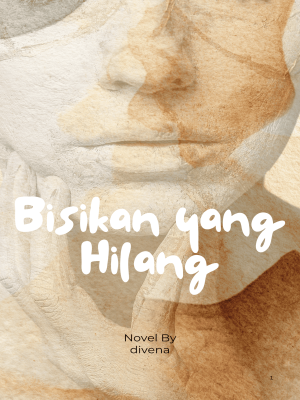









ga ada typo, bahasanya puitis tapi ringan, setiap bab yang di baca dengan mudah membawa masuk ke cerita. ceritannya juga unik, jarang banget orang mengedukasi tentang KESEHATAN MENTAL berbalut romance. dari bab awal sampe bab yang udah di unggah banyak kejutannya (tadinya nebak gini taunya gini). ini cerita bagus. penulisnya pintar. pintar bawa masuk pembaca ke suasananya. pintar ngemas cerita dengan sebaik mungkin. pintar memilih kata dan majas. kayaknya ini bukan penulis yang penuh pengalaman...
Comment on chapter PROLOG