Ada hal-hal yang terus kulakukan bukan karena ingin, tapi karena merasa harus. Karena jika tidak, sesuatu di dalam dadaku bergetar, seolah dunia bisa retak hanya karena satu garis tak sejajar.
**
Ada hari-hari ketika semuanya terasa berjalan seperti biasa. Bangun pagi, masuk kelas, menyelesaikan revisi, makan siang di kantin, lalu kembali ke studio. Hari-hari seperti itu... terlihat normal dari luar. Tapi di dalam kepala, aku seperti sedang berlari, terus-menerus, tanpa jeda.
Orang bilang aku rajin. Terorganisir. Teliti. Tapi mereka tidak tahu, betapa menakutkan rasanya kalau meja kerjaku sedikit berantakan. Atau pintu kamar tidak kugembok dua kali. Atau keran air tidak kuputar sampai benar-benar terasa “pas.”
Awalnya aku pikir ini cuma kebiasaan kecil. Tapi lama-lama, aku merasa dikendalikan oleh sesuatu yang tidak bisa kulawan. Seolah, kalau aku tidak mengikuti semua “aturan” itu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan hari itu... Dita mulai memperhatikan. Dita menatapku lebih lama kali ini. Tapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak menyela, tidak memotong, hanya diam dan mendengarkan.
Hari itu aku datang ke studio lebih pagi dari biasanya. Meja kerjaku belum disentuh siapa pun. Maket setengah jadi masih tertutup plastik, rapi, tanpa debu. Aku membuka laci, lalu mulai menyusun ulang alat gambar: penggaris harus di kanan, pensil 2B di atas pensil mekanik, penghapus harus menghadap ke bawah. Satu per satu. Ulangi. Ulangi lagi.
“Pagi banget,” suara Dita muncul dari balik tiang. Aku menoleh. Ia berjalan sambil menguap dan menjinjing dua cup kopi.
Aku tersenyum kecil. “Nggak bisa tidur.”
“Wah, berarti kita sama. Tapi kamu kayaknya lebih produktif.” Ia duduk di sebelahku, lalu meletakkan satu cup kopi di ujung mejaku. “Ini buat kamu.”
Aku mengangguk. Tapi sebelum menyentuhnya, tanganku mengambil tisu dari tas. Aku lap dulu bagian tutup plastiknya. Hati-hati. Dua kali putaran. Sama seperti biasanya.
Dita memperhatikan. Tapi tidak langsung komentar. Beberapa menit berlalu. Kami menggambar dalam diam. Tapi entah kenapa, aku tahu dia memperhatikanku lebih dari biasanya. Matanya tidak hanya sekilas melirik. Tapi mengikuti.
“Aku salah gambar garis ini,” kataku, setengah berbisik. Padahal garis itu cuma miring seperempat derajat. Hampir tak terlihat. Tapi aku mengambil cutter, memotong bagian karton itu, mengganti yang baru.
“Kayaknya... masih bisa ditolerir deh,” kata Dita pelan.
Aku diam. Tanganku terus bekerja.
“Kamu tahu nggak, Ra,” lanjutnya, “Aku suka kagum sama ketelitian kamu. Tapi akhir-akhir ini... kamu kayak terlalu nyiksa diri.”
Aku menoleh.
Dita menatapku serius. “Aku liat kamu mencuci tangan berkali-kali di toilet fakultas. Tadi pagi juga, waktu aku dateng, kamu buka tutup laci sampai tiga kali. Dan... kamu bolak-balik ke pintu cuma buat ngecek kunci.”
Aku terdiam. Rasanya seperti terjebak dalam sorotan cahaya yang terlalu terang. Tapi Dita tidak bicara dengan nada curiga, apalagi menuduh. Suaranya tetap pelan, datar, tapi ada kehangatan di baliknya.
Dia mengangkat bahu kecil-kecil, lalu menyisipkan rambut ke belakang telinganya. “Aku sih nggak ngerti ya... mungkin itu cuma kebiasaan kamu. Tapi... aku baru sadar aja. Kamu kayak... makin sering ngulang-ngulang sesuatu akhir-akhir ini.”
Aku memaksakan senyum. “Kebiasaan aja, Dit. Biar tenang.”
“Tenang?”
Aku mengangguk pelan. “Kadang kalau aku nggak ulang, aku ngerasa... ada yang nggak bener. Kayak... bisa aja ada hal buruk yang akan terjadi karena kesalahan kecil.”
Dita menatapku lebih lama kali ini. Tapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak menyela, tidak memotong, hanya diam dan mendengarkan.
Suara alat potong maket dari meja sebelah terdengar tajam, disusul tawa pelan dua mahasiswa laki-laki yang sedang bercanda tentang desain bentuk tangga. Di pojok ruangan, Bu Diah sudah datang, memeriksa satu per satu maket dengan clipboard di tangan. Bau lem dan karton mengambang di udara, campur aduk dengan aroma kopi dingin yang belum disentuh.
Aku kembali membetulkan posisi miniatur pohon di maketku. Dita tetap duduk di sebelahku, tak lagi banyak bicara, hanya menggambar sketsa kasar di bukunya sambil sesekali melirik ke arahku.
“Kamu bawa cutter yang tipis nggak?” tanyanya tiba-tiba, santai, seolah tadi tidak ada obrolan serius sama sekali.
Aku mengangguk, merogoh tempat pensil, lalu menyerahkan cutter itu ke arahnya. Ia menerimanya sambil tersenyum tipis.
“Oke Makasih.”
Kami kembali diam, tapi bukan diam yang canggung. Lebih seperti… diam yang cukup. Yang nggak perlu diisi dengan apapun.
“Aku tuh kadang suka mikir ya,” katanya pelan, masih sambil menggambar, “orang-orang yang keliatan paling teratur justru yang paling takut kalau ada yang keluar dari rencana.”
Aku melirik sekilas. Tidak membalas. Tapi Dita tidak menunggu jawaban. Dia memang tidak sedang bertanya.
Dari arah depan, Bu Diah mulai berjalan mendekat ke meja kami. Aku cepat-cepat merapikan maket, membetulkan sudut-sudutnya, memastikan semuanya presisi. Keringat dingin mulai muncul di telapak tanganku.
“Tenang aja,” bisik Dita pelan, dengan nada meyakinkan. Bukan menenangkan. Hanya mengingatkan bahwa aku tidak sendiri. Dan entah kenapa, itu cukup. Untuk hari itu, cukup. Tapi hanya sampai hari itu saja.
**
Malamnya di rumah, aku duduk di meja makan sambil menggulir layar ponsel. Mama masih di dapur, menyendok sayur bening ke mangkuk besar. Uapnya naik perlahan, memburamkan kacamatanya.
“Ayo makan dulu,” katanya sambil menaruh sendok, “nanti keburu dingin.”
Aku mengangguk, bangkit dari kursi. Tapi sebelum duduk, aku memutar ulang posisi kursi makan yang terasa miring. Lalu memutar ulang lagi. Dua kali. Tiga kali. Harus pas.
Mama melihat. Tidak bicara. Kami makan berdua. Sunyi, seperti biasa. Tapi aku tahu Mama memperhatikan. Beberapa menit kemudian, ia bertanya tanpa menoleh.
“Kamu tadi sore pulang jam berapa, Ra?”
“Jam lima. Dari studio,” jawabku singkat, mataku tetap tertuju ke nasi yang belum sempat kuaduk rata.
Mama diam sejenak. Lalu berkata pelan, “Kamu belakangan ini kelihatan... beda. Lebih sering ngulang-ngulang hal kecil. Kayak... tadi pagi, pintu udah dikunci kan? Tapi kamu naik turun ke lantai atas cuma buat ngecek lagi.”
Aku berhenti mengunyah. Jantungku berdetak lebih cepat.
“Kalau kamu capek, atau ada yang kamu takutin... Mama bisa dengar, Ra.”
Aku mengangguk pelan. Tapi tidak bicara. Tak tahu harus mulai dari mana.
Mama tidak bertanya lebih jauh. Hanya menambahkan, “Nanti coba Mama masakin wedang jahe, ya. Biar tenang badannya.”
Aku hanya mengangguk. Suara sendokku pelan menyentuh piring. Suara detik jam di dinding lebih terdengar daripada obrolan kami.
“Mama juga sering, kok. Kalau gugup, suka bolak-balik ngecek kompor,” katanya lagi, berusaha menyamakan.
Aku menunduk. Ingin menjelaskan bahwa ini... bukan sekadar gugup. Tapi aku tahu, Mama tidak bermaksud mengecilkan. Dia hanya mencoba memahami dengan cara yang ia tahu.
“Kadang... kita emang perlu lebih hati-hati, ya,” lanjutnya. “Mungkin kamu cuma lagi stres karena tugas kuliah. Biasalah, mahasiswa baru. Capek, takut salah.”
Aku menatap mangkukku. Sayur beningnya sudah mulai dingin. Tapi di kepalaku, suara-suara itu belum berhenti. Mama tak berkata apa-apa lagi. Ia bangkit, membereskan piring tanpa menoleh. Aku sempat menunggu, mungkin ia akan bertanya lebih lanjut, mungkin akan duduk kembali dan bilang sesuatu. Tapi yang kudengar hanya suara air keran dan piring-piring beradu pelan.
Ada sesuatu yang menggantung di udara. Seperti kekhawatiran. Tapi juga kebingungan. Aku tahu Mama melihat caraku menyusun sendok yang harus sejajar, caraku mengulang tutup laci tadi pagi. Tapi mungkin ia berpikir itu cuma... kelelahan. Dan aku juga belum tahu pasti. Apakah ini cuma stres? Atau cuma caraku bertahan? Yang jelas, aku hanya ingin semuanya terasa benar. Terasa aman. Terasa... terkendali. Dan mungkin, itu saja sudah cukup melelahkan.
Malam turun dengan sunyi yang berbeda. Angin dari jendela mengibaskan tirai tipis, dan lampu kamar kupadamkan setengah, cukup terang untuk melihat, tapi cukup redup untuk merasa sendirian. Aku berdiri di depan pintu kamarku. Menatap gagangnya. Lalu, kuputar perlahan. Klik. Kututup kembali. Kunci. Buka lagi. Kunci ulang. Lalu kutarik pelan, memastikan terkunci. Satu. Dua. Tiga. Entah berapa kali. Aku tahu pintu itu sudah terkunci sejak tadi. Tapi pikiranku tidak percaya. Tubuhku tidak percaya.
Kutatap tanganku yang gemetar. Jemariku merah karena terlalu sering cuci tangan hari ini. Lima kali setelah dari kampus. Dua kali setelah makan. Dua kali lagi setelah menyentuh gagang pintu luar.
Aku duduk di lantai. Bersandar ke tempat tidur. Menutup wajah dengan telapak tangan. Ini melelahkan. Lebih melelahkan dari ujian. Dari revisi maket. Dari semua tekanan dosen. Karena ini datang dari dalam. Dari pikiran sendiri. Aku menoleh ke meja. Buku jurnal kecil terbuka. Aku menuliskan satu kalimat malam itu:
"Aku takut semuanya salah kalau aku berhenti memastikan."
Lalu kuletakkan pena. Menarik selimut. Tapi sebelum benar-benar rebah, aku turun lagi dari ranjang. Mengecek ulang jendela. Memutar keran kamar mandi. Menyalakan saklar. Mematikannya lagi. Setelah semua ritual-ritual kecil itu akhirnya selesai untuk malam ini, aku berbaring. Tapi mataku tetap terbuka.
Aku teringat, di laci meja ada surat yang belum sempat kubuka sejak kemarin. Mama yang menerima dan menyerahkannya kepadaku, sambil berkata: “Dari Bara. Tadi siang dikirim lewat petugas lapas.”
Aku membuka lipatannya pelan. Tulisan tangan Bara masih seperti dulu, agak miring ke kanan, rapi tapi terkesan buru-buru.
“Nara, Kamu pasti sibuk banget sekarang. Namanya juga mahasiswi baru, semester awal memang melelahkan. Dulu abang juga gitu, sibuk banget sampai lupa kalau jadi manusia nggak harus selalu beres.
Mama bilang kamu sekarang makin rajin. Tapi kamu juga harus istirahat, Ra. Dunia udah cukup galak, jangan ikut-ikutan galak ke diri sendiri.
Abang di sini baik-baik aja. Banyak waktu buat mikir. Kadang mikir Mama, kadang mikirin Papa, dan kadang mikirin kamu… semoga kalian semua baik-baik aja ya..
—Bara”
Tanganku bergetar sedikit saat selesai membaca. Surat itu sederhana, bukan kalimat puitis, dan tidak panjang, tapi kata-katanya menyentuh, seperti ditulis oleh seseorang yang... masih menaruh bagian kecil dari dirinya di dalam rumah ini. Di dalam aku.
Aku ingin membalas. Ingin bilang: "Aku nggak baik-baik aja, Bang. Aku nggak tahu cara tenang lagi. Rasanya semua harus sempurna... biar nggak ada yang hilang lagi."
Tapi malam itu aku hanya melipat ulang suratnya. Meletakkannya kembali di laci. Dan menatap langit-langit yang terasa makin berat. Seperti segala hal di kepalaku, tak ada yang benar-benar bisa kuletakkan.


 bunca_piyong
bunca_piyong














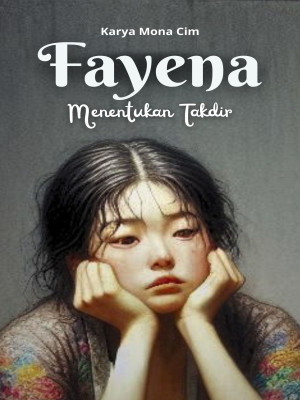



Eh eh eh eh bab selanjutnya kapan ini? Lagi seru serunya padahal.. kira-kira Nara suka Nata juga ga ya??? Soalnya kan dia anhedonia🧐 .