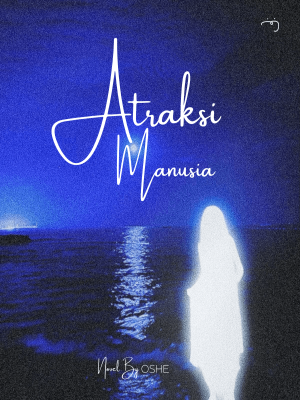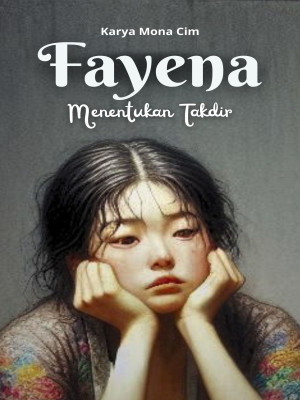Aku datang ke sekolah hari ini pagi-pagi sekali, namun rasanya sia-sia saat yang kau tunggu-tunggu tidak datang juga. Sebenarnya, tujuanku datang pagi adalah untuk bertemu dengan Boom—menanyakan kenapa dia dengan iseng menaruh surat di dalam kotak surat rumahku, dan apakah dia memang sengaja meniru tulisanku untuk mengelabuiku. Tapi rencanaku untuk menginterogasinya gagal. Dia tidak datang hingga istirahat pertama tiba. Aku bahkan sudah mencarinya ke sekeliling sekolah, termasuk ruang kesenian tempat kemarin kulihat dia bermain piano, tapi hasilnya nihil. Kemana sebenarnya anak itu pergi?
Jam istirahat aku hanya menghabiskan waktu di kelas, menyantap bekal buatan bibi Gum-gum sambil diam-diam mengamati wajah teman-teman sekelas.
"Eh, John..." panggilku pelan.
John menoleh dengan malas, wajahnya masih menempel di meja sambil membaca komik seri ke-47. Aku tidak tahu judulnya, hanya sempat melihat sampulnya sekilas.
Dia menatapku sambil mengangkat alis, mengodekan tatapan bertanya.
"Anak itu... sepertinya bukan anak asli sini, ya?" Aku memberi isyarat ke arah seorang anak laki-laki yang duduk sendirian di tengah kelas, sibuk membaca buku tebal. Dari pengamatanku, dia belum pernah terlihat berbincang dengan siapa pun.
John mengerutkan kening, lalu mengikuti arah pandanganku.
"Oh, si Brian..."
Aku mengedikkan bahu, tidak yakin.
"Anak laki-laki yang gak punya temen itu, kan? Yang matanya agak sipit dan kulitnya lebih terang dari kita semua." John tersenyum. "Dia nggak bisa Bahasa Indonesia."
"Kenapa?" tanyaku penasaran. "Dia orang asing? Tapi wajahnya kayak orang Asia... Cina, Jepang? Thailand mungkin?" aku menerka-nerka.
John menggeleng. "Nggak ada yang tahu. Dia pernah bilang kalau asalnya dari Chicago. Rumahnya yang di dekat pantai, yang paling besar. Kau tahu, kan?" jelasnya lagi.
Aku menggeleng pelan.
"Sayangnya, nggak ada yang ngajak dia ngobrol," lanjut John.
"Nggak ada yang pernah nyoba?"
"Pernah. Tapi dia kayaknya nggak ngerti yang kita omongin. Bahasa Inggris kita juga jelek, kecuali dua anak itu." Dia menunjuk ke arah depan, ke Kenan dan Nube.
Nube sempat menoleh, menyadari dirinya disebut, tapi ia kembali fokus mengerjakan tugasnya. Kenan tidak tampak, dia memang jarang ada saat istirahat.
"Tapi mereka juga nggak pernah ngobrol sama Brian."
Aku mengangguk.
"Bagaimana Bahasa Inggrismu?" tanya John.
Aku mengangkat bahu. "Tidak yakin..."
John mengangguk dengan senyum jahil. "Nggak mau nyoba nggodain? Siapa tahu dia tertarik sama kamu."
Aku memelototinya. "Ih, nggak, makasih."
"Padahal dia cakep, lho. Jujur aja, walaupun aku cowok, aku akui itu. Anak perempuan biasanya suka sama yang cakep. Kalau kamu tertarik, aku bantu deh."
Dia tertawa, lalu kembali tenggelam dalam komiknya.
Setelah obrolan tak penting itu, aku menyentuh surat di dalam laci dan bersiap kembali mencari Boom. Tapi sebelum aku sempat berdiri, Nube sudah memergoki gerak-gerikku.
"Eh, eh! Mau ke mana kamu?" tanyanya tajam, nada suaranya mencurigai.
"Ke toilet," jawabku cepat sambil menyelipkan surat ke saku rok.
"Jangan sampai ketinggalan bel, ya!" dia memperingatkan.
Aku hanya mengangkat dua jariku membentuk simbol OK, lalu melangkah cepat ke luar.
Sekarang aku harus menemukannya.
Kenapa aku begitu ingin bertemu dengannya?
Aku berjalan menyusuri lorong-lorong sekolah, menyempatkan diri memeriksa beberapa ruangan kosong—laboratorium, gudang perlengkapan, bahkan taman kecil di belakang aula. Setiap sudut seolah berkonspirasi menyembunyikan sosok yang kucari. Nafasku sedikit tersengal. Langkahku membawa ke arah bangunan sisi timur yang jarang dipakai, tempat ruang seni lukis berada.
Ruang itu tampak sepi, tapi pintu gesernya sedikit terbuka. Aku melongok ke dalam.
Ruangannya tenang dan lengang. Dindingnya dipenuhi rak cat minyak, kuas, dan kanvas besar. Aroma khas minyak linseed menyergap hidung. Cahaya siang hari masuk dari jendela tinggi, menerangi sosok yang berdiri di depan kanvas besar.
Dia.
Boom.
Dia berdiri dengan punggung menghadapku, kuasnya bergerak pelan seolah sedang merangkai kenangan yang ingin ia abadikan. Satu-satunya suara hanyalah desir kuas di atas permukaan kanvas.
Aku berdiri di ambang pintu, hatiku berdebar. Dia berhenti, lalu menatap pantulan diriku lewat cermin besar di sisi ruangan.
Senyum tipis terbit di wajahnya. Ia tidak mengatakan apa-apa seolah tidak terkejut melihatku berdiri di sana—seolah memang sudah sewajarnya aku mencarinya.
Aku melangkah masuk, menahan rasa kesal yang menggelayut. Aku mengangkat surat itu tinggi-tinggi.
"Ini punyamu, kan?" tanyaku ketus.
Dia tetap membelakangiku, tangannya tak berhenti menggerakkan kuas di atas kanvas. Suaranya terdengar datar, seolah keluar begitu saja tanpa emosi. "Merindukanku?"
Aku mendengus jijik, menyodorkan surat itu ke arahnya. "Kau sengaja menaruh ini di kotak suratku? Meniru tulisanku? Apa kau pikir ini lucu?"
Dia mengambil surat itu dengan tenang, membuka lipatannya. Di dalamnya ada foto kue tiramisu, dengan latar jendela dan hujan.
"Tiara yang mengirimkan ini, bagaimana ini bisa denganmu?" gumamnya.
"Omong kosong! Kau cuma meniruku! Kau pikir aku tidak sadar? Aku tidak kenal kau! Jangan sok dekat!"
Dia menatapku lama, lalu meletakkan kuasnya. Tapi bukan untuk menjawab pertanyaanku, malah melangkah mundur, mengambil posisi baru di depan kanvas. Gerakan tangannya seolah ingin melanjutkan lukisan, tapi kemudian terhenti lagi.
"Hei!" panggilku dengan tegas. Dia menghentikan gerakannya.
"Kau memanggilku?" tanyanya pelan, masih tak menoleh.
"Memangnya siapa lagi yang ada di sini?"
"Ada apa lagi?"
"Memangnya Tiara yang kau maksud itu tinggal di rumahku?"
"Aku tidak tahu, kami saling mengirimkan surat—"
"Apa yang kau tahu tentang Tiara?" potongku.
Dia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Seorang gadis yang penuh percaya diri dan membuatku percaya dengan mimpiku."
Aku tertawa meremehkan.“Kau sedang mencoba mengejekku, kan? Kau menggoda agar aku tertarik denganmu? Karena aku tuli, dan kau ingin menarik simpati dariku, kan?”
"Kau sedang mendengarkan aku bicara, kan? Kau pikir itu yang disebut dengan tuli? Jika kau tidak merasa mengirimkan surat itu, kau bisa meninggalkan aku sendiri sekarang." Nada suaranya tak kalah dingin dari nadaku.
Aku menghela napas kesal. "Apa yang kau inginkan sebenarnya dariku?"
Dia terdiam, mencoba mengabaikanku, dan kembali ke lukisannya.
Dia menatapku lama, lalu meletakkan kuasnya. "Kalau kau bukan Tiara yang kumaksud, seharusnya kau tak perlu merasa tersinggung."
Aku mengepalkan tangan. "Kau pelukis?" fokusku teralihkan melihat gambarannya yang belum begitu jadi, tapi abstrak, entah apa yang akan dia gambar.
Dia tidak menjawab langsung. Hanya meletakkan kuasnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tiara yang kukenal... Penuh percaya diri. Dia membuatku percaya pada mimpi. Kalau kau memang dia, dia berbeda berbeda denganmu, dan seharusnya dia tahu siapa aku."
Aku mengerutkan kening, tersinggung oleh ucapannya. "Penuh percaya diri? Kau yakin kau sedang bicara tentangku sekarang?" tanyaku, suaraku terdengar getir. "Aku bahkan belum bisa menerima kenyataan kalau aku... seperti ini."
Dia menghela napas pelan, tetap menatap lukisannya. "Kau bisa meninggalkan aku sendiri sekarang—mungkin aku hanya bertemu dengan doppelganger-mu," katanya lirih.
Doppelganger?
Aku membeku. Kata itu asing. Tapi nadanya membuatku tidak nyaman. Kenapa dia tiba-tiba begitu dingin padaku? Setelah berhari-hari dia muncul begitu saja di hadapanku, mengikutiku dengan ekspresi yang sulit diartikan, sekarang dia bersikap seolah aku ini bukan siapa-siapa.
Apa mungkin benar aku tidak sesuai harapannya dan akhirnya dia menyerah? Kalau begitu... mungkin memang lebih baik seperti ini.
***
Bel sudah berbunyi, dan saat aku kembali ke kelas, aku mendapati papan tulis penuh dengan daftar kelompok. Namaku tidak ada di sana, namun nama John dan Nube sudah tertulis dengan kelompok yang berbeda.
Nube langsung menghampiriku saat aku masih berdiri terpaku di dekat loker belakang kelas.
"Oh, maafkan aku, Tiara. Aku berusaha keras agar kamu masuk ke dalam kelompokku, tapi mereka sudah menyerahkan daftar nama ke Pak Sam. Katanya, kalau nama sudah dikumpulkan, nggak bisa diubah lagi." Nube tampak menyesal. "Sayangnya John juga begitu. Kami berdua tadi nyari kamu waktu kelas mulai, tapi Pak Sam juga nggak ada... tiba-tiba nama kami sudah dimasukkan oleh teman-teman. Sekarang kita cuma disuruh diskusi menentukan tugas kelompok masing-masing."
Aku mendengus pelan. "Tugas apa?"
"Praktikum kesenian. Bebas mau tampilkan apa, asal kerja sama tim."
Aku mengedikkan bahu. "Siapa saja yang belum punya kelompok?"
"Ku pikir... kamu, Misno, Brian... dan entah siapa lagi. Aku nggak terlalu hafal nama sekelas. Maaf, ya."
"Misno yang mana?" tanyaku.
"Anak laki-laki yang duduk paling depan dekat pintu masuk. Yang rambutnya kayak tentara."
Aku menoleh. Ya, aku mengenali dia. Duduk tegap dan... hampir tidak bergerak.
"Dia dijuluki 'hantu kelas'. Jarang bicara. Serem juga. Maaf, tapi kayaknya kamu bakal masuk kelompok aneh-aneh."
Aku menatap punggung Brian, yang duduk diam sambil membaca. "Sepertinya aku bisa mengatasi kalau Brian."
"Tapi aku nggak yakin kamu bisa hadapi yang ini." Nube mengisyaratkan ke dua kursi kosong—tempat yang kemarin sempat ditempati Boom.
"Kenapa?"
"Kami bahkan nggak yakin dia murid tetap di kelas ini. Nggak tahu nama lengkapnya, asalnya, atau kapan tepatnya dia mulai masuk. Dia... misterius."
Aku menghela napas. Sebenarnya aku sudah cukup putus asa. Haruskah aku mengerjakan tugas ini bersama mereka—anak-anak yang tampak terabaikan?
"Baiklah... Akan kuurus. Kapan daftar kelompok terakhir dikumpulkan?"
"Sebelum pulang sekolah."
Aku memutuskan untuk mulai dari Brian. Tapi sebelum aku sempat menghampirinya, dia sudah menoleh dan melambai pelan ke arahku.
Do you have a team for exam? tanyanya dengan lirih dari kejauhan sambil memeluk tas.
Aku menggeleng. Dia mengangguk.
Kami jadi satu kelompok. Tersisa kami bertiga—aku, Brian, dan Misno. Dan seperti lelucon, ternyata hanya kami bertiga yang belum punya kelompok dan entah siapa satunya lagi, apa mungkin itu Boom?
Saat istirahat, Brian menghampiriku. "Misno?" tanyanya sambil mengangguk ke arah anak itu.
"Terserah," jawabku. Brian tersenyum.
"Ya, aku Brian," katanya lagi, duduk di bangku depan mejaku—yang biasanya ditempati Kenan. Nube mengintip dari bangkunya, tampak antusias. John hanya melirik sebentar lalu kembali membaca.
"Kamu anak baru, ya?" tanya John tiba-tiba, terkejut karena Brian mulai bicara.
Nube bahkan mendekatkan kursinya ke Brian. "Kau bisa bahasa Indonesia?" bisiknya nyaris tak terdengar.
Brian mengangguk pelan.
"Tapi kenapa nggak pernah bicara dengan kami?"
"Kalian nggak pernah ajak aku bicara pakai bahasa kalian. Aku nggak ngerti apa yang kalian tanya," jawab Brian pelan, dengan aksen asing yang khas.
"Maksudnya, bahasa Inggris kalian buruk," selaku sambil meledek.
"Aku nggak bilang begitu," sahut Brian cepat.
"Tapi kenapa nggak pernah bilang kalau kau nggak ngerti?" tanya John, sedikit kesal.
"Semua mata menatapku... seperti menghakimi. Aku nggak suka jadi pusat perhatian. Aku harap kalian ngerti."
Akhirnya mereka mengerti. John dan Nube meminta maaf. Mereka bahkan berjanji akan lebih baik padanya.
Setelah suasana mencair, Brian mengajakku mencari anggota keempat. Kami mencari anak laki-laki misterius yang sempat masuk kelas tadi dan langsung keluar dengan tas olahraga. Setelah bertanya pada beberapa teman, kami tahu dia sedang ada di lapangan.
Ternyata dia bukan Boom. Aku bahkan tidak tahu Boom masuk di kelompok mana, jangankan itu nama aslinya saja aku tidak tahu. Bahkan untuk memastikan dia sekelas denganku apalagi.
"Leo, mau masuk kelompok kami?" sapa Brian langsung saat kami menemukannya sedang berdiri di tepi lapangan, mengamati teman-temannya bermain bola.
Leo menatap kami. "Menurutmu aku mau?"
"Setidaknya kita selesaikan administrasinya dulu," kata Brian terbata.
Leo mengangguk santai acuh tak acuh sambil fokus dengan kegiatannya. Kami akhirnya punya empat orang.
Tinggal satu lagi: Misno.
Kami langsung menuliskan namanya tanpa persetujuan. Saat diberitahu, dia hanya menjawab singkat, "Ya."
Misno, anak paling kalem. Tidak pernah bicara kecuali ya dan tidak. Tidak pernah bereaksi. Sejujurnya, aku tidak yakin dia bisa diandalkan, tapi... sudah terlanjur.
Dari semua, Brian yang paling antusias. Meskipun kesulitan bahasa, dia aktif berdiskusi denganku. Kami mulai saling bertukar cerita.
Brian ternyata keturunan Korea- Indonesia, lahir di Kanada. Dia tinggal di pulau ini karena mengikuti ayahnya yang bekerja sebagai insinyur di proyek pembangunan tangki kilang minyak—pekerjaan yang membuat mereka berpindah-pindah dari satu daerah terpencil ke daerah lainnya. Desas-desus bahwa dia berasal dari Chicago ternyata salah. Dan meski belum lancar berbahasa Indonesia, dia diam-diam jadi idola karena wajahnya yang rupawan dan senyum hangatnya.
Tapi justru karena keterbatasan komunikasi itulah, dia sering dihindari untuk kerja kelompok.
Kini, temanku pulang sekolah bukan hanya Nube, tapi juga Brian. Dia menceritakan betapa selama ini dia tidak punya teman bicara. Anak-anak terlalu cepat menilai hanya dari penampilannya.
Hari itu, Nube mengajakku lagi ke kedai kue yang kami datangi kemarin, katanya untuk merayakan Brian yang akhirnya "punya teman" sejak datang ke pulau ini.
Saat kami tiba, aku refleks melihat ke arah pintu. Boom. Namanya langsung muncul di benakku. Entah kenapa.
“Sepertinya cuaca cerah sampai nanti sore, mau duduk di balkon saja?” usul Nube.
Kami menyetujui. Kami memesan roti manis dan minuman favorit kami masing-masing. Brian memilih coklat panas. Aku dan Nube memesan es cappuccino.
Beberapa siswa SMA lain juga singgah, memilih nongkrong sejenak sebelum pulang.
"Pernah dengar istilah 'Doppelganger'?" tanyaku tiba-tiba.
Nube mengerutkan kening. Brian mengangguk.
"Itu seperti kembaran kita yang hidup di dunia ini. Katanya, kalau kita melihat doppelganger, itu pertanda buruk," jelas Brian.
"Aku... membacanya sekilas di perpustakaan," kataku, berbohong.
Benarkah Boom melihat kembaranku? Atau... semua ini lebih rumit dari yang kubayangkan?
Ayah tiba-tiba menelepon. Menyuruhku pulang lebih cepat. Katanya, jangan lama-lama di luar.
Aku pamit pada Brian dan Nube, lalu turun ke lantai satu. Saat membuka pintu kedai, aku nyaris bertabrakan dengan seseorang—Kenan. Dia hanya menatapku sekilas, lalu pergi begitu saja. Kami tidak saling menyapa.
Dalam perjalanan pulang, aku melihat berbagai aktivitas desa. Anak-anak naik sepeda, marching band latihan di lapangan sepak bo;a, dan suara seruling dari rumah panggung tua.
Sesampainya di rumah, aku disambut Ayah, Bibi Gum-gum, dan Paman Hendra. Meja makan dipenuhi ikan bakar besar, sambal tomat, dan aroma sedap.
Setelah makan, Ayah memberikanku kotak kecil. Alat bantu dengar baru.
Aku berterima kasih, lalu pamit naik ke kamar. Di balkon kamar, aku menikmati matahari terbenam yang lambat di pulau ini.
Saat malam turun, aku menulis di buku harianku. Tentang Boom. Tentang surat. Tentang hari-hari ini.
Mataku tertumbuk pada walkman-ku. Aku menyalakannya, dan suara yang mengalun membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Lagu itu... seperti membawa kembali serpihan memori yang sudah lama terkubur. Aku menutup mata, mencoba mengingat.
Dulu, aku sering menunggu surat datang dari seseorang. Seorang teman pena yang tidak pernah kutemui, tapi rasanya seperti mengenalnya begitu dalam. Kami saling bertukar cerita, berbagi mimpi, dan menyemangati satu sama lain lewat tulisan-tulisan panjang. Aku selalu menunggu-nunggu surat darinya di kotak pos rumah. Tapi, semua berhenti tiba-tiba—tepat setelah kecelakaan itu.
Sejak aku kehilangan pendengaranku sebagian, dan duniaku berubah, surat-surat itu pun berhenti datang. Awalnya kupikir dia hanya bosan. Tapi lama-kelamaan aku menyadari, mungkin akulah yang pergi lebih dulu tanpa pamit. Meninggalkan tanpa bisa menjelaskan.
Kini, suara dalam lagu itu—potongan nada yang terputus—seolah memanggil kembali serpihan diriku yang lama hilang. Ada sesuatu yang mengetuk kesadaranku—pelan, namun tak bisa diabaikan.
Aku segera melepaskan earphone dan mulai mencari kotak kardus tempat buku harian lama kusimpan.
Aku menemukannya. Membuka salah satu buku tahun 2011. Di sana ada nama yang sudah lama tak kuingat.
Noah...
Nama itu menempel di sudut-sudut halaman yang lusuh. Bukan hanya satu kali, tapi berulang. Saat itu aku menuliskan banyak hal tentang seseorang bernama Noah. Kegiatan kami berkirim surat, tentang impian kami, tentang pertunjukan yang ingin kuhadiri dengannya. Bahkan, aku masih ingat dia pernah bilang akan ikut audisi seni di kota—katanya, itu hadiah kecil yang ingin dia persembahkan untukku. Hari ketika dia berjanji akan datang... adalah hari di mana semuanya tiba-tiba hancur karena kecelakaan itu. Semuanya terasa begitu hangat dan nyata.
Aku menatap tulisan tanganku dengan jantung berdegup kencang.
Boom... apakah mungkin? Jangan-jangan... dia Noah?
Aku tidak lupa. Aku hanya menyimpannya terlalu dalam. Tapi sekarang, sesuatu dalam diriku... bangkit, menuntut untuk diakui.
Aku menutup buku harianku perlahan, seolah bisa menghentikan gelombang yang datang. Tapi tidak. Ini bukan sekadar kenangan. Ini adalah bagian dari diriku yang selama ini kutolak untuk kuakui—bagian yang memegang kunci pada semua yang tak selesai.
Aku menarik napas panjang. Kali ini, aku tak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Jika Boom memang Noah... maka aku harus bertanya, harus tahu. Dan mungkin... harus berani mengingat semuanya dengan jujur.
Aku buru-buru memakai jaket, pamit ke Ayah dan Bibi. Kataku, aku akan ke rumah Nube.
Padahal aku tidak tahu ke mana akan pergi.
Langit malam kelam. Angin dari laut menusuk.
Di taman bermain tidak jauh dari rumahku, aku melihat sepedanya.
Aku menemukannya. Duduk sendirian di pondok kecil, menghadap laut. Wajahnya hanya tampak dari samping, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat langkahku terhenti. Bukan karena aku mengenalnya. Aku tidak mengenal Boom. Tapi... bagaimana jika dia adalah orang yang sama? Bagaimana jika dia adalah Noah?
Nama itu, Noah, perlahan muncul kembali—tidak dengan gegap gempita, tapi seperti embusan angin yang menggerakkan sesuatu yang selama ini diam dalam diriku. Teman suratku yang tak pernah kutemui, tapi terasa begitu dekat. Seseorang yang berjanji akan datang... pada hari yang justru menjadi hari paling kelam dalam hidupku.
Aku pernah menyangkalnya. Pernah meyakinkan diriku sendiri bahwa Boom bukan siapa-siapa, hanya anak aneh yang suka mencampuri hidupku. Tapi sekarang, dengan diamnya yang terasa begitu familiar, aku tak bisa tidak bertanya—bagaimana jika benar dia adalah orang yang sama?
Apa dia tahu tentang kecelakaan itu? Tentang surat-suratku yang tak pernah kukirim lagi? Apa dia tahu bahwa aku bukan menghilang karena bosan, tapi karena patah?
Aku berdiri di sana, terdiam. Satu langkah memisahkanku dari kebenaran yang mungkin selama ini sudah berdiri tepat di hadapanku. Tapi aku belum siap. Atau mungkin... aku terlalu takut untuk tahu jawabannya.
"Noah..." bisikku lirih. Hanya seperti suara angin yang menyentuh daun.
Aku tak punya keberanian lebih. Karena jujur saja, meski aku mengingat surat-surat itu, aku juga harus mengakui satu hal penting—aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung sebelumnya. Semua yang kutahu tentang dirinya berasal dari kertas dan kata-kata. Tapi saat ini, jika dia benar-benar Noah, maka hari ini aku melihatnya untuk pertama kalinya. Dan rasanya... seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang hilang.
Aku hanya berdiri di tempatku.
Setengah jam berlalu, aku belum beranjak. Aku hanya memandanginya dari kejauhan, sementara angin laut terus bertiup dan langit malam menggantung sunyi di atas kepala kami. Dia juga tak bergerak, tetap duduk di sana. Keheningan itu terasa dalam, seperti kami saling berbicara lewat diam.
Aku sangat ingin menyapanya. Mendekatinya perlahan dan berkata, "Aku ingat sekarang. Aku yang menulis semua surat itu. Aku yang menunggu."
Dan aku... sangat ingin mengenalnya.
Tapi yang lebih membuat dadaku sesak adalah kenyataan bahwa sebelumnya aku telah menyakitinya. Kata-kata kasarku waktu itu—di ruang seni, ketika aku menuduhnya mempermainkanku, ketika aku menyebutnya cowok kampungan dan peniru—semua kembali terputar di kepalaku seperti gema yang tak henti.
Dan anehnya. Belakangan ini, dunia ini terlalu sunyi untuk didengar dengan benar—semua suara mengambang seperti bayangan di balik kaca.
Tapi suaranya... menembus batas itu. Ia tak mengetuk dari luar, tapi seperti muncul dari dalam, dari sesuatu yang telah lama tertidur dan menolak dibangunkan.
Mengapa hanya suaranta yang bisa ku dengar dengan jelas?
Kadang aku bertanya-tanya, apakah dia berbicara dalam bahasa yang dulu pernah kumiliki? Bahasa yang kini bahkan aku sendiri tak lagi mengerti?
Atau mungkin... dia bukan datang untuk didengar, tapi untuk mengingatkan. Bukan tentang siapa dia, tapi tentang siapa aku, sebelum semuanya hancur.


 tavxoc
tavxoc