Jiwa Soya seperti mengambang. Dibilang melayang pun juga rasanya belum sejauh itu untuk meninggalkan raganya di sekolah, di sudut ruang serbaguna yang masih disinari lilin-lilin hangat. Ia terperangkap di sini, di antara orang-orang yang bersukacita karena berhasil mendaftarkan teater Layar Surya ke ... ke apa, tadi? Lomba?
Jangankan mengikuti lomba, Soya saja merasa diperangkap untuk menjadi penggenap anggota Layar Surya!
Ia ingin menolak. Ingin sekali. Namun, nasi terlanjur menjadi bubur. Namanya telah tercatat sebagai anggota Teater Layar Surya untuk lomba entah kapan.
“Pak?” lirih suara Soya kala menghampiri punggung Sastra. “Pak. Saya mau ngomong.”
Ia kira suaranya terlalu pelan untuk didengar, apalagi ketika kawan-kawannya sibuk membicarakan drama apa kiranya yang bakal mereka bawakan. Namun, Sastra mendengarnya. Pria itu berbalik badan dengan alis terangkat.
“Boleh!” senyum yang tersungging di bibir beliau membuat Soya merasa tidak nyaman. Tidak pernah ia melihat Sastra tersenyum secerah ini, bukan tawa mencemooh seperti yang pernah diterima Soya dua kali.
Alih-alih menuju lorong, Sastra menggiring Soya ke arah panggung auditorium. Cewek itu mengikuti dengan langkah berat. Mengapa kemari? Memang, sih, keriuhan kawan-kawannya tidak seberapa terdengar di sini dibanding lorong luar, tapi ... melihat hamparan aula dengan ratusan kursi yang belum ditumpuk membuat Soya gugup. Ia membayangkan ratusan orang tua dari acara pembagian rapor lalu duduk di sana, sementara ia dan Sastra menaiki panggung. Bayangan itu cukup untuk membuatnya berkeringat dingin.
“Pak.” Suara Soya serak, gugup oleh kursi-kursi kosong. “Kayaknya saya ....”
“Kamu berani, loh, Soya.”
Ucapan Sastra membuatnya terperanjat. Apa ia tidak salah dengar?
“Gimana rasanya membela diri? Lega?” Sastra bertanya lagi dengan senyum lembut. Gurat-gurat halus bertebaran di wajah berusia awal empat puluhan itu, melengkapi cambang halus yang belum dicukur selama seminggu terakhir. Soya curiga Sastra adalah tipe pria yang hanya bercukur karena peraturan sekolah menghendakinya begitu.
“Lega?” Ketika suaranya sekarang gemetaran, dan ia benar-benar butuh membasahi tenggorokannya dengan air?
“Tenggorokan saya sakit, Pak.” Soya menelan ludah bulat-bulat. “Saya nggak pernah—hampir nggak pernah, teriak kayak gitu.”
Meski, Soya yakin, teriakannya tadi tidak seberapa keras. Barangkali hanya berupa lengkingan spontan. Tidak seheboh seorang pemimpin upacara.
Namun, Sastra hanya menggeleng pelan sambil terkekeh. Bukan tawa yang mencemooh. “Tahu, nggak? Nggak semua orang bisa membela diri bahkan setelah dewasa. Malah ada yang lebih milih lari. Kabur, karena mengira udah tahu bakal kalah.”
Soya mengernyit. Apa Sastra baru saja mengimplikasi bahwa dirinya hampir kalah terhadap Juni?
“Juni yang ngerekam saya duluan tanpa izin, Pak.” Tangannya terkepal. “Saya ... saya nggak suka direkam.”
Itu berarti, ia juga tidak suka tampil di panggung. Baca naskah di depan kelas saja tidak mampu. Kenapa ia malah terdaftar sebagai penggenap peserta lomba teater?
“Betul, Soya. Kamu nggak salah. Tapi, Juni juga nggak salah—dari kacamatanya—karena itu kebiasaan dia.” Kala Soya membeliak, Sastra melanjutkan dengan senyum-senyum. “Juni nggak akan tahu kalau perbuatannya juga salah, sampai kamu berani bersuara. Dan, itu, yang nggak semua orang dewasa bisa lakukan. Mereka lebih memilih bungkam. Kabur. Padahal masih ada satu kesempatan untuk membela diri.”
Soya tercenung. Dia lebih ingin minum air daripada mendengarkan ceramah Sastra. Intinya guru itu baru saja mengapresiasinya. Mengherankan, mengingat Sastra pernah menertawakannya, tapi pria itu sendiri adalah sosok yang aneh.
“Saya ... saya nggak bisa ngomong, Pak,” ujarnya kecut. “Baca naskah di depan kelas aja saya nggak sanggup. Yang tadi pun, kalau nggak karena kepaksa, saya ....”
Sastra mengayunkan tangan ke arah ratusan kursi kosong. “Teater bisa bantu kamu ngomong, Ya.”
“P-Pak, saya gugup!”
“Gugup karena apa? Ditertawakan? Salah ngomong?” Sastra menghampirinya, mendaratkan tepukan keras di bahu Soya. “Hanya di teater, kamu ditertawakan karena memang kamu bertugas menghibur mereka. Hanya di teater, kamu nggak akan disalahkan kalau keliru ngomong, karena mereka mengira itu bagian dari aktingmu. Dan, mereka cuma jadi penonton. Yang tugasnya mendengarkan kamu, bukan menilai kamu.”
Soya ingin membalas, tetapi tak ada kata-kata yang terpikirkan. Bahkan hingga Sastra berlalu, lantas kembali lagi dan menaruh sebotol air mineral di kepala Soya, dan pergi untuk kedua kali.
Sebelum botol itu meluncur jatuh dari kepalanya, Soya menangkapnya dengan cepat.
Kembalinya Soya ke ruang serbaguna bukan berarti ia setuju untuk jadi peserta lomba. Meski begitu, otaknya sudah memikirkan berbagai kemungkinan. Bukankah jadi panggung tak melulu tentang tokoh utama? Siapa tahu nanti Soya hanya perlu jadi pohon atau kelinci yang melompat-lompat. Ia ingat pernah jadi manusia pohon di ujian praktek Bahasa Indonesia saat kelas enam dahulu.
Toh, Sastra juga pernah bilang bahwa Soya bisa jadi penata artistik, alias tukang menata dekorasi. Walau, tampaknya Daru ingin lebih dari itu.
“Yuk, kumpul. Duduk semua.” Sastra menepuk tangan kala ruang serbaguna kembali sesak. Pancaran lilin menunjukkan senyum lebarnya yang tak kunjung redup. “Karena masalah pendaftaran lomba udah beres, kita kesampingkan dulu soal itu. Hari ini kita bahas kepengurusannya. Juni?”
Juni memberenggut. Ia beranjak dan mengarahkan kamera ponselnya ke ruangan, tanda merekam. Soya, yang duduk memeluk lutut di pojok ruang, mengatupkan bibir rapat-rapat. Ternyata itu kebiasaan karena disuruh Sastra sendiri.
Kaspian perlahan bergeser ke samping Soya, ikut menyandarkan punggung ke dinding berpenutup kain hitam.
“You okay, Ya?” bisiknya.
Soya butuh mencerna beberapa detik dulu maksud pertanyaan Kaspian, lantas mengangguk.
“Nggak terpaksa, kan?”
Soya mulai bimbang dengan arah pembicaraan tersebut. Semula ia mengira ini tentang Juni, tetapi tampaknya Kaspian menanyakan perkara gabungnya ia ke ekskul. Bagaimana pun, mereka pernah mengumpati Sastra bersama di kafe.
“Aku ... bakal bohong kalau bilang nggak.”
Kaspian menggumamkan pembenaran. “Seenggaknya kamu nggak sendirian.”
Soya menekuk wajah. “Kamu yang nggak sendirian.”
Kaspian terkekeh pelan. Alih-alih menjawab, ia mengulurkan tangan. Soya menjabatnya dengan malas-malasan.
“Oke!” Sastra menepuk tangan sekali lagi, begitu bersemangat sampai-sampai api lilin terdekat bergoyang mengancam. “Ketua kita tetap Kas, wakilnya Nova, sementara Juni sebagai sekretaris. Daru dan Soya, ada yang mau jadi bendahara?”
Daru mengangkat tangan. “Saya biasa bantu Mbah hitung duit tiap hari, Pak.”
“Lolos!” Sastra mengangguk puas, sementara Soya memandang punggung kawannya itu penuh keheranan.
Ia tidak tahu kalau Daru bisa bersemangat soal teater.
“Selanjutnya ... penanggung jawab tiap divisi.” Sastra mengucapkannya seolah sudah lama menantikan ini. “Karena selama semester lalu anggotanya hanya tiga, jadi anak-anak ini kewalahan menanggung banyak peran.”
Kaspian berceletuk, “Nggak ngapa-ngapain juga.”
Sastra memelotot padanya. “Nah. Kebetulan kita sudah daftar lomba, jadi kita punya kegiatan resmi. Juni, kemarin siapa pegang divisi apa?”
“Juni pegang divisi properti dan dokumentasi, Pak.” Cewek itu senantiasa memutar ponselnya untuk merekam ruangan, padahal penerangannya temaram. “Kas sebagai koordinator produksi. Nova divisi akting dan artistik.”
Sastra menjentikkan jari. “Soya memegang bagian tata artistik. Nova, temannya dibimbing.”
Kala Nova menoleh ke arahnya dan menyunggingkan seringai, Soya hanya membalas dengan ringisan canggung.
Kaspian mengembuskan napas. “Untung ada kamu.”
“Kenapa?”
Alih-alih menjawab, Kaspian hanya menggeleng, membuat cewek itu bertanya-tanya. Namun, tanpa Kaspian menelurkan pendapat misterius pun, sudah banyak pertanyaan yang berkelebat di benak Soya.
“Kenapa bukan kamu yang pegang divisi akting?” tanyanya sambil berbisik. “Kan kamu dulunya aktor cilik?”
Ekspresi Kaspian mengeras. “Bukan berarti aku harus megang divisi itu, kan? Buktinya aku ketua.”
“I-iya.” Soya merasa salah bertanya, maka buru-buru ia mengganti topik. “Ng, soal Juni ... casing hapenya ....”
Ekspresi cowok itu melunak, walau kernyitan di dahinya masih bertahan samar. “Nggak usah khawatir,” katanya, sambil mengerling ke arah Soya, memastikan ekspresi kawannya yang tampak tertekan 24/7. “Nanti aku bicarakan ke Juni.”
“Maaf ngerepotin.” Soya memilin ujung bajunya dengan gugup. Padahal bukan itu yang sebenarnya ia inginkan. Ia ingin tahu apakah ia mesti mengganti casing ponsel Juni atau tidak, tapi bantuan Kaspian juga tidak buruk.
Omong-omong, ini membuatnya jadi makin penasaran. “Kalian ... pacaran?”
Kaspian mendengus, seolah berusaha menahan tawa. “Kamu udah orang keseratus yang tanya gitu. Nggak. Kita cuma tetangga. Kebetulan mamanya Juni sering nitipin dia ke mamaku.”
Bibir Soya tersingkap membentuk huruf ‘O’. Sekarang ia paham mengapa Kaspian dan Juni duduk bersebelahan di kafe kala itu. Kaspian tegang karena sedang menghadapi ibunya sendiri. Juni senyam-senyum karena ibu Kaspian jelas takkan mengomelinya. Plus, melihat kawan sendiri dimarahi orang tua itu bisa menjadi hiburan.
Soya baru saja membuka mulut, tetapi suara Juni menyeruak. “Sst! Anak baru diem!” Matanya memelotot ke arah Soya, desisannya masih mengandung dendam dari kejadian sebelumnya.
Sastra tersenyum masam. “Juni, ayo, pilih mau relakan divisi yang mana untuk dipegang Daru.”
Dari balik ponselnya, Juni mencebik. “Dokumentasi, dong! Kecuali Daru udah punya pengalaman merias lebih lama daripada aku!”
Daru menggaruk kepalanya yang tidak gatal. “Tapi ... aku nggak punya kamera atau hape bagus.”
“Juni, nanti pinjamkan ke Daru, ya?”
“Merepotkan. Iya, deh.”
Sastra tak pernah terlihat lebih senang daripada saat ini. Sambil menepuk tangan untuk kesekian kali, ia berkata, “Terima kasih, anak-anak! Dengan ini, Teater Layar Surya sudah bisa dijalankan lagi!”


 andywylan
andywylan








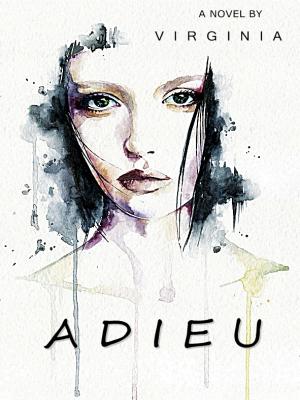

Haruskah kita bertemu lagi dengan efis---
Comment on chapter Prolog: Ambang Batas