Semestinya Soya makan satu mangkuk sambal bakso, bukan sesendok saja.
Ia berharap sakit tipesnya tidak sembuh secepat ini. Lebih parah, kalau bisa. Dioperasi ususnya sekalian tidak mengapa. Asalkan satu: ia tidak perlu berbicara di depan kelas.
Ia ingin ambruk.
Pingsan.
Kalau bisa, dan fisiknya mampu, Soya bakal melompati meja-meja kayu itu, menerjang jendela yang terbuka, dan lompat dari lantai dua. Namun, ia tahu di sisi kanan bangunan adalah pagar dengan juntaian semak-semak kembang sepatu yang disayang Ibu Kepala Sekolah. Ketahuan mencabut satu daun dihukum lari tiga putaran keliling lapangan. Mencabut satu bunga dihukum jadi pemimpin upacara pada Senin mendatang.
Yah. Soya tak mau mengambil risiko merusak sepetak semak-semak. Apa jadinya ia nanti?
“Ayo, Ya!” teguran Sastra membuat Soya melonjak kaget. Lembar pertama dari bendelan di tangannya hampir lecek. Itu naskah Siti Nurbaya. Hari ini, pada penghujung pertemuan pelajaran Sastra Indonesia di semester ganjil, Soya tahu-tahu dipilih untuk membacanya.
Mata Soya terasa lebih basah daripada biasanya saat menatap dua puluhan wajah yang tengah menanti. Dua puluhan pasang mata yang tatapannya menghunjam kepadanya. Cara Sastra melipat tangan juga tidak membantu. Bersandar di dinding belakang kelas, Soya mampu melihat ujung sepatu beliau mengetuk-ketuk tidak sabar.
“K-kira-kira pukul satu siang ....” Ia mengawal, suaranya tersendat dari gigi yang terkatup. “Kelita ... eh, kelihatan ... dua orang anak muda—“
“Kurang keras!” sahut teman sekelasnya yang duduk paling belakang. Dengan badan segempal itu, ia tidak kesusahan berseru dengan lantang.
Soya berusaha mengencangkan suara, tetapi dentam jantung membuat kata-katanya meluncur dengan gemetaran. “Ber ... bernaung di bawah pohon ketang—ketapang yang rindang ....”
Gadis yang duduk tepat di depan Soya menghela napas keras-keras. Nova namanya. “Aduuh, kalau bacanya gitu terus, dua jam nggak selesai-selesai, nih!”
Tahu-tahu Nova beranjak. Ia menyambar naskah di tangan Soya dan menyikutnya. “Duduk aja, sana,” ujarnya, lantas berbalik menghadap kelas. “Pak Sastra! Saya aja yang bacain, ya!”
“Kamu tuh, bisa-bisanya! Siapa yang suruh gantikan Soya?” Meski begitu, Sastra tidak tampak marah. Ia terbahak-bahak. “Udah kelas sebelas masih nggak bisa baca, gimana sih, Soya ... Soya! Duduk! Kembali ke tempatmu.”
Soya hampir menangis. Bahkan mungkin sudah. Ia tidak tahu apa rasa basah di pipinya ini akibat keringat suhu pukul satu siang di dalam kelas yang kipas anginnya mati, atau karena tangisan.
Soya mengatupkan bibir rapat-rapat saat menyeret kaki menuju bangku. Ia ingin protes. Aku kan baru sembuh dari tipes! Baru keluar dari rumah sakit! Namun, itu juga bukan pembelaan yang masuk akal. Apa hubungannya tipes dengan kelancaran membaca naskah Siti Nurbaya di depan kelas?
Kala ia melesakkan tubuh ke kursi kayu yang keras, Daru, teman sebangkunya, terbangun dari tidur. Dengan linglung, Daru menepuk-nepuk bahu Soya. “Tisu?”
Gadis itu terlalu lemas untuk bisa menjawab. Ia melirik Daru telah sigap merogoh tas kumal yang teronggok di bawah meja. Ia mengeluarkan tisu yang dilipat-lipat kecil, masih bersih, walau ada sobekan furing tas yang menyangkut di permukaannya.
Soya menerima sodoran Daru, semata-mata tidak enak kalau menolak. “Makasih,” bisiknya lirih. Sambil mengusap pipi dengan tisu, lengkingan Nova mengejutkan seisi kelas.
“Dengerin, ya! Aku nggak mau ngulang dua kali.” Nova mengacungkan bendelan naskah di tangan. Saat cowok-cowok di jajaran belakang menyerukan “Huu!” untuk mencemooh, Nova balas merespons dengan menyibakkan rambutnya yang bergelombang. Mengacuhkan koor mereka, ia berdeham, dan mengacungkan telunjuk tinggi-tinggi.
“Kira-kira pukul satu siang ....” Nova memulai, badannya condong sedikit, suaranya dalam dan—entah bagaimana—selantang ejekan cowok-cowok tadi. Cara telunjuknya mengabsen satu-satu wajah, seluwes burung merak yang mengumumkan kedatangannya. Seolah berkata: Awas kalau kalian nggak memerhatikan aku.
“Kelihatan dua orang anak muda ....”
Seisi kelas menjadi senyap. Tanpa bantuan Sastra, Nova telah membuat tiap-tiap mulut bungkam. Hanya terdengar gemerisik pohon beringin dan mangga, dan tiupan angin panas yang bikin gerah, seolah-olah mengiringi bacaan selanjutnya:
“Bernaung di bawah pohon ketapang yang rindang, di muka sekolah Belanda Pasar Ambacang di Padang ....”
Soya termasuk ke dalam dua puluhan murid yang ikut diam, tapi tidak ikut menyaksikan. Walau suara Nova menembus gendang telinganya, Soya menatap nanar kepada Daru. Teman sebangkunya itu tidur di waktu Soya maju, tetapi kini matanya terpaku bulat-bulat pada pembacaan Nova, seolah ikut tersedot ke dalam kisah Siti Nurbaya.
**
Sebelum bersukacita menyambut libur akhir tahun, sebagian siswa mesti memeras perasaannya dulu. Terutama pada salah satu dari beberapa tanggal keramat. Keramat sejak Soya mengenal apa itu rapotan dan ujian.
Hari ini: 22 Desember 2017.
Lokasi yang mendadak lebih mengerikan daripada biasanya: SMA Surya Cendekia dan bangunan tuanya yang merupakan bekas sekolah elit sejak tahun 1901. Lebih menakutkan daripada saat ujian akhir!
Namun, bunga-bunga kembang sepatu justru mekar semegah-megahnya di sepanjang tepi pagar besi sekolah. Pohon beringin dan trembesi sedang rindang-rindangnya, meneduhkan jajaran mobil-mobil mengilap yang menyesaki halaman parkir sekolah. Langit juga—sayangnya—sedang cerah-cerahnya, padahal kemelut hati Soya sekelam awan kelabu padat yang siap menyambut badai amukan Papa Soni dan Mama Yasmin.
Kelas XI-B terletak di ujung lorong, bersebelahan dengan pendapa yang biasa digunakan anggota OSIS rapat di penghujung siang yang bikin ngantuk. Namun, kali ini, pendapa itu sesak oleh jajaran meja-meja kayu yang dijadikan alas presensi dan para orang tua. Harum semerbak parfum berpadu dengan canda tawa para ibu yang saling menyapa, dan senyum-senyum pasrah tiap anak.
Jika ada yang tidak tersenyum hari itu, pastilah Soya, dan mungkin beberapa anak lagi yang belum terlihat. Entah kenapa semua kawannya tampak semringah hari ini. Heran. Begitu pula Daru yang berlari membawakan lembar presensi ke meja tempat neneknya menunggu, juga berseri-seri.
“Mbah! Tanda tangan, Mbah! Bisa, kan? Masa aku tanda tangani juga, kan nggak boleh!”
Soya mengatupkan bibir rapat-rapat. Ia tahu Daru bisa tersenyum lepas karena dia rajin menangkring di peringkat tiga teratas. Namun, bukan itu masalahnya. Teman-temannya juga! Bahkan para tukang hina yang telah menguasai tiga peringkat terakhir kelas juga tetap petantang-petenteng bangga saat orang tuanya yang tak kalah sangar mampir, membuat murid-murid lain menganga, seolah ingin mengatakan, “Lihat, aku keren karena bapak aku ya super keren!”
Heran. Bagaimana mereka bisa tetap senang dengan peringkat belasan dan dua puluhan?
Memangnya orang tua mereka nggak pernah marah? Soya termangu saat menunggu wali kelasnya menjelaskan program sekolah yang sudah berlalu. Dari balik salah satu jendela, ia mengintip Papa Soni dan Mama Yasmin duduk berdampingan di bangku paling depan, di bangku Nova.
“Saya akan umumkan peringkat semester ganjil 2017/2018.” Seiring ucapan Bu Oris, sekretaris kelas mengambil spidol dan mulai menulis angka satu, dua, dan tiga di papan.
“Peringkat satu ....”
Cewek sekretaris yang siaga itu mulai menulis nama yang disebutkan Bu Oris. Namanya sendiri.
“Peringkat dua ....”
Pasti Daru, batin Soya.
“Alam Darusena!”
Soya menghela napas lega. Sudah ia duga. Meski, itu berarti, menyisakan peringkat ketiga. Sudah terbayang omelan Soni dan Yasmin. Jantung Soya berdebar-debar. Pada kelas sepuluh lalu, gadis itu paling banter duduk di peringkat ketiga. Ia telah menjanjikan kedua orang tuanya jika bisa menyabet peringkat kedua dengan mengambil jurusan Bahasa, jurusan dengan jumlah peminat paling sedikit itu. Soya sudah menggunakan segala taktik agar diizinkan memilih jurusan Bahasa, sehingga—
“Peringkat tiga ....”
Soya.
Soya.
Soya Mayanura. Soya, tolong Tuhan, tuliskan nama Soya di sana!
“Nova Carissa!”
Kala Soni dan Yasmin bertukar pandang, lantas menggeleng pelan, Soya tahu dirinya mesti kabur dan melompat dari lantai dua saat itu juga.


 andywylan
andywylan

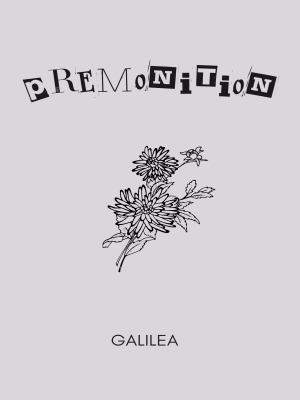




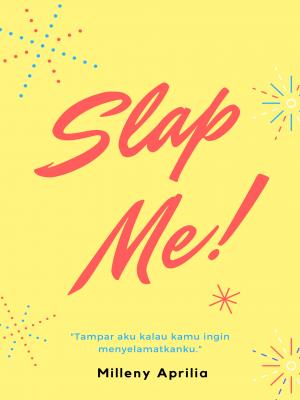



Haruskah kita bertemu lagi dengan efis---
Comment on chapter Prolog: Ambang Batas