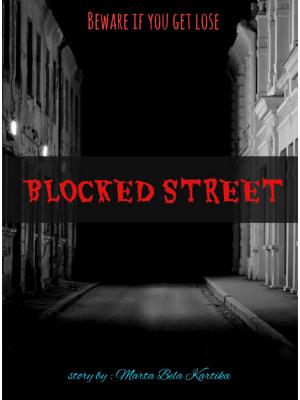Pagi itu terasa seperti halaman kosong. Udara dingin berembus melewati sela jendela kamar, membawa suara dedaunan yang bergesekan seperti bisikan dari masa lalu. Maura duduk di tepi ranjang Maureen, memperhatikan tempat tidur yang rapi dan tidak tersentuh, seperti sengaja dijaga agar tak hilang jejaknya.
Tidak ada yang berubah sejak kepergian Maureen. Seprai putih bersih dengan pola awan tipis masih terpasang, boneka kelinci yang lusuh duduk di sudut bantal, dan lampu meja kecil yang biasanya dibiarkan menyala semalaman kini tetap padam. Semua tetap di tempatnya, kecuali Maureen.
Seno duduk diam di ruang tamu sejak subuh. Seperti biasa, dengan koran terbuka, tetapi tak terbaca. Tangan kirinya menahan kepala, sementara tangan kanan hanya sesekali membalik halaman, lebih karena kebiasaan ketimbang minat.
Riana, di dapur, sibuk membuat teh seperti tanpa jeda, seakan air hangat bisa menyamarkan kekosongan yang mendera rumah itu. Tidak ada percakapan. Hanya suara detak jam dinding dan sesekali derit kursi saat salah satu dari mereka mencoba terlihat sibuk.
Maura menatap langit-langit kamar mereka. Di sanalah, Maureen pernah menempelkan bintang-bintang fosfor yang kini hanya menjadi bayangan samar di siang hari. Ada keheningan yang terlalu padat di ruangan ini—seperti bisa ditelan jika dibiarkan terlalu lama.
Di bawah bantal, Maura menemukan kertas yang terlipat dua, sedikit menguning di pinggirnya. Surat terakhir dari Maureen. Ia sudah membacanya berkali-kali, tapi tetap saja terasa seperti dibacakan oleh suara Maureen sendiri, lirih dan ragu:
“Di cermin jam 6 pagi, aku…”
Hanya sampai di sana. Tidak ada titik, tidak ada lanjutan. Hanya kehampaan yang menggantung seperti pertanyaan.
Maura menatap jam dinding. Sudah pukul tujuh pagi. Ia menggenggam surat itu, memejamkan mata. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya.
“Di cermin jam 6 pagi, aku…”
Apakah itu metafora? Apakah Maureen melihat sesuatu di cermin? Dirinya sendiri? Atau sesuatu yang lain?
Saat Maura kembali ke area tempat tidurnya, ia membuka laci meja belajar yang sudah lama tak disentuh. Di sana, tersimpan sebuah buku catatan berwarna hitam dengan tepi sobek, milik Maureen. Buku itu pernah menjadi jurnal pribadi mereka berdua—tempat mereka berbagi cerita, rahasia, dan sandi-sandi pribadi.
Di halaman pertama tertulis dengan spidol merah:
Langit sebelah timur selalu lebih gelap bagiku.
Maura membacanya dengan napas tertahan. Itu adalah kalimat yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Sandi. Dulu, mereka menyebut sisi timur sebagai “arah ketakutan”, karena jendela kamar mereka menghadap ke sana, dan Maureen selalu takut tidur menghadap ke luar.
Maura membuka halaman berikutnya. Ada simbol-simbol kecil, seperti segitiga terbalik, kupu-kupu patah sayap, dan angka 23 yang diulang dua kali dalam lingkaran.
Ia menyalin semuanya ke selembar kertas. Tangannya gemetar. Apa maksud semua ini?
ꕤꕤꕤ
Sekolah dimulai kembali seminggu setelah pemakaman. SMU Pelita Bangsa menyambut Maura dengan keheningan tak kasat mata. Tidak ada yang terang-terangan menatap, tetapi Maura bisa merasakan beban pandangan yang tersembunyi di balik senyum simpati yang dipaksakan.
Lorong sekolah berwarna abu-abu terang itu terasa seperti kabut. Setiap langkah seperti mengambang. Poster ekstrakurikuler yang dulu mereka komentari bersama kini hanya seperti hiasan dari dunia lain.
Di kelas, Nana menyapanya dengan hati-hati. “Maura... kalau butuh teman cerita ... aku ada, ya?” katanya, sambil memegang lengan Maura dengan canggung.
Maura hanya mengangguk. Kata-kata seperti “terima kasih” atau “aku baik-baik saja” terasa seperti kebohongan yang terlalu berat diucapkan.
Setelah bel usai, seorang guru perempuan berdiri di depan pintu kelas. Sosoknya tenang, matanya tajam, tetapi lembut.“Maura, kamu bisa ikut saya ke ruang BK?”
ꕤꕤꕤ
Ruangan BK seperti lemari tempat rahasia dikumpulkan. Tenang, rapi, dan penuh tumpukan kertas. Di dalamnya, Bu Rissa duduk di belakang meja kecil yang penuh dengan buku dan tanaman kecil.
“Kamu boleh duduk di mana saja,” katanya, sambil menunjuk kursi di depannya.
Maura duduk, diam. Tangannya memegang buku catatan Maureen yang ia bawa dalam tas.
“Bagaimana kamu merasa hari ini?” tanya Bu Rissa perlahan.
Maura menoleh padanya, matanya kering, tetapi gelap. “Seperti berjalan dalam kabut.”
Bu Rissa mengangguk. Ia mencatat sesuatu. “Apa yang kamu rindukan dari Maureen?”
Pertanyaan itu seperti pukulan. Maura menggigit bibirnya, lalu membuka buku catatan itu dan menunjukkannya pada Bu Rissa.
“Dia meninggalkan ini. Simbol. Kata-kata aneh. Aku rasa ... dia mau bilang sesuatu, tapi aku telat.”
Bu Rissa membaca sepintas halaman yang ditunjukkan. Matanya sempat menatap simbol kupu-kupu patah dan angka 23 dalam lingkaran.
“Kadang, mereka yang terluka tidak tahu cara bicara dengan dunia,” kata Bu Rissa pelan.
Maura menggenggam buku itu lebih erat. “Tapi aku seharusnya tahu. Aku kembarannya.”
ꕤꕤꕤ
Sore hari, rumah itu kembali sunyi. Riana duduk di meja makan dengan teh yang tak disentuh, pandangannya kosong. Seno belum pulang. Maura mendekati meja, mencoba berbicara.
“Ma ... Maureen ninggalin buku. Ada catatan yang aneh di dalamnya.”
Riana mengangkat wajahnya. “Jangan bahas itu lagi, Maura. Kita harus lanjut hidup.”
“Tapi—”
“Sudah. Dia tenang sekarang. Kita juga harus begitu.”
Maura menatap ibunya dengan getir. Ketika seorang anak hilang, satu bagian dari ibu juga hilang. Namun, Riana memilih untuk menguburnya bersama tubuh Maureen.
ꕤꕤꕤ
Malam itu, Maura duduk di depan cermin kamarnya pukul 6 pagi—waktu yang disebut Maureen dalam surat. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajah yang dulu serupa dengan Maureen, kini terasa berbeda.
“Di cermin jam 6 pagi, aku…”
Ia menulis kalimat itu lagi di buku catatan barunya. Di bawahnya, ia menambahkan: “Aku akan mencari makna dari setiap patah kata yang kau tinggalkan. Maureen, tunggu aku di antara halaman yang belum selesai.”


 chococeanic
chococeanic