"Teteh, Aa, sasarap dulu. Ibu sudah masak bubur ayam kesukaan kalian. Jangan kebiasaan langsung berangkat kerja kalian, ya," Dita berteriak pada anak-anaknya dengan suara nyaring.
Pramesti Ayundya atau kerap dipanggil Ames adalah Anak Sulung Dita. Ames bekerja di salah perusahaan kontruksi besar di Bandung. Jam kerjanya yang tinggi membuat Dita jarang bertemu Ames. Anaknya itu selalu berangkat pagi sekali, dan pulang larut sekali.
Sama dengan Ames, Dermawan Chandra yang disingkat namanya menjadi Dewa , anak kedua Dita, juga tidak kalah sibuknya. Lulus kuliah dengan jurusan teknik membuat Dewa menjadi kepala teknik di sebuah parbrik besar di Bandung. Anak laki-laki satu-satunya di keluarga kecil itu juga memiliki jam kerja yang tinggi. Tak jarang, ia bahkan menginap di kantor, membawa baju-bajunya sudah seperti hendak kabur ke luar kota. Sama dengan Ames, Dewa juga berangkat pagi dan pulang larut malam.
Untuk itu, ketika anak-anaknya berkumpul di rumah, sarapan adalah waktu terbaik untuk bertemu mereka.
Sementara, anak bungsu Dita--Berly, sudah duduk cantik di meja makan sembari menyantap nasi goreng kesukaannya. Seragam batik sekolah berwarna cokelat muda sudah rapi dikenakan gadis itu.
Tak lama, Pramesti keluar dari kamarnya tepat pukul enam pagi. Dengan menenteng tas laptop dan tas pribadinya yang sebesar harapan Ibu, ia sudah tergupuh mengambil minum di dispenser lalu menegaknya sampai habis. "Bu, aku nggak sarapan, deh. Masih kenyang. Lag--"
"Pramesti ..." sela Dita. "Ibu nggak mau sita banyak waktu kamu yang selalu kamu bilang berharga itu. Ibu cuma minta 10 menit. Sama kita ngobrol sebentar, teteh bisa sasarap dulu, ya."
Pramesti terdiam beberapa saat. Tatapannya jatuh ke dua mangkok berisi bubur ayam yang sudah tertata di meja makan, lengkap dengan kerupuknya dan yang jelas tanpa kacang karena Pramesti alergi dengan biji-bijian itu. "Iya, deh. Ames makan sebentar. Makasih sarapannya, Bu."
"Nah, begitu. Ibu senang kita sarapan bareng-bareng."
Pramesti menarik kursi di depan Berly. Ia melihat sarapan Berly berbeda dengan miliknya, juga dengan milik Dewa. "Kenapa Berly makan nasi goreng?" tanya Ames.
"Aih Teteh, kumaha? Memang Teteh pernah lihat Berly makan bubur?"
"Nggak."
"Nggak per--"
"Nggak tau, Bu. Ames gak pernah perhatiin," ujar Ames. Ia buru-buru menelan bubur ayam buatan Dita. "Oh iya, Ibu kurang cocok ngobrol pake bahasa Sunda. Aneh dengernya. Jangan maksain, Bu. Tinggal di Bandung nggak mesti harus bisa bahasa Sunda."
Dita diam sejenak. Ia tersenyum. "Iya, Mes. Ibu mah belajar dikit-dikit," ujar Dita. "Mes, Ibu nanya lagi. Serius Teteh nggak tau Adik nggak suka bubur ayam?"
"Serius. Ngapain juga hal kecil gitu harus bohong sama Ibu, sih?"
Dita mengelus dada. "Padahal kalian sudah tinggal bersama bertahun-tahun, loh. Masa sekadar adikmu nggak suka apa, kamu nggak tau?"
"Ames nggak tau, Bu. Lagian itu bukan hal yang penting buat Ames."
Pergerakan tangan Berly yang sedang terampil menyuap nasi goreng ke mulutnya terhenti kala mendengar ucapan Ames. Ia menatap lamat-lamat Kakak perempuannya itu. "Bu, biarin aja. Teh Ames tau atau enggak kesukaan Berly, itu nggak ada efek apapun dalam hidup Berly. Jadi nggak usah dibahas, ya, Bu,"
"Nah, itu Berly pinter," Ames berdiri dan menyambar kedua tas miliknya. "Bu, Ames berangkat, ya. Udah telat banget. Takut macet juga di jalan."
"Lah? Ini belum habis, Mes ..."
"Kenyanggggg, Bu," Ames mencium singkat kening Dita, disusul Berly yang menghanturkan tangan untuk salim pada Kakak perempuannya itu. "Ames berangkat, ya. Jangan nungguin pulang, soalnya hari ini padet banget. Kemungkinan Ames tidur di kantor. Bye!"
Setelah berpamitan, Ames menghilang di balik pintu. Dengan mengendarai mobil merah menyala keluaran 2017, Ames pergi ke kantor.
Bergantian, kini Dewa yang sudah duduk di meja makan rumah tua ini. Dengan setelan polo shirt dan celana kain hitamnya, juga tak lupa tas punggung besar yang kini sudah duduk manis di sampingnya, laki-laki itu sudah memulai aktifitas makannya.
"Astaga, ini sarapan paling enak yang ada di muka bumi!" Puji Dewa. Ia lahap sekali, sampai mangkoknya hampir kosong kurang dari 5 menit.
"Halah, kamu bisa aja. Itu kamu muji Ibu atau karena buru-buru?"
Dewa nyengir. "Keduanya, Bu," jawabnya polos. "Dewa ada meeting pagi. Terus ada kunjungan juga ke pabrik di Lembang, jadi jadwal padat banget. Kemungkinan Dewa nggak pulang, ya, Bu."
"A, kamu udah gak pulang seminggu, semalem aja baru pulang jam sebelas malam, Ibu udah tidur. Terus ini nanti nggak pulang lagi?"
Dita menerawang mata putranya dengan mata basahnya. Entah. Jika menyangkut anak-anaknya, Dita memang gampang menangis. Mungkin juga ini faktor umur.
Di usianya yang sudah menginjak 54 tahun, jiwa keibuannya semakin menggebu baginya. Sering merasa kesepian, merindukan anak-anaknya, dan merasa ditinggalkan. Kadang Dita rasa perasaan itu memang berlebihan. Namun, perasaan ini tak bisa ia hindari, hanya saja masih bisa ia kelola dengan baik agar tidak memberatkan dirinya sendiri maupun anak-anaknya.
Meski susah, Dita berusaha tidak terlalu posesif ke anak-anaknya yang memiliki banyak pekerjaan itu. Terkadang, Dita lebih memilih melakukan banyak kegiatan untuk menghindari perasaan egois dirinya.
"Bu, maaf, ya? Dewa lagi banyak kerjaan karena ada rekan Dewa yang habis kecelakaan. Jadi, mau nggak mau, Dewa take kerjaannya."
Dita segera menghapus air mata yang menetes di pipinya. "Iya, iya, Ibu mengerti. Sekarang kamu makan, habisin, ya?"
Dewa mengangguk. "Makasih udah ngerti Dewa, Bu," ujarnya. Tatapan Dewa lalu beralih ke Berly. Adik perempuannya itu kini ia amati lekat-lekat. Bagaikan memakai kaca pembesar, laki-laki itu memeriksa setiap inch penampilan adiknya. "Berly ..." panggilnya.
"Hm?"
"Harus banget kamu ke sekolah pakai lipgloss begitu? Terus rambutnya di curly kayak gitu? Nggak riweuh?"
Berly memeriksa penampilannya. "Bukannya Berly begini udah sejak satu tahun lebih tujuh bulan yang lalu, A? Serius ini baru Aa komentarin sekarang?"
"Iya, soalnya aneh. Jaman Aa sekolah, nggak ada yang penampilannya kayak kamu begini. Bahkan buat pakai lipgloss aja nggak ada yang berani, apalagi sampai curly rambut."
Berly cepat menenggak susu cokelat buatan ibunya. Ia ingin menghilang dari hadapan Dewa, sudah malas ia mendengar ceramah Dewa yang suka tiba-tiba datang tak diundang itu. "Kapan-kapan Aa harus main ke sekolah Berly. Biar apa? Biar wawasan Aa tentang perubahan jaman itu bisa lebih luas! Nggak kuno muluk!"
Dewa mendelik. "Gimana? Kuno?"
"Iya! Kuno banget! Udah mode bapak-bapak!" balas Berly. "Udah, ah. Berly udah telat. Bye! Berly berangkat dulu!" Berly bergegas mencium kening ibunya, lalu disusul ia yang memeluk singkat Dewa.
"Jangan ngebut bawa sepedanya, Berly!" teriak Dita. Anak gadisnya itu kini sudah membuka pagar dan mengeluarkan Bombom dari halaman. Tak lupa Dita melirik, memastikan bahwa Berly sudah memakai helm bogo pink ciri khas anak gadisnya itu.
"Bu, bilangin Berly buat ubah itu penampilan sekolahnya. Masa iya anak baru kelas 2 SMA sekolahnya pakai lipgloss? Rambut di-curly? Mau jadi apa dia, Bu?" Dewa masih menyuarakan isi hatinya.
"Ya, jadi apa? Jadi yang dia maulah, A," Dita menjawab tenang sembari ia membereskan meja makan. "Lagian, kenapa curly sama lipgloss nggak boleh, A? Mau bagaimana penampilan Berly, tetap nilai yang diutamakan di sekolah dia, A."
"Lain kali, kalau ada waktu, main ke sekolah Berly. Biar kamu tau, kalau jaman udah berubah, A. Jamanmu dan jamannya Berly sangat berbeda jauh. Maklum, umur kalian saja terpaut 13 tahun."
•••
Baru saja menginjakkan kaki di ruang kelas X Ipa 1, Berly terpatung di tempatnya berdiri, tepat di pintu kelas.
Matanya sibuk menelisik keadaan kelas yang riuh.
Ruangan kelas yang biasanya damai, kali ini ramai. Ah, lebih tepatnya, tempat ia duduk di belakang sana yang kini ramai dengan sekumpulan laki-laki di sana.
"Berly! Akhirnya kamu dateng!"
Dengan napas tersengalnya, Jessie--teman sebangku Berly--kini menggenggam erat lengan Berly. "It..Itu!" Ia menunjuk bangku kedua dari belakang yang kini penuh dengan siswa yang entah datangnya dari mana.
"Mereka siapa, sih? Kok di--"
"Helm!" teriak Jessie.
"Helm?"
"Helm di kantin yang kemarin kamu lukis!"
"Ah? Helm putih polos yang dekil itu?"
Jessie melotot mendengar jawaban asal Berly itu. Bisa-bisanya Berly menjawab seperti itu, membuatnya makin pening saja.
Sedang, kini Berly mengingat lagi. Iya, memang. Kemarin ketika selesai ekskul lukis, Berly memutuskan mengambil sebuah helm putih di kantin, yang sudah lama ada di bawah rak penyimpanan. Helm itu sudah lusuh, dekil, bahkan cat atasnya mengelupas.
Untuk itu--dengan keterampilan tangannya, Berly melukis helm tak bertuan itu menjadi warna pink dengan bubuhan bunga Daisy di sekelilingnya. Dalam beberapa detik, helm itu jadi helm yang manis. Apa yang salah dari itu, sih?
"Iya? Kenapa sama helmnya, Jess?"
"It-itu ..."
Segerombolan siswa di bangku Berly pun beranjak. Mata Berly membulat kala melihat siswa-siswa itu menyingkir, lalu terlihatlah seorang Siswa yang duduk di bangkunya itu.
Wajah tampan seorang Siswa itu mencuri perhatiannya. Berly jelas sangat mengenali wajah rupawan itu. Sekali lagi--SANGAT! Terlebih, saat ini sebuah helm pink terpasang di kepalanya, membaur dengan ketampanannya. Bahkan, bunga-bunga daisy yang terlukis di helm itu menambah manis dari senyum ranum laki-laki ini.
Namun, meski begitu, dibalik wajah tampan dan senyumnya yang penuh arti ini, wajah dongkol laki-laki ini tak bisa ia sembunyikan. Ia menamati Berly lamat-lamat dari kejauhan, dengan posisi duduknya yang bossy dan tak santai itu. "Jadi benar ini kelakuan kamu?" tanyanya datar pada Berly.
"Kamu yang udah lukis helm putih 'dekil' ini?" tanyanya menyindir Berly. Ia sebal. Helm seharga 1,8 juta miliknya ini bisa-bisanya dihina dekil. Sungguh tak berhati nurani perhelm-an.
Berly menelan ludah. Ia menatap Siswa itu sama lamatnya. Hatinya berdebar kencang, susah untuk ia kendalikan. Entah ini karena takut atau karena ia justru berdebar karena berbincang dengannya?
Pertanyaan yang terlontar bahkan belum sempat dijawab Berly. Ia frezee. Ia tak bisa berkata-kata.
Korban lukisan random Berly itu bernama Jhagad Braga Utama atau famous dengan nama tengahnya, Braga. Tak kalah indahnya dengan jalanan kota Bandung yang sama dengan namanya, Braga juga terkenal dengan ketampanannya yang mentereng se-antero sekolah.
Belum juga mendapat jawaban, kini Braga bersuara lagi. "Sini kamu!" perintahnya.
Jessie menggoyangkan lengan Berly untuk mengembalikan kesadaran temannya ini. "Berly! Sadar! Astaga malah ngelamun ini anak! Itu ... dipanggil sama Kak Braga!" ujar Jessie.
"Ah? Iya."
Dengan polosnya Berly mendekat ke Braga yang masih duduk bossy di bangkunya. Ia tersenyum tipis. "Iya, Kak?"
Sedang, segerombolan Siswa di sekeliling Berly, yang kini Berly kenali, mereka adalah pasukan Braga yang juga anggota SVARGA. Mereka memandangnya dari atas sampai bawah kaki. Dengan tangan terlipat--ada pula yang sedang duduk di meja, mereka menamati dengan tatapan penuh penilaian ke Berly. Hal itu membuat bulu kuduk Berly berdiri. Seram juga mereka ini.
"Nama kamu?"
"Berly, Kak."
Braga melepas helm yang ia pakai, lalu menyodorkan itu ke Berly. "Ambil."
"Buat?" Berly menerima dengan bingung.
"Bersihkan helm itu sekarang juga."
"Ya nggak bis--"
"Nggak bisa?"
"Hari ini full ujian, Kak. Mungkin ini bisa hilang 3 hari lagi. Nggak mungkin sekarang."
Braga berdiri dari singgasananya. Ia memasukkan kedua tangannya ke saku celana dan semakin meneliti Berly lamat-lamat.
Karena tinggi badannya dengan Berly berbeda jauh, laki-laki itu merundukkan tubuhnya, mensejajarkan diri dengan telinga Berly. "Kalau buat salah, harus apa Berly?" bisik Braga.
"Min-minta maaf, Kak," jawab Berly pelan.
"Hm, pintar. Terus?"
"Terus?" tanya polos Berly.
"Iya. Setelah minta maaf, gimana?"
"Tang-tanggung jawab?"
"Pintar," puji Braga lagi. "Kamu mau tanggung jawab, kan? Masa setelah lukis helm cowok se-matcho aku jadi pinky, kamu nggak mau tanggung jawab, sih?"
Berly menegak ludah susah payah. "Iy-iya, Kak."
"Iya apa?"
"Tang-tanggung jawab."
"Good girl. So, nanti istirahat, bawa helm pink bunga-bunga itu ke Mabes. Aku tunggu. Jangan sampai telat. Aku nggak suka buang waktu." Setelah mengucap demikian, Braga beranjak dari bangku Berly diikuti teman-temannya yang satu komplek itu.
"Kak!" panggil Berly.
Braga menoleh. "Apa?"
"Maaf."
Braga mengangguk kecil. "Maaf diterima."
Dengan senyum cerah yang terbit di bibirnya, Braga melanjutkan langkah meninggalkan ruang kelas Berly diikuti gerombolannya.
"Yoksi! You doin great, Braga!"
Sementara, selepas perginya Braga dari kelasnya, tubuh Berly lemas. Ia terkulai di lantai sembari berpegangan pada ujung meja.
Matanya terpejam penuh beban. Tak pernah ia bayangkan bahwa ia akan berkomunikasi dengan Braga dengan seperti ini.
Astaga! Ini mah bukan sekadar komunikasi, ini namanya cari masalah sama Braga, Berly!


 yoanarahani
yoanarahani





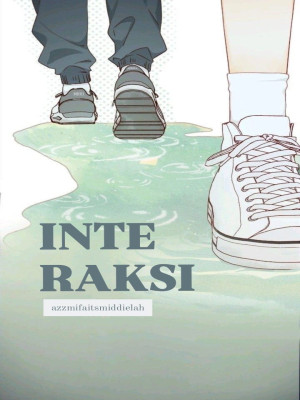




Bagus kak ❤
Comment on chapter P R O L O GNext Part Kapan Nih kak ???