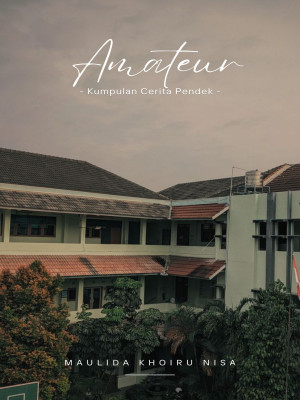Untuk kali kedua, Phiko terduduk di sebelah ranjang kakaknya. Kali ini Finna yang terbaring di sana. Nasal canulla dan jarum infus menempel di tangan kanannya. Phiko setia menggenggam tangan kiri Finna. Beberapa menit lalu, Finna menjerit ketakutan, ia tak ingin sendiri, katanya.
Finna juga melolong minta tolong, memanggil Phiko dan Vino bergantian. Kepala bagian belakang Finna sudah dilakukan tindakan, hasilnya Finna dinyatakan akan mengalami ketulian secara permanen karena benturan tadi merusak saraf yang berhubungan langsung dengan komponen indra pendengaran.
Phiko menidurkan kepalanya di atas punggung tangan Finna. Matanya tetap memandang lekat pada wajah Finna, barangkali kakaknya terbangun sewaktu-waktu nanti. Untuk pertama kali Phiko melihat wajah cantik itu sangat pucat, tidak ada senyum, dan begitu dingin.
“Fin.” Air mata kembali menggenang. Buru-buru Phiko menyeka air matanya sebelum benar-benar jatuh. “Gue minta maaf.”
“Kamu bicara, Phi? Nggak kedengeran ....” Finna mulai membuka kedua matanya.
“Kalian cacat karena gue. Kalian celaka karena gue. Harusnya gue yang ada di posisi kalian.”
Meski tidak dapat mendengar, Finna berusaha membaca pergerakan mulut adiknya. “Memang ada bukti kalau kita begini karenamu?”
“Kalian harus bekerja keras karena gue nggak bisa kerja.”
Finna tertawa remeh. Ia membuang pandangannya untuk menyembunyikan tangisan.
Dunia itu ... sangat hening. Dunia yang Finna miliki sekarang hening. Tidak ada lagi bising di kepalanya, tidak ada lagi suara yang menyuruhnya untuk terus mencari uang agar lampu di rumah menyala, agar Bapak bisa makan obat. Finna sekarang bisa tidur tanpa adanya bisikkan-bisikkan di telinga.
“Phi, tasku ada di mana?”
Phiko mengusap jejak air mata di wajahnya. Ia menuruti permintaan kakaknya. Dengan tangan yang kosong, Finna merogoh untuk mencari sesuatu. Phiko hendak membantu, tapi Phiko sendiri tidak tahu apa yang sedang dicari kakaknya.
“Belikan obat untuk Bapak.” Tak lama Finna mengeluarkan dompetnya, diberikan kepada Phiko.
Lelaki itu terkesiap. Dalam kondisi begini, Finna masih saja memikirkan tentang obat untuk Bapak. Lagipula, mereka seharusnya hanya melipir ke rumah sakit untuk beli obat, bukannya menginap dan butuh perawatan begini.
“Fin. Udah, Fin. Lihat kondisi lo sekarang.”
“Phi.” Finna menyandarkan kepalanya dengan lemah. “Tolong, Phi. Aku, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan kamu.”
Finna memberikan beberapa uang lembar itu. Phiko menghitung secara sekilas. Enam lembar uang merah. Phiko tidak tahu berapa total harga obat Bapak.
“Jangan buang waktu hidup kamu untuk rasa bersalah, Phi. Hidup harus tetap berjalan. Aku ikhlas nerima takdir ini. Aku masih, aku masih cinta sama diriku sendiri asalkan kamu, Bapak dan Vino nggak benci sama aku. Jadi, tolong kamu pun jangan benci sama dirimu sendiri. Ini bukan salahmu, bukan salah siapa pun. Ini takdirku, Phi. Mungkin, Tuhan memiliki tujuan agar aku tidak mendengar sesuatu yang buruk di masa depan.”
Dirasa tidak ada tanggapan, Finna menarik adiknya agar lebih dekat. Finna mengusap wajah Phiko, merasakan cairan yang membasahi pipinya.
“Stt, jangan menangis, Phi. Tidak apa, tidak apa-apa.”
Gadis itu menggenggam wajah adiknya yang semakin terisak. “Tolong, Phiko.”
Pada akhirnya, Phiko mengangguk-angguk. Perlahan ia melepaskan genggaman Finna.
“Tunggu sebentar. Gue akan kembali sece—”
Ucapan Phiko terpotong saat dirinya melihat pintu dibuka dengan cepat. Mata Phiko terbelalak. Finna juga ikut terkejut sampai memaksa tubuhnya duduk.
“No? Lo? Lo bisa?”
Vino menyeringai. “Jalan.”
Phiko sungguh membeku di tempat. Menatap kakak sulungnya yang kini berdiri, benar-benar berdiri menggunakan dua kakinya. Tangan kirinya memegang sebuah tongkat siku. Vino tersenyum bangga ke arah Phiko. Bapak menuntun Vino sedari awal masuk. Kemudian mereka mendekat ke ranjang Finna.
“Kayaknya, kaki kanan gue nggak cukup fungsi kayak tangan kanan gue,” ucap Vino memberitahu.
Ya, Phiko bisa melihatnya. Vino menyeret-nyeret kaki kanannya selama ia melangkah.
Kini Vino sudah berada tepat di sebelah Finna. Ia meraih tangan Finna, begitu pula dengan Bapak yang mengusap wajah Finna. Tanpa bertanya pun mereka tahu jika kini gadis itu sudah kehilangan penglihatannya.
“Gue udah bisa pakai kaki palsu yang lo kasih waktu itu, Fin.”
Finna terlihat senang melihatnya. Namun, sesaat kemudian gadis itu menggeleng lemah. “Aku nggak bisa denger suara kamu, No.”
Vino terdiam. Seluruh tubuhnya serasa melemas seketika. Ia menggigit bibir bawahnya dengan kuat. Seharusnya, perban yang ada di kepala dan kedua telinga sudah menandakan semuanya, tapi Vino bersiteguh dengan kepercayaannya bahwa adiknya baik-baik saja. Vino akhirnya menunjuk kedua kakinya, memperlihatkan kaki palsu, lalu menunjuk diri Finna. Dari sana Vino hendak menyampaikan makna yang sama seperti ucapannya barusan.
Dari kejauhan, rahang Phiko mengeras. Bukan karena iri melihat interaksi itu. Namun, Phiko dibuat marah, tidak habis pikir. Pasti ada seorang dalang yang sudah membuat kakak-kakaknya begini. Mulai dari sopir truk yang menghilang, hingga pembekukan sekelompok orang di tempat kerja Finna, Phiko semakin curiga, dipastikan ada orang yang mengenal mereka dan ingin menghancurkan mereka.
“Phi, kamu mau ke mana, Nak?”
Langkah Phiko terhenti saat hendak menghampiri pintu. Bapak memanggilnya.
“Ke bawah bentar, Pak.”
“Gue temenin, ya?”
“Nggak usah, No. Gue bisa sendiri.”
“Gue gak mau ngebiarin lo sendiri.”
Phiko menatap mata kakaknya. Vino keras kepala, seperti dirinya. Namun, Phiko masih bisa mengalah. Lantas ia memilih membiarkan Vino ikut dengannya.
Keduanya menyusuri lorong rumah sakit menuju lantai bawah, tempat toko apotek berada. Phiko menuntun Vino dengan sangat hati-hati. Sesekali lelaki itu terjatuh karena memang belum lancar menggunakannya.
“Mau ngapain ke apotek?”
“Finna nyuruh gue beli obat Bapak.”
Vino mengangguk mengerti.
“Eh, lo tau gak? Tongkat siku ini Pak RT yang ngasih. Anaknya pernah patah tulang cukup lama.”
Kali ini Phiko yang mengangguk-angguk. Tidak bisa ditandingi lagi kebaikan yang diperbuat ketua RT itu. Ia selalu mengayomi para warga tanpa ada niat untuk mengorupsi seluruh dana untuk kampung.
“Resep ini diberi kapan oleh dokter?”
Phiko dan Vino saling melempar pandang saat petugas apotek bertanya. Mereka lupa-lupa ingat tentang petugas tersebut. Entah mungkin si petugas ingin memeriksa ingatan anak pasiennya atau bagaimana. Namun, yang jelas memang biasanya yang membeli obat adalah Finna, bukan Vino apalagi Phiko.
“Dua bulan lalu. Terakhir kali Bapak dirawat di sini. Kata dokternya, kalau obat Bapak udah habis, kita tinggal beli lagi aja pakai resep ini,” jelas Vino.
Petugas itu mengangguk-angguk paham. Setelah itu membuka buku arsip yang berada di belakangnya, sembari mencocokkan dengan catatan berisi resep obat.
“Bulan depan Pak Adithama harus check up ya. Kalau bisa, bapaknya harus rutin check up sebanyak tiga bulan sekali, soalnya resep ini dibuat saat Bapak Adithama terkena serangan yang kedua.”
Phiko mengulum bibir, sebelum akhirnya melontarkan pertanyaan. “Biasanya berapa, Mbak?” Ia yakin Vino juga tidak mengetahui jawabannya. Bapak tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan.
“Tergantung. Mulai dari dua ratus sampai lima juta rupiah.”
Phiko menyisiri rambutnya yang mulai menutupi mata itu. Ucapan petugas itu terus terngiang-ngiang di telinganya sampai ia dan kakaknya terduduk di kursi tunggu depan apotek.
Setidaknya, Phiko harus mulai mengumpulkan uang untuk pemeriksaan Bapak bulan depan. Dari mana dirinya bisa mengumpulkan uang sekiranya lima juta dalam waktu singkat? Ia sudah tidak memiliki tabungan. Tabungan yang dimiliki Vino sekarang pun, pasti akan dipakai untuk membayar biaya rumah sakit Finna, itu pun ada tambahan dari pihak hotel karena lalai dalam keamanan.
“Gue pasti bakalan ngumpulin duit lagi buat lo, Phi.”
Phiko mengembuskan napas gusar. Ia menyandarkan kepala pada dinding di belakang, menatap lekat kedua mata Vino.
“Nggak perlu mikirin masa depan gue, No.” Tangan Phiko menggapai paha Vino. “Tabungan lo itu kita pakai sekarang. Pergunakan terutama buat lo sendiri. Kuliah gue gampang, itu masalah nanti. Lagian, belum tentu keumuran juga, kan?”
“Hush! Lo ngomong apa sih? Gak usah ngomongin umur.”
Phiko mencengkeram lutut erat-erat. Akhir-akhir ini, perutnya selalu berputar dan merasakan nyeri yang tidak terkira, kepalanya juga selalu pusing, belum lagi jantungnya kerap berdebar tanpa sebab. Namun, Phiko enggan memberitahu keluarganya. Ia akan menerima rasa sakit ini secara diam-diam, barangkali sebuah karma yang diturunkan Tuhan. Diam-diam pula Phiko mencari tahu melalui internet, jujur saja dirinya merasa was-was dengan hasil yang ditunjukkan padanya.
Vino menarik adiknya ke dalam rangkulan, menyandarkan kepala itu ke pundaknya. Vino yakin, Phiko sedang membutuhkan istirahat sekarang juga. Meski penderitaan telah menimpa pada keluarganya, setidaknya Phiko ikut merasa terbebani. Terhitung sudah tiga kali Phiko berada di rumah sakit, melihat keluarganya terbarik di brankar rumah sakit. Pertama Bapak dengan serangan jantung, kedua dirinya dengan kecelakaan fatal, dan sekarang Finna.
Baik Phiko, Finna, dan Vino sudah tidak memiliki tabungan sekarang. Tabungan Phiko habis untuk Bela, Vino habis untuk biaya rumah sakit Finna, dan sebagian tabungan berhasil diambil oleh perampok yang berhasil kabur. Uang untuk membeli obat Bapak adalah tabungan terakhirnya.
“Atas nama Bapak Adithama,” panggil apoteker.
Kala Phiko mengangkat kepala, Vino lebih cepat beranjak. “Gue aja.”
Vino mengambil obat tersebut dan kembali. Lelaki itu berdiri di hadapan adiknya. Mereka saling pandang dengan tatapan nanar. Obat tersebut diberikan kepada Phiko karena Vino sedikit kesulitan membawanya.
“Lo pulang, ya? Sama Bapak. Biar gue yang jaga Finna di sini.”
Kantung mata Phiko mendadak menggenang, membuat Vino mengernyitkan keningnya. Tak lama, bulir bening itu menyeruak keluar, hingga memecah isakan cukup besar. Phiko menangis terseguk-seguk, Vino dibuat panik. Masih ada beberapa orang di area apotek ini, mereka sekarang menatap si kembar dengan tatapan menuduh Vino sebagai pelaku.
“Heh! Heh! Jangan nangis. Orang kira gue abis marahin lo,” peringat Vino.
Lelaki itu lantas menyeret adiknya keluar dari rumah sakit. Susah payah ia menuntun Phiko dengan tangan kanannya yang cacat itu, belum lagi kaki kanannya juga tidak bisa terangkat sempurna untuk melangkah.
Keduanya kini berada di pinggir pintu depan rumah sakit. Duduk di bangku panjang. Vino membiarkan adiknya menangis sampai dirasa puas. Vino jadi teringat akan masa kecil mereka. Sedari dulu, Vino jarang sekali menangis. Sementara Phiko adalah anak yang paling cengeng sedunia. Awalnya, Vino sempat berpikir jika Phiko sudah berubah saat adiknya itu bersikap dingin terhadap keluarga. Tapi, Phiko tetaplah Phiko.
Perlahan tangis Phiko mulai berhenti. Ia menghapus jejak air matanya di wajah. “Gue takut, No.”
Vino mengembus napas gusar. “Takut kenapa?”
“Gue takut nggak kuat.”
“Kenapa? Lo punya gue, punya Finna, punya Bapak. Lihat gue, Phi, walaupun keadaan gue kayak gini, gue tetep kuat. Ya, meskipun pernah gak semangat hidup selama sebulan, sih. Tapi, itu cara gue belajar nerima diri gue yang baru. Lihat Bapak, Phi. Bapak diselingkuhin sama perempuan yang dia cintai, dan Bapak tetep kuat bareng kita. Sekarang, lihat Finna, dia baru dinyatakan buta sama dokter, belum genap satu hari tapi Finna udah bisa senyum. Artinya apa? Artinya dia yakin bakal kuat menghadapi semua ini. Sekarang gue tanya, kenapa lo sampai bilang begitu, Phi?”
Pandangan Phiko lantas menerawang menatap langit malam. “Gue ... gak punya jati diri, No.”


 thisadciel
thisadciel