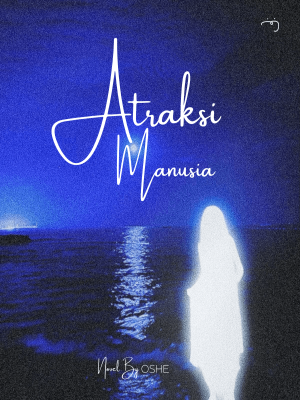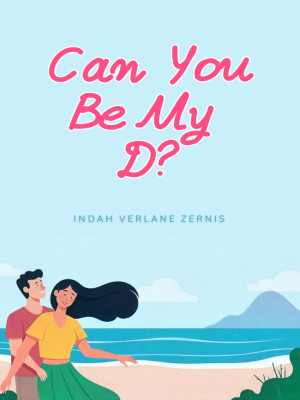Vino benar tentang Finna. Belum genap seminggu gadis itu kehilangan pendengarannya, sehari setelah keluar dari rumah sakit, ia berani kembali masuk sekolah. Tak peduli adanya omongan negatif dari warga sekolah, Finna benar-benar melangkahkan kaki di sekolah sekarang.
Banyak yang menyayangi Finna. Mendengar kabar penyergapan yang membuat Finna kehilangan indra penglihatan, teman-temannya banyak yang datang menjenguk, lebih banyak daripada Vino kemarin. Bahkan saat di rumah pun masih ada yang menjenguknya. Teman-temannya menuntun Finna hingga masuk ke kelas, mereka berkumpul di bangku Finna untuk sekadar mengobrol atau menghibur gadis itu. Finna menggantungkan buku cacatan kecil di leher, agar memudahkan orang-orang bisa berkomunikasi dengannya.
Phiko hanya bisa melihat interaksi itu dari kejauhan, di bangku paling depan.
“Tenang aja, kalau ada guru yang bicara, nanti bakal aku tulis di sini, ya,” ujar teman sebangkunya.
Phiko mengulum senyum tipis. Mengembalikan posisi tubuh menghadap ke depan. Mungkin, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk Finna. Bahkan Vino sekalipun. Phiko melihat kakak sulungnya berada di lapang basket yang terlihat dari dalam kelasnya. Lelaki itu sudah berani melepaskan arm sling di sekolah, memperlihatkan keadaan tangan kanannya yang sebenarnya. Vino juga tampak percaya diri dengan kaki palsu dan tongkat siku di tangan kirinya itu. Kedua kakaknya sudah percaya diri dengan keadaan terbaru mereka. Namun, di sini Phiko yang makin terpuruk.
“Nilaimu katanya hancur ya, Phiko?”
Jam pelajaran pertama sudah dimulai. Diawali oleh guru menyebalkan, Pak Goyara. Guru muda itu mendekatkan wajahnya dengan wajah Phiko, memiringkan kepala. Masalahnya, Pak Goyara berbicara seperti itu ketika kelas sedang hening, lebih tepatnya ketika beliau tengah berorasi tentang ambisi seorang anak kelas dua belas.
“Sayang sekali, justru nilai kelas dua belas adalah nilai terpenting yang harus kalian peroleh jika ingin meneruskan ke perguruan tinggi. Jangankan perguruan tinggi, bekerja pun kalian masih membutuhkan nilai.”
Phiko hanya bisa menundukkan kepala untuk menghindar dari kontak mata Pak Goyara. Guru itu akhirnya berjalan menuju tengah kelas, mendekati Finna. Pak Goyara menatap Finna secara sekilas. Jelas beliau sudah tahu kabar buruk tentang gadis itu. Namun, ia tampak tak selera membahasnya.
“Di sini ada yang nilainya stabil?” Pak Goyara kembali membahas topik yang sama, nilai.
Salah seorang murid lelaki mengangkat tangan.
“Saya, Pak. Nilai saya di kelas sepuluh memang kecil, tapi makin sini nilainya terus meningkat.”
Pak Goyara bertepuk tangan bangga. “Bagus. Pertahankan. Kalian semua juga pertahankan, usahakan di semester satu ini nilai kalian bagus-bagus. Sebab penentuan untuk masuk PTN jalur prestasi hanya dihitung hingga semester lima saja.” Pak Goyara berjalan kembali ke depan kelas. “Beruntunglah kalian yang tidak menggebu di awal-awal.”
Bunyi tongkat siku saling bersentuhan dengan permukaan tanah terdengar mendominasi di sepanjang gang menuju toko Bapak di pasar. Phiko sedari tadi menatap punggung kedua kakaknya dengan pandangan sendu. Kedua remaja disabilitas itu saling menuntun, sementara adiknya yang normal tak bergeming sembari menyakukan kedua tangan.
“Tadi pagi, Pak Goyara nyebelin banget, kan, Phi? Huh, kalau boleh mengumpat, aku udah ngomong kasar daritadi,” celetuk Finna memecah keheningan.
“Nyebelin gimana?” tanya Vino penasaran. Ia mengangkat bahu. Finna membaca pertanyaan Vino dari gerakan mulutnya
“Masa, beliau nyindir Phiko terang-terangan di kelas karena nilai Phiko turun? Maksudnya, kalau mau negur tuh gak perlu depan kelas gitu. Aku tau karena temen sebangkuku yang bilang di buku ini.”
Gadis itu mengangkat buku di lehernya.
Vino mendengkus. Kali ini ia berhenti sejenak, menuliskan responsnya di buku Finna karena cukup panjang. “Dia tuh apa sih? Guru baru lulus atau pindahan?”
“Katanya pindahan, dipindahin kepala sekolahnya.”
“Pantas aja. Di sekolah sebelumnya juga pasti gak disuka tuh sama muridnya.” Kali ini Vino tak berniat memberitahu responsnya kepada Finna.
Kepala Phiko tiba-tiba pening lagi. Dadanya berdebar kencang, kali ini disertai sesak. Phiko tidak bisa ikut nimbrung pembicaraan bersama kedua kakaknya. Dada Phiko makin nyeri. Ia memberhentikan langkah, mencoba mengatur deru napas, tapi tidak bisa, tak sadar dirinya sudah tertinggal jauh.
Phiko mulai bersimpuh. Pandangannya memburam. Samar-samar, ia melihat kedua kakaknya menyadari ketertinggalan Phiko. Namun, Phiko tak bisa mengembalikan kesadarannya. Secara perlahan, pandangannya mulai gelap, ia tak bisa mendengar apa pun selain deru napasnya sendiri.
Jika benar penyakit yang ditemukannya di internet memang ia derita—menyebabkan kematian, tolong jangan sekarang. Phiko ... masih harus membalas budi kepada keluarganya.
“Asam lambung itu biasanya disebabkan oleh pikiran, cemas berlebih, atau bahkan depresi. Tapi, melihat keadaan adik Phiko ini, sudah memasuki diagnosa gerd. Saran saya, sebelum menyembuhkan penyakit di tubuhnya, kita juga harus menyembuhkan penyakit di mentalnya. Karena jika mentalnya masih sakit, pasien masih sering cemas berlebih, maka gerd itu pun akan terus membuntutinya.”
Penjelasan dokter sangat jelas sekali, menusuk ke hatinya. Kini giliran Phiko yang terbaring di ranjang rumah sakit. Tangan Phiko yang bebas dari infusan digenggam erat oleh Finna. Beberapa langkah di belakang Finna, ada Ibu yang duduk dengan dagu terangkat, wajah datar, dan sedikit marah. Mungkin ... karena waktunya terganggu oleh anak merepotkan seperti Phiko.
Phiko pingsan di gang menuju toko Bapak. Karena terlalu mendadak, Finna membuat keputusan yang dirasa benar, tapi rupanya salah total. Finna menyuruh Vino untuk pergi memberitahu Bapak, sementara dirinya menelepon Ibu untuk meminta bantuan.
Ibu memang datang, menggunakan mobilnya. Antara terkejut karena Finna menjadi gadis tuli, atau kesal karena tempat Phiko pingsan ada di dalam gang, sepanjang perjalanan Ibu tak henti-hentinya mengomel. Pekerjaan di rumahnya tertundalah, ia terpaksa menitipkan bayinya di tetanggalah, dan banyak lagi amarah Ibu yang diluapkan kepada Finna. Namun, Finna tidak bisa mendengarnya, hal ini membuat Ibu bertambah kesal. Belum lagi, katanya Bapak hampir terkena serangan jantung saat mendengar Phiko pingsan. Aneh, sebelumnya, saat kemalangan menimpa Vino dan Finna, Bapak tampak tegar dan kuat. Mengapa Bapak bisa melemah hanya karena Phiko pingsan?
Bagaimana jika setelah ini Bapak mendengar Phiko mendapatkan riwayat gerd? Apakah Bapak tak akan ikut pingsan nantinya? Sekarang Bapak sedang dalam perjalanan bersama Vino.
“Memang, apa yang gue khawatirin ya, Fin? Sampai bisa kena gerd gini, lebay banget,” ujar Phiko dengan nada lemah.
Kepala Finna terangkat karena merasakan getaran pertanda Phiko sedang berbicara. Ia memberanikan diri melepas salah satu tangannya untuk meraba leher adiknya, lantas menggapai wajah tampan itu. Kemudian Finna tersenyum manis. Jemarinya menyisiri helaian rambut hitam Phiko dengan lembut.
Phiko menghela napas panjang. Ia memejamkan kedua matanya. “Pusing, Fin.”
Kali ini Finna bisa tahu. “Aku pijitin, ya.” Finna bangkit dari duduk, melepaskan genggaman, kedua tangannya mulai memijati pelipis Phiko.
“Apalagi yang kamu butuhin, hm? Minum? Makan? Atau apa? Perutnya masih sakit?”
Phiko menggeleng lemah. Entah untuk menjawab pertanyaan Finna yang mana, Phiko sendiri tidak tahu. Ada banyak pertanyaan di kepalanya yang mengganggu.
“Gue sakit apalagi selain gerd, Fin? Gue nggak begitu inget sama penjelasan dokter tadi.”
Finna sangat ingin bertanya. Finna sangat ingin menyuruh Phiko menulis ucapannya di buku kecil itu. Namun, Finna tidak berani, Finna tidak mau tenaga adiknya terbuang karena dirinya.
“Siapa yang bayar biaya rumah sakit, Fin?”
Kali ini Finna terdiam, pijatannya juga berhenti. Finna bisa membaca gerakan mulut Phiko. Gadis itu menurunkan kedua tangan. Sejujurnya, Finna juga tak tahu siapa yang akan membayar biaya rumah sakit Phiko ke depannya. Ibu memang membayar biaya awal untuk mendapatkan kamar rawat, tetapi untuk besok-besok? Entahlah. Uang tabungan Finna sudah habis, Vino juga. Uang Bapak pasti tidak seberapa, mengingat harga buku bekas tidak ada jaminannya.
Pintu kamar dibuka, Phiko menoleh, Finna juga menyadari kedatangan Bapak dan Vino.
“Phiko!” seru Bapak. Namun, langkahnya langsung terhenti begitu Bapak menangkap sosok Ibu yang baru berdiri dari sofa.
Mata Bapak sedikit membesar. Ibu ... terlihat elegan menurutnya. Memakai baju kasual berwarna putih, rambutnya tertata rapi, ada wewangian yang tercium bahkan dari jarak dua meter. Diam-diam Bapak mengulum senyum, mantan istrinya itu tampak sejahtera jika tidak bersama dirinya.
Berbeda dengan Bapak yang berbinar, hati Ibu berkata sebaliknya. Mungkin, karena bertahun-tahun dilayani seperti ratu oleh uang dari suami barunya, Ibu memandang Bapak rendah. Apalagi anak-anaknya. Vino memakai kaki palsu, Finna buta, dan sekarang apalagi? Phiko menderita penyakit pencernaan serius.
“Kamu becus tidak mengurus anak?” Pertanyaan itu lolos menjadi sapaan setelah mantan pasangan itu tidak bertemu selama bertahun-tahun. “Kalau tidak sanggup, kirimkan saja mereka ke panti asuhan.”
“Kara, aku—”
“Jawab pertanyaanku, kamu bisa tidak mengurus anak?” Ibu melangkah mendekati Bapak “Sewaktu perceraian kita, kamu sok-sokan mau ambil hak asuh anak. Sekarang, kamu jadikan mereka berkorban, apa itu yang dimaksud bisa mengurus anak?”
“Ini rumah sakit, Kara, jangan bertengkar di depan anak-anak juga. Phiko sedang sakit.”
Ibu mengibaskan tangannya. “Biarkan! Biarkan mereka tau, jika mereka sebenarnya punya ayah yang tidak berguna seperti kamu!”
“Aku sudah mencoba, Kara.”
“Mereka tidak mungkin bekerja sampai mereka cacat jika bukan karenamu, Adithama!”
Kali ini Bapak terdiam. Ia menundukkan kepala, menyembunyikan air mata dari siapa pun yang sedang melihatnya sekarang. Di benaknya, mantan istrinya ini ada benarnya. Tidak mungkin Vino dan Finna bekerja jika ia bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seharusnya, Vino dan Finna menjadi anak remaja pada umumnya seperti Phiko yang hanya memikirkan cara masuk perguruan tinggi.
Dilihat dari sisi seorang ibu, tidak ada ibu yang menginginkan anaknya kesulitan dalam hidup. Ibu memang kurang memedulikan anak-anaknya setelah bercerai, tapi melihat kondisi ketiga anaknya seperti ini, cukup melukai hatinya hingga tak sadar memarahi Finna secara berlebih.
“Jika tidak, kau saja yang mati, daripada merepoti anak-anakmu, Adithama.” Ibu lantas pergi, secara sengaja menabrak bahu Bapak dengan cukup keras.
Setelah Ibu benar-benar pergi, ruang menghening. Finna bergegas mendekat. Apa pun yang diucapkan Ibu barusan, mungkin itu tidak baik untuk bapaknya. Terlebih melihat reaksi tidak mengenakkan dari Vino dan Phiko.
“Bapak, jangan dipikirkan, ya?”
Finna memeluk Bapak dengan erat. Tubuh Bapak terasa bergetar, tapi tak terdengar sedikit pun isakkan.
“Bapak jangan pergi ke mana-mana. Bapak harus tetap hidup bareng kita. Kita juga nggak akan pergi ke mana pun asal ada Bapak di rumah.”
Bapak hanya diam saja. Setelahnya pun Bapak hanya diam. Bapak jarang mendatangi rumah sakit untuk menemani Phiko. Setiap malamnya, Phiko hanya ditemani oleh kedua kakaknya. Kakak-kakaknya juga bilang, kalau Bapak jadi pemurung, malas minum obat, dan menghabiskan waktunya di kamar saja.
Hari ini, Phiko bisa melihatnya secara langsung. Tiga hari mendapat perawatan intensif, Phiko akhirnya diperbolehkan pulang. Ibu yang membiayai semua pengobatan Phiko. Bersama dua kakak kembarnya, mereka pulang menggunakan taksi online. Bapak tidak menyambut kepulangannya di rumah. Suasana rumah hening sekali. Dapur pun tidak berasap, tidak ada satu pun masakan di meja makan.
Phiko memberanikan diri berdiri di depan pintu kamar Bapak yang tertutup rapat. Sejenak ia menoleh ke belakang, menatap kedua kakaknya yang berada di ruang sofa.
“Gapapa, masuk aja,” ujar Vino. Lelaki itu tersenyum sekilas.
Vino bilang, mungkin hanya Phiko yang bisa membujuk semangat Bapak. Mengingat sedari dulu, Phiko setia di sebelah Bapak saat sehat maupun sakit. Phiko tidak pernah mengeluh, Phiko selalu menuruti kata Bapak, Phiko juga berprestasi dan sudah membuat Bapak bangga dengan pencapaian akademiknya. Bukan berarti kepada Vino atau Finna Bapak tidak bangga, tetapi dua anak itu memang tidak cukup dekat dengan Bapak.
Hari itu, saat Ibu memarahi Bapak secara tiba-tiba di rumah sakit, sebenarnya mereka berdua ingin mengelak, kalau bekerja adalah keinginan mereka. Dulu juga Bapak sempat melarang, tapi mereka tetap keras kepala. Bapak sebenarnya sanggup membiayai kebutuhan anaknya, sekadar makanan sederhana atau biaya bulanan, Bapak pasti bisa. Namun, Vino dan Finna selalu menganggapnya kurang.
“Bapak, Phiko udah pulang.” Phiko membuka pintu kamar Bapak setelah yakin penuh. Matanya beredar, hingga menemukan pria paruh baya itu tengah terduduk di kursi, menghadap ke jendela dengan buku biru di tangannya, buku kesukaannya.
Bapak menoleh. Dua sudut bibirnya terangkat. “Anak Bapak. Sudah sehat, Nak?”
Phiko bisa bernapas lega saat mengetahui Bapak baik-baik saja. Lelaki itu menutup pintu setelah masuk, duduk di tepi kasur bapaknya. “Lumayan, Pak.”
“Perutnya masih sakit?”
Phiko menggeleng pelan. “Sudah tidak.”
Bapak bangkit dari kursinya, duduk di sebelah Phiko, meletakkan buku di meja kecil sebelah kasur. Phiko menatap buku itu lekat. Di kamar sederhana ini, ada rak buku cukup tinggi, berisi buku-buku lama koleksi Bapak, sebagian lagi buku pemberian Phiko. Namun, Bapak hanya membaca buku itu setiap kali Phiko jumpai.
“Itu sebenarnya buku apa, Pak? Dari aku masih kecil sampai sekarang, Bapak cuman baca buku itu terus.” Phiko menatap Bapak penuh harap.
“Bukan isi bukunya yang Bapak selalu baca.”
Phiko mengernyitkan kening. “Lalu?”
Bapak mengambil bukunya kembali. Ia membuka halaman paling akhir. Phiko melongokkan kepala. Terdapat sebuah kalimat yang ditulis tangan menggunakan pulpen di sana.
Tetap hidup demi anak-anak kita, Mas.
“Dari ... Ibu?” tebak Phiko.
Bapak mengangguk-angguk. “Tapi, bukan ibu yang kalian kenal.”
Phiko tersentak, matanya membesar. Sungguh ucapan Bapak tidak dapat dimengerti olehnya.
“Maksudnya? Bapak selingkuh juga?” Suara Phiko cukup tinggi, mengundang dua kakaknya berkumpul di kamar Bapak.
Finna kini duduk di sebelah Bapak. Finna memeluk lengan Bapak secara perlahan. Sementara Vino menarik buku tersebut dan membacanya, duduk di kursi dekat jendela.
“Bapak tidak pernah selingkuh, Phi,” lirih Bapak. Ia mengangkat kepala, menahan air mata agar tidak turun di depan ketiga anaknya.
“Kemarin, kalian berulang tahun yang kedelapan belas, ya?”
Vino dan Phiko kompak mengangguk. Bapak rasa, ini sudah saatnya ia menceritakan semua hal sebenarnya. Bapak mengambil buku yang dikalungkan dari leher Finna. Anak tengahnya ini juga harus tahu percakapan yang terjadi sekarang.
“Ibu yang selama ini kalian kenal, Ibu Kara, bukanlah ibu kandung kalian.” Bapak mengambil sesuatu dari bawah bantal, menunjukkannya kepada anak-anak. Sepasang kekasih yang baru saja menikah. “Ini ibu kandung kalian. Aleena, namanya.”
Ketiganya saling melemparpandang. Seorang perempuan di dalam foto ini memang jauh berbeda dengan ibu yang selama ini mereka kenal. Wajahnya lebih bulat, persis mirip seperti Finna. Gadis itu jadi gelagapan karena dimiripkan dengan seorang perempuan cantik.
“Saat mengandung kalian, ibu kalian terkena sakit autoimun. Dokter memprediksi, ia tak akan selamat saat melahirkan nanti. Satu bulan sebelum kalian dilahirkan, ibu kalian menyuruh Bapak menikah dengan sahabatnya, Kara, yang hingga kini kalian kenal sebagai Ibu. Aleena tidak ingin kalian tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Meski Bapak sudah menolak keras, tapi Aleena terus memaksa Bapak dengan ancaman akan membawa kalian bersamanya jika Bapak tidak menuruti keinginannya.”
Bapak mengembuskan napas gusar. “Prediksi dokter benar, Ibu mengalami pendarahan yang cukup hebat sampai merenggut nyawanya.”
“Itu sebabnya Bapak tidak pernah semangat setiap kali kita ulang tahun, ya?” ujar Finna.
Bapa menoleh, mengangkat dagu putrinya, mengusap wajah yang mirip dengan mendiang istrinya itu dengan lembut. “Bukan tidak semangat.” Bapak mengambil napas dalam-dalam. “Hanya teringat dengan ibu kalian.”
“Kenapa Bapak tega?”
Kali ini Vino yang bersuara.
“Kenapa Bapak tega menyembunyikan rahasia besar ini? Kenapa Bapak tega membuat kita percaya bahwa ibu melakukan hal sekeji itu dengan berpaling ke pria lain? Kenapa Bapak tega membuat kami sejahat itu kepada wanita yang sudah merelakan nyawanya?”
Phiko menendang pelan kaki palsu Vino saat kakaknya itu mulai meninggikan nada suara. Matanya terbelalak memperingati. Bapak tidak bisa berkutik. Ia mengulurkan tangannya, membuka halaman buku yang masih ada di tangan Vino. Lelaki itu membaca kalimat yang ditunjuk Bapak, lagi-lagi tulis tangan pena.
Jangan beritahu anak-anak bahwa aku adalah ibunya, Mas. Tunggu mereka sampai siap. Kasihan. Takutnya mereka akan marah kepadaku, kepadamu, atau kepada Kara.
Jika kamu memberitahunya saat mereka telah dewasa, kemungkinan besar mereka akan mengerti maksud baikku kepada mereka. Jika kamu memberitahu saat mereka dewasa, kemungkinan mereka akan sedikit paham dibarengi pertanyaannya, jawab setiap pertanyaan mereka, Mas. Dan jika kamu memberitahunya saat masih kecil, mereka pasti merengek dan meminta agar aku dihidupkan kembali.
Mas, sehat-sehat terus. Hiduplah bersama Alvino, Alfinna, dan Alphiko. Sengaja kubuat nama depannya mirip seperti namaku, agar kamu terus mengingat diriku hingga kita dipertemukan kembali nanti.
Vino tak kuasa memegang buku ini. Ia memberikannya secara paksa kepada Phiko. Sedangkan dirinya membuang pandangan kal menyadari adanya bulir air mata di kelopak matanya.
“Ibu kalian hanya menyuruh Bapak hidup bersama kalian, bukan bersama Kara.” Kemudian Bapak tertawa getir. “Jadinya Bapak ikhlaskan dia saat dia sudah menemukan pria idamannya.”
Bapak menyentuh lutut Phiko. Membuat pandangan Phiko tertarik. Bapak tersenyum kepadanya.
“Maka kamu juga ikhlaskan Ibu Kara bersama keluarga barunya, ya?”
Phiko menggigit bibir bawahnya. Beberapa saat kemudian, ia mengangguk kaku. Phiko meletakkan buku di atas meja kecil, lalu beranjak dari duduknya.
“Aku mengerti sekarang.” Phiko menghampiri jendela, menghirup udara kampung yang sedari kecil ia tempati. Meski aromanya kendal dengan sawah, tetapi di sinilah tempatnya tumbuh dan menjadi seorang Alphiko yang katanya ‘pintar’ itu.
“Kurasa, aku sudah menemukan jati diriku.” Phiko membalikkan tubuh. “Bersama kalian. Bersama Bapak, Finna, dan Vino.”
Phiko kembali mendekati keluarganya. Melempar senyum paling ikhlas yang bisa ia tunjukkan. Setelah kesalahpahaman yang Phiko lakukan kepada dua kakaknya, juga anggapan tentang hubungan pernikahan orang tuanya, rasanya kini adalah akhir dari drama ini semua. Sudah waktunya mereka menjalani kehidupan normal selayaknya keluarga. Meski tak ada ibu, tapi rumah harus tetap hangat tanpa ada dinding pemecah.
“Mulai hari ini, Phiko harap, kita bisa saling terbuka satu sama lain.”
Sore itu, Bapak mengajak tiga anak kembarnya ke pemakaman. Lebih tepatnya bertemu ibu kandung mereka. Tangis hingga tawa mengisi ruang selama hampir dua jam. Phiko yang lebih banyak bicara. Ia memberitahu Ibu bahwa Vino sudah main balap-balapan dengan temannya, meski langsung ditepis oleh Vino, balapan yang dimaksud adalah yang paling cepat menurunkan barang dari truk di pasar. Banyak lagi cerita yang Phiko adukan, salah satunya, di depan keluarganya, ia mengaku bahwa dokter memvonis—selain gerd—dirinya mengidap penyakit autoimun seperti Ibu.


 thisadciel
thisadciel