Bumi melangkah keluar kelas dengan tenang.
Di ambang pintu, Rika sudah berdiri menunggunya. Sebuah buku ia peluk erat di dada—seolah itu bisa menahan detak gugup yang tak mau tenang. Rambutnya sedikit berantakan ditiup angin dari jendela koridor, namun sorot matanya tak lepas dari Bumi.
"Ada apa, Rik?" tanya Bumi santai, tanpa ragu, tanpa formalitas.
Beberapa anak yang masih duduk di dalam kelas spontan menoleh. Dahi mereka mengerut. Bumi memanggil Rika tanpa 'Kak'? Dan lebih mengejutkan lagi, Rika tidak terlihat terganggu sedikit pun.
Rika mengulurkan buku yang dipeluknya. Sebuah novel Agatha Christie dengan sampul lusuh.
"Ini. Katanya lo mau pinjam setelah gue," ucapnya, sedikit tercekat.
Bumi menerima buku itu, lalu menyunggingkan senyum kecil. "Cepet juga lo bacanya."
Rika tersentak, seolah ucapan santai itu mengungkap sesuatu yang selama ini ingin ia sembunyikan.
"I-iya... Gue emang biasa baca cepat," katanya cepat, salah tingkah.
Bumi hanya mengangguk kecil. Lalu hening merambat di antara mereka. Rika mulai gelisah, menatap lantai sesekali, sementara Bumi tetap tenang seperti biasa—seakan waktu memang berjalan lebih lambat di sekelilingnya.
"Kalau gitu... gue duluan, ya." Rika mulai berbalik.
Namun langkahnya terhenti ketika suara Bumi terdengar lagi, pelan namun jelas.
"Udah makan belum?"
Rika menoleh, ragu.
"Gue laper. Mau ikut ke kantin?" lanjut Bumi, masih dengan nada santai.
Rika terdiam sesaat. Matanya mencari isyarat di wajah Bumi, seakan ingin memastikan ia tak sedang salah paham. Tapi Bumi hanya menatapnya, ringan, tanpa beban.
Akhirnya, Rika mengangguk pelan. "Boleh."
Bumi berbalik dan mulai berjalan tanpa menoleh lagi. "Yuk."
Rika buru-buru menyamakan langkah, wajahnya belum berhenti memerah.
Mereka melewati Geri dan Nino yang sedang bersandar di tembok dekat pintu kelas. Mata Nino membulat, mengikuti punggung Bumi dengan ekspresi tak percaya.
"Gila... Skill gaet cewek dia bener-bener level dewa," gumamnya kagum.
Geri, yang sejak tadi ternganga, hanya bisa mengangguk-angguk setuju.
***
Mereka duduk di salah satu pojok kantin, agak tersembunyi dari hiruk-pikuk anak-anak yang baru saja keluar kelas.
Bumi menyantap semangkuk soto ayam hangat dengan tenang, sesekali meniup uapnya sebelum menyuap perlahan. Di hadapannya, Rika masih menatap sotonya yang mengepul, tapi tak kunjung disentuh. Tangan kanannya menggenggam sendok, namun tidak bergerak.
Dari kejauhan, ia bisa melihat gengnya duduk di deretan meja tengah. Karla, Gina, dan Nora menatap ke arahnya—wajah mereka campuran antara bingung dan tidak percaya.
Getaran halus terasa di saku roknya. Rika merogoh pelan dan melirik layar ponselnya.
1 pesan masuk: Karla
GILA! Lu ngapain sm cowok serem anak kelas X itu??
Rika menggigit bibir. Lalu, tanpa banyak pikir, ia mengetik balasan singkat:
nnti gw critain.
Ia memasukkan kembali ponselnya, berusaha menjaga ekspresi netral.
“Kenapa?” tanya Bumi, tanpa menoleh. Suaranya datar, tapi ada nada penasaran yang samar.
“Enggak apa-apa,” jawab Rika cepat, sambil berpura-pura sibuk merapikan sedotan di gelasnya.
Bumi melirik sebentar ke arah meja geng cewek di tengah kantin, lalu kembali memandang Rika. “Ohh... temen-temen lo nanyain, ya?”
Jantung Rika berdetak kencang. Dia tahu? Bagaimana bisa?
“Kalau mau gabung sama mereka, enggak apa-apa kok,” lanjut Bumi sambil menyuap lagi makanannya. Nada bicaranya tenang, tak terkesan tersinggung sama sekali.
Rika buru-buru menggeleng. “Enggak, enggak apa-apa. Nanti juga ketemu mereka di kelas.”
Bumi hanya mengangguk pelan, tapi sudut bibirnya terangkat sedikit. Nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat dada Rika makin sesak oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan.
Ia mencoba menyuap sotonya. Tapi karena terlalu gugup, ia lupa bahwa kuahnya masih panas.
Begitu rasa panas menyambar lidahnya, Rika langsung terbatuk.
Tanpa melihat, Bumi menggeser gelas minumnya ke arahnya. “Hati-hati...”
Rika menerima gelas itu, meneguk sedikit sambil menunduk malu. Saat ia meletakkannya kembali, Bumi justru tengah memandangi wajahnya.
“Mata lo jernih banget, ya,” katanya, datar. “Gue jarang lihat mata cokelat sebersih itu.”
Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang mengomentari cuaca. Bukan seperti cowok yang baru saja melontarkan pujian paling menohok untuk cewek paling populer di sekolah.
Seketika, Rika membeku.
Wajahnya memanas. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut Bumi bisa mendengarnya. Tapi cowok itu? Ia kembali menyuap sotonya seperti tak terjadi apa-apa.
Rika menggigit bibir, menunduk dalam, berusaha keras menahan senyum yang hampir pecah.
Dari jauh, mata lain memperhatikan.
Theo, salah satu teman dekat Raka, berdiri membeku di dekat konter minuman. Tatapannya mengarah lurus ke meja pojok tempat Bumi dan Rika duduk. Ia menyipitkan mata, lalu berbalik dengan ekspresi gelap dan langkah cepat meninggalkan kantin.
***
Bumi tersenyum tipis. Ia bisa membaca Rika dengan mudah. Gadis itu sudah jatuh dalam pesonanya—tinggal satu sentuhan terakhir untuk membuat semuanya berjalan sesuai rencana.
Dan kesempatan itu datang.
Dari kejauhan, Bumi melihat Raka memasuki kantin dengan wajah marah. Tatapannya menyapu ruangan, mencari seseorang. Badai sedang bergerak mendekat, sementara Rika masih tenang menyuap sotonya, tak menyadari apa yang akan terjadi.
Mata Raka akhirnya menangkap mereka.
Bumi tersenyum licik.
Dengan tenang, ia menoleh ke arah Rika. Tangan kanannya terangkat pelan, lalu menyibak rambut panjang gadis itu, menyelipkannya ke belakang telinga. Gerakan itu sederhana tapi penuh makna. Rika mengerjap cepat, kaget. Ia menatap Bumi yang kini tersenyum dengan pesona percaya diri yang tak tergoyahkan.
“Hati-hati... rambut lo hampir kena kuah soto,” ucapnya ringan.
Rika menggigit bibir, dan kali ini, senyumnya tak bisa lagi ia sembunyikan.
Dari seberang, Raka tampak seperti naga yang baru saja menghirup bara. Ia melangkah cepat ke arah mereka, lalu—
BRAK!
Telapak tangannya menghantam meja hingga beberapa sendok bergetar.
Rika melonjak kaget. Tapi Bumi tetap tenang, bahkan nyaris terlihat menikmati kekacauan ini.
“Maksud lo apa?” bentak Raka, suaranya bergetar penuh amarah. “Lo sengaja kan deketin Rika?”
Bumi mengangkat wajah, keningnya berkerut kecil. “Gue enggak ngerti maksud lo.”
Rika langsung berdiri, menatap Raka tajam. “Lo ngapain di sini?”
“Kamu ngapain sama dia?” balas Raka, nadanya penuh tuduhan.
Rika mendengus. “Apa urusan lo gue mau ngapain sama siapa?”
Ekspresi Raka berubah—putus asa, campur marah. “Rikaa... dia deketin kamu tuh ada maunya...”
Rika melangkah maju, berdiri tegak di hadapan mantan pacarnya. “Terus kenapa? Kita udah putus, Raka. Udah selesai. Berapa kali harus gue bilang? Kita udah enggak ada hubungan apa-apa. Jadi stop ganggu gue!”
Di belakang mereka, Bumi menyandarkan punggung ke kursi, kedua tangannya terlipat santai di dada. Ekspresinya datar, tapi sudut bibirnya terangkat sedikit—senyum tipis yang sulit ditebak: dingin, puas, licik. Ia nampak cukup menikmati drama yang tersaji di hadapannya sekarang.
Dada Raka naik turun cepat. Ia tahu semua mata kini tertuju padanya. Si pentolan sekolah, ditolak mentah-mentah di depan umum oleh Rika—cewek paling populer.
Ia menatap Bumi tajam. “Kita bakal ketemu lagi nanti.”
Lalu ia berbalik dan pergi tanpa menoleh.
Bumi hanya menatap punggungnya, tersenyum miring.
Rika kembali duduk. Sisa ketegangan masih menggantung di napasnya.
“Sorry... jadi ribut. Gue udah putus sama dia. Tapi dia masih suka maksa buat balikan,” katanya pelan.
Bumi mengangkat bahu. “Enggak apa-apa. Wajar kalau ada yang enggak bisa move on dari lo.”
Ucapan itu membuat pipi Rika kembali memanas. Ia tertawa kecil, lalu terlihat ragu-ragu sejenak.
“Gue boleh minta nomor lo?”
Bumi menggeleng pelan. “Gue enggak punya HP.”
Rika mengerjap. “Oh… gitu…”
Ada sedikit kekecewaan yang menyelinap. Tapi juga ada rasa penasaran yang makin menguat. Masa sih dia enggak punya HP? pikirnya. Tapi daripada menjauhkan, justru itu membuat sosok Bumi semakin sulit ditebak.
Dan di dunia Rika, misteri selalu lebih menarik daripada kepastian.
***
“Bumi! Bumi!”
Dirga tergopoh menyusuri koridor lantai tiga, napas tersengal. Ia baru saja keluar kelas ketika melihat Bumi berjalan santai di kejauhan. Tapi saat ia mendekat, Bumi malah lewat begitu saja tanpa menoleh
“Heh, Bum! Lo abis ribut sama Raka di kantin, ya?”
Bumi mengangkat alis. “Ribut? Dia yang tiba-tiba aja dateng terus marah-marah. Gue sih cuma makan.”
“Lo sengaja deketin Rika buat mancing dia, kan?”
“Gue cuma makan bareng Rika. Dia bilang udah enggak ada hubungan sama Raka. Jadi… salah gue di mana?”
Dirga menghela napas frustrasi. Ia baru paham kenapa ibunya sering menyerah kalau bicara dengan Bumi. Anak ini keras kepala setengah mati.
Saat mereka sampai di lantai satu, Dirga kembali bicara, kali ini lebih serius. “Kalau Raka bales lo gimana? Sampai kapan lo mau main api?”
Bumi berhenti. Matanya menatap dingin. “Sampai dia nyerah... atau hancur.”
Seketika, seorang cowok muncul dari arah seberang.
“Theo…” gumam Dirga.
“Raka mau ngomong,” ucap Theo datar.
“Enggak usah ikut dia. Kita pulang aja,” bisik Dirga.
Tapi Bumi hanya menoleh sebentar. “Lo duluan aja.”
Tanpa menunggu, ia mengikuti Theo menuju lorong belakang sekolah. Tempat sepi.
Enam orang sudah menunggu. Raka berdiri di tengah, wajah gelap dan tangan mengepal. Bumi melangkah mendekat tanpa ragu.
Raka mencengkeram kerahnya. “Lo sengaja deketin Rika buat mancing gue, kan?!”
Bumi tersenyum miring. “Gue cuma mau buktiin satu hal. Lo mungkin bisa ambil barang gue, tapi gue bisa ambil cewek lo. Dan itu... gampang.”
Raka mengangkat tangannya, siap menghantam. Tapi Bumi malah tertawa. Keras.
“Lo mau mukul gue karena cewek lo lebih suka gue?” Ia mendekat. “Menyedihkan.”
Raka mulai goyah. Bumi menurunkan suaranya.
“Lo sama aja kayak Pak Erhan. Cuma bisa pakai kekerasan karena enggak punya otak.”
Ia melengkungkan bibirnya, senyumnya tipis dan menyakitkan. “Kalau mau ribut, boleh aja. Tapi lo pikir, kalau Rika tahu lo mukul gue… dia bakal kagum?”
Hening. Hanya suara angin sore yang berembus di antara mereka.
“Dia enggak cuma bakal benci,” lanjut Bumi, pelan tapi menusuk. “Dia bakal liat lo sebagai cowok payah. Yang kasar. Yang posesif. Dan yang paling penting... dia bakal makin simpatik sama gue.”
Hening. Hanya suara angin sore yang berembus di antara mereka.
Cengkeraman Raka melemah.
Bumi merapikan kerahnya, lalu menepuk bahu Raka. “Santai aja. Cewek di dunia ini banyak. Kalau gue dapet Rika, lo masih bisa cari yang lain.”
Ia berbisik, “Itu pun kalau mereka enggak mikir lo sekarang pecundang.”
Lalu ia pergi, tenang. Seperti habis menuntaskan ujian—dengan nilai sempurna.
Raka tetap berdiri kaku. Wajahnya kosong.
“Ayo hajar dia!” seru Theo. Tapi Bumi sudah hilang di tikungan.
Raka mengepalkan tinju, hendak mengejar. Namun Ikmal tiba-tiba menarik lengannya.
“Kenapa?!” bentaknya.
“Entar dulu, Ka. Gue... sebenernya dari kemarin mau ngomong ke lo.”
Raka mengerutkan kening. “Apa?”
“Gue cari tahu soal Bumi. Temen gue satu SMP sama dia.”
Raka menatapnya tajam. “Terus?”
“Katanya… dia dikeluarin dari SMP-nya dulu gara-gara mukulin tujuh orang. Sendirian. Tujuh-tujuhnya masuk rumah sakit. Tapi yang paling ngeri...”
Ikmal menelan ludah. “Katanya mereka yang dipukulin jadi beda setelah itu. Ada yang jadi paranoid. Ada yang enggak berani sekolah lagi. Dan… gosipnya, Bumi kemungkinan... psikopat.”
Hening.
Sore yang dingin terasa makin mencekam.
Raka menatap ke arah Bumi menghilang. Ketakutan mulai merayap, tapi kebenciannya... justru makin membara.
Dan itu… bisa jauh lebih berbahaya.


 dwyne
dwyne

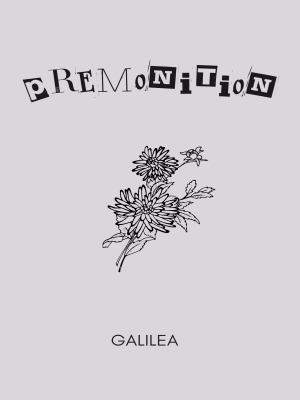






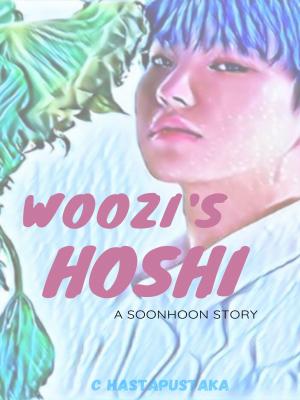


suka dengan bagaimana kamu ngebangun ketegangan di awal, adegan di toilet itu intens, tapi tetap terasa realistis. Dialog antar karakter juga hidup dan natural, terutama interaksi geng cewek yang penuh nostalgia masa SMA; kaset AADC dan obrolan ringan itu ngena banget.
Comment on chapter Pandangan Pertama