Entah sejak kapan, Rika mulai merasa ada yang kurang jika hari itu tidak melihat Bumi.
Cowok itu mulai muncul di sudut-sudut harinya seperti bayangan, di koridor, di kantin, di antara rak-rak perpustakaan. Tak selalu dekat, tak selalu bertemu mata, dan tak pernah menyapa. Tapi cukup untuk mengisi ruang kosong yang tak bisa didefinisikan.
Dan anehnya, kini ia justru mulai mencarinya.
Jika hari itu Bumi tidak terlihat, Rika merasa gelisah. Seolah ia telah kehilangan bagian dari rutinitas yang pelan-pelan menjadi obsesi.
Sore itu, selepas sekolah, Rika kembali ke perpustakaan dengan sedikit harapan bisa tanpa sengaja melihat Bumi di sana.
Ia mengembalikan beberapa buku ke penjaga, lalu berjalan perlahan di antara rak-rak fiksi. Jemarinya menyusuri punggung-punggung novel dengan kebiasaan yang kini terasa personal, seolah berharap sentuhan itu bisa menarik sesuatu lebih dari sekadar bacaan.
Saat tiba di bagian yang ia cari, ia menghela napas pelan. Agatha Christie.
Belakangan ini, buku-buku misteri dari penulis itu menjadi pelarian favoritnya. Dan hari ini, ia berniat membawa pulang satu lagi.
Tangannya terulur, hendak mengambil sebuah buku bersampul hijau tua.
Tapi sebelum sempat menyentuhnya, satu tangan lain muncul, nyaris bersamaan.
Rika reflek menoleh.
Bumi.
Cowok itu berdiri di sampingnya, terlalu dekat untuk sekadar kebetulan. Datar. Tenang. Dan sekali lagi, membuat jantung Rika berdegup lebih cepat tanpa alasan yang masuk akal.
“Mau minjem juga ya?” tanya Bumi, nyaris seperti gumaman.
Rika mengangguk pelan.
Bumi menarik tangannya. “Yaudah. Duluan aja.”
Ia berbalik. Tapi sebelum benar-benar pergi, Rika menelan gugupnya dan bertanya,
“Suka Agatha Christie juga?”
Langkah Bumi berhenti. Ia tak langsung menoleh, hanya sedikit menolehkan kepala. Diam sejenak, seolah sedang menilai apakah pertanyaan itu pantas dijawab.
Lalu ia berbalik perlahan. Wajahnya tetap tanpa ekspresi.
“Enggak,” jawabnya datar. “Cuma penasaran kenapa banyak yang suka.”
Rika mengangguk, mencoba tetap terlihat santai. “Tapi pernah baca?”
Bumi mengangkat bahu. “Beberapa.”
Jawaban itu terlalu ringan. Terlalu mengambang.
Ada keraguan yang muncul di hati Rika. Ia sudah sering bertemu cowok yang berpura-pura menyukai apa yang ia suka hanya untuk mencuri perhatiannya.
Apa jangan-jangan dia juga begitu?
Rika memiringkan kepala sedikit. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya.
“Yang mana?” tanyanya datar.
Bumi diam.
Setengah detik.
Satu detik.
Dua detik.
Suara AC di langit-langit mendadak terdengar lebih keras.
Wajah Bumi tetap tak berubah. Tapi diam itu... terlalu panjang bagi seseorang yang katanya pernah membaca.
Ketahuan. Rika hampir yakin.
Tapi kemudian—
“The Murder of Roger Ackroyd,” jawab Bumi pelan.
“Awalnya ngebosenin. Terlalu banyak ngobrol. Tapi makin ke belakang... twist-nya bagus. Gue enggak nyangka bakal seberani itu. Penulisnya gila juga sih, bisa bikin pembaca ngerasa ditipu dengan elegan.”
Rika terdiam.
Itu... persis dengan yang ia rasakan saat membaca buku itu.
“Oh... lo udah baca itu ya?” gumamnya. Nada curiganya perlahan mencair.
Bumi hanya mengangguk kecil. Tak menatapnya lama. Tak terlihat tertarik membuatnya kagum. Justru karena itu... Rika makin penasaran.
Ada ketenangan dalam suaranya. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik itu.
Dan yang tak ia tahu, semua itu bukan dari Bumi.
Bumi tersenyum tipis.
***
Sagara melangkah pelan di sepanjang jalan menuju rumah, ranselnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena buku, tapi karena sebuah kotak mungil berhias pita merah muda di dalamnya, hadiah dari seorang teman cewek di sekolah yang diam-diam menyukainya. Sagara tidak pernah tahu bagaimana cara menolak secara halus. Dan kini, perhatian itu mulai terasa seperti beban yang menggelayut di pundaknya.
Setiap kali hendak bicara jujur, lidahnya menolak bekerja. Rasa iba menahan semua penolakan yang sudah disusun rapi di kepalanya.
Ketika ia membuka pintu rumah, aroma masakan langsung menyambutnya.
“Udah pulang, Gara?” sapa Indira dari dapur, tangannya sibuk menyiapkan makan sore untuk Agni yang sedang asyik bermain di depan televisi.
Sagara mengangguk tanpa suara. Ia berjalan menuju kamarnya, sempat berjongkok sebentar di hadapan adiknya yang kecil itu untuk memastikan mainan plastik yang sedang ia kunyah tidak tertelan.
“Ala,” gumam Agni sambil tetap mengemut mainan bulat di tangannya.
Sagara tersenyum tipis, menepuk lembut kepala Agni singkat, lalu bangkit dan menuju kamar.
Saat pintu kamarnya terbuka, Sagara langsung berhenti di ambang pintu. Seseorang sedang duduk santai di atas tempat tidurnya, kaki terjulur, dan sebuah buku Agatha Christie terbuka di tangannya. Seolah ruangan itu miliknya.
“Ehhh… Gara udah pulang,” sapa Bumi santai, senyumnya tipis dan menyebalkan.
Sagara menarik napas keras. “Ngapain lo di sini?” tanyanya dengan nada tidak suka.
“Cuma mau minjem buku,” jawab Bumi tanpa rasa bersalah.
Sagara menyipitkan mata, memperhatikan buku di tangan saudaranya. “Sejak kapan lo baca buku kayak gitu?”
Bumi mengangkat bahu. “Gue cuma pengen tahu kenapa banyak orang suka sama buku ini. Lo suka baca Agatha Christie, kan?”
Sagara masih menatapnya curiga, tapi akhirnya duduk di kursi meja belajarnya dan menjawab juga. Ia menjelaskan singkat kenapa ia menyukai gaya penceritaan Christie yang penuh teka-teki.
“Lo sendiri, buku favorit lo yang mana?” tanya Bumi setelahnya, nadanya seperti obrolan biasa.
Sagara berpikir sejenak. “The Murder of Roger Ackroyd.”
“Kenapa?”
Ia menjelaskan alasannya, alur yang pelan tapi memutar, kejutan di akhir yang brilian, dan bagaimana penulis mampu memperdaya pembaca dengan cerdas. Bumi hanya mengangguk-angguk, seolah menyerap semua informasi.
Lalu ia kembali menatap buku di tangannya, membalik halamannya dengan malas.
“Gue sempet baca sekilas,” katanya sambil menimang-nimang buku. “Tapi gue udah bisa langsung nebak pelakunya dari bab pertama. Heran deh, di mana serunya baca kayak gini.”
Sagara mengangkat alis. “Ya itu kan lo. Buat orang lain, nyari petunjuk dan ngerakit teka-teki itu seru.”
Bumi mengangkat bahu acuh. “Gue sih punya bacaan yang lebih seru.”
Sagara mengerutkan kening. Tapi sebelum sempat bertanya, Bumi tiba-tiba menyeringai lebar.
Ia mengangkat buku yang tadi dibacanya, dan mulai membaca nyaring.
“'Sagara, sejak pertama kali aku lihat kamu, aku ngerasa ada sesuatu yang beda…'”
Jantung Sagara mencelos.
Surat cinta dari teman ceweknya di sekolah yang ia selipkan di rak buku sekarang ada di tangan Bumi.
Panik, ia bangkit dan maju cepat.
“Balikin!” serunya.
Tapi Bumi tetap duduk santai dan melanjutkan,
“'Kamu enggak kayak cowok-cowok lain. Maaf aku harus kasih surat ini, soalnya setiap kali ngomong langsung sama kamu, jantung aku berdebar-debar enggak karuan…'” Bumi membacanya dengan gaya dramatis.
“BUMI!! BALIKIN!!!” Sagara maju, mencoba merebut buku itu.
Tapi Bumi sudah berdiri, menjauh dengan tinggi badan yang sulit dijangkau Sagara.
“'Aku suka sama kamu, Sagara. Kamu mau enggak jadi pacar aku?'”
Tawa Bumi meledak, kasar dan puas.
Sagara mengumpat keras, tak peduli kalau ibunya mungkin bisa mendengar dari dapur. Ia berusaha meraih buku itu, tapi Bumi hanya mengangkatnya lebih tinggi sambil terkekeh, membuat Sagara tidak bisa menjangkaunya karena perbedaan tinggi mereka.
“Gara… Gara… pantesan lo kemarin ‘ngompol’, udah punya pacar ternyata…” godanya dengan tawa yang sulit ditoleransi.
“KELUAR!!!!” raung Sagara, wajahnya memerah karena malu dan marah.
Bumi melempar buku berisi surat itu ke tempat tidur, lalu membuka pintu sambil melambai dan tertawa. “Maaah! Sagara udah punya pacar!” teriaknya.
Sagara melempar buku tebal ke arah pintu—terlambat. Buku itu hanya menghantam kayu yang baru saja tertutup rapat.
Ia berdiri di tengah kamar, napasnya terengah karena emosi. Dari balik pintu, samar-samar, tawa Bumi masih terdengar memudar, menggema, dan entah kenapa… jauh lebih menyebalkan dari biasanya.
***
Rika sempat menatap Bumi selama beberapa detik, sebelum kemudian menyodorkan buku Agatha Christie yang ia ambil tadi. “Lo mau baca duluan? Gue cuma iseng aja tadi ambil yang ini. Gue bisa ambil yang lain.”
Bumi melihat buku di tangan Rika, lalu menggeleng sambil tersenyum kecil.
“Enggak apa-apa. Lo duluan aja,” Bumi akan berbalik pergi, tapi kemudian ia menoleh lagi.
“Nanti gue baca setelah lo ya,” katanya sambil menyeringai kecil. Seringai penuh percaya diri yang membuat Rika merasa kehilangan keseimbangan, seolah lantai di bawahnya terlalu goyah untuk dipijak.
Setelah mengatakan itu, Bumi berbalik pergi dan tidak menatapnya lagi.
Rika menatap buku di tangannya. Setelah bimbang beberapa saat, akhirnya ia memutuskan meminjam buku itu dan membawanya pulang.
Dan sampai malam tiba, pikiran tentang Bumi tidak bisa hilang dari kepalanya.
Rika berbaring di ranjangnya, lampu sudah dimatikan, tapi matanya belum juga terpejam.
Di meja belajarnya, buku Agatha Christie yang belum sempat ia baca tergeletak diam, tapi justru itu yang membuat pikirannya tidak tenang.
Bayangan percakapan singkat di perpustakaan itu kembali muncul, tatapan mata Bumi, kalimatnya yang pelan tapi mantap, dan senyum tipisnya yang terlalu sulit ditebak.
Rika melirik buku itu lagi.
“Aneh nggak sih… kalau gue nyamperin dia cuma buat ngasih ini?”
Ia menggeleng cepat.
“Kaya gue yang ngejar-ngejar dia… gila, gengsi banget.”
Ia menarik selimut menutupi wajahnya. Tapi hatinya gelisah. Ada yang terasa seperti mendesak keluar dari dadanya.
Satu menit.
Dua menit.
Ia menghela napas keras, melempar selimut ke samping, bangkit, lalu meraih buku itu dan memasukkannya ke dalam tas.
“Ya udah lah… cuma nganter buku. Enggak apa-apa kan harusnya?” gumamnya.
Tapi bahkan dirinya sendiri tahu, itu cuma alasan.
***
Jam istirahat siang. Tapi Rika masih duduk di kelasnya sambil menggenggam tali tas.
Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya.
Ia berdiri.
“Mau ke mana lu, Rik?” tanya Karla, yang duduk sebangku dengannya.
“Gue ada urusan bentar. Kalau mau ke kantin, kalian duluan aja. Nanti gue nyusul.”
Karla, Gina, dan Nora saling berpandangan bingung. Rika jarang pergi sendirian ketika jam istirahat.
Tapi kali ini, dia melangkah sendiri. Naik ke lantai tiga. Dan berhenti di depan kelas X-E.
Anak-anak di dalam langsung melirik. Beberapa berbisik. Beberapa bahkan menunjuk diam-diam.
“Eh, itu Rika...”
“Yang dari marching band?”
“Ngapain dia ke sini?”
Seorang cowok duduk di dekat pintu memberanikan diri bertanya, “Cari siapa, Kak?”
Rika menegakkan badan, berusaha menguasai diri dari kegugupannya. “Bumi-nya… ada?”
Cowok itu jelas terkejut. Tapi ia mengangguk dan segera bangkit. Tidak cukup percaya diri untuk memanggil dari tempatnya, ia berjalan ke belakang kelas, menyentuh hati-hati bahu Bumi yang sedang membaca.
Bumi mengangkat kepala perlahan. Sekilas tatapannya kosong, tapi lalu ia tersenyum tipis. Ia berdiri pelan.
Mangsanya telah terjerat.


 dwyne
dwyne










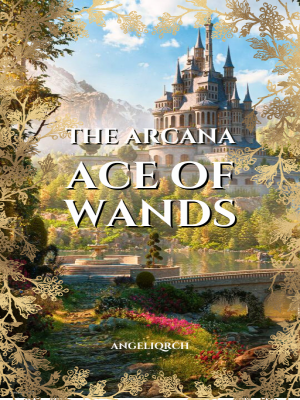
suka dengan bagaimana kamu ngebangun ketegangan di awal, adegan di toilet itu intens, tapi tetap terasa realistis. Dialog antar karakter juga hidup dan natural, terutama interaksi geng cewek yang penuh nostalgia masa SMA; kaset AADC dan obrolan ringan itu ngena banget.
Comment on chapter Pandangan Pertama