Setelah insiden di belakang sekolah, mereka berlima digiring ke ruang BK oleh Pak Iwan—guru bimbingan konseling yang terkenal suka memberi ceramah panjang lebar. Tidak ada korban. Tidak ada pelaku. Sekolah menganggap semua yang terlibat sebagai biang keributan. Sama rata. Sama salah.
Kini mereka duduk berjajar, mendengarkan Pak Iwan berkhotbah soal pentingnya menjaga keharmonisan, larangan berkelahi, dan kewajiban menjadi siswa teladan. Suaranya monoton, tapi penuh tekanan moral.
Bumi melipat lengan, lalu mendengus pelan. “Wah, wah… sampah-sampah ini…” gumamnya, sambil mengangguk kecil ke arah tiga siswa kelas XII yang tadi memalak Dirga—dan kini masih menunduk ketakutan di hadapannya. “Mereka lebih lama di sekolah ini daripada saya. Tapi sepertinya nggak ada satu pun nasihat Bapak yang mereka serap selama tiga tahun ini. Saya jadi penasaran… mereka yang bodoh, atau Bapak yang gagal ngedidik?”
Senyum tipis terukir di bibir Bumi. Datar. Dingin. Tapi cukup untuk membuat wajah Pak Iwan memerah hebat.
“Be-berani-beraninya kamu ngomong begitu ke guru?!” bentaknya sambil menunjuk Bumi dengan jari gemetar.
Dirga yang duduk di ujung kursi tersentak, tubuhnya menciut seketika oleh bentakan itu.
Tapi Bumi? Tetap tenang. Bahkan senyumnya masih bertahan.
Tepat saat atmosfer ruangan mulai memanas, pintu terbuka. Seorang perempuan masuk, menatap sekeliling dengan sorot mata tajam. Di lengannya, tergendong seorang bayi perempuan berusia sekitar setahun. Ia mengenakan kain gendongan dan menatap Pak Iwan dengan wajah cemas namun tegas.
“Maaf, permisi, Pak. Saya Indira. Ibu dari Bumi dan Dirga.”
Langkahnya mantap, suaranya sopan namun berwibawa. Sesaat, matanya beralih ke Bumi—tatapan tajam yang hanya bisa dimiliki seorang ibu yang sudah hafal betul kelakuan anaknya. Tapi Bumi tetap tenang, seperti biasa, seolah semua ini tak ada artinya.
Pak Iwan menunjuk Bumi dengan tangan gemetar karena emosi. “Anak Ibu ini… dia bikin onar di sekolah!”
Bumi hanya mengangkat alis, tak berkomentar. Wajahnya datar, tampak enggan untuk membela diri.
Namun Dirga tiba-tiba bersuara, suaranya sedikit bergetar karena gugup. “Mereka… mereka yang malak Dirga duluan, Ma!” Ia menunjuk tiga siswa kelas XII itu, berusaha terlihat tegar meski jelas masih ketakutan. “Bumi cuma… belain Dirga!”
Mata Indira menyipit. Rahangnya mengeras. Ia melangkah pelan ke arah Pak Iwan. Tatapannya dingin, seperti udara yang menurun tiba-tiba. Dan entah mengapa, Pak Iwan—yang beberapa detik lalu masih penuh kemarahan—terasa membeku di tempatnya.
“Saya mau tahu, Pak Iwan,” ucap Indira, suaranya tetap tenang. “Kenapa bisa ada pemalakan di sekolah ini? Bukannya ini sekolah favorit?”
Pak Iwan membuka mulut hendak menjawab, tapi belum sempat bicara, Indira melanjutkan.
“Dan saya juga mau tahu,” katanya, kini dengan nada lebih datar. “Kenapa cuma saya yang dipanggil ke sekolah? Orang tua dari tiga anak itu ke mana?”
Pak Iwan gelagapan. “Karena… karena Bumi yang mukulin, Bu.”
Indira mendengus pendek. “Oh, gitu. Coba, ya, Pak Iwan. Kalau anak Bapak yang dipalak, lalu melawan balik… adil nggak kalau cuma anak Bapak yang dihukum?”
Hening. Pak Iwan menunduk. Tapi Indira belum selesai.
“Kalau sistem sekolah ini nggak bisa melindungi murid-muridnya, jangan salahkan kalau murid harus melindungi dirinya sendiri.” Ia menatap langsung ke mata Pak Iwan. “Paham, Pak?”
Pak Iwan mengangguk pelan. Napasnya berat.
Indira menarik napas. “Dan asal Bapak tahu… anak saya… bukan pembuat onar.” Nada suaranya berubah tajam, penuh penekanan.
Pak Iwan menelan ludah.
Indira melirik sekilas ke arah tiga anak kelas XII yang kini tampak menyusut di kursinya, lalu menoleh ke dua anaknya.
“Bumi. Dirga. Ayo.”
Bumi berdiri lebih dulu, gerakannya santai, nyaris malas. Dirga menyusul, menunduk sekilas ke arah Pak Iwan, lalu berjalan di belakang Bumi.
Ketika pintu tertutup, ruangan itu seketika tertinggal dalam keheningan yang menusuk.
***
Kantin sekolah kosong.
Hanya suara kipas langit-langit tua yang berderit pelan, seperti napas berat dari bangunan yang sudah lelah berdiri.
Indira menarik Bumi dan Dirga masuk. Langkahnya terhenti di depan deretan kursi plastik yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Ia mengembuskan napas panjang, lalu mengusap wajahnya yang kusam oleh kantuk dan hari yang terlalu panjang.
“Ini baru hari pertama, Bumi… hari pertama, dan kamu udah bikin masalah,” katanya, suaranya serak, separuh putus asa.
Bumi mengangkat alis. “Aku bikin masalah? Emangnya aku tahu kalau Dirga bakal dipalak? Lagian—bukannya Mama sendiri yang nyuruh aku jagain dia?”
Nada suaranya terdengar menantang. Tapi wajahnya tetap datar.
Dirga hanya menunduk. Jemarinya menggenggam ujung kemeja yang lecek karena tarik-menarik di belakang sekolah.
Indira menghela napas lebih keras, seperti ingin mengusir dunia dari dadanya. “Masih bisa ngejawab…” gumamnya, menekan pelipisnya sejenak.
“Bumi, dengar ya.”
Suaranya mulai bergetar, pelan namun menghantam. “Mama enggak pernah minta apa-apa dari kamu. Tapi kamu anak pertama. Kamu punya tiga adik. Dan semuanya butuh hidup.”
Tangannya membetulkan gendongan. Agni masih tidur, tak tahu betapa beratnya dunia yang berusaha ditahan ibunya di pundak itu.
“Kamu tahu enggak kenapa Papa kamu sekarang pulang malam terus? Habis ngajar, dia kerja lagi di tempat lain. Karena Mama enggak bisa bantu di klinik Bu Risma sejak ngelahirin Agni.”
Bumi terdiam.
Kata-kata itu jatuh perlahan, seperti batu-batu kecil yang tenggelam ke dada Bumi dan tak pernah muncul lagi.
“Adik-adik kamu, Dirga masih sekolah, Sagara juga. Agni masih bayi. Semua butuh uang. Kalau kamu sampai dikeluarin lagi, terus harus pindah sekolah… dari mana biayanya, Bumi?”
Indira akhirnya duduk. Bahunya merosot.
Sorot matanya bukan marah lagi. Tapi letih. Letih yang memerah di mata dan membungkukkan punggung.
“Mama enggak minta kamu ranking satu. Enggak minta jadi paling hebat. Mama cuma minta satu hal…” Suaranya nyaris tenggelam dalam kantin kosong itu.
“Jangan bikin masalah.”
Mata mereka bertemu.
Dan kali ini, Bumi tak bisa berpaling.
Di matanya, ibunya itu berdiri bukan sebagai benteng yang kuat, tapi sebagai manusia yang hampir rubuh—berdiri di atas sisa-sisa tenaga dan harapan.
“Apa Mama harus sujud di kaki kamu supaya kamu mau ngerti? Harus Mama jatuh sejatuh-jatuhnya dulu baru kamu berhenti ngelawan?”
Bumi menggertakkan gigi. Tapi tak ada jawaban. Tapi rasa bersalah itu perlahan tumbuh—seperti duri yang menyembul dari dalam dadanya, menusuk tiap hela napas.
Indira menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan. “Mama pulang dulu. Takut Agni keburu bangun. Susunya belum Mama siapin—Mama tadi buru-buru ke sini…”
Bumi hanya bisa menunduk, menatap kaki ibunya yang kotor oleh debu lantai, hanya beralas sandal tipis.
“Langsung pulang. Jangan keluyuran.”
Tak ada pelukan. Tak ada isak.
Hanya langkah pelan yang bergema di lantai—suara sandal yang terdengar terlalu keras dalam sepi, seolah mengukirkan luka yang tak dikatakan.
Bumi dan Dirga tetap diam.
Tak satu pun dari mereka bicara.
Tapi diam itu menyimpan sesuatu.
Sebuah janji.
Yang belum diucapkan, tapi mulai tumbuh di dada yang bersalah.
***
Malam itu di rumah, Bumi dan Dirga masih belum berani bicara lagi dengan ibu mereka. Mereka berdua hanya duduk di meja makan, menatap kosong pada nasi hangat dan sayur asem yang baru saja dihidangkan.
“Kenapa pada diem?” suara Indira yang baru saja menaruh telur dadar di meja membuat Bumi dan Dirga sedikit tersentak dari lamunan mereka.
“Makan,” katanya dengan nada tenang tapi sedikit memerintah tanpa melihat ke mereka berdua. Dan mulai sibuk menyiapkan makanan untuk Agni yang bolak balik duduk dan berdiri di dekat jendela, seperti menunggu sesuatu.
Bumi dan Dirga bertukar pandang sesaat, lalu akhirnya mulai menyendok nasi mereka ke piring.
Tiba-tiba terdengar suara deru motor yang masuk ke dalam pagar rumah mereka. Agni langsung berdiri dan melompat-lompat di depan pintu dengan tidak sabar. Tak lama pintu akhirnya terbuka, sesosok pria tinggi tegap muncul dengan wajah lelah dan kaku. Namun wajah itu langsung berubah ketika melihat bayi perempuannya melompat kegirangan menyambutnya di depan pintu.
“Agniiiii…. Agni nungguin Papah yaaa?” katanya ceria sambil mengangkat Agni yang yang sedari tadi tidak sabar berteriak ‘ndong, ndong!!’.
Dirga mencibir melihat pemandangan itu, “Perasaan mukanya enggak pernah seceria itu kalau ngeliat kita,” bisiknya pelan ke Bumi.
Bumi hanya mengangkat bahu, tidak terlalu peduli.
“Sebentar ya… Papa ganti baju dulu,” katanya lembut ke Agni sambil mendudukkan di baby walker sebelum kemudian bergerak cepat ke kamar dan kembali beberapa menit kemudian dengan kaos santai bersih.
Ayah mereka, Arjuna, duduk di kursi di depan mereka. Dan mulai menyendok nasinya sendiri ke piring sambil sesekali tersenyum melihat Agni di baby walker-nya.
Indira kembali, duduk di sebelah Arjuna dan mulai menyuapi Agni.
“Tadi aku dipanggil ke sekolah…” kata Indira tiba-tiba ke Arjuna tanpa basa basi.
Bumi dan Dirga tersedak kecil, belum siap dengan pembicaraan mendadak ini.
“... Bumi mukul anak kelas XII. Katanya gara-gara Dirga dipalak. Mereka berdua tadi dipanggil sama guru BK,” tambah Indira.
Arjuna melirik sekilas ke Bumi dan Dirga. Matanya terlihat tajam, dan itu membuat Dirga buru-buru menunduk.
Setelah mengatakan itu, ibu mereka berdiri dan berjalan kembali ke dapur untuk mengambil sesuatu.
Begitu suara langkahnya hilang, ayah mereka—Arjuna—menoleh ke Bumi tanpa mengubah ekspresinya yang tenang.
“Kenapa kamu mukul mereka?” tanyanya, seolah ingin mengkonfirmasi cerita Indira tadi.
Bumi tidak langsung menjawab. Ia mengunyah pelan, lalu menjawab datar, “Mereka malak Dirga.”
Arjuna mengangguk singkat, lalu kembali menyendok nasi. Seolah perkelahian di sekolah adalah berita cuaca.
Ia lalu menoleh ke Dirga. “Terus kamu ngapain waktu dipalak?”
Dirga agak malu-malu. “Kabur.”
Arjuna mendecak kecil. “Lawan. Orang kaya gitu kalau nggak dilawan malah makin berani. Jangan keliatan takut. Kamu mau dikerjain terus?”
Bumi tidak berkata apa-apa. Tapi sudut bibirnya terangkat sedikit. Ia menyendok sambalnya, berusaha menyembunyikan senyum kecilnya.
“Jadi aku boleh mukul?” tanya Dirga pelan.
Arjuna menatapnya, “Kalau dipukul, pukul balik. Yang penting jangan mulai duluan.”
Langkah Indira terdengar dari dapur. Ia kembali ke meja dengan piring berisi tempe goreng di tangan. Matanya menyipit, curiga pada ketiganya yang duduk terlalu serius—dan terlalu senyap.
“Ngomongin apa kalian?” tanyanya curiga.
Arjuna tersedak sedikit, lalu tertawa canggung. “N-nasihatin anak-anak... Bumi, jangan kaya gitu lagi ya.”
Nada bicaranya terdengar terlalu datar untuk jadi teguran sungguhan.
Bumi menunduk cepat, berpura-pura mengambil sendok yang jatuh, menahan tawanya. Dirga menatap piringnya dalam-dalam, pundaknya naik turun menahan senyum.
Indira sempat mempersempit matanya... tapi akhirnya hanya menggeleng dan duduk kembali.
“Mana Sagara?” tanya Arjuna ketika baru menyadari anak ketiganya tidak ada di meja makan.
“Dia lagi….”
“...belajar,” sahut Bumi dan Dirga bersamaan dengan nada datar dan bosan sebelum ibunya menyelesaikan kalimatnya.
Indira menyipitkan mata sekilas ke mereka berdua sebelum kemudian berteriak memanggil Sagara. “Garaaa.. Ayo makan dulu!”
Beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu berderit terbuka dan langkah tenang berjalan ke meja makan. Sesosok anak laki-laki berusia 13 tahun dengan tubuh kurus dan kulit pucat muncul. Wajahnya terlihat tenang—terlalu tenang dan dewasa untuk anak seusianya.
Ia menarik kursi di dekat ibunya. Lalu mulai menyendok nasi ke piring.
Wajah Indira terlihat lebih cerah ketika melihat anak ketiganya itu. “Pah, tadi aku ketemu gurunya Gara waktu di pasar. Katanya Gara hebat lho, dia pernah dikasih soal level anak SMA tapi dia bisa kerjain,” katanya ke Arjuna dengan penuh bangga.
Dirga memutar mata, “Anak emas,” gumamnya ke Bumi yang hanya mendengus pelan mendengarnya.
Sagara nampak tidak peduli dan tetap menyuap nasinya.
Bumi menyipitkan mata ke adiknya itu. Sagara sangat pendiam dan selalu kelihatan tenang. Tapi karena itu, Bumi jadi suka untuk mencoba menguji batas kesabarannya. Dan hari ini, ia memiliki bahan untuk melakukan itu.
Bumi tersenyum licik.
“Ma,” katanya santai. “Sagara tadi pas subuh-subuh nyuci seprainya sendiri. Kayaknya dia ngompol.”
Sagara tersedak air putihnya.
Dirga langsung menoleh. Arjuna mengangkat alis. Indira berhenti menyuapi Agni.
“Iya, Gara?” tanya Indira memastikan.
Sagara menatap Bumi tajam. “Gue enggak ngompol!” serunya.
“Oh ya?” Bumi mengangkat alis dengan senyum liciknya itu. “Terus… lo abis ngapain sampe nyuci seprei sendiri?”
Wajah Sagara menjadi merah, ia membuka mulut, tapi tak satu kata pun keluar.
Bumi menyuap nasinya sambil menatap Sagara dengan seringai lebar di wajahnya, menunggu ia menjawab. Menunggu adiknya itu masuk perangkapnya.
Dirga—yang polos tapi jenius—berkata, “Oh… mimpi basah ya?”
Bumi tertawa pelan, menikmati situasi, sementara Dirga mulai cekikikan.
Wajah Sagara merah padam. Ia menggertakan gigi, tangannya terkepal erat, dan dengan kesal, ia melempar sepotong tempe ke Bumi—yang tentu saja dengan mudah menghindar sambil tetap duduk tenang.
Sagara menghela napas keras, kemudian berdiri kasar, membuat kursinya terseret dengan bunyi nyaring, lalu berjalan cepat ke kamarnya dan membanting pintu.
Arjuna hanya mengangkat bahu dan melanjutkan makan, seolah pemandangan itu adalah hal yang biasa ia lihat sehari-hari.
Sementara Indira menoleh ke Bumi, matanya tajam.
“Bumi.”
“Apa?” sahut Bumi datar. “Aku cuma bantu ngasih tau,” katanya santai sambil menggigit tempe gorengnya. Ia menunduk menyuap makanannya dengan senyum licik itu masih bertahan di sana.


 dwyne
dwyne




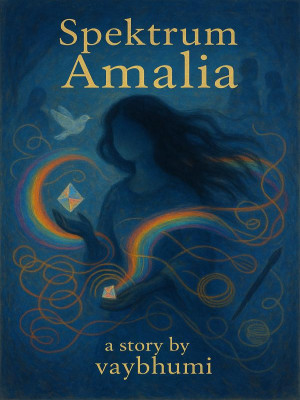






suka dengan bagaimana kamu ngebangun ketegangan di awal, adegan di toilet itu intens, tapi tetap terasa realistis. Dialog antar karakter juga hidup dan natural, terutama interaksi geng cewek yang penuh nostalgia masa SMA; kaset AADC dan obrolan ringan itu ngena banget.
Comment on chapter Pandangan Pertama