Bumi menghela napas panjang dengan wajah datar, nyaris seperti sedang menahan beban tak kasatmata yang menempel di dadanya.
Sekarang dia paham kenapa cewek bernama Sophia itu dijauhi teman-temannya.
Sejak pagi hingga menjelang jam istirahat siang, tangan Sophia tak henti terangkat. Bahkan guru pun kadang belum selesai menjelaskan, dan ia sudah mengacungkan tangan seperti refleks. Pertanyaannya panjang, ruwet, dan terlalu teknis untuk ukuran anak SMA baru masuk. Sebagian anak di barisan tengah sampai membuat permainan sendiri: menghitung berapa kali Sophia angkat tangan. Tiap satu jari naik, tawa tertahan mengikuti.
Jam menunjukkan pukul 11.58. Dua menit lagi menuju istirahat makan siang. Perut para murid sudah menari-nari tak sabar, perhatian mereka hanya tertuju pada jam dinding dan aroma kantin yang mulai menyelinap dari balik jendela.
Lalu… tangan itu terangkat lagi.
Seluruh kelas serempak mendesah. Keras. Seolah ada satu suara kolektif yang lelah.
Pak Reza, guru Kimia mereka, menoleh, “Apa lagi, Sophia?” katanya dengan nada lelah.
Sophia tidak terganggu. Ia langsung memulai monolog, menjelaskan kebingungannya pada persamaan reaksi kimia yang bahkan belum sempat Bumi mengerti cara menulisnya. Beberapa anak memutar mata. Satu dua mulai mengemasi buku diam-diam.
Bel istirahat berbunyi.
Namun suara lonceng itu seperti tidak menyentuh ruang tempat Sophia berada. Ia tetap bicara, dan Pak Reza—entah kenapa—ikut larut menjelaskan. Diskusi dua arah itu menjadi simfoni kecil yang menyayat telinga semua yang kelaparan. Hingga akhirnya, 10 menit setelah bel berbunyi, Pak Reza menutup buku, mengucapkan “lanjut nanti,” dan keluar kelas dengan cepat.
Satu per satu siswa berhamburan pergi. Ada yang melirik ke arah meja Sophia dengan ekspresi jijik. Salah satu geng cewek sempat melontarkan komentar cukup keras saat melewati bangku belakang.
“Caper amat, sih.”
Sophia mendengarnya. Tapi tidak menanggapi. Ia hanya menunduk. Tangannya merapikan buku perlahan, seperti menyusun ulang harga dirinya.
Bumi masih duduk di tempat. Tangannya terlipat di dada, pandangannya menatap lurus ke depan seperti patung penjaga gerbang. Lalu, tanpa menoleh, ia berkata pelan tapi jelas, “Heh.”
Sophia mengangkat wajahnya.
“Gue enggak peduli kalau lo mau caper di kelas,” kata Bumi. Suaranya datar. Bukan marah, tapi membuat udara di sekitarnya menegang.
Ia akhirnya menoleh. Tatapannya menusuk, dingin, dan penuh tekanan.
“Tapi kalau kelas udah mau selesai…” ia menyipitkan mata. “Jangan banyak nanya. Lo udah ngebuang waktu gue.”
Untuk sesaat, dunia jadi hening. Tak ada langkah kaki di lorong, tak ada suara dari kantin.
Sophia menelan ludah. Matanya membulat sebentar, lalu ia mengangguk kecil. Tidak membela diri. Tidak bertanya balik. Hanya… diam.
Bumi berdiri. Ia mengambil kotak makan siangnya dari bawah meja, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Suara langkahnya menggema di lantai yang dingin.
Begitu pintu kelas menutup, Sophia tetap duduk di bangkunya.
Tangannya bergerak pelan ke sudut matanya, menghapus jejak air yang belum sempat jatuh.
***
“Ini ruang multimedia.”
Bagas menunjuk sebuah ruangan berlapis kaca di ujung koridor lantai dua. Di dalamnya terlihat beberapa komputer berjajar dan proyektor tergantung di langit-langit.
“Di sana perpustakaan,” lanjutnya sambil menggerakkan tangannya ke arah seberang koridor, tempat sebuah pintu kayu besar berdiri angkuh dengan papan nama usang di atasnya.
“Ruang guru di sini,” tambahnya lagi, menunjuk ruangan dengan kaca buram di dekat tangga tengah.
Setelah menghabiskan bekal makan siang mereka di kelas, Bagas mengajak Dirga berkeliling. Langkah mereka menyusuri koridor terasa santai, seperti dua penjelajah yang sedang menandai peta dunia baru.
“Woah… kayaknya lo udah tau banyak ya tentang sekolah ini?” kata Dirga, setengah kagum, setengah heran.
Bagas mengangguk cepat. “Dulu waktu ngambil rapor, nyokap suka ajak gue ke sekolah kakak gue juga. Jadi gue kadang iseng keliling-keliling sendiri.”
“Oh, gitu…” Dirga mengangguk pelan, lalu menoleh ke bawah. Dari koridor lantai dua, ia bisa melihat ke lapangan di bawah. Seorang anak laki-laki duduk sendirian di bangku beton, makan siang tanpa bicara. Tubuhnya tegap, posturnya tenang.
“Lo punya kakak?” tanya Bagas.
Dirga menahan napas sejenak. Pandangannya masih tertuju pada sosok di bawah sana. Bumi.
“Yah… bisa dibilang gitu…” gumamnya, tanpa mengalihkan tatapan.
Bagas mengerutkan kening, merasa bingung dengan jawaban setengah hati itu. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, sesuatu bergetar di saku celananya.
Ia mengeluarkan benda kecil berwarna hitam dan putih—Nokia 6600.
Dirga menatap ponsel itu seolah sedang melihat benda alien. Matanya membulat, refleks. Sekilas, dunia seperti berhenti berdetak.
Benda itu… indah. Layar warnanya terang, tombol navigasinya elegan, dan bentuknya seperti masa depan yang bisa digenggam.
Bagas melirik layar. “Kakak gue SMS. Dia nyuruh gue ke kantin.”
Ia menoleh ke Dirga sambil menyelipkan kembali ponsel ke saku. “Gue duluan ya.”
Dirga hanya mengangguk, masih terpaku.
“Bye,” kata Bagas sambil melambai santai, lalu berbalik meninggalkan koridor.
Begitu langkah Bagas menghilang, Dirga mengerjap cepat. Napasnya pelan, seperti baru bangun dari mimpi singkat.
Ia memandangi tangannya sendiri, kosong.
Lalu menoleh ke sekeliling.
Satu anak duduk di bangku, memegang ponsel lipat.
Dua anak bersandar di dinding, tertawa sambil menunjukkan layar ponsel mereka ke satu sama lain.
Tiga anak duduk di lantai, main Snake II sambil adu skor.
Dan ia sendiri, hanya berdiri.
Dirga menarik napas dalam.
Rasa ingin itu muncul di dadanya, bukan seperti keinginan biasa, tapi seperti kebutuhan yang menekan dari dalam.
Ia ingin.
Sangat ingin.
Satu ponsel saja. Benda kecil itu.
Agar bisa terlihat sama seperti mereka.
Agar tidak lagi merasa seperti satu-satunya manusia yang masih hidup di zaman batu.
Tapi kemudian ia menghela napas lagi. Ia tahu tidak mungkin. Melihat ekonomi keluarga mereka, dia bisa sekolah saja itu sudah bagus.
Dengan muram Dirga melangkah menuruni tangga ke lantai 1 untuk pergi ke toilet sebentar sebelum jam pelajaran berikutnya dimulai. Ia berjalan menyusuri lorong hingga sampai ke depan lorong kecil yang menuju ke toilet anak laki-laki. Ia masih melihat Bumi duduk di pinggir lapangan, tapi wajahnya seperti tidak mau diganggu, sehingga ia memutuskan untuk mengabaikannya saja.
Saat ia masuk menyusuri lorong kecil itu, ia melihat 3 orang siswa laki-laki dengan seragam berantakan terlihat berkumpul sambil tertawa di depan toilet anak laki-laki.
Dan entah mengapa alarm di dalam kepala Dirga menyala. Firasatnya buruk, ia merasa sepertinya lebih baik ia putar balik. Dengan jantung berdebar cepat, Dirga melangkah pelan dan berusaha tetap terlihat tenang, ia membalikkan badannya perlahan, tapi kemudian—
“Heh, anak baru kan lo? Sini.”
Dirga memejamkan mata, menarik napas dalam.
Ia akhirnya berbalik perlahan.
“Sini,” kata salah seorang dari mereka lagi dengan senyum miring.
Dirga berjalan mendekat dengan hati-hati. “I-iya Bang?”
Salah satu cowok dengan rambut berantakan membuka tangannya, “Sini duit lo.”
Dirga menggigit bibir. Ia merapatkan tangan ke saku celananya. Ia hanya mengantongi uang satu-satunya yang harus dihemat-hemat sampai akhir minggu ini.
“Enggak bawa uang Bang,” jawab Dirga berbohong.
Cowok dengan rambut berantakan itu mengangkat alis, “Jangan sampai lo gue geledah, terus gue nemuin duit ya.”
Dirga menelan ludah. Lalu saat mereka bertiga mulai melangkah mendekat, tanpa berpikir panjang lagi–Ia lari.
“Woi! Mau kemana lo??”
Dirga berbalik dan berlari sekuat yang ia mampu keluar dari lorong kecil itu. Ia berlari menyusuri koridor lantai 1. Beberapa anak memekik tertahan ketika ia hampir saja menabrak mereka.
Tiga orang itu masih berlari mengejarnya di belakang. Dirga tidak tahu harus ke mana, ia hanya terus berlari sampai akhirnya napasnya mulai tidak kuat lagi dan dia kini berada di belakang gedung sekolah yang sepi. Dan ketika langkahnya mulai melambat, salah satu dari mereka berhasil mencengkram bahunya dan menghempaskannya ke dinding.
Bahu Dirga membentur dinding beton. Ia meringis kesakitan. Lalu tiga orang itu langsung menyergapnya seperti sekawanan singa yang menemukan anak rusa.
“Berani banget lo kabur!” seru salah seorang di antara mereka sambil mengeplak kepala Dirga keras.
Dan yang lainnya mulai mencari-cari di saku baju dan celana Dirga hingga akhirnya ia menemukan lembaran uang 5 ribuan dari saku celana kanannya. Mereka tersenyum lebar.
“Kata lo enggak bawa duit,” kata si cowok rambut berantakan dengan nada mengejek.
Dirga menarik napas, “Bang, jangan Bang… itu satu-satunya…” pinta Dirga memelas.
Namun mereka tidak peduli, “Berisik lo!” si cowok rambut berantakan itu mengangkat tangan bermaksud memukul Dirga lagi.
Tapi tiba-tiba suasana berubah.
Udara terasa lebih berat. Seperti ada bayangan tebal turun dari langit-langit.
Mereka membalikkan badan.
Bumi.
Ia berdiri di ujung lorong.
Tangannya terlipat di depan dada. Wajahnya datar.
Tapi matanya—dingin. Terlalu dingin untuk anak seusianya.
Ia berjalan pelan. Setiap langkahnya bergema di ubin kosong.
Salah satu dari mereka secara naluriah melangkah mundur.
Bumi menatap si cowok rambut berantakan yang tadi sudah mengangkat tangan untuk memukul Dirga. Tatapannya dingin. Tajam. Berbahaya. Si cowok itu menelan ludah.
“Cuma gue yang boleh mukul si bodoh ini,” geram Bumi.
Lalu...
BUK!
Satu pukulan lurus menghantam rahang cowok itu. Tubuhnya terpelanting ke tembok.
Yang kedua tak sempat bereaksi sebelum Bumi mengunci lehernya dan menghantamkan lutut ke perutnya.
Yang ketiga mencoba kabur—tapi Bumi menarik kerahnya, melemparnya ke lantai seperti karung.
Si cowok rambut berantakan berusaha berdiri dan memukul balik Bumi, tapi Bumi menangkap tinjunya dan memelintir tangan itu. Cowok itu mengerang kesakitan. Tapi Bumi tidak melepaskan tangannya, ia berkata dengan nada rendah nyaris berbisik, “Kalau lo masih mau nyoba, gue patahin tangan lo di sini. Mau?”
Cowok itu menggeleng cepat. Keringatnya bercucuran, napasnya memburu. Ia tidak hanya kesakitan, tapi juga terlihat ketakutan luar biasa. Bumi akhirnya mendorong cowok itu hingga ia tersungkur ke tanah.
Dirga duduk terengah, memegangi dadanya. Pandangannya kabur.
Sementara Bumi berdiri tenang di antara tubuh-tubuh yang meringis kesakitan.
Lalu tak lama, suara langkah kaki berderap cepat menuju mereka karena mendengar keributan-keributan yang terjadi di belakang gedung sekolah.
“HEI! KALIAN NGAPAIN DI SANA?!”
Pak Iwan. Guru BK.
Bumi menghela napas kecil.
Ia tidak menoleh. Tapi matanya menyipit, seolah sudah tahu konsekuensinya setelah ini.


 dwyne
dwyne








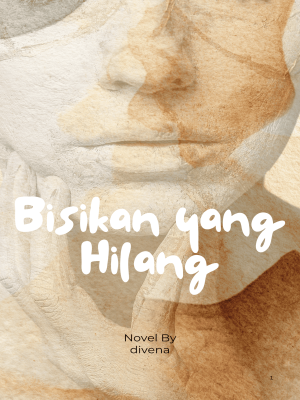


suka dengan bagaimana kamu ngebangun ketegangan di awal, adegan di toilet itu intens, tapi tetap terasa realistis. Dialog antar karakter juga hidup dan natural, terutama interaksi geng cewek yang penuh nostalgia masa SMA; kaset AADC dan obrolan ringan itu ngena banget.
Comment on chapter Pandangan Pertama