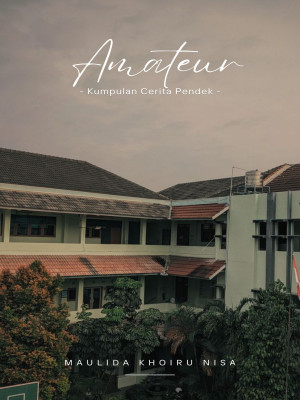Detik jam dinding di ruang perawatan terdengar seperti hitungan mundur. Pak Nohan menatap sosok kecil di balik kaca—tubuh rentannya terlihat rapuh, tapi identitasnya adalah bom waktu untuk Pak Nohan. Arsya. Nama yang tertulis pada tanda pasien yang tergantung di pintu mengiris ingatannya. Anak ini seharusnya bersama rahasia mereka, kini terbaring di sini—bernapas.
Bagaimana jika Pak Aswan tahu? Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan terjadi dengan dirinya dan Arsya?
Pak Nohan menelan ludah. Ruangan ini terasa lebih sempit dari sebelumnya, seolah dindingnya saling mendekat.
“Nohan, ada yang bisa saya bantu?”
Pak Nohan tersentak. Ia tidak menyadari bahwa Dokter Nata sudah berdiri di sampingnya. “Anak ini bisa mengguncang segalanya, bisa membuka kembali luka lama yang selama ini kami tutupi.” batinnya
Tapi apa yang bisa dia lakukan? Menghilangkan anak ini dari rumah sakit mungkin satu-satunya cara untuk melindungi semuanya. Meski bagian kecil dari dirinya tahu bahwa itu salah.
“Apa kamu punya kepentingan dengan pasien saya? maksud saya Arsya, anak yang sedang berbaring di sana” ujar Dokter Nata lagi.
Dia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan kecemasannya. “Saya hanya datang untuk memeriksa keadaan anak ini, atas permintaan Pak Aswan.” Nada suaranya terdengar tenang, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang meluap.
Dokter Nata menatapnya dengan penuh kewaspadaan. “Saya masih menjalankan tugas sesuai permintaan beliau. Anak ini masih membutuhkan perawatan. Kami tidak akan menerima intervensi apapun yang bisa membahayakan kesembuhannya.”
“Tapi, bukannya Bapak Aswan meminta anda memindahkannya? kenapa dia masih di sini? Dia harusnya sudah tidak ada di sini,” sanggah Pak Nohan
Dokter Nata menangkap ketakutan yang jelas di matanya.
“Pindahkan dia. Sekarang juga!” perintah Pak Nohan, sambil mengeluarkan ponselnya, siap untuk menghubungi seseorang. “Datanglah ke ruang VIP rumah sakit. Kita harus memindahkan seseorang.” lanjut Pak Nohan
Di tempat tidurnya, Arsya yang semula tertidur atas permintaan perawat yang datang menjenguknya, mulai terusik oleh suara-suara di sekitarnya.
Pak Nohan mencoba menerobos ruangan dengan langkah terburu-buru. Ponselnya tergenggam erat di tangan, jemarinya mengetuk-ngetuk permukaannya dengan gelisah. Matanya langsung tertuju pada sosok kecil di ranjang, sebelum akhirnya beralih ke Dokter Nata yang berdiri di sisinya, menggenggam gagang pintu, menghalangi jalannya.
“Dokter, saya ulangi—Pak Aswan ingin anak ini dipindahkan hari ini juga. Ke panti asuhan,” katanya tegas, tanpa basa-basi.
Dokter Nata tidak langsung menjawab. Dia melangkah ke depan, menghentikan pergerakan Pak Nohan tepat di ambang pintu. Matanya menajam, meneliti pria itu dengan sorot waspada.
“Permintaan atau ancaman, Nohan?” suaranya datar, tapi ada ketegasan yang sulit diabaikan. “Karena sebagai dokter, saya hanya tunduk pada kondisi medis.”
Pak Nohan mengalihkan pandangan, menghindari tatapan langsung. Tangannya masih sibuk mengetuk ponsel, seolah mencari pegangan dalam kegelisahannya.
“Bukan urusan Anda,” ujarnya pendek. “Saya hanya menjalankan tugas. Pindahkan dia. Sekarang.”
Dokter Nata mendekat, suaranya lebih rendah, namun penuh tekanan. “Urusan saya adalah nyawa pasien.” Dia menoleh sekilas ke arah Arsya yang masih terbaring tak sadar, tubuh kecilnya tampak rapuh di balik perban yang melilit. “Arsya belum stabil—luka dalam, trauma kepala, dan amnesia. Anda mau memindahkannya dalam keadaan seperti ini?”
“Dia harusnya sudah tidak ada di sini,” desak Pak Nohan lagi.
Arsya mulai merasa kebingungan. Siapa mereka? Mengapa mereka membicarakan dirinya? Apa yang mereka maksud dengan ‘dia harusnya sudah tidak ada di sini?’
“Nohan,” sahut Dokter Nata dengan suara yang lebih sengit. “Anak ini belum pulih. Pak Aswan meminta saya merawatnya sampai dia benar-benar sembuh. Itu kesepakatannya.”
“Nata... aku tahu kau peduli padanya.” Tangannya mengetuk-ngetuk ponsel gugup. “Tapi kalau bos tahu identitas sebenarnya dari anak ini... kau pikir dia masih berpikir memerintahkanmu mengantarnya ke panti?” tanya Pak Nohan dengan diakhiri senyum meremehkan. “Dia akan melenyapkannya tanpa sepengetahuanmu! Anak ini akan dibungkam, selamanya.”
Kata-kata Pak Nohan membuat bulu kuduk Arsya berdiri. ‘Melenyapkan?’ pikirnya. Bukankah kata itu berarti membuat seseorang menghilang... selamanya? Apakah itu berarti hidupnya dalam bahaya?
“Tidak. Itu tidak mungkin.” batin Arsya. Dalam diam, ia mencoba menepis bisikan yang terus menghantuinya. “Tidak ada yang peduli padamu. Kau sudah dibuang. kau akan lenyap. Artinya, kau harus mati.”
Jantung Arsya berdegup lebih cepat. Tangannya gemetar di balik selimut. Ia ingin tetap diam, tetapi rasa takutnya lebih besar dari kehendaknya. Arsya mulai bergerak resah, membuat Dokter Nata menyadari bahwa dia sudah bangun.
“Sst, diamlah, Nohan!” perintah Dokter Nata dengan tegas. Pak Nohan tampak ingin membantah, namun menahan diri.
Dokter Nata kemudian berbalik kepada Arsya. “Nak, Arsya... kamu sudah sadar?” tanyanya dengan suara lembut, nada yang menenangkan dan jauh berbeda dari dinginnya suara Pak Nohan.
Akhirnya, Arsya memberanikan diri membuka matanya. “Apakah aku seharusnya mati?” tanyanya polos, penuh keputusasaan.
Kalimat itu mengejutkan Dokter Nata, membuatnya terpaku sejenak. “Anak ini... mendengar hal yang tak seharusnya ia dengar,” batinnya penuh penyesalan. “Ah, seharusnya aku bicara dengan Nohan di luar, aku membuat kesalahan di depan pasien.” lanjutnya.
Penyesalan dokter Nata terdengar oleh Arsya. Membuatnya semakin yakin, bahwa kalimat ‘melenyapkan’ itu memang ditujukan padanya. “Apa aku nggak boleh hidup?” ulang Arsya, dengan suara serak menahan air mata.
Dokter Nata cepat-cepat memutar otak, mencari cara untuk menenangkan bocah itu tanpa harus menjelaskan langsung—terlalu berisiko. “Arsya, kamu dulu anak nakal, ya?” canda Dokter Nata dengan senyum kecil yang berusaha mencairkan suasana. Usahanya berhasil membuat wajah Arsya yang ketakutan berubah menjadi kebingungan sejenak.
“Anak kecil tidak boleh ikut campur urusan orang dewasa,” lanjutnya sambil tersenyum.
“Bukan begitu…” jawab Arsya dengan suara bergetar. “Kalian… berbicara di sampingku.”
Dokter Nata menunduk sejenak, lalu mengubah nadanya menjadi lebih lembut. “Arsya, dengar Pak Dokter, ya? Kami di sini hanya ingin membuatmu nyaman dan cepat pulih. Lagipula, Pak Nohan—dia tidak mengatakan itu untukmu. Dia mengatakan itu untuk…”
Dokter Nata sedang berusaha menenangkannya, dia sengaja berbohong agar Arsya tidak lagi ketakutan, namun tetap saja dibohongi itu menyakitkan. “Bohong!” teriak Arsya tiba-tiba. “Dokter berbohong!”
Arsya mencoba bangkit, tetapi rasa sakit menjalar dari perutnya. Dia mengerang dan kembali berbaring, lemas. “Aku... aku harus mati, kan?” suaranya serak. “Aku tidak boleh hidup. Mereka ingin aku mati, lenyap.” tangisannya semakin keras.
Dokter Nata menatap Pak Nohan dengan tatapan penuh amarah. “Nohan, tolong keluar sebentar, aku ingin berbincang dengan pasienku.” nada suaranya tegas dan tidak terbantahkan.
“Tapi…” Pak Nohan tampak ragu, mencoba membela diri.
“Keluar,” ulang Dokter Nata lebih keras. “Aku ingin bicara dengan pasienku.”
Mau tak mau, Pak Nohan menurut. Dia meninggalkan ruangan, dan Dokter Nata berbalik kembali ke Arsya.
Arsya masih menangis tersedu-sedu. Dia hanya seorang anak yang kehilangan ingatan, bahkan keluargapun dia belum tentu memilikinya. Dokter Nata memahami betul bahwa Arsya tidak punya cara lain untuk mengungkapkan perasaannya selain dengan air mata. Wajar saja kalau dia merasa takut dan bingung.
“Nak, dengarkan Bapak sebentar, ya?” Dokter Nata mencoba menenangkan Arsya dengan suara lembut. Namun Arsya menggelengkan kepalanya, menolak untuk mendengarkan. Dia merasa dibohongi, tidak ada lagi yang bisa dia percaya.
“Arsya…” panggil Dokter Nata dengan nada penuh kasih sayang, berharap bisa meredakan ketakutan yang menyelimuti anak itu.
“Bohong! Dokter bohong!” Arsya melawan dengan suara yang serak, matanya basah karena air mata.
“Maaf, ya…” kata Dokter Nata dengan tulus. Dia menyesali kata-kata yang mungkin membuat Arsya semakin ketakutan. “Bapak yang salah. Bapak akan menunggu sampai kamu siap mendengarkan. Hari ini, kamu pasien Bapak satu-satunya. Sampai kamu tenang, Bapak akan tetap di sini.”
Dokter Nata duduk di kursi di samping tempat tidur, kedua tangan terlipat rapi di atas pangkuan. Matanya tak lepas dari Arsya yang masih membenamkan diri dalam selimut, punggungnya bergetar tersedu-sedu. Ruangan itu sunyi, hanya diisi detak jam dinding dan rintihan lirih Arsya.
‘Tunggu…’
Suara dari pikiran Dokter Nata tiba-tiba terdengar oleh Arsya. Bocah itu mengencangkan genggaman pada selimut, tapi dokter sengaja tetap diam.
‘Biarkan dia yang memutuskan kapan mau percaya.’
“Sudah lebih tenang, Nak?” tanyanya dengan suara teduh, sambil menjaga jarak aman.
Arsya tidak menjawab. Tangannya yang kecil menyembul dari balik selimut, mencengkeram kain hingga buku-buku jarinya memucat. Dokter Nata menyorot gemetar di ujung jemari itu—tanda ketakutan yang masih mendominasi.
“Sudah puas menangis?” Kali ini, senyum hangat mengiringi pertanyaannya. Kursi bergeser perlahan mendekat, tapi berhenti sebelum memasuki zona personal Arsya. ‘Biarkan dia merasa aman dulu.’
Arsya menghela napas pendek, tubuhnya yag masih lemas kemudian perlahan kembali ke posisi berbaring. Selimut tersibak perlahan, memperlihatkan wajahnya yang basah oleh air mata. Sebelum butir berikutnya jatuh, Dokter Nata sudah mengulurkan tangan, menyeka pipinya dengan ujung jari halus.
“Maaf ya, Nak…”
Arsya menutup mata, tubuh kaku bak patung yang menanti hantaman. Tapi yang datang justru usapan lembut di pipinya. Saat matanya terbuka kembali, dokter masih di sana—wajah tenang, alis tak berkerut, napas tetap teratur.
“Kamu pasti ketakutan sekali,” bisiknya sambil menyelipkan tisu ke tangan Arsya. “Bangun di ruang asing, tanpa kenal siapa-siapa… bahkan dirimu sendiri.”
Bibir bocah itu bergetar. Dokter Nata kembali menyeka sisa air mata, kali ini menggunakan tisu. ‘Sentuhan langsung mungkin masih terlalu mengancam baginya.’
“Dan pasti badanmu terasa sakit,” lanjutnya, mata tertuju pada selang infus di lengan Arsya. “Tanganmu berat, ada alat-alat yang menempel… Tapi lihat,” jarinya menunjuk pergelangan tangan Arsya, “sebagian sudah bisa dilepas. Artinya, kamu mulai pulih.”
Arsya mengangguk pelan. Benar—alat-alat aneh yang terpasang di sana banyak yang tinggal kenangan.
“Kalau Bapak tanya, bagian mana yang paling sakit?”
Diam. Tidak ada respons—baik anggukan atau gelengan. Dokter Nata tak terburu-buru. Ia menunggu, sambil memutar-mutar stetoskop di lehernya, membiarkan Arsya mengamati benda itu seperti mainan, bukan alat medis.
“Ah, mungkin karena Bapak masih asing, ya?” Dokter Nata tertawa pendek, mencondongkan badan sedikit. “Tapi kita akan sering bertemu. Bagaimana kalau kita kenalan dulu?”
Arsya mengangguk. Dokter Nata menghela napas pelan, bahunya turun tanda lega.
“Nah, nama dokter…” Ia sengaja berhenti, menyentuh name tag di sakunya. “Kamu bisa membacanya?”
Arsya menyipitkan mata, dahi berkerut seperti sedang memecahkan teka-teki. “Lin...ga Na...Nata...ya.”
“Pintar sekali!” Dokter Nata tersenyum lebar, tangan kanannya refleks mengacak rambut Arsya. “Mulai sekarang, panggil saja Dokter Nata. Supaya lebih akrab.”
Arsya mengamatinya: rambut hitam pekat, mata jernih yang bersinar, dan lesung pipi yang dalam. Tidak ada aura mengancam dari sosok ini. Setiap perkataannya jelas, tanpa makna tersembunyi. Mungkin dia orang baik.
“Bapak tahu namamu Arsya,” lanjut Dokter Nata, suara selembut kapas. “Itu kata terakhir yang kamu ucapkan sebelum tertidur panjang.”
Arsya menggaruk pelipisnya, wajah berkerut. Namanya sendiri terasa asing, seperti kata dari dongeng.
“Arsya, bagian tubuhmu mana yang paling sakit?”
Perlahan, tangan mungil itu merayap ke perutnya. Di balik perban, kulitnya terasa panas bagai disentuh matahari.
“Oh, di sini?” Dokter Nata mengangguk, ekspresinya tenang namun serius. “Boleh Bapak periksa sebentar?”
Setelah anggukan pelan Arsya, dokter itu membuka perban dengan gerakan ahli. Jahitannya merah meradang, tapi tak ada nanah.
“Tidak apa-apa,” bisiknya, jari menunjuk garis jahitan. “Ini hanya tanda tubuhmu sedang berusaha keras menyembuhkan diri.”
“Kenapa aku terluka di sini?”
Dokter Nata menarik napas. “Beberapa waktu lalu kamu kecelakaan. Saat dibawa ke sini, perutmu perlu diperbaiki seperti… ” Keningnya berkerut mencari analogi. “ Memperbaiki Boneka yang sobek. Kita buka bagian yang rusak, perbaiki, lalu jahit kembali.”
“Operasi?”
“Ya. Tapi lihat,” telunjuknya menelusuri ujung jahitan, “sekarang sudah mulai menutup. Artinya, kamu mulai sembuh.”
Arsya meraba perutnya lagi. Kepal kecil menunduk, suara parau keluar. “Kenapa aku tidak ingat?”
Dokter Nata menatapnya lembut. “Tidak masalah kalau kamu belum ingat. Nanti perlahan-lahan akan kembali.”
Kemudian kejadian yang sebelumnya terjadi seolah terulang. Tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan. Penyemangat dari Dokter Nata seolah tidak mencapai hati Arsya. Dia justru menatap kosong ke arah jendela, di mana cahaya sore mulai memudar. Pikirannya masih berkabut, mencerna penjelasan Dokter Nata tentang operasi, luka, dan benang-benang yang menahannya tetap utuh. Perutnya berdenyut-denyut, tapi entah mengapa, rasa sakit itu terasa... berbeda sekarang. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya, mencegahnya meledak.
Dokter Nata mengamatinya dengan saksama. Dia sedang memindai ruangan, pikirnya, mencari celah di antara kekacauan yang mengurungnya.
“Apa kamu merasa lebih baik sekarang?” Suara Dokter Nata mengambang lembut, mencoba menarik Arsya kembali ke realitas.
Arsya mengangguk pelan. Bukan karena rasa sakitnya berkurang, tapi karena suara itu—seperti jangkar di tengah badai pikiran yang menerpa.
“Bagaimana?” Dokter Nata bersandar lebih santai di kursi, siku menempel di sandaran. “Haus? Atau lapar?”
Lapar? Arsya menekan perutnya. Hampa, tapi bukan rasa ingin diisi. Seolah ada lubang gelap di sana. Namun di baliknya, keroncangan halus memberontak—tubuhnya memang butuh sesuatu.
Ia mengangguk lagi, jempol menggenggam ujung selimut.
Dokter Nata tersenyum, bangkit perlahan-lahan—memberi jeda bagi Arsya untuk mengubah keputusan. “Mari mulai dengan air putih dulu, ya?”
Gelas plastik berisi air disodorkan. Arsya menggenggamnya dengan kedua tangan seperti menerima benda rapuh. “Pelan-pelan,” bisik Dokter Nata sambil menopang gelas. Air mengalir dingin ke kerongkongan, membasahi kekeringan yang tak disadarinya.
“Hari ini kamu sudah boleh makan,” ujar Dokter Nata sambil menaruh gelas. “Nanti Bapak bantu, ya?”
Arsya menatap tangannya sendiri: pucat, kuku-kuku pendek yang masih terselip debu halus. Aku bisa pegang sendok?
Tanpa komando, Dokter Nata mengatur sandaran tempat tidur hingga Arsya setengah duduk. Tekanan di perutnya mengendur. Dentang jam bergema ritmis—tik… tok… tik… tok—iringan setia bagi suap demi suap yang masuk ke mulut Arsya. Ruangan sunyi, tapi sunyi yang hangat oleh kesabaran.
Tiba-tiba, Dokter Nata menarik napas panjang. Suaranya berubah, berat seperti akan menjelaskah sesuatu yang rumit.
“Arsya tahu, dokter punya tanggung jawab besar.”
Arsya mengerutkan dahi.
“Selain ke Tuhan yang memberi ilmu…” Dokter Nata memutar stetoskop di leher, meletakaannya di atas nakas, dia kemudian menatap Arsya, menunggu Arsya mengunyah perlahan, “…kami juga punya sumpah. Namanya Sumpah Hippokrates.”
Hippo…? Kata itu aneh—seperti nama hewan raksasa di buku gambarnya. Bayangan tubuh abu-abu gemuk yang memiliki rahang luas saat menguap, tiba-tiba muncul. “Hippo…” ucapnya terbata, ia mencoba mengulang, tapi hanya teringat sebagian. Pipinya memanas. Arsya menundukkan kepalanya. Dia merasa malu karena tidak bisa memahami satu kata baru yang didengarnya. Dia mungkin terlihat bodoh di mata Dokter Nata.
Dokter Nata tidak menertawakannya. “Hippokrates,” ucapnya perlahan, seperti mengajari anaknya sendiri. “Susah, kan? Dulu Bapak selalu salah sebut.”
Arsya menatapnya. Dia juga pernah salah? Tapi dari sorot mata dokter, suara yang menyatakan sebenarnya dia tidak pernah salah mengucapkan terdengar. Namun, Arsya tahu Maksud Dokter Nata tadi bukan olok-olok, tapi menenangkan Arsya.
“Itu janji,” lanjut Dokter Nata, telapak tangan membentuk lingkaran imajiner. “Janji untuk menolong, bukan menyakiti. Arsya tahu tugas dokter?”
“…Menyembuhkan orang sakit?” jawab Arsya, suara kecilnya menguat.
“Betul!” Dokter Nata tersenyum, tapi matanya tak kehilangan kesungguhan. “Tapi juga… melindungi.” Ia menunduk hingga pandangannya sejajar dengan Arsya. “Termasuk melindungimu.”
Arsya diam. Tangannya memelintir ujung selimut, menyalurkan semua emosinya padanya.
“Contohnya…” Dokter Nata mengetuk name tag-nya. “Dokter nggak boleh beri obat sembarangan. Enggak boleh bentak pasien. Dan…” Jarinya mengarah ke Arsya, berhenti tepat di jarak aman. “…harus pastikan kamu merasa aman.”
Aman. Kata itu menggantung. Bagi Arsya, seolah kata asing dan bagi Dokter Nata seolah janji yang harus dia jaga.
Arsya menatap langit-langit. Kelopak matanya tiba-tiba terasa terbakar.
Tanpa bicara, Dokter Nata menyelipkan tisu ke tangannya. “Pegang ini,” bisiknya. “Kalau mau nangis, jangan ditahan. Dokter juga nggak boleh larang pasien menangis.”
Arsya memejamkan mata. Tisu itu remuk dalam genggamannya.
Tapi untuk pertama kalinya sejak terbangun, di balik kabut ketakutan, ia merasakan sesuatu…
...bahwa di ruangan ini, ada seseorang yang takkan menjadi bagian dari luka-lukanya.
“Arsya mau mempercayai Pak Dokter?”
Arsya menatap Dokter Nata. Matanya yang masih sembap menyapu setiap kerutan di wajah dokter itu: senyum yang tak pernah sepenuhnya lebar, tarikan napas yang tertahan, seperti sandiwara yang direkam frame per frame, bagi Arsya.
Tapi aku tidak kenal dia. Bagaimana jika dia jahat?
Anehnya, tanpa izin dari pikirannya sendiri, jari-jari mungilnya meraih ujung jas lab Dokter Nata. Dari suatu tempat di dalam bayang-bayang, bisikan asing menyelinap: ‘Kamu bisa membedakan, Nak…’ Arsya tahu, namun keraguan masih saja hadir ‘Bagaimana jika aku salah?’
Dokter Nata membeku. Namu, tidak menarik tangan, tidak pula menghela napas. Hanya mata hitamnya yang berkedip pelan, menahan seluruh dunia di balik kelopak.
Lambat-laun, anggukan Arsya terlihat.
Tangisnya pecah lagi—bukan air mata, melainkan getaran jiwa yang meronta. “Dokter nggak akan berbuat jahat, kan?” bisiknya, suara serak, tangannya dengan brutal mengusap kasar wajahnya yang basah oleh air mata.
Dokter Nata mengulurkan jari kelingkingnya, sebuah lengkung kecil yang kokoh di antara mereka. “Enggak akan. Dokter janji.”
Arsya mengernyit. “Kenapa dokter begitu?”
“Ini cara berjanji yang paling sakti,” jelas Dokter Nata sambil dengan hati-hati melingkarkan jari kelingkingnya ke jari mungil Arsya. “Kalau sudah kait seperti ini, nggak ada yang bisa bohong.”
Ia menekan ibu jari Arsya dengan lembut, mencap sebuah ikrar tanpa tinta. Saat senyum mereka nyaris bertemu—
Di luar ruangan, di koridor yang diterangi lampu neon pucat, bayangan Pak Nohan memanjang, meninggalkan bayang mengerikan. Jarinya menari di layar ponsel, cahaya birunya menusuk kegelapan. Pesan terkirim ‘Datanglah ke ruanganku. Aku membutuhkan seseorang bisa kutugaskan untuk menjaga dan melaporkan keadaan seorang anak.’
Ia menengok ke arah pintu kamar Arsya. Cahaya hangat dari celah pintu berkedip, memotret siluet Dokter Nata yang sedang tertawa. Pak Nohan mengeratkan rahang. Langkahnya menjauh, setiap hentakan sepatu boot-nya menggemakan gema yang tercekik.
Di dalam ruangan, Arsya tertawa renyah saat Dokter Nata membuat wajah konyol.
Di luar, sepotong kertas laporan medis disobek paksa oleh Pak Nohan—nama ‘Arsya’ tercoret merah, dan di sudutnya, stempel ‘CONFIDENTIAL’ terlihat, senyum aneh terlukis di wajahnya, dia kemudian merobek laporan menjadi lebih kecil, hingga informasi yang tertulis sepenuhnya tidak terbaca. Kertas-kertas itu berakhir di kotak sampah


 hanyaselingan
hanyaselingan