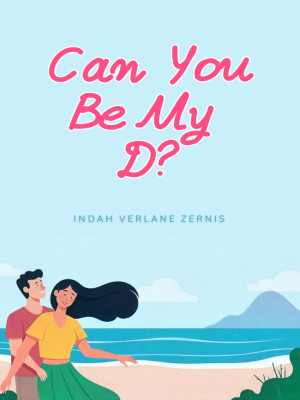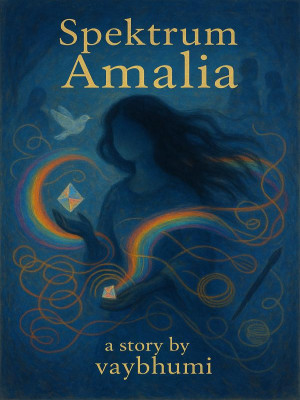“Aku adalah buku yang halaman-halamannya telah robek, cerita yang terputus di tengah jalan. Dipenuhi teka-teki yang tak terjawab, sebuah enigma yang terus melangkah. Ironisnya, aku lebih mengenal dunia ini daripada diriku sendiri. Siapakah aku, jika bahkan namaku adalah bisikan samar dan wajahku hanyalah bayangan yang tak kukenali?”
__ Arsya Abiseka Gantari
Kelopak mata Arsya terbuka perlahan, disambut aroma klorin dan alkohol menyengat masuk ke dalam hidungnya, menggerus sisa kantuk dari mimpi-mimpinya yang tidak bisa ia pahami. Cahaya putih menyilaukan menerpa retina setelah mencoba mengerjap perlahan, bayangan kabur dari matanya membeberkan panorama asing, dinding putih steril, tiang infus intravena menjulang, dan nasa kanula yang membelit hidungnya.
Ia mencoba mengepalkan jari. Otot-ototnya menolak, lemas seolah tulang berlapis daging itu bukan miliknya sendiri. Kepalanya terasa hampa—sebuah ruang kosong tempat ingatan seharusnya bersemayam justru semakin menyadarkannya akan ruang kosong disana, ingatannya seakan hilang, menyisakan kekosongan yang mencekam, mengundang deretan pertanyaan. Siapakah aku? Desahan napasnya tertahan ketika jantungnya mulai berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Di mana ini? Apa yang terjadi padaku?
Sebelum napasnya sempat teratur, tirai Tirai biru di sampingnya tiba-tiba tersibak. Seorang perawat muda berdiri kaku, pupil mata membesar seperti menyaksikan hantu. “Pasien siuman!” teriaknya, suara melengking di antara deru monitor EKG. “Nak, jangan tidur lagi. Aku akan panggil dokter!” pintanya sebelum segera bergegas pergi.
Arsya membuka mulut, tapi yang keluar hanya desis udara dari tenggorokan yang kering. Ia memejamkan mata, menggali kuburan ingatan, namun kegelapan di balik kelopaknya tak membawa jawaban—hanya serpihan ingatan yang menguap sebelum bisa ditangkap. Setiap upaya untuk mengingat hanya menusuk pelipisnya dengan nyeri berdenyut.
Derap sepatu kets mendekat dalam ritme kacau. Arsya ingin tetap membuka mata, penasaran dengan suara-suara yang semakin mendekat. Mungkin mereka bisa memeri jawaban tentang siapa dirinya, tapi kelopak matanya terasa berat. “Jangan tertidur!” suara perawat itu kembali, jari-jari dinginnya menjepit pergelangan tangan Arsya seperti ingin menambat nyawa yang melayang.
“Arsya?” Suara bariton lembut mengiris udara.
Arsya, nama itu... Terasa asing di ruang hampa pikirannya. “Apakah itu namaku?”pikir Arsya
“Bisakah kau mendengarku?” tanya suara sama yang memanggilnya dengan nama Arsya. Dia mendengar pertanyaan itu, dia ingin menjawab, namun suaranya tertahan. Setidaknya Ia ingin mengangguk, sebagai isyarat jawaban, namun meskipun dia telah berusaha, sepertinya orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihatnya.
Senter kecil menyorot refleks pupilnya yang lamban. “Nak… Tolong bertahan,” desis Dokter Nata sambil mengamati grafik EEG yang fluktuatif. “Kami di sini untukmu.” suaranya terdengar meyakinkan, tetapi bagi Arsya, semuanya hanya terasa seperti kebingungan yang semakin dalam. Suaranya terdengar meyakinkan, tetapi bagi Arsya, semuanya hanya terasa seperti kebingungan yang semakin dalam.
Alin menggigit bibir bawah.”Dia membuka matanya tadi—aku lihat sendiri!” perawat yang melihat Arsya sadar berusaha membela diri. Jarinya sibuk memilin ujung seragamnya hingga terlihat sedikit kusut.
Dokter itu tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada monitor EKG, di mana garis hijau bergerak tak menentu.
“Efek residual anestesi,” jawabnya setelah beberapa saat. “yang kamu lihat hal wajar, kesadaran pasien seringkali tidak stabil setelah operasi” lanjutnya berusaha menenangkan Alin.
Di sebelah Dokter Nata, seorang pria berdiri dengan kemeja putih yang masih pristine—tidak ada lipatan, tidak ada noda, seolah baru saja dikeluarkan dari etalase butik. Tak ada jejak darah di mansetnya yang rapat menutupi pergelangan tangan Rolex. Tak ada noda di sepatu Oxford-nya yang mengkilap.
Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tiga jam lalu menjepit tubuh Arsya di antara pintu mobil Mercedes-nya dengan tangan-tangan gemetar mengeluarkan Arsya dari bangku penumpang. Tak ada kesan panik di wajahnya yang sekarang tersusun rapi, tak ada bayangan rasa bersalah di balik kerutan dahi yang terlihat lebih seperti kekesalan daripada kekhawatiran.
Aswan Mahatma Wasesa.
Sosok yang sekarang berdiri tegak dengan sikap seorang eksekutif ini adalah versi yang sama sekali berbeda dari pria yang ketika berlari membawa Arsya ke UGD, dengan napas tersengal-sengal dan rambut basah oleh keringat, yang sekarang sudah rapi kembali disisir ke belakang.
Tangannya mengetuk-ngetuk casing ponsel bermerk, layarnya terus menyala—Istri: 7 Missed Calls, berkedip seperti alarm yang diabaikan.
Matanya, sesekali melirik ke arah tempat tidur, tapi tidak benar-benar melihat Arsya. Alisnya berkerut, tapi bukan karena khawatir atas tubuh bocah yang terbaring lemas—lebih karena rahangnya terkunci terlalu kencang, menahan amarah yang tidak boleh keluar di sini.
‘Dia harus sadar sebelum media mencium bau busuk ini,’ pikirnya, membayangkan headline surat kabar: ‘Putra Grup Maheswari Tabrak Anak Jalanan dalam karena bertelepon sambil berkendara.’
“Berapa lama lagi?” suara Pak Aswan menginterupsi kesibukan Dokter Nata.
Dokter Nata menghela napas. “Tidak bisa dipastikan. Cedera kepalanya parah. Kami masih memeriksa—”
“Jam atau hari?” Pak Aswan memotong, langkahnya mendekati tempat tidur. Suaranya rendah tapi menusuk. “Saya butuh angka.”
Arsya, yang kini berada dalam keadaan setengah sadar, mendengar percakapan itu seperti gema jauh yang tak bisa ia tangkap sepenuhnya. Suara mereka berbaur dengan denyut sakit yang menjalar dari kepala hingga ke ujung jarinya.
Siapa mereka? pikirnya dalam kebingungan. Kenapa mereka menginginkan aku segera bangun? Aku juga menginginkan itu, tapi __” Rasa sakit kembali datang, menusuk-nusuk kepalanya dengan ratusan jarum tak kasat mata. Tubuhnya seolah ditindihi puluhan batu yang begitu berat, hingga sekadar menggerakkan jari pun terasa mustahil. Udara di sekitarnya terasa pekat, menekan dadanya seolah enggan membiarkannya bernapas bebas.
Cahaya putih di langit-langit terasa semakin buram, suara monitor medis mulai berubah menjadi dengungan samar di telinganya. Dunia perlahan menjauh, memudar, hingga akhirnya hanya ada kegelapan yang pekat. Kemudian semua kembali hening bagi Arsya.
Tapi di luar kesadarannya, monitor medis terus berbunyi monoton—ritme yang kini dikelilingi suara tegang dua sosok, sang dokter dengan prinsip tergores, dan si penguasa dengan kalkulasi tersembunyi.
“Kami sudah memaksimalkan upaya, Pak Aswan,” Dokter Nata menekankan, jarinya mengetuk berkas pasien dengan ritme tegang. “Tapi kondisi trauma kepala tidak bisa dipaksa. Ada proses alamiah yang—”
“Alamiah?” Pak Aswan menyela, bibirnya melengkung dalam senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Suaranya merdu seperti penyiar radio, bertolak belakang dengan isyarat tangannya yang mematung—jari telunjuk menunjuk ke monitor jantung Arsya. “Dokter, kita sama-sama tahu ‘alamiah’ bisa dipercepat dengan teknologi. Atau…” Ia mendekat, aroma parfum mahal menyengat di antara bau antiseptik, “...apakah rumah sakit ini kekurangan sumber daya?”
Dokter Nata mengerutkan kening. Ada racun terselubung dalam kata-kata itu—tawaran bantuan yang sekaligus ancaman. “Bukan itu persoalannya, Pak. Kami khawatir—”
“Ah, kekhawatiran!” Suara Pak Aswan merendah. Tangannya terangkat seolah menenangkan, jari-jemari yang bersih tanpa noda itu menekan pelipisnya dengan ritme terukur—gerakan yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan senyum tipis di sudut bibirnya.
“Kita semua resah, Dokter.” Matanya menyipit. “Lihatlah dia—” Ia menunjuk ke arah Arsya “—masih begitu muda, begitu... lemah. Tentu saja saya ikut khawatir.”
Dokter Nata mengepalkan tangan di saku jasnya. Pengakuan Pak Aswan terasa hambar, bagaikan retorika yang kosong meski dibungkus kemanusiaan. Dokter Nata mengenang
Baru 36 jam lalu, pria ini tampil sebagai pahlawan dadakan di UGD - pakaiannya yang kotor dipenuhi darah dan lumpur, napas tersengal-sengal sambil membopong tubuh Arsya yang lemas. “Aku menemukannya di pinggir Jalan,” katanya waktu itu, suara bergetar yang sempat membuat Nata tersentuh. “Mungkin korban tabrak lari.”
Saat itu, Nata hampir termakan acting-nya. Caranya membawa Arsya, menjelaskan situasi, hingga kesediaannya menanggung semua biaya pengobatan, sempat menimbulkan anggapan bahwa investor rumah sakit itu adalah pribadi yang berjiwa humanis.
Kini, dengan setiap detik yang berlalu, puzzle mulai tersusun. Kekhawatiran palsu Pak Aswan berubah menjadi tuntutan terselubung. Gestur ‘penyelamatan’ kemarin - yang semula terlihat heroik - sekarang terasa seperti adegan yang terlalu dipentaskan. Semua rangkaian kejadian itu membuat prasangka Dokter Nata menguat, Pak Aswanlah yang membuat Arsya seperti sekarang.
Di ranjang pasien, jari Arsya bergerak lemah. Dokter Nata mengamatinya, lalu menatap Pak Aswan yang sedang asyik memantau jam tangannya. Menjadi isyarat dua jenis waktu yang berjalan bersamaan. ‘Waktu biologis Arsya yang berjuang untuk pulih dan waktu psikologis Pak Aswan yang sedang menghitung mundur’
“Dokter,” Pak Aswan menundukkan kepala sejenak, suaranya melunak. “Begini, saya akan menceritakan sesuatu, tolong posisikan diri Anda sebagai saya yang menghadapi situasi ini.” Ia berhenti sejenak, napasnya terdengar berat. “Anak ini... tiba-tiba menyeberang di tengah hujan deras. Saya tidak sempat menghindar.” jelas Pak Aswan dengan lancar, seolah semua sudah dia rencanakan. Namun, matanya menghindari tatapan Dokter Nata, seolah ada sesuatu yang disembunyikan.
Penjelasan singkat Pak Aswan membuka pemahaman Dokter Nata, sayangnnya bukan dalam cara yang Pak Aswan harapkan. Ia menyadari bahwa niat Pak Aswan mempercepat kesadaran Arsya hanya punya satu tujuan. Memastikan ingatan anak itu mengenai kejadian yang menimpanya, serta usaha Pak Aswan agar tetap terlihat bersih dari kecerobohannya berkendara. Pasti saat itu dia sedang mabuk, atau tidak fokus mengemudi.
“Jadi… “ Pak Aswan melirik Name tag yang tergantung di jas dokter Nata “Dokter Nata, kamu tentu paham... rumah sakit ini butuh donasi untuk renovasi ICU, bukan?” Pak Aswan mengambil alih laporan medis Arsya dari genggaman Dokter Nata. Jarinya mengetuk-ngetuk laporan medis Arsya. “Aku bisa menjadikan itu prioritas.”
Tepat di seberang Dokter Nata berdiri, Adalah jendela kaca yang kini menampakkan bayangan Dokter Nata terlihat kaku—persis seperti hari ia pertama kali bersumpah sebagai dokter, Pak Aswan yang terlihat santai karena sudah memperkirakan dia yang akan memenangkan penawaran, dan selang cairan infus menetes perlahan seperti detak jam bom.
“Biaya bukan masalah,” Pak Aswan melanjutkan sambil menyetel cincin berliannya ke arah cahaya. ‘Permata ini bisa membeli sepuluh nyawa seperti dia’, batinnya. “Tapi reputasi? Itu mahakarya seumur hidupku.”
Dokter Nata menarik napas dalam. Bau antiseptik bercampur aroma mewah parfum Pak Aswan kembali terasa menusuk. “Dengan segala hormat, Pak. Sumpah Hippokrates saya—”
“Ah, sumpah!” Potong Pak Aswan sambil tersenyum—senyum yang tidak sampai ke mata. “Kau masih muda, Nata. Dunia ini dijalankan oleh orang-orang yang tahu kapan harus membungkuk.” Dia menyentuh pundak dokter itu, sentuhan dingin seperti ular logam. “Kapan saya akan mendengar kabar anak ini sudah sadar?”
Dokter Nata akhirnya menatapnya. Ada sesuatu di sorot mata Pak Aswan yang membuatnya waspada—bukan sekadar khawatir, tapi harus memperhitungkan semua kemungkinan. Kemudian dengan penuh perhitungan, Dokter Nata mencoba membuat penawaran “Jika stabil, mungkin 48 jam. Tapi jika ada perdarahan lagi—”
“Baiklah… Intinya tetap belum ada kepastian, kalau begitu begini saja, permintaanku lebih disederhanakan. Dia anak jalanan tanpa identitas, hidup setelah mengalami kecelakaan sudah hal mewah baginya,” Pak Aswan mendekati Doker Nata kemudian berbisik di telinganya “Dia tidak boleh ingat apa-apa.”
Dokter Nata membeku. Ini bukan permintaan—ini perintah. “Amnesia pasca-trauma tidak bisa dijadikan jaminan, Pak.” sahut Dokter Nata berusaha tetap professional.
Pak Aswan kembali tersenyum “Kalau tidak alami, buatlah terlihat alami.” tangannya meraih lengan Dokter Nata, menjabat kuat. “Kalau dia sadar dan mulai bicara, karier Anda akan lenyap sebelum sempat meminta maaf. Pastikan dia tetap diam. Aku tidak peduli apa yang harus kalian lakukan.”
Monitor jantung tiba-tiba memekik dengan ritme panik –bip…bip…bip…bip- seolah jantung Arsya yang terperangkap itu berusaha mewakilinya menjerit melalui mesin. Tubuhnya yang tak bergerak, wajahnya yang pucat, semua bertolak belakang dengan garis-garis liar di layar EKG yang bergerak naik turun seperti grafik keputusasaan.
Dokter Nata langsung mengambil tindakan yang diperlukan. Memandu Alin membantunya sesuai dengan prosedur. Di ambang pintu, Pak Aswan berhenti sejenak. Cahaya koridor membentuk siluet tubuhnya yang ramping, seperti bayangan ancaman yang membentang hingga menyentuh tempat tidur Arsya. “Aku menunggu kabar baik anak itu, besok pagi,” ujarnya lagi, kali ini dengan intonasi yang membuat kata terakhirnya terdengar seperti vonis hukuman mati.
Pintu menutup dengan bunyi yang terlalu halus untuk sesuatu yang terasa seperti pukulan. Dokter Nata menatap Arsya yang masih bergulat antara hidup dan mati. Di dahi bocah itu, butiran keringat dingin terlihat. Tangannya yang kurus, dengan pembuluh darah biru yang jelas terlihat, tergeletak lemas di atas selimut.
“Tahan, Nak,” bisik Dokter Nata sambil menyesuaikan oksigen. Suaranya parau, mengandung beban yang tidak bisa diungkapkan pada pasien koma. Ia menyeka peluh di dahinya, lalu menundukkan kepala sejenak. ‘Bagaimana mungkin seorang anak menjadi pion dalam permainan kekuasaan orang dewasa? Bagaimana aku bisa memilih antara sumpah dokter dan ancaman yang menggantung di udara seperti pisau bedah?’
Monitor mulai stabil, —bip... bip... bip...—ritme yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuat Dokter Nata semakin waspada. Ia menarik napas dalam, udara dingin ruang ICU mengiris paru-parunya.
Di jendela, bayangannya seolah terbelah dua, sosok dokter berjas putih yang tegak, dan seorang lelaki dengan bahu sedikit membungkuk, seperti menanggung beban yang tak terlihat.
“Kau bisa pergi dulu, Alin,” ujarnya pada perawat, suaranya lebih berat dari biasanya. “Aku ingin memeriksanya lagi.”
Ketika pintu menutup, barulah ia membiarkan dirinya berlutut di samping tempat tidur Arsya. Jemarinya yang biasanya mantap kini gemetar saat menyeka pipi basah itu.
“Sakit, ya?” Bisikannya serak, “Aku janji, aku akan usahakan yang terbaik... Tapi kau harus membantuku juga. Bangunlah, Nak. Ceritakan padaku... siapa yang harus kuberi tahu bahwa kau ada di sini? Katakan, siapa yang membuatmu terluka sampai separah ini?”
Tapi Arsya tetap diam. Hanya kelopak matanya yang berkedut, seolah merespons dalam mimpi.
Pikiran Dokter Nata melayang saat pertama kali melihat Arsya di UGD. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Baju Arsya terlihat begitu sederhana—seolah ia meninggalkan segalanya dalam tergesa-gesa. Memar di tubuhnya yang menegaskan alasan Arsya sendirian saat hujan deras tengah malam. Kancing baju bagian atas terputus, seperti ditarik paksa. Ditambah lututnya yang terluka. “Apakah ada yang mengejarmu, Nak?”
Selain itu ingatannya saat memeriksa monitor EEG berkedip-kedip dengan pola yang tidak biasa, seolah aktivitas otak Arsya terlihat terlalu aktif meski tubuhnya tak bergerak. Dokter Nata mengerutkan dahi. “Ada sesuatu yang tidak wajar tentang anak ini,” gumamnya pelan.
Tiba-tiba, peringatan Pak Aswan bergema lagi di kepalanya: ‘Pastikan dia tetap diam. Aku tidak peduli apa yang harus kalian lakukan.’ Genggamannya pada tempat tidur Arsya mengencang. “Apa yang sebenarnya anda sembunyikan, Pak Aswan?”
Dan di balik semua itu, pertanyaan yang terus menghantui. “Siapa kau sebenarnya, Arsya? Dan mengapa Pak Aswan begitu takut akan kesaksianmu?”
Sama seperti Dokter Nata yang begitu tertekan atas perintah Pak Aswan, Arsya juga tertekan dengan keadaannya. Dia kembali sadar namun tidak lagi di kamar rawat, dia terhisap ke dalam labirin gelap yang tiba-tiba bermetamorfosis menjadi dunia kabur antara tidur dan jaga. Di sini, waktu berdetak dalam ritme tidak menentu—seperti film bisu yang diputar ulang dalam kecepatan lambat.
Air matanya membasahi pipi, jatuh ke hamparan ilusi yang menyerupai lantai marmer dingin. Setiap tetesannya memantulkan fragmen ingatan, bayang-bayang Dokter Nata yang mengerutkan dahi, suara Pak Aswan yang menggema seperti guruh, dan tubuhnya sendiri yang terbujur kaku bagai patung
Tiba-tiba, suara yang begitu Arsya kenal terdengar, menyusup ke ruang hampa itu.
“Kembali lagi, Nak?”
Suara itu mengubah kegelapan menjadi kamar kecil berpendar keemasan. Sosok itu duduk di sampingnya, tangan transparannya mengusap rambut Arsya dengan gerakan lembut
“Bunda… Aku nggak mau tinggal di sana. Ada orang jahat” keluhnya, pada sosok wanita yang dia kenali dengan sebutan ‘Bunda’. Jemarinya mencengkeram tepi gaun sosok itu—kainnya terasa hangat seperti sinar mentari pertama di musim semi, tapi terus menguap seperti asap di antara sela jarinya.
Sosok itu tersenyum, “Kamu nggak perlu khawatir, Nak. Di sana, sebelum bertemu Kakekmu banyak orang yang menyanyangimu juga, nantinya.” ujarnya menenangkan.
“Tapi aku tidak mengenali siapapun di sana, aku lupa semuanya. Bagaimana aku tahu kalau dia orang baik?”
“Kamu bisa mengetahuinya, kamu mampu membedakannya, Nak.”
“Bagaimana caranya?” tanya Arsya, namun sebelum mendapatkan jawaban, lagi-lagi sosok itu menghilag. Meninggalkan Arsya yang kebingungan dengan senyum menenangkan
“Kamu akan tahu caranya. Bangunlah, Nak! Kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun”
Setelah perintah itu terdengar, tubuh Arsya terasa tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dunia mimpi hancur berkeping-keping di sekelilingnya. Cahaya keemasan berubah menjadi lampu yang memendarkan cahaya putih ruang rawat rumah sakit, Sentuhan hangat menjelma dinginnya selang infus di lengan. Kemudian, suara lembut itu terdistorsi menjadi gema asing yang menyapa indra pendengarannya. Membuatnya seolah hampir dikuasai oleh ketakutan. Tapi di kedalaman jiwanya, denyut aneh tetap bergetar—seperti kode dari alam bawah sadar yang menjanjikan “Kau bisa membedakannya, Nak.”
Saat Arsya kembali membuka matanya, ruangannya terasa berbeda. Tidak ada lagi masker oksigen yang menutupi hidungnya, dan alat-alat medis di sampingnya berkurang. Pandangannya masih kabur, tapi kali ini ia menyadari bahwa ada ranjang lain di sebelahnya. Seorang pasien terbaring di sana, dijaga oleh dua orang yang tampak memperhatikannya. Saat mata Arsya belum sepenuhnya terbuka, mereka mengira dia masih tertidur.
Tiba-tiba, suara-suara mulai terdengar. “Sudah dua hari anak itu tidak bangun. Tidak ada yang mengunjunginya. Bukankah seharusnya ada orang tua yang menjaganya?” ucap salah seorang penjaga dengan nada khawatir.
“Kenapa kita tidak boleh membicarakan anak itu kepada orang lain? Ruangan ini terasa misterius.” Suara lain menyahut, kali ini lebih tenang tapi penuh pertanyaan.
Arsya mengerutkan dahi. Suara itu... jelas terdengar, tapi bibir mereka tidak bergerak. ‘Apa yang terjadi padaku?’ pikirnya. ‘Mengapa mereka berbicara tentang dirinya? Dan mengapa mereka terdengar tidak berbicara satu sama lain? Seolah ada percakapan yang tidak saling bersambung?’.
Setelah beberapa saat, perawat masuk dan membantu pasien di samping Arsya untuk pindah ke ruangan lain. Ketika ruangan itu kosong, tiga perawat mendekati Arsya.
“Nak, maaf ya, dokter sedang sibuk memeriksa pasien lain. Nanti dia akan menyusul ke sini. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada bagian tubuh yang sakit?” tanya salah satu perawat dengan lembut.
Arsya menggeleng perlahan. Tidak ada yang terasa sakit. Aneh, pikirnya, dia bahkan tidak bisa merasakan apapun tubuhnya.
Perawat itu membantu menyesuaikan tempat tidur Arsya agar lebih nyaman. “Apa ini lebih baik?” tanyanya lagi.
Arsya mengangguk, dan ketika perawat itu memintanya berbicara, Arsya menjawab dengan suara pelan, “Sudah lebih nyaman.”
“Nak, boleh saya tahu di mana kamu tinggal sebelumnya? Kami perlu menghubungi keluargamu,” lanjut perawat itu.
Arsya terdiam. Harusnya ia bisa menjawab pertanyaan itu, tapi tidak ada apapun di kepalanya. Tidak ada yang bisa dijadikan jawaban.
“Aku... aku tidak ingat apapun,” ucapnya jujur.
Ruangan itu tiba-tiba hening. Perawat-perawat di sekeliling Arsya saling bertukar pandang, ada yang menampilkan ekspresi bingung dan pula yang penuh simpati.
“Amnesia?” gumam salah satu perawat dengan nada rendah. Arsya mendengar suara mereka, tapi bibir mereka tidak bergerak. Bagaimana mereka bisa berbicara tanpa bicara? pikirnya.
“Padahal harapan kami, anak ini bisa sembuh dan tidak dibuang ke panti,” gumam suara lain, tetapi sekali lagi, tak ada yang mengucapkan kata-kata itu secara langsung.
Arsya merasa semakin bingung. Dua suara terdengar di kepalanya—satu menanyakan tentang amnesia, yang lain berbicara tentang harapan. Tapi tak satupun yang berasal dari perawat-perawat yang ada di depannya.
“Namamu Arsya,” ujar salah satu perawat, suaranya lebih lembut. Membuat Arsya terkejut karena tanpa sadar dia melamun. ‘Arsya’ nama itu muncul lagi, apakah itu sungguh nama aslinya?
“Kamu ingat?” tanya perawat itu lagi.
Arsya menggeleng. Dia bahkan lupa namanya. Arsya menundukkan kepalanya, air mata mulai menetes dari sudut matanya.
Tiba-tiba, suara-suara berbisik terdengar di telinganya, namun tidak ada yang benar-benar mengucapkannya. “Ya Tuhan... anak ini bahkan lupa ingatan.” bisik salah satu suara, penuh simpati.
“Kasihan...,”sahut yang lain, suara lirih yang seolah datang dari kejauhan.
Namun, ada suara lain yang lebih tajam, lebih menusuk. “lebih baik kemarin kamu tidak membuka mata lagi, kamu sudah di buang, tidak ada yang peduli padamu. Kamu akan selalu terjebak dalam permainan orang lain jika terus hidup” suara itu bergema dalam pikirannya, bagaikan racun yang menyebar cepat. “Apa gunanya hidup kalau semua kamu lupakan?”
Arsya menutup matanya rapat-rapat, berharap suara-suara itu hilang. Namun, suara-suara itu terus mendengung di pikirannya, menjerumuskan dia lebih dalam ke jurang keputusasaan. Apa yang bisa kuharapkan sekarang? pikirnya, tubuhnya semakin gemetar dalam pelukan dirinya sendiri. Haruskah aku berhenti berharap? Apakah ada yang akan datang menolongku?
Suara lembut perawat itu kembali terdengar, namun kali ini terasa jauh. “Kamu istirahat dulu, ya?” katanya, mencoba menenangkan Arsya. “Mungkin kamu hanya takut, dan itu membuatmu sulit mengingat.”
Arsya ingin sekali percaya pada perawat itu. Namun, rasa takutnya terlalu kuat, seperti dinding yang tak bisa ditembus. Dia melihat para perawat di depannya—empat sosok yang berbeda, tapi semua tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa.
“Kamu nggak sendirian, Nak. Kita akan cari tahu semuanya, perlahan-lahan.” salah satu perawat menggenggam tangan Arsya erat, berusaha menyalurkan ketenangan yang sama yang seharusnya dirasakan Arsya.
Namun, dalam hati kecil Arsya, ketakutan itu terus membesar. Bagaimana jika dia tidak pernah ingat siapa dirinya? Bagaimana jika dia selamanya terjebak dalam kekosongan ini? Setiap kata yang diucapkan perawat seolah hanya menambah jarak, membuat Arsya semakin terisolasi dalam pikirannya sendiri.


 hanyaselingan
hanyaselingan