Air hujan masih menetes dari rambut Atha ketika ia mendorong pintu rumah dengan bahu. Gemeretak kunci yang beradu dengan logam terdengar nyaring, terlalu nyaring, seperti suara dunia yang ingin ia hentikan paksa.
Tidak ada kata. Tidak kepada ibunya yang bergegas keluar dari dapur dan bertanya dengan napas tertahan, tidak kepada ayahnya yang menoleh dari ruang tengah dengan alis berkerut—yang entah kenapa ada di rumah padahal sedang hari kerja. Tatapannya kosong, bahkan tidak menyapu ruangan. Kakinya langsung melangkah ke arah kamarnya, basah kuyup, meninggalkan jejak air di lantai seperti sisa banjir yang baru surut.
“Tha?” suara ibunya terdengar ragu. “Kamu dari mana? Kenapa basah gitu—Tha, kamu kenapa, nak? Kok udah pulang jam segini?”
Atha tidak menjawab. Langkahnya hanya semakin cepat. Pandangannya melewati semua tanpa benar-benar melihat.
Pintu kamarnya menutup tanpa suara. Ia mengunci, menyalakan lampu sebentar hanya untuk mengganti baju yang lengket di tubuhnya, lalu mematikan lampu lagi. Gelap. Hanya bunyi napasnya yang berat, seperti sedang menanggung satu dunia di dada.
Atha duduk di pinggir kasur, tangan masih gemetar. Bukan karena dingin. Tapi karena tubuhnya sudah tak tahu lagi cara tenang. Semua yang ia tahan sejak minggu lalu—tentang Niko, tentang Dero, tentang dirinya sendiri—bercampur jadi satu ledakan sunyi yang tidak meledak ke mana-mana. Hanya diam. Membatu. Menekan dari dalam.
“Kenapa harus gue terus sih yang ditinggal?” bisiknya sendiri, nyaris tak bersuara. “Apa salah gue sampai segininya...?”
Sudah lama ia tidak merasa seperti ini. Terlalu lama, hingga ia lupa caranya bertahan dalam keadaan ini.
Beberapa bulan lalu, ketika pengumuman kelulusan dibacakan dan namanya tidak disebut, Atha menahan senyum pahit di depan teman-teman. Ia bilang sistem salah input, nilainya harusnya aman, pura-pura sibuk isi formulir untuk ujian susulan. Semua dusta yang dipelajari dari hidup. Padahal kenyataannya, ia tidak lulus. Tidak cukup nilai. Tidak cukup kuat. Dan sekarang, semua rasa gagal itu datang lagi, dengan cara yang jauh lebih busuk.
Saat itu ia pikir ia sudah melewati titik terendah. Tapi rupanya, tanah bisa runtuh lebih dalam.
Ia menatap layar ponsel di samping bantal, mati. Notifikasi pun tidak ada. Tidak ada pesan dari Dero. Tidak ada kabar dari Niko. Tidak ada suara dari siapa pun.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti tirai gelap yang tidak kunjung terbuka. Atha tidak masuk sekolah. Bahkan tidak membalas pesan wali kelas yang mulai menanyakan kehadiran. Ia hanya bangun ketika suara ibunya mengetuk pintu dengan suara cemas. Ia makan beberapa sendok nasi, cukup agar tidak disuapi. Lalu kembali tenggelam ke kasur.
“Tha… kamu bisa cerita, ya… Mama enggak marah kok,” suara ibunya di balik pintu selalu lembut, selalu penuh kekhawatiran. Tapi Atha hanya menarik selimut menutupi wajah.
Langit-langit kamar menjadi satu-satunya pemandangan. Dinding menjadi penjara yang tidak perlu palang besi. Jam menjadi angka-angka acak yang tak ia pedulikan. Ia bahkan tidak tahu ini hari keberapa. Atau apakah itu penting.
Kadang ia mendengar suara ayahnya dari luar kamar, bicara pelan. Kadang ibunya masuk membawa pakaian bersih dan duduk sebentar, tidak bicara, hanya menyentuh lengan Atha yang dingin. Tapi tak ada yang menembus perasaannya. Tak ada yang cukup kuat membakar kabut di kepalanya.
Ia rusak. Lagi.
Dan yang paling menyakitkan dari semua ini adalah ia sudah pernah sembuh. Sudah pernah merasa lebih baik. Sudah pernah percaya bahwa ia bisa jadi orang normal. Bahwa luka-lukanya bisa dirawat. Tapi ternyata harapan itu cuma jeda. Bukan akhir. Cuma istirahat sementara sebelum dihantam lagi. Kali ini, bahkan lebih dalam.
Layar ponsel menyinari wajah Atha yang pucat. Ia menggulir jempolnya pelan, membuka aplikasi demi aplikasi tanpa arah. Instagram. Galeri. WhatsApp. Instagram lagi. Semua hanya untuk menambah luka, untuk memastikan bahwa ia benar-benar ditinggalkan.
Akun Dero. Tertutup. Profil kosong. Tombol ‘Mengikuti’ masih abu-abu. Permintaan yang dikirimnya seminggu lalu belum juga direspons. Begitu juga dengan Niko. Bahkan nama akun Niko pun sudah diubah. Foto profilnya disembunyikan. Bio yang tadinya berisi kutipan lagu kini hanya satu titik.
Atha menarik napas. Tapi yang terasa masuk ke paru-parunya bukan udara, melainkan kehampaan yang dingin. Ia menekan tombol home. Lalu kembali membuka Instagram, seolah berharap sesuatu berubah. Tidak ada yang berubah.
Bibirnya kering. Pandangannya kabur. Dan entah kenapa, ia justru membuka galeri. Deretan foto muncul: potret Niko dengan senyum lebar dan gitarnya di dalam kamar, kemudian Dero yang diam-diam ia ambil saat sedang tertidur beralaskan lengannya di kelas. Satu folder berisi foto-foto coretan papan tulis, catatan, dan foto bersama kertas hasil remedial—semua tumpukan kecil yang pernah membuat Atha merasa dia juga mampu belajar, juga bisa mengejar.
Kini semua itu seperti milik orang lain. Bukan miliknya lagi.
Ia meletakkan ponsel di dada. Lama menatap langit-langit, lalu bergumam kecil, nyaris tak terdengar. “Gue salah apa, sih...?”
Jelas tak ada yang menjawab. Hanya suara kipas angin tua di sudut kamar yang terus berdengung malas.
Ia membuka catatan. Mengetik satu-dua kata. Hapus. Ketik lagi. Kali ini lebih banyak.
Capek.
Gagal mulu.
Bodoh.
Enggak bisa dijadiin sandaran.
Gue ini beban.
Nggak ada satu pun yang mau deketin gue kalau tahu siapa gue sebenernya.
Ia menatap tulisan itu. Jari-jarinya menggigil. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam. Karena bahkan rasa sakit pun sudah tidak berbentuk jelas.
Bunyi kipas angin berganti menjadi suara mikrofon di aula sekolah. Samar-samar, nama-nama dipanggil. Bayangan itu membuat pikiran Atha mengantarkan ke masa-masa menyakitkan.
Atha duduk di baris ketiga dari belakang. Seragam putihnya sudah kusut. Matanya terus melirik map-map biru yang dibagikan satu per satu, setiap nama disambut tepuk tangan kecil dan pelukan dari teman-teman.
“Zahra Ayu Pratiwi.”
Terdengar tepukan tangan. “Selamat ya!” suara gemuruh aula saling bersahutan. “Akhirnya selesai juga ya!”
“Zidan Rahadian.”
Lagi-lagi dan terus-menerus tepukan tangan, lambaian tangan, sampai tawa riang gembira memenuhi seisi aula.
Namun seolah seperti ada kesalahan, nama Athariel Pradana tidak disebut-sebut. Ia tetap tersenyum tipis, seperti tahu semua mata akan memerhatikan. Ia menyilangkan tangan, pura-pura sedang berpikir. Sesekali mengetuk-ngetuk lututnya agar terlihat tidak gugup. Tapi jantungnya terasa ingin keluar dari tulang rusuk.
Nama terakhir dipanggil. Map terakhir dibagikan.
Atha masih duduk.
Suasana aula mulai lengang. Satu per satu bangku dikosongkan. Teman-temannya berkumpul di depan, selfie bersama guru, memamerkan map biru di tangan. Atha berdiri perlahan, berjalan ke luar aula. Tidak ada yang menghampirinya. Tidak ada yang bertanya.
Di koridor, ada cermin kecil. Ia sempat menoleh, lalu tersenyum ke bayangannya sendiri.
“Gak apa-apa,” bisiknya.
Tapi senyum itu hanya bertahan beberapa detik. Setelahnya, ia berjalan lurus ke arah gerbang, tanpa suara, tanpa arah. Bersama dengan itu, Atha baru tersadar dari lamunan. Dia terhenyak beberapa detik setelah ponselnya mati yang bahkan sebenarnya dia tidak peduli dengan baterai di ponselnya.
Atha menoleh ke arah jam dinding, dia menatap setiap angka yang melingkar di sana. Jam menunjukkan pukul sepuluh malam, tetapi Atha belum makan. Bahkan air putih pun tidak.
Ibunya mengetuk pintu tadi sore. Bertanya pelan. “Tha... enggak keluar makan, Nak?” Tapi Atha hanya menjawab, “Nanti,” lalu diam lagi.
Ia belum keluar kamar sama sekali.
Semuanya terasa seperti racun yang mengendap. Tidak menggebu, tapi perlahan menumpuk dan meracuni setiap inci kesadarannya. Ia tidak marah. Ia hanya benci. Pada dirinya sendiri. Pada bayangannya di cermin. Pada semua keputusan yang ia buat. Pada semua kata yang tak ia ucapkan. Dan pada semua kata yang terlalu terlambat ia sadari.
Ia meringkuk di kasur, menggenggam bantal seperti pegangan terakhir dalam dunia yang semakin hilang bentuk. Tak ada tangis, tak ada teriakan. Hanya sunyi panjang, dan pikiran yang berputar tanpa arah seperti roda rusak.
Dan di tengah gelap itu, satu kalimat berulang di benaknya, seperti mantra yang tak bisa dihentikan. “Kenapa gue harus ada kalau semua lebih tenang tanpa gue?”
Atha pun manusia, jadi ada kalanya dia merasa lapar. Dia menyerah dengan aksi mogok makannya, sekitar jam delapan malam kurang akhirnya Atha keluar kamar. Di sana tampak ibu dan ayahnya masih menunggu dirinya keluar, di meja makan. Ya, mereka juga bahkan belum menyentuh hidangan yang kini sudah dingin.
Tidak ada kalimat yang signifikan, hanya tatap mata saja, Atha pun duduk. Sang Ibu menatapnya dalam, kemudian tersenyum, mencoba mendapatkan balasan dari anaknya, tetapi hal itu nihil.
Suara piring beradu pelan di meja makan. Lampu ruang tengah menyala kuning, menggantung pasrah di langit-langit seperti sisa kehangatan yang tidak tahu harus ditujukan ke siapa. Jam menunjukkan pukul delapan malam. Makan malam sudah disajikan sejak satu jam lalu, tapi baru sekarang Atha keluar kamar.
Ia duduk di ujung meja. Tangan kirinya menopang dagu, sementara tangan kanan menyendok nasi tanpa melihat. Ayahnya hanya sesekali melirik, tidak tahu harus memulai dari mana. Ibunya menatap Atha seperti hendak bicara, tapi ragu.
“Tha,” suara Ibu pelan, nyaris seperti bisikan, “kamu besok sekolah, ya?”
Atha tidak menjawab. Hanya anggukan kecil yang entah artinya iya atau sekadar ingin percakapan cepat selesai.
Suara jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya.
Ibunya menatap piringnya, lalu kembali memandang Atha. Kali ini lebih teguh. “Mama enggak ngerti kamu kenapa, tapi tolong, jangan kayak dulu lagi, ya.”
Kata-kata itu menggantung di udara. Lama. Seperti bau luka lama yang dibuka kembali tanpa niat menyembuhkan. Ya, setelah kejadian kelulusan kelas 12 lalu, Atha sempat stres berat, sampai dia sakit karena kekalutan dalam pikirannya sudah melebihi ambang batas. Bukan penyakit terbuka, tetapi lebih ke menyerang mentalnya. Sekitar tiga bulan Atha sempat dirawat jalan dengan psikiater karena gangguan tidur.
Atha ingin bicara. Ingin menjelaskan kalau dirinya hancur, kalau semuanya sakit, kalau rasanya seperti tenggelam di laut yang tidak berujung dan tidak ada pelampung.
Tapi yang keluar dari mulutnya hanya satu gumaman. “Aku capek.”
Ibunya berhenti mengunyah. Ayahnya mendongak pelan. Tapi Atha tidak menambahkan apa-apa. Ia hanya kembali menunduk, menyuapkan satu sendok nasi ke mulut lalu menatap meja kosong di hadapannya.
Tak ada yang bicara setelah itu.
Suasana makan malam yang seharusnya hangat berubah jadi ruang hampa tempat tiga orang duduk seperti asing yang dipaksa berpura-pura sebagai keluarga.
Atha tahu mereka khawatir. Tapi justru karena itu, ia merasa lebih bersalah. Karena ia tak sanggup menjelaskan. Karena ia tak tahu kenapa rasanya sesakit ini. Karena ia ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan, tapi dunia tak bekerja seperti itu.
Ia berdiri sebelum suapan terakhirnya selesai. Membawa piringnya ke wastafel, membilasnya asal, lalu kembali naik ke kamar. Langkah-langkahnya pelan, berat. Di belakang, terdengar suara kursi digeser dan piring yang belum selesai dimakan.
Dan ia tahu, malam ini pun ia akan tidur dengan rasa bersalah baru—karena gagal menjadi anak yang bisa dimengerti.
Malam turun seperti kabut tebal. Kamar Atha tenggelam dalam separuh gelap, separuh sunyi. Lampu gantung tidak ia nyalakan. Hanya cahaya dari layar ponsel yang menyala samar di meja belajar, tertancap pada kabel charger yang nyaris putus di bagian kepala.
Dengan langkah malas dan tubuh masih terasa berat, Atha meraih ponsel itu. Hanya iseng. Atau mungkin sekadar ingin memastikan dunia luar masih ada—meski ia tak merasa menjadi bagian dari dunia itu lagi.
Ia menyalakan layar. Tidak ada pesan masuk di WhatsApp. Tidak ada update di Instagram. Bahkan tidak ada notifikasi dari SMS. Tapi di ikon email, ada satu angka merah kecil.
Satu email. Tanpa nama pengirim.
Judulnya: “Maaf.”
Atha membuka. Dan membaca. Pelan-pelan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai Atha,
Gue enggak tahu harus mulai dari mana. Tapi kalau gue terus diem, kayaknya gue bakal meledak.
Gue yang nyebarin kabar itu. Tentang lu—tentang soal ujian bocor. Gue yang mulai semua fitnah itu.
Gue dapet akses soal ujian dari grup anonim, gak perlu gue sebutin. Jadi gue cari tumbal. Gue ngedit bukti. Screenshoot. Chat. Semua gue manipulasi. Gue pilih lu karena gue gak suka sama lu. Lu adalah orang di sekolah yang jauh beda sama gue. Yah, bisa dibilang gue iri sama lu.
Lalu gue kirim semua bukti itu ke akun sekolah lewat akun fake. Gue bikin seolah-olah lu yang nyebarin, lu yang buka jalur soal bocor.
Dan ternyata mereka percaya.
Gue pikir itu cukup. Tapi ternyata sekolah bener-bener ngelakuin investigasi. Lu ditarik, lu diinterogasi, dan lu enggak lulus.
Semua orang pikir itu kesalahan lu. Gue diem. Bahkan waktu semua mulai ngejauhin lu, gue seneng banget. Dulu.
Sekarang, gue nulis ini karena gue udah enggak kuat. Gue ngerasa jadi bangkai setiap hari. Gue bahkan udah enggak bisa ngaca.
Gue tahu surat ini enggak bakal cukup. Gue tahu gue egois. Tapi setidaknya lu harus tahu—
Lu enggak salah. Dan kayaknya lu tau kalau lu gak salah.
Gue yang salah.
Gue yang hancurin semuanya.
Maaf.
From: seseorang yang seharusnya berani ngaku dari lama
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atha duduk terpaku di ujung kasurnya. Layar ponsel menyorot wajahnya yang pucat dan kaku. Ia membaca ulang sampai lima kali.
Setiap kalimat seperti pecahan kaca yang ditancapkan ke dinding kepalanya. Ia tidak tahu siapa. Tidak tahu suara mana yang bicara. Tapi jelas—orang ini mengenalnya. Terlalu dekat. Terlalu tahu.
Tangannya gemetar, tapi bukan karena marah. Bukan juga karena sedih. Ia hanya kosong. Otaknya seperti mesin rusak yang terus dipaksa menyala. Hanya mengeluarkan suara berderak tanpa mampu menghasilkan sesuatu yang utuh.
Ia ingin tahu. Siapa? Kenapa? Tapi juga terlalu letih. Terlalu runtuh.
Di luar, hujan mulai turun lagi. Di dalam, hanya satu pertanyaan mengiang di kepalanya. Bukan kepada si pengirim. Tapi kepada semesta.
“Kalau semua ini salah orang lain… kenapa tetap gue yang rusak?”


 harrisradcliffe
harrisradcliffe









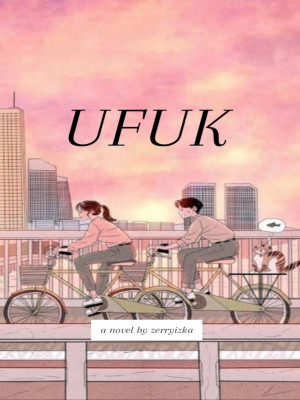
arrghhhhh. aku bacanya ikut frustrasiiiiiii
Comment on chapter BAB 3: TIDAK LAYAK BERTAHAN