Atha tidak langsung tidur setelah panggilan itu. Dia hanya duduk di atas kasur, bersandar pada dinding yang dingin, sementara lampu meja menyala redup di sisi lain ruangan.
Dia mencoba mengingat suara di ujung sambungan telepon tadi. Bukan suara, tepatnya. Hanya dengung pelan, napas samar, dan keheningan yang terasa terlalu sengaja. Seolah ada seseorang di sana, benar-benar mendengarkannya, tapi menolak bicara.
Beberapa kali remaja itu memutar ulang momen itu di kepala. Detik ketika dia bertanya, “Niko?” dan tidak ada jawaban. Detik ketika sambungan terputus. Detik ketika dia menatap layar ponsel yang kembali gelap, seperti lubang hitam yang menyerap semua kemungkinan.
Perlahan Atha berbaring, tubuhnya menyelip di antara lipatan selimut yang belum sempat dirapikan sejak pagi. Tapi otaknya masih terjaga. Jantungnya masih berdetak terlalu keras untuk disebut tenang.
Remaja itu menatap langit-langit. Satu bayangan kecil berputar karena kipas angin. Dia ingin percaya bahwa mungkin itu hanya mimpi. Mungkin ia tadi salah tekan. Mungkin itu bukan suara napas. Mungkin itu hanya getaran dari sinyal buruk.
Tapi kenyataannya terlalu nyata untuk diabaikan.
Atha memejamkan mata, tetapi tubuhnya tidak ikut lelap. Malam terus berjalan, tetapi baginya waktu terasa beku. Seakan dunia menahan napas, menunggu sesuatu pecah.
Beberapa jam kemudian, ia sempat tertidur. Tapi tidurnya tidak damai. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, dada sesak, dan tenggorokan kering. Dalam mimpinya, ia berada di lorong sekolah yang gelap, dan seseorang memanggil namanya dari balik pintu yang terkunci. Suaranya familiar, tapi samar. Ia tidak sempat melihat wajah siapa pun. Hanya siluet, dan suara itu.
Ia menyalakan ponsel. Tidak ada notifikasi baru.
Jam menunjukkan pukul 03.41.
Ia menghela napas panjang. Entah kenapa, angka itu terasa seperti batas. Seolah malam sudah terlalu larut untuk berharap akan ada sesuatu yang baik terjadi.
Atha duduk kembali. Menarik lutut ke dada, menyembunyikan kepala di antara lipatan lengan. Sampai akhirnya pagi datang tanpa jeda.
Atha tidak benar-benar tidur semalam. Hanya sempat menutup mata, tapi tak pernah benar-benar jatuh ke dalam lelap. Ketika alarmnya berbunyi pukul enam pagi, tubuhnya masih menggigil seperti baru ditarik paksa dari laut malam yang dingin.
Remaja itu duduk di sisi tempat tidur, menggenggam ponsel yang kini terasa lebih berat dari biasanya. Tatapannya buram, kepala ringan, dan pikirannya melayang entah ke mana.
Dia bahkan tidak yakin kapan terakhir kali merasa sepenuhnya utuh.
Air mandinya pagi ini terasa seperti tamparan. Dingin yang menghantam wajahnya bukan menyegarkan, tapi hanya mengingatkan bahwa hari akan berjalan dan dia harus tetap ikut di dalamnya.
Sarapan tidak sempat disentuh. Ibunya hanya sempat menanyakan, “Kamu kurang tidur?” dan dia menjawab dengan gumaman pendek. Tidak ingin menjelaskan. Tidak ingin dimengerti. Hanya ingin sampai di sekolah dan mungkin—mungkin saja—bisa mengalihkan pikirannya.
Tapi sekolah bukan tempat untuk lari.
Di gerbang, beberapa siswa menatapnya seperti biasa—asing. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang memanggil. Dan Atha tidak butuh sapaan itu, tapi tetap saja keheningan sosial semacam itu menusuk pelan dari sisi yang tak terlihat.
Langkahnya menuju ruang kelas 13 seperti menginjak lantai es yang licin. Kepalanya berat. Matanya terasa seperti berisi pasir. Tapi dia tetap berjalan.
Sesampainya di kelas, Dero sudah duduk di bangkunya. Dengan jaket hoodie hitam ditarik sampai kepala, remaja itu hanya melirik singkat sebelum kembali sibuk dengan ponsel.
Tidak ada sapaan.
Atha meletakkan tas di bangkunya, duduk perlahan. Punggungnya bersandar pada sandaran kursi seperti biasa. Posisi itu memberinya sedikit kenyamanan, seolah sandaran itu bisa menopang beban yang tidak bisa ia ceritakan.
Beberapa siswa lain mulai masuk. Ada yang langsung sibuk dengan musik. Ada yang tertawa pelan sambil memperlihatkan video lucu dengan suara dimatikan. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan satu sama lain.
Kelas 13 memang bukan tempat untuk keterhubungan. Ini adalah ruang isolasi yang disamarkan sebagai pendidikan.
Atha menatap langit-langit. Pandangannya kabur. Kelopak matanya berat sekali. Ia sempat memejamkan mata sebentar—tidak sampai satu menit—lalu buru-buru membuka lagi ketika merasa hampir terlelap.
Dari sisi lain kelas, Dero melirik. Sekilas. Hanya satu detik. Tapi cukup untuk tahu bahwa anak di depan itu tidak dalam kondisi baik. Namun, seperti biasa, dia tidak mengatakan apa-apa.
Beberapa jam pelajaran berlalu seperti bayangan. Suara guru seperti gumaman dari dunia lain. Setiap kali ada yang menyebut namanya, Atha terkejut seolah ditarik dari dasar air. Tapi tidak ada yang menyebut. Tidak ada yang peduli dia mendengar atau tidak.
Saat istirahat, dia keluar kelas. Mencoba berjalan ke koridor untuk mencari udara. Tapi malah merasa makin pening. Cahaya pagi terlalu terang. Dunia terasa goyah.
Dia bersandar ke tiang beton. Menggosok-gosok wajah dengan tangan. Nafasnya berat. Tubuhnya kelelahan, tapi pikirannya tidak berhenti memutar-mutar pertanyaan yang belum punya jawaban.
Tiba-tiba langkah seseorang mendekat. Dero. Dengan ekspresi datar, tapi suara sedikit lebih pelan dari biasanya. “Lu kenapa? Mukanya kayak habis digilas truk.”
Atha tidak langsung menjawab. Hanya menatap balik, lalu angkat bahu. “Enggak tidur.”
Dero bersedekap. Tatapannya tidak sepenuhnya sinis, tapi juga bukan simpati. Lebih seperti seseorang yang ingin peduli, tapi tidak tahu bagaimana caranya agar tidak terlihat lemah.
“Masih mikirin yang semalam?”
Atha mengangguk. Pelan. Matanya merah, tapi bukan karena menangis. Hanya sisa dari malam yang tidak beristirahat.
Remaja di depannya mendengus. “Lu gak akan dapet jawaban kalau cuma bengong begitu.”
“Terus gue harus gimana?”
Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Tapi ada sesuatu dalam diam itu—sebuah kejujuran yang tidak bisa diucapkan. Bahwa mereka sama-sama tidak tahu harus berbuat apa.
Bel masuk berbunyi. Dero berjalan lebih dulu, kembali ke kelas. Tapi sebelum benar-benar masuk, dia sempat menoleh, “Kalau lu pingsan di luar, gue gak mau tanggung jawab.”
Atha hanya tersenyum kecil. Tidak lucu, tapi lebih baik dari apa pun.
Dia kembali ke kelas dengan langkah goyah, duduk, dan sekali lagi mencoba bertahan. Hari ini terlalu panjang. Dan dunia, seperti biasa, tidak menunggu siapa pun untuk pulih.
Waktu sudah menjelang tengah hari ketika suara gaduh kembali mengisi ruang kelas 13. Seperti biasa, suasana kelas itu tidak benar-benar riuh, tetapi juga jauh dari tenang. Kebisingan yang ada bukan berasal dari semangat belajar, melainkan dari suara ponsel yang tidak pernah hening, obrolan tidak penting, dan tawa yang lebih sering terdengar kosong.
Atha duduk di meja paling depan, dekat dengan papan tulis yang jarang disentuh spidol. Kepalanya disandarkan ke lengan, mata memandang kosong ke arah meja guru yang masih terdapat buku agenda di atasnya. Sedangkan, di belakang, beberapa suara mulai terdengar lebih jelas—bukan karena Atha memperhatikan, tapi karena tubuh dan pikirannya sudah terlalu lelah untuk menutup telinga.
“Eh, lu inget Niko enggak, yang dulu suka main ke studio musik belakang sekolah waktu kelas dua belas?” suara itu milik seseorang yang duduk di bangku tengah—suara yang nyaring tapi tidak familiar bagi Atha. Mungkin dari siswa yang akhirnya ‘naik pangkat’ ke kelas 13.
“Yang rambutnya french crop acak-acakan itu? Iya, gue kira dia udah pindah sekolah, lama gak masuk soalnya,” jawab yang lain, terdengar santai.
“Bukan pindah,” tiba-tiba Rizal menyahut dari jajaran bangku belakang, mengangkat ponsel dan tertawa kecil. “Katanya sih... sakit jiwa.”
Atha mengangkat kepalanya perlahan. Telinganya menangkap nama yang terlalu ia kenal.
Rizal, duduk menyandar malas di kursinya, dengan kaki naik ke besi bawah meja, mulai melontarkan cerita dengan nada setengah main-main. “Gue denger dari temen gue yang masih sering nongkrong di kantin bawah tuh, katanya waktu kelas dua belas akhir, si Niko udah mulai aneh. Sering ngomong sendiri, trus katanya pernah nangis di kamar mandi sekolah.”
“Serius?” sahut salah satu siswa lain.
“Ya mana gue tahu bener apa kagak, tapi waktu itu sempet rame di grup angkatan, kan. Gue inget banget, soalnya fotonya dia juga pernah bocor—yang dia duduk diem di depan ruang UKS, mata kosong. Kayak... kayak orang abis ngelihat setan.” Rizal tergelak, seolah cerita itu hiburan baginya.
“Lu percaya semua omongan dari grup itu?” celetuk Dero dari belakang. Suaranya rendah, tapi cukup membuat beberapa kepala menoleh.
Rizal mengangkat alis, “Yah, daripada lu cuma duduk diem, mending denger gosip dikit, kan? Daripada mati gaya.”
Dero tidak menjawab. Hanya kembali menunduk ke layar ponsel, meskipun sesekali matanya melirik ke arah Atha.
Atha sendiri membeku. Tidak sepenuhnya karena cerita itu, tapi karena serpihan memori mulai menyatu perlahan. Dia teringat Niko yang sempat membahas soal malam-malam panjang, tentang tidak bisa tidur, tentang ‘suara-suara aneh’ yang kadang membuatnya takut sendiri. Hal ini semua Atha dengar dari lagu-lagu ciptaan Niko, bahkan semuanya tergambar jelas di lagu demo yang Niko kirimkan terakhir kali.
Kini semuanya terasa seperti sandi yang baru terpecahkan.
“Gue juga denger kabar... dia sekarang udah enggak keluar rumah,” lanjut Rizal, suaranya lebih pelan, seperti ingin mempertegas dramanya. “Katanya dikunciin, bro. Sama ortunya. Enggak boleh keluar kamar. Lu bayangin aja, anak segila itu dikurung di kamarnya sendiri. Gila kan?”
Beberapa siswa tertawa kecil. Ada yang terlihat tidak nyaman, tapi tidak ada yang benar-benar membantah.
“Lu denger dari mana semua itu?” tanya Atha, pelan namun cukup jelas, hingga kepala-kepala mulai menoleh ke depan.
Rizal seperti tidak menyangka Atha akan bersuara. Ia melirik sebentar, lalu mengangkat bahu.
“Dari temen gue yang pernah satu band sama dia. Dulu kan Niko anak seni tuh. Tapi katanya, sejak ujian nasional gagal, dia jadi kayak orang ilang arah. Katanya mulai sering ngurung diri. Nggak makan, nggak mandi, diem doang. Gue yakin sih, mentalnya kena.”
“Lu yakin itu bukan cuma gosip?” Atha bertanya lagi. Kali ini nadanya terdengar datar, tapi lebih tegas.
Rizal menghela napas panjang, lalu menyandarkan kepala ke dinding, tampak malas menanggapi lebih jauh. “Terserah lu, lah. Gue cuma nyampein apa yang gue denger. Kalo lu deket banget sama dia, ya tinggal tanya langsung. Gue kira lu duduk sebelahan gitu karena kalian udah kenal lama dan sahabatan.”
Atha terdiam. Jantungnya berdetak tak teratur. Tangan yang tadi memegang ujung meja kini terkepal diam-diam.
Sementara itu, dari baris belakang, Dero mencuri pandang. Ada kegelisahan samar di wajahnya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih menahan. Mungkin karena gengsi. Mungkin karena belum saatnya.
Bel masuk berbunyi. Guru yang mengajar selanjutnya masuk tanpa senyum. Satu per satu siswa mengambil posisi duduk semula. Namun suasana kelas terasa berbeda. Ada semacam ketegangan yang menggantung tipis, entah dari cerita barusan, atau dari tatapan Atha yang kini kosong menembus papan tulis.
Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, Atha tidak merasa mengantuk. Dadanya sesak oleh sesuatu yang lain—oleh pertanyaan yang kini terdengar lebih menakutkan daripada malam tanpa tidur:
Bagaimana jika semua itu benar? Dan jika benar... kenapa Niko tidak pernah bilang apa-apa?
Langit sore tampak keruh. Awan menebal pelan, menutupi warna oranye yang biasanya menyembul malu-malu dari sela gedung sekolah. Atha berjalan cepat menuju parkiran, melewati koridor dengan langkah lebar dan kepala tertunduk. Tas ranselnya membentur pinggang bagian belakang setiap kali dia mempercepat langkah. Matanya terlihat letih, tapi ada ketegangan lain yang kini menyetir tubuhnya: niat untuk segera pergi ke rumah seseorang yang selama ini hanya dia ingat sebagai tawa, suara, dan kabut.
Ketika hampir sampai ke motornya, suara berat yang akrab terdengar dari belakang.
“Mau ke mana?”
Atha menoleh. Dero berdiri di sana, menyilangkan tangan di depan dada, masih mengenakan jaket hitam tipis yang menempel longgar di tubuh tinggi kurusnya.
“Enggak urusan,” jawab Atha singkat. Tangannya sudah meraih kunci motor.
“Rumah Niko?” tebak Dero tanpa basa-basi.
Atha diam sejenak, lalu menghela napas. “Gue harus tahu, Der.”
Dero melangkah lebih dekat. Tatapannya tetap dingin, tapi tak menyembunyikan keresahan. “Gue ikut.”
“Ngapain? Ini bukan urusan lu.”
“Gue ketua kelas. Gue juga punya hak tahu,” jawab Dero ringan, meskipun sorot matanya mengeras. “Lagian, lu tuh... enggak tidur, enggak makan, sekarang mau ngebut ke mana lagi sendirian? Gue yang nyetir.”
Atha terdiam, masih menggenggam helm di tangan. Dero mengulurkan tangan, meminta kunci.
“Serius, Atha. Gue bawa aja. Lu tinggal duduk.”
Setelah jeda yang panjang, Atha akhirnya menyerahkan kunci motor. Dero mengambilnya, lalu naik ke motor dengan gerakan yang mantap. Atha naik di belakang, membetulkan posisi duduk, dan tanpa banyak kata, motor itu melaju meninggalkan halaman sekolah.
Perjalanan menuju rumah Niko tidak panjang, tapi cukup untuk membuat udara sore menyusup lewat sela jaket dan celana seragam yang sudah mulai kusut. Atha memeluk tasnya erat-erat di depan dada. Matanya tak lepas dari jalan, tapi pikirannya lebih sibuk membayangkan kemungkinan buruk—dan yang lebih buruk dari itu.
Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah yang beberapa minggu terakhir cukup sering Atha kunjungi. Dero pertama kali datang, dia tahu karena arahan dari Atha. Ada mobil hitam terparkir di garasi yang terbuka setengah. Atha menatapnya sejenak, seperti mencari tanda-tanda kehidupan.
Dia turun dari motor dan bergegas melangkah ke pintu pagar kecil, menekan bel beberapa kali. Suaranya nyaring, menyayat udara yang mulai dingin.
Tidak langsung ada jawaban.
Sekitar satu menit kemudian, pintu rumah terbuka dari dalam. Seorang wanita keluar, berdiri tegak di ambang pintu. Rambutnya hitam pekat, tersisir rapi ke belakang dalam sanggul bersih. Wajahnya tajam—dagu tegas, alis tinggi, dan mata yang tidak tersenyum. Dia mengenakan blus sutra putih dengan setelan rok panjang abu, sepatunya hak tinggi, dan langkahnya mantap.
Atha baru sadar. Wajah itu familiar.
Itu... ibu Niko. Penyanyi lawas yang dulu sering muncul di televisi nasional, dikenal karena suaranya yang kuat dan sikapnya yang tak pernah goyah. Sosok yang dulu dikagumi karena ketegasan dan profesionalismenya. Sekarang, dia berdiri di hadapan Atha dan Dero dengan sorot mata yang sama—tajam, menjaga, tidak terbuka.
“Ada perlu apa?” tanyanya singkat.
Atha menelan ludah, mencoba bicara. “Kami... kami teman sekolah Niko, Bu. Kami cuma... mau tahu kabarnya.”
Wanita itu menatap mereka bergantian, seperti sedang menilai apakah perlu menekan tombol keamanan atau tidak. “Niko sedang tidak bisa diganggu. Dia tidak menerima tamu.”
“Sebentar saja,” sahut Atha, nyaris memohon. “Kami enggak akan lama. Kami cuma... pengin lihat dia. Beneran.”
Tatapan wanita itu tak berubah. Tapi sebelum dia sempat menjawab, Dero melangkah maju setengah langkah.
“Bu,” katanya, suaranya lebih dalam dari biasanya, sedikit lebih sopan dari nadanya sehari-hari. “Kami tahu ini mendadak. Tapi teman kami ini... dulu bantu banyak orang, termasuk kami. Sekarang dia lagi sulit. Kami bukan mau ganggu, kami cuma pengin pastiin dia enggak sendirian.”
Bantu? Bantu apa? Atha justru bertanya-tanya dalam hati, tetapi dia tidak protes.
Ada jeda. Sunyi. Angin sore lewat, membawa bau bunga dari taman kecil di depan pagar.
Wanita itu mengerjapkan mata sekali. Perlahan, bahunya yang tadinya tegang mulai mengendur. Dia menarik napas, lalu mengangguk kecil.
“Baiklah. Tapi tidak lebih dari sepuluh menit.”
Pintu pagar terbuka perlahan. Suaranya menggesek pelan.
Atha dan Dero saling pandang sebentar, lalu masuk beriringan, melangkah melewati lantai marmer yang mengilap menuju pintu rumah yang kini terbuka lebar—seolah menanti.
Dan di ambang itu, rasa cemas yang sejak tadi hanya menggantung mulai menebal.


 harrisradcliffe
harrisradcliffe








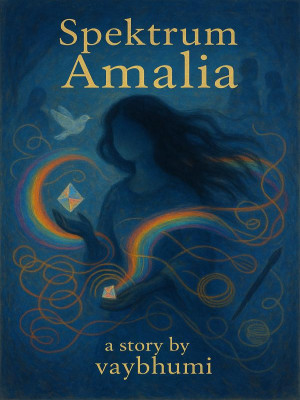

arrghhhhh. aku bacanya ikut frustrasiiiiiii
Comment on chapter BAB 3: TIDAK LAYAK BERTAHAN