Bodoh, kemana, sih, ini orang?
Atha menatap layar ponselnya yang gelap, memantulkan samar bayangan wajahnya sendiri—kusut, pucat, dengan mata yang sedikit cekung karena tidur yang selalu terlambat akhir-akhir ini. Suara kipas kecil yang menempel di dinding kamarnya mendesis pelan, menyapu udara hangat yang terasa berat sejak siang.
Dia duduk bersila di lantai, bersandar pada tembok dengan satu tangan memegang ponsel dan tangan lain menahan kepala yang perlahan terasa berat. Hari Sabtu sore seharusnya memberi ruang istirahat, tapi yang terasa sekarang hanyalah ruang kosong. Sunyi. Seperti layar obrolan yang tak berubah sejak dua minggu lalu.
Obrolan dengan Niko masih ada di urutan atas aplikasi pesan, seolah-olah percakapan itu penting, atau setidaknya menunggu dilanjutkan. Tapi kenyataannya, sudah nyaris sebulan sejak Niko tak lagi muncul di sekolah. Kursinya persis di samping kursi Atha tetap kosong setiap pagi dirinya masuk kelas.
Sudah beberapa kali Atha membuka layar ini—dan setiap kali pula, harapan kecil muncul. Harapan bahwa akan ada satu pesan singkat muncul, seperti dulu. “Gak bisa masuk.” Atau, “Masih di rumah, acara belum beres, nih, santai aja.” Tapi sekarang, tidak ada. Tidak bahkan sekadar balasan titik tiga yang muncul. Hanya satu centang abu-abu.
Awalnya, Atha tak merasa cemas. Niko sempat membalas beberapa pesan. Masih ada tanggapan, meski singkat. Tapi seiring hari berganti, jeda-jeda yang muncul di antara pesan mereka semakin lebar. Dari jam menjadi hari. Dari hari menjadi minggu. Dari dua centang menjadi satu. Kini, tidak ada tanda kehadiran sama sekali. Atha menekan layar, menahan jemarinya pada ikon profil Niko, lalu melepaskannya sebelum benar-benar membuka. Dia bahkan tak yakin Niko masih menyimpan nomornya. Atau masih punya ponsel yang menyala.
Kepalanya bersandar ke dinding. Mata Atha memejam sejenak. Dalam benaknya muncul potongan ingatan yang belum lama terjadi—waktu dia duduk di kamar di rumah Niko, saat mereka tertawa mendengar suara aneh dari keyboard milik Niko yang sangat dicintainya. Lagu buatan Niko waktu itu masih ada di ponselnya. Masih diputar hampir setiap malam. Tapi sekarang, lagu itu mulai kehilangan makna. Karena tak ada lagi tawa yang menyertainya. Tak ada lagi komentar spontan Niko yang biasanya selalu menyela setelah satu bagian selesai dimainkan: “Ini masih jelek, jangan disimpen.”
Atha membuka galeri dan memutar satu video pendek yang diam-diam dia rekam hari itu. Dalam video itu, Niko tampak menunduk sedikit, fokus memainkan tuts-tuts keyboard. Di akhir video, Niko melirik kamera dan tertawa, lalu bilang, “Hapus aja deh, ini gak proper.” Tapi Atha tidak menghapusnya. Justru dia ulang beberapa kali. Sebagai pengingat bahwa Niko pernah ada. Pernah bicara. Pernah nyengir. Dan sekarang, semua itu terasa seperti fiksi.
Sekolah pun tidak membantu. Hari-hari Atha di Kelas 13 kembali berjalan seperti semula: sepi, asing, penuh orang-orang yang seolah bernafas di dalam ruang mereka sendiri. Bahkan saat pemilihan Ketua Murid yang ribut besar antara Rizal dan Dero terjadi, Atha tak benar-benar terlibat. Dia ingat suasana ruangan kala itu—teriakan, bantahan, Pak Narya yang bersikukuh menunjuk Dero tanpa pemungutan suara. Tapi Atha hanya duduk diam. Memandang kosong ke depan. Semua suara itu seperti berasal dari luar dinding. Seolah dia berada di dalam akuarium, menyaksikan dunia tanpa bisa menjangkaunya.
Kini, suara paling keras justru suara di dalam kepalanya. Suara yang terus-menerus bertanya: Kemana Niko pergi? Kenapa tidak bilang apa-apa? Apa dia baik-baik saja? Atau jangan-jangan… Tapi kalimat itu tak pernah selesai. Atha takut menyelesaikannya.
Ponselnya kembali mati layar. Dan sekali lagi, Atha menatap kosong, membiarkan waktu bergulir tanpa kejelasan. Kipas di atas terus berputar, menyapu angin ke arah yang sama berulang-ulang. Tidak ada perubahan. Tidak ada jawaban. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satu pun penjelasan.
Kayaknya gue harus ke rumah Niko lagi, deh. Siapa tau sekarang udah ada orangnya.
Sore itu, Atha meluncur pelan di atas motornya, menyusuri jalanan kompleks perumahan yang tertata rapi dan sepi. Bayangan pepohonan dari sisi kiri jalan bergoyang malas diterpa angin. Udara sore terasa lembab di balik helm yang belum dia buka, meskipun telah mematikan mesin motornya sejak beberapa menit lalu. Ban motornya berhenti persis di depan rumah yang sudah tidak asing—pintu pagar tinggi berwarna hitam, dinding cat abu, dan taman kecil yang tetap rapi meski terlihat tak tersentuh.
Atha turun dari motor. Helm masih dia biarkan menempel di kepala, seolah malas untuk terlalu betah. Langkahnya berat menuju pagar. Sepasang matanya langsung menelusuri ke dalam lewat celah, dan seperti yang sudah dia duga—tak ada perubahan. Tidak ada lampu menyala. Tidak ada suara. Bahkan tirai jendela pun tetap tertutup seperti minggu-minggu sebelumnya.
Dia mengangkat tangannya, menekan bel satu kali. Suara ‘ting-tong’ yang bersih terdengar dari dalam rumah, lalu hening lagi. Tidak ada derap kaki. Tidak ada sahutan. Remaja menunggu sekitar dua puluh detik, lalu mengetuk-ngetuk pagar besi perlahan.
“Pak… Bu… Niko?” panggilnya, suara agak tertahan, seperti orang yang sudah berkali-kali memanggil di tempat yang sama. Lagi-lagi tak ada respons.
Atha menghela napas, tangannya merogoh ponsel dari saku celana. Dia membuka WhatsApp, menekan tombol panggil pada kontak Niko, menunggunya beberapa saat, kemudian mematikannya lagi. Begitu terus berulang sampai beberapa kali, sebelum akhirnya menyimpan ponsel itu lagi. Pandangannya kembali ke rumah. Dari pagar, lelaki dengan tinggi 170 sentimeter itu berjinjit, mencoba memastikan lewat celah-celah jendela—tidak tampak bayangan siapa pun.
Untuk sesaat, Atha sempat berpikir—bagaimana kalau dia panjat saja pagarnya? Tapi segera pikiran itu ditepis. Ini perumahan elite. Pasti banyak CCTV. Dan meskipun dia niatnya cuma khawatir, dia tahu tidak semua orang bisa memahami niat itu.
Dia mengedarkan pandangan ke sekitar. Sebuah rumah di seberang jalan tampak terbuka, seorang ibu paruh baya sedang menyapu teras. Atha mendekat, melepas helm, dan sedikit membungkuk sopan.
“Permisi, Bu. Maaf ganggu… Saya mau nanya soal rumah itu. Penghuninya lagi pergi, ya?” tanyanya pelan.
Ibu itu menoleh, lalu mengerutkan dahi. “Oh, rumah Niko ya? Harusnya ada orangnya. Dari luar sih gak kelihatan kosong.”
“Bu, saya udah beberapa kali ke sini. Tapi gak ada yang jawab. Bel juga gak pernah dibukain…”
“Hmm… saya juga gak tahu ya, Mas. Soalnya mereka jarang keluar. Bapaknya itu kan jarang kelihatan, ibunya juga gitu. Kita-kita di sini paling cuma senyum-senyum kalau papasan. Gak pernah ngobrol panjang.”
Atha mengangguk pelan. Terima kasih, katanya, lalu kembali ke motornya.
Sebelum naik, dia sempat menatap rumah itu sekali lagi. Kali ini lebih lama. Ada rasa sepi yang aneh. Bukan sepi karena sunyi, tapi sepi yang seperti menyembunyikan sesuatu. Rumah itu tidak terlihat ditinggalkan, tapi juga tidak terasa ditinggali.
Dan yang paling mengganggu: seolah-olah keberadaannya sengaja dihapus dari kehidupan orang lain—termasuk dari dirinya.
Selain kekacauan dalam hatinya terkait cemas, gelisah, khawatir, keingintauan, sebenarnya rasa kesal pun ada memenuhi dadanya sampai sesak. Atha merasa lama-lama muak juga pada Niko, menghilang tanpa kabar, bahkan mereka baru berteman, maksudnya apa?
Atha pun melajukan motornya.
Tidak lama, motor matic itu berhenti di depan minimarket dengan plang merah-putih yang mulai pudar. Atha memarkirnya pelan, menekan standar tengah, dan melepas helm yang masih menghangatkan rambutnya. Udara senja tak banyak membantu mendinginkan pikirannya yang sejak siang terus berputar-putar. Hanya ada satu alasan dia berhenti di tempat ini: membiarkan dirinya diam, meskipun hanya lima menit.
Pintu kaca terbuka dengan bunyi lonceng kecil. AC menyambut wajahnya dengan hembusan dingin buatan. Atha melangkah masuk, mengambil keranjang, dan mulai berjalan tanpa arah pasti di antara rak-rak minuman ringan, camilan, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang tidak ia perlukan.
Tapi langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok tak terduga di balik meja kasir.
Dero.
Seragam merah cerah dengan apron hitam tergantung rapi di tubuh kurus itu. Rambutnya yang cepak tampak lebih terlihat kulit kepalanya di bawah pencahayaan lampu toko. Dero menunduk, mengatur tumpukan nota sambil sesekali mengusap kening. Wajahnya serius, sedikit letih. Bukan wajah yang biasa Atha lihat di kelas—bukan ekspresi penuh tatapan meremehkan atau komentar sinis.
Atha hampir menjatuhkan botol air mineral yang baru saja dia pegang.
“…Dero?” bisiknya nyaris tak terdengar. Bukan karena takut, tapi karena otaknya butuh waktu lebih untuk mencerna kenyataan di depannya.
Dia memutar keranjang di tangannya, ragu. Tapi cepat-cepat menguasai diri dan berpura-pura seperti biasa. Dipilihnya beberapa barang yang sebenarnya tak dia butuhkan—roti tawar, susu kotak, sabun cair—lalu berjalan menuju kasir dengan napas setengah ditahan.
Dero baru menyadari keberadaannya ketika Atha sudah menaruh barang-barang itu di meja kasir.
Tatapan mereka bertemu.
Sebentar.
Kemudian Dero langsung menunduk lagi.
Atha mencoba tersenyum kecil. “Kerja di sini ya?”
Tak ada jawaban.
Atha menelan ludah. “Dari kapan?”
Dero men-scan barang-barang itu satu per satu. Pipinya sedikit memerah. Mungkin karena lelah. Mungkin karena malu. Atau mungkin karena dia sedang menahan sesuatu.
Atha menunggu, berharap Dero akan membalas, bahkan satu patah kata pun akan cukup. Tapi yang terdengar hanya bunyi beep dari mesin pemindai, lalu suara pelan dari Dero, “Dua puluh delapan ribu lima ratus.”
Atha menyerahkan uang tanpa berkata apa-apa lagi. Dia menyerah—untuk saat itu. Namun, ketika dia berbalik, suara keras meledak di dalam ruangan kecil itu.
“Dero! Berapa kali gue bilang, jangan tinggalin kasir kalau belum izin! Tadi siapa yang naro barang keliru di rak minuman?! Kerja gitu aja gak bener, sama gak gunanya kamu kayak keluargamu!”
Atha membeku. Dia menoleh pelan.
Seorang pria paruh baya berseragam sama mendekati Dero dengan wajah penuh amarah. Suaranya memecah keheningan toko yang sepi. Dan Dero—yang biasanya begitu tajam dan percaya diri—kini berdiri tegak tanpa membela diri sedikit pun. Kepalanya menunduk. Tangannya mengepal di sisi apron.
Atha berdiri beberapa meter dari sana. Ingin berpaling tapi tidak bisa. Ingin maju tapi tak berhak. Hanya bisa menyaksikan—satu bagian kecil dari seseorang yang selama ini dia pikir sudah dia pahami, tapi nyatanya tidak.
Si atasan pergi sambil mendengus, meninggalkan Dero di balik meja kasir dengan wajah kaku dan lelah. Tak ada satu pun pengunjung lain di toko itu, hanya mereka berdua dan jarak yang tiba-tiba terasa lebih panjang daripada sebelumnya.
Atha melangkah ke luar tanpa banyak suara. Kantong belanja tergenggam di tangan. Tapi pikirannya tertinggal di meja kasir itu—di tempat di mana seorang remaja paling keras kepala di kelas 13 berdiri diam tanpa bisa membalas sepatah kata pun.
Langit sudah lebih gelap, dan lampu minimarket mulai tampak lebih terang dibandingkan tadi. Atha berdiri di depan motor untuk beberapa saat, menatap kursi panjang kecil di sisi kanan pintu. Biasanya dipakai orang menunggu ojek online atau ngerokok sebentar. Tapi sekarang kosong.
Dia berjalan ke sana dan duduk.
Tangannya menggenggam botol air mineral yang dinginnya mulai menghilang. Atha membuka ponsel, layarnya masih di ruangan chat dengan Niko. Lalu dia menatap jam.
“Masih jam tujuh malam.” Remaja itu bergumam pelan.
Kalau benar Dero kerja shift dua seperti dugaan Atha—karena dia tidak masuk sekolah dan kasir ini biasanya jaga sore sampai malam—maka Dero baru selesai sekitar jam sepuluh.
“Tiga jam.”
Atha menarik napas. Tidak ada alasan kuat untuk menunggu. Tidak ada janji atau kepastian akan bicara. Tapi dia duduk di sana. Dan dia akan tetap duduk di sana. Sampai waktu itu datang. Dan, mungkin ini saatnya untuk bisa memulai pendekatan pertemanan dengan Dero.
Angin malam berembus pelan di depan minimarket yang semakin sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di aspal yang lembap. Dari tempat duduknya, Atha menatap jam ponsel yang nyaris tak berubah sedari tadi. Waktu terasa seperti melambat ketika tidak ada yang bisa dikejar—selain penjelasan, dan seseorang yang tak kunjung keluar.
Beberapa kendaraan lewat, beberapa orang mampir dan pergi. Tapi tak satu pun dari mereka yang diperhatikan Atha. Dia hanya sesekali menggoyang kaki, meremas botol air yang sudah kosong, dan memikirkan apa yang akan ia katakan nanti. Kalau Dero benar-benar keluar. Kalau Dero tidak mengabaikannya lagi. Kalau...
Bunyi pintu kaca akhirnya terdengar.
Dan Atha langsung menegakkan punggungnya.
Dero keluar sambil melepas apron dan merapikan seragam. Raut wajahnya tampak kelelahan, tapi tidak ada emosi jelas yang bisa dibaca. Dia menunduk, menaruh apron di tas selempang hitam, baru kemudian mengangkat wajah—dan berhenti.
Tatapan mereka bertemu dalam sorotan lampu toko.
Atha bangkit berdiri.
Dero mengernyit pelan. “...Loh?” suaranya rendah, terdengar lebih defensif ketimbang bingung. “Masih di sini?” tanyanya lagi, nadanya terdengar seperti ingin menuduh tapi ditahan.
Atha mengangkat satu bahu, mencoba netral. “Iya. Nunggu lu.”
Dero memicingkan mata. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin melontarkan sarkasme. Tapi dia urung. Yang keluar hanya embusan napas.
“Ngapain?” tanya Dero akhirnya.
Atha kembali duduk di kursi panjang, lalu menepuk tempat kosong di sebelahnya. “Cuma mau ngobrol.”
Dero tidak langsung mendekat. Dia berdiri beberapa langkah dari situ, ragu-ragu.
“Ngobrol apaan? Lu mau ngejek, ya?” katanya tajam, “Mau cerita ke anak-anak kalo Dero kerja di minimarket? Gitu?”
Atha menggeleng, pelan tapi mantap. “Bukan.”
Dero tertawa pendek, sinis. Tapi tertahannya lebih panjang dari suara itu sendiri. “Pasti aneh, ya. Ketua kelas tapi nyari duit di kasir. Harusnya kan anak pinter ngeles privat, bukan ngerapiin rak sabun. Lucu, ya?”
Atha tidak menjawab. Dia hanya menatap Dero—diam, tenang, tidak ikut menertawakan, tapi juga tidak menyangkal keras-keras. Tatapan itu yang membuat Dero sedikit kehilangan keseimbangan emosinya.
“Gue enggak ngetawain, Der,” kata Atha akhirnya, pelan. “Gue nunggu karena... pengin ngobrol baik-baik. Itu aja.”
Dero mengernyit lagi, kali ini lebih bingung ketimbang curiga. Dia masih tidak duduk, tapi langkahnya mulai mendekat sedikit.
Atha menatap ke arah jalan kosong. “Selama ini kita enggak pernah benar-benar ngobrol. Kamu kayak benci gue, gue juga enggak ngerti kenapa. Tapi tadi pas liat lu dimarahin di dalam... gue gak tahu, rasanya kayak—gue enggak bisa pura-pura enggak peduli.”
“Ya terus?” potong Dero, suaranya pelan tapi tidak tajam. “Lu pengen kasihanin gue sekarang? Urus hidup lu sendiri, deh.”
Atha menggeleng lagi, kali ini lebih cepat. “Enggak. Gue cuma pengen tahu... siapa lu sebenarnya. Bukan yang keliatan di kelas. Tapi yang ada di balik itu.”
Dero terdiam.
Sebuah jeda menggantung di antara mereka, sementara malam terus bergulir. Suara kendaraan semakin jarang, dan lampu toko mulai sedikit meredup—pertanda jam operasional akan segera habis.
Atha kembali bersandar. “Gue juga enggak datang ke sini buat kepo. Gue cuma... mau tahu lu sebagai ketua kelas. Dan—”
Dia ragu sebentar.
“Dan siapa tahu... lu tahu sesuatu tentang Niko.”
Dero mengangkat wajahnya, untuk pertama kali tampak agak tertarik.
“Niko?” ulangnya pelan.
Atha menoleh, menatap mata Dero. “Iya. Kan udah sebulan dia enggak masuk. Gue udah bolak-balik ke rumahnya, tapi enggak ada siapa-siapa. Chat juga enggak dibales. Lu tahu dia ke mana?”
Dero tidak langsung menjawab. Tapi sorot matanya berubah—tidak lagi menyalahkan, tidak lagi menyerang. Ada sesuatu yang bergerak di balik matanya. Mungkin informasi. Mungkin keraguan.
“Mungkin,” kata remaja kusut tersebut akhirnya. “Gue enggak janji.”
Dan untuk pertama kalinya malam itu, Dero duduk di kursi di sebelah Atha. Bukan karena nyaman. Tapi karena mungkin... waktunya sudah cukup larut untuk berhenti pura-pura kuat sendirian.
“Sebenernya, kemarin dia ada chat gua,” sambungnya.


 harrisradcliffe
harrisradcliffe


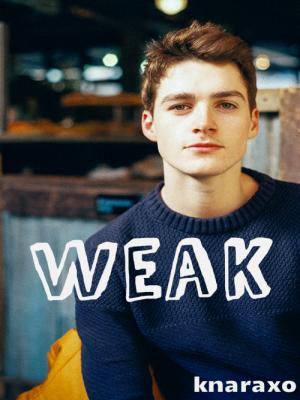


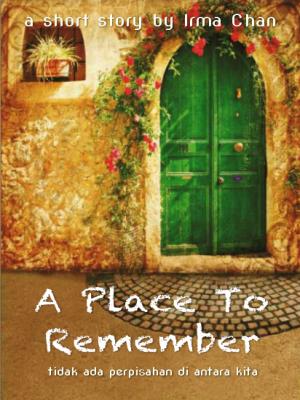




arrghhhhh. aku bacanya ikut frustrasiiiiiii
Comment on chapter BAB 3: TIDAK LAYAK BERTAHAN