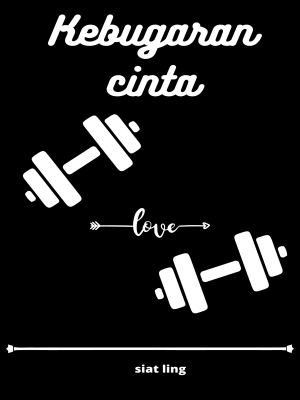“Lo tau jembatan merah di kampung sebelah? Nah, itu tempat lo dipungut sama Mama. Makanya nama lo nggak ada Fadilla-nya, hahaha.”Hima terbahak setelah melemparkan lelucon yang sama di setiap makan bersama. Rosa Kartika—Adikku—terlihat tak senang dan melirikku sesaat dengan menyipitkan mata.
“Semua orang di rumah emang jahat,” katanya. “Asal Kak Anbi tau ya, Iffaa aja pernah lemparin barang sampai aku harus dijahit delapan kali di kaki,” adunya.
Tawa di sekitar meja terhenti dan beberapa pasang mata melirikku diam-diam, hanya Anbi Sakardja yang memandangku terang-terangan dengan ekspresi tanya di wajahnya. Aku menyimpan alat makan di piring hingga denting nyaring terdengar, sebagai bentuk emosiku. Dalam sekejap, tawa sebelumnya pun terhenti.
“Luka lo bisa sembuh. Sedangkan, luka gue belum pudar sedikitpun.” Kukatakan hal itu dengan penekanan. Kudorong kursi ke belakang untuk meninggalkan meja makan yang jarak tiap kursinya hanya sekepal tangan. Pintu kayu berkaca sebagai pemisah ruang dapur itupun kututup dan dengan lenggang kuhela napas yang panjang.
Mendengar Rosa berbicara hanya membuat kepalaku mendidih dan jauh dalam lubuk hati, aku menikmati kecanggungan interaksi kami. Aku menyadari bahwa memaafkan adikku itu adalah langkah yang sulit, tetapi aku juga bertanya-tanya apakah aku mau melakukan itu?
“Hadapi masalah. Jangan melarikan diri.”
Kutertawakan sticky note di dinding meja belajar kamarku. Tertulis omong kosong besar di sana, cibirku. Namun, satu hal yang pasti adalah aku masihlah pengecut yang tidak bisa menghadapi masalah. Penakut.
Senyum kali ini kupastikan miris sekali.
Ramainya ruang makan bisa terdengar meski berbeda ruang. Aku seharusnya bisa mengendalikan emosi lebih baik saat orang asing berada di sekitar, baiknya Anbi Sakardja tak mengetahui sisi burukku yang sensitif.
Usai mencuci piring, dengan langkah sedikit pincang aku kembali mengompres kakiku dengan es batu di kursi depan televisi. Dari sini, aku bisa melihat kesibukan di meja makan yang menyelesaikan makan malamnya atau mendengar perbincangan mereka soal alergi kacang Anbi.
Mengesankan, cowok bertahi lalat di atas alis itu dengan mudahnya beradaptasi seolah mereka merupakan kenalan lama. Meladeni setiap kata yang keluar dari bibir keluargaku, Anbi sesekali meringis. Apalagi pertanyaan pacar Hima yang menanyakan tipe kekasih idaman.
“Lo ngerti kali, bang,” jawaban Anbi mencurigakan, apalagi lirikkan Hanif padaku yang berohria dengan anggukan kepala. “Oh, ngerti gue ngerti.”
“Bapak ke mana, Ma?” Hima mencomot topik lain. Sedaritadi, mataku memang tak menemukan kehadiran seorang kepala keluarga sampai Mama mengatakan bahwa beliau membantu pekerjaan tetangga. Hima mengomeli, “Bapak bandel banget sih, Ma. Dokter ‘kan suruh istirahat dan jangan kerja, terus Bapak juga belum cek kondisinya. Kalau masalah uang, Hima nggak keberatan bantu. Hima ‘kan cuma mau Bapak sehat-sehat aja.”
Kulihat senyum Mama yang terulas tipis. Keluarga kami memang dalam kondisi kesulitan sejak dua tahun terakhir Bapak didiagnosis memiliki penyakit gagal ginjal hingga harus menjalani operasi. Kondisi ekonomi keluarga tak stabil karena keadaaan Bapak yang diminta untuk beristirahat total di rumah. Namun, enam bulan terakhir Bapak sering memaksakan diri bekerja.
Entah apa yang dipikirkan beliau, aku tak menyukainya. Jauh dalam hati, aku selalu bertanya-tanya, “Apa Bapak bosan hidup? Atau Bapak ingin mati?” Aku tahu bahwa pemikiranku mungkin terlalu jauh, tetapi kekhawatiran tak membatasi pikiran. Sama seperti yang kakakku katakan, sebagai anaknya aku ingin ia baik-baik saja.
Dua tahun yang lalu pula, hubungan kami terbentuk canggung setelah berminggu-minggu Bapak menjalani operasi. Hanya satu kesalahan, tetapi rasa kecewaku tak memudar setelah detik demi menit berlalu.
Dimulai dari kesalahan Mama yang mengambil uang tabunganku tanpa izin untuk melunasi biaya operasi dan obat Bapak. Kepalaku selalu diliputi amarah dan aku mulai tak patuh untuk mematuhi orang tua, cukup kurang ajar. Bahkan emosiku kian memanas setelah Bapak membanting gitar pemberiannya saat aku menduduki Sekolah Dasar. Tak habis pikir, mengapa harus gitarku yang menjadi pelampiasan emosi Bapak karena alasan terganggu oleh suara musikku?
Beberapa hari kemudian, Rosa meledek saat aku makan malam sendiri, “Kasian nggak bisa main gitar lagi. Rosa nggak pernah suka lo main gitar karena jelek dan berisik.”
Dalam sedetik pula, piring berisi nasi itu melayang terbang menuju Rosa hingga nyaring teriaknya mengundang seisi rumah untuk mengitari anak itu. Aku hanya memandang kaki Rosa yang berdarah dan anehnya aku mengukir senyum. Tak peduli sakitnya tamparan Mama, aku mengatakan hal kejam, “Tadinya aku mau lemparin pisau.”
Beberapa hari kemudian pula, aku mendapatkan pengakuan Rosa setelah menemukan kamarku berantakan dengan laci meja belajar yang kehilangan isinya. “Rosa bakar buku musik lo. Udah Rosa bilang jelek. Mending lo diam aja.”
Aku mengamuk. Entah itu mencakar kulit Rosa, menjambak rambut, menendang kaki, atau bahkan keinginanku untuk membuat kepala Rosa berdarah dengan gelas kaca di tangan kiriku. Namun, Bapak menghentikan dan menamparku keras seraya melemparkan gelas di tanganku sembarang arah.
“Ini salah Bapak. Semua juga gara-gara Bapak!” Kulampiaskan emosiku yang meledak-ledak. Aku membenci semuanya, termasuk diriku sendiri.


 azzmifaitsmiddielah
azzmifaitsmiddielah