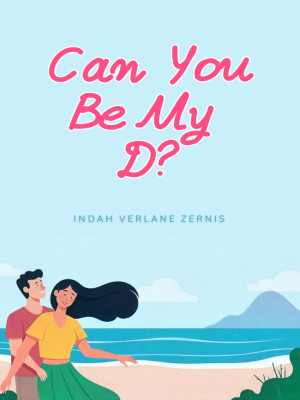Menjelang malam. Bisa dibilang sedang senja. Angin kencang sudah tidak lagi menerpa kota. Kakiku melangkah menaiki anak tangga menuju ruang di lantai tiga paling atas. Aku tidak meneguhkan tangan kiriku pada kayu pegangan tangga, sebab langkahku sudah hafal betul setiap rentang undakan tangga yang kunaiki satu per satu. Suara ketukan tongkatku menggema pada lorong sunyi. Seperti biasa, tidak ada suara penghuni lain di lantai tiga ini kecuali diriku.
Sesampainya di dalam rumah—tanpa perlu menyalakan lampu tentunya, aku menaruh jaketku pada tiang hanger dekat pintu masuk. Aku menaruh kaca mata hitamku di depan mata boneka jerapah raksasa yang terpajang di sebelahnya. Apartemen ini berukuran sangat sedang, semua tata letak dan juga furnitur kubuat seleluasa mungkin agar kakiku tidak melulu tersandung benda di sisi kanan kiri jalurku menapak.
Seorang pelayan kepercayaanku bernama Ramani Darlӧf datang tiga hari sekali untuk membantuku berbersih. Wanita paruh baya itu sudah lima tahun mengabdi sejak aku masih menghuni Eagle Castle. Ramani justru sangat senang ketika aku memintanya untuk menjadi asisten di apartemen. Lagi pula ia sudah terbiasa dengan segala yang kubutuhkan. Membersihkan bercak darah yang terkadang tertinggal di baju, sepatu, bahkan dinding rumahku. Aku tidak perlu meragukan kesetiaannya.
Biasanya, hal yang sering kulakukan setiap pulang kerja adalah mandi kemudian tidur. Melewatkan makan malam dan lebih suka membenamkan diri di balik selimut. Namun kali ini, tampaknya perutku tidak sanggup menahan gejolak rasa ingin makan sesuatu.
Hal yang tidak sulit bagiku, mencari bahan makanan di dalam lemari es. Mengambil beberapa butir telur, bawang, tomat dan juga sayuran yang masih terasa segar—kurasa. Dengan caraku sendiri, aku sudah benar-benar hafal di mana letak peralatan dapurku. Menyusun mereka dengan sangat rapi dan tertata di atas meja dapur.
Dalam hitungan lima belas menit, aku sudah mengiris bawang, sayuran dan juga tomat dengan keahlian indera peraba. Menuangkan satu per satu bahan-bahan yang kuperlukan untuk sekadar memasak telur omlete. Harum margarin dan juga paduan telur menyunggingkan senyum kecil di sudut bibirku. Suara gemerincing minyak di atas panci penggorengan membuat suasana dapur menjadi senantiasa ramai. Hal yang paling kusukai dalam kesendirianku di tempat ini. Berbaur dengan kesibukan yang menjadi obat penenteram.
Diakhiri dengan menikmati makananku di meja makan. Tanpa sendok atau garpu, sebab tangan kananku lebih baik kugunakan untuk mendapati tekstur makanan sebelum berakhir di dalam mulut. Aku memutar musik klasik dari mp3 player yang menyala setelah menekan beberapa tombol pada remote, sambil menikmati kunyahan omlete dan juga buah tomat. Terhanyut. Sesekali bibirku menyunggingkan senyum sendiri. Aku mulai menikmati kesendirianku. Ritual agung sebelum melakukan pekerjaan nanti malam. Setiap orang punya cara mereka masing-masing untuk menikmati kesendirian, bukan?
Tak ada alasan yang membuatku bertanya saat tiba-tiba terdengar suara dentuman lompatan kaki di atas rooftop.
Dahiku mengernyit, disusul dengan dengkusan kesal.
Lagi-lagi, suara dentuman kaki berdentam. Kemudian suara beberapa pria tertawa berdengung.
"Lompatanmu seperti orang tua osteoporosis, Dave!" Seruan seorang pria memanggil temannya yang kemudian melompat setelahnya.
Keributan itu lagi. Tanpa sadar tanganku bergerak memukul permukaan meja hingga suara kelentingan piring terdengar. Raut wajah mengesal. Mendengkus. Rasanya aku ingin bangkit dan berlari ke atas atap untuk membuat perhitungan pada para pria—entah mereka remaja atau anak-anak, aku tidak peduli. Terang saja aku tidak suka atap rumahku di jadikan tempat mainan.
Hampir setiap sore, rooftop yang berada tepat di atas kepalaku berdentum keras dan mengeluarkan suara gema. Terkadang lampu gantungku sampai bergetar akibat ulah mereka. Apa tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan di atas sana? Ini sudah berlangsung puluhan kali sejak para pria pengangguran itu menjadikan kawasan padat penduduk ini sebagai lahan parkour.
"Jangan menghinaku. Aku hanya salah membuat kuda-kuda sekali, lihatlah pendaratanku sempurna. Tidak sepertimu yang terlihat mirip wanita tua yang tersungkur." Ahh, kurasa dialah si pria bersuara bariton yang bernama Dave.
Aku memejamkan mataku kuat sembari menarik napas. Berusaha tenang, agar meja yang tak bersalah tidak lagi menjadi pelampiasanku. Kalau saja kau lihat bola mataku saat aku membukanya, barangkali kau akan langsung mengalihkan pandangan. Kau tidak akan menemukan bayangan apa pun di mataku selain warna retina yang berselaput pucat. Juga kelopak mata yang tidak lagi berbentuk wajar. Begitu yang pernah kudengar dari orang-orang terdekatku di Eagle Castle.
Terus terang, aku benci kebisingan. Aku benci keributan. Dan aku benci bila ada orang lain yang mengganggu ketenanganku. Meski aku tidak mungkin membunuh mereka, hanya saja para pengganggu itu sudah merusak ritualku. Bahkan ketika suara mereka menghilang dan tak lagi terdengar pun aku masih duduk di tempat semula. Mendiami diriku sendiri selama sepuluh menit dengan musik klasik yang kuharap bisa memulihkan semangat berburu.
Aku melanjutkan makan malam.
***
Beruntung, tugasku malam ini berjalan dengan baik.
Di lorong 21, jam 11 malam. Pria bernama Peter itu menghantar- kan nyawanya sendiri padaku. Jelas saja tak akan ada satu orang pun yang curiga seorang wanita tunanetra sepertiku punya kemampuan membunuh secara terlatih. Aku hanya perlu berdiri dan sedikit melangkahkan kakiku untuk berjalan pada lorong yang dimaksud.
Bau pekat yang sama dengan pertanda itu. Dan suara derap langkah mencurigakan terendus. Ciri yang sama seperti yang diberi tahu oleh sang agen. Aku pun dengan lihai menajamkan pendengaran hingga lambat laun langkah pria itu mulai mendekat.
"Anda berada di tempat yang salah, Nona. Apakah Anda tersesat?" Pria itu diam sebentar, bau pekat itu semakin menusuk hidungku. "Kau buta?" Kemudian ia meringis tawa.
Aku berpura-pura gugup, menyudutkan diriku pada tembok dingin dan membiarkannya menertawaiku tentunya.
"Jangan takut, Nona. Aku tidak akan menyakitimu jika kau bersedia memberikan tas mungilmu itu padaku."
"Pergilah! Jangan menggangguku," gertakku.
Mendekatlah. Rayulah aku sebisamu sebelum kau kehilangan kesempatan.
"Dan entah bagaimana kau membuatku semakin tertarik untuk mengganggu. Apa kau takut?"
Yang benar saja, memangnya dia bisa melihat aura ketakutan tanpa melihat mataku? Lima puluh persen pria yang suka menghabiskan waktu di jalanan dan berbuat kriminal terkadang memang dilingkupi kebodohan akut dan tak berdasar pada pengalaman langka .
Aku menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri mencari posisinya. Menajamkan indra penciumanku semaksimal mungkin. Sebelah kanan, dan jaraknya hanya 30 sentimeter. Aku tidak akan menggunakan boton sword kali ini, lagi pula aku tidak membawanya. Hanya sebilah pisau cutter kecil yang kusimpan di dalam saku mantel, baru kubeli dua hari yang lalu saat belanja bulanan.
"Boleh aku bertanya?" Suara pria itu semakin mendekat ke telinga kananku. "Apakah kau pernah becermin? Sebab wajahmu itu cantik sekali. Apa kau tidak menyadarinya? Terus terang, aku— HAKKRHH...!"
Pisauku menancap tepat di jakun pria itu. Kutarik ke samping untuk membelah arteri dan melumpuhkan pembuluh darahnya seperti binatang ternak. Darah mengalir ke tanganku. Aku yakin mata pria itu mendelik hampir keluar, kedua tangannya menggenggam tanganku dengan gemetaran yang hebat.
"Tentu saja aku cantik, dan kau pasti menyesal karena telah memuji kecantikanku."
Tak perlu tenaga penuh untuk mencabut pisau itu. Aku bisa mendengar suara erangan pria itu mengejang, terjatuh dan beberapa detik kemudian mati bersimbah darah. Kematian yang cepat, itu iba yang kuberikan padanya.
Aku berjongkok meraba tubuhnya yang sudah tak bernapas. Membersihkan pisau dan juga tanganku menggunakan ujung bawah kemejanya. Kemudian aku berdiri, mengetukkan tongkatku ke tubuh pria tersebut memastikan sekali lagi kalau dia benar-benar sudah mati.
Pekerjaanku selesai dengan mudah sebagaimana biasanya. Tongkat kuketuk dan kugeser di depan, kaki melangkah melewati jasad si pria mengenaskan, keluar dari lorong gelap dengan langkah santai. Begitu aku sudah berada di pinggir trotoar jalan besar dan jauh dari lorong 21, aku mengambil tisu basah dari dalam tas dan membersihkan telapak tangan dari bau anyir darah yang barangkali terciprat.
Aku pulang, menunggu bis malam di halte yang sudah kuhafal jumlah langkahku untuk menghitung jarak menuju letaknya. Aku duduk di bangku halte sendirian tanpa ada satu pun hawa panas orang lain di sekitarku. Situasi yang menguntungkan hingga sepuluh menit berikutnya.
Bis berhenti di depanku, suara pintu terbuka, dan aku masuk dengan langkah hati-hati. Seorang kondektur membantu, menuntunku ke kursi dan memastikan aku duduk dengan nyaman tanpa penumpang lain di sebelahku. Tak lupa aku mengucapkan terima kasih padanya dan memberi tahunya untuk menurunkanku di halte ke lima setelah ini.
Pelan-pelan aku merasakan bis mulai bergerak dengan kecepatan sedang. Lantas berhenti lagi di halte berikutnya. Seorang pria, masuk dan entah kenapa ia memilih untuk duduk di sebelahku. Padahal aku yakin masih banyak kursi kosong yang bisa ia duduki tanpa harus mengganggu kenyamananku.
Bis melaju lagi. Aku memainkan tali pada ujung kepala tongkat lipatku. Diam di kursi dan berusaha relaks. Pria di sampingku berdeham. Aroma parfum Desire tercium jelas di indraku. Aku berpikir mungkin dia sedang memperhatikan. Terang saja, tidak ada orang lain yang bias mengalihkan pandangannya dari jenis manusia yang berbeda sepertiku. Aku mafhum, dan sudah terbiasa menjadi pusat perhatian.
"Maaf, Nona, apa tangan kirimu terluka?" Pria itu bersuara.
Aku terkesiap. Terluka? Apa aku meninggalkan noda darah di tangan kiriku? Apa mungkin pria di sebelah ini mengetahuinya?
"Tanganku?" tanyaku kembali memastikan.
"Iya, ada darah mengering di pergelangan tanganmu, dan kupikir tanganmu terluka."
Tangan kananku refleks meraba pergelangan kiriku mencari noda yang dimaksud. Kemudian menyungging senyum kecil untuk menutupi kecanggungan.
"Oh, aku tidak terluka. Tadi sebelum aku menunggu di halte, hidungku mimisan. Dan kurasa darahnya mengenai tanganku. Ahh, aku lupa membersihkannya menggunakan tisu basah."
"Di lehermu juga, dan di tongkatmu."
Astaga, bagaimana bisa aku seceroboh ini meninggalkan percikan darah di mana-mana. Aku hanya berharap, pria ini bukan detektif, polisi atau intelijen. Jelas itu mengkhawatirkan di situasi panik seperti ini.
Aku mulai gugup, mengambil tisu basah di dalam tas kemudian membersihkan pergelangan tangan kiriku terlebih dahulu.
"Seharusnya aku minta bantuan temanku untuk membersihkan darah mimisanku yang berceceran. Maaf jika ini mengganggu penglihatanmu, Tuan," ujarku beralasan.
Pria itu meringis senyum. Aku bisa merasakan embusan napasnya yang keluar seakan memaklumi.
"Berikan padaku beberapa lembar tisu, biar kubantu membersihkan bagian leher dan juga tongkatmu."
Aku menurut. Menyerahkan beberapa lembar tisu sesuai perminta- annya kemudian membiarkan tangannya bergerak di leherku. Ia meng- usap-usap kulitku lumayan kuat. Kurasa nodanya benar-benar mengering hingga sulit jika dibersihkan sekadar.
"Maaf merepotkanmu, Tuan," kataku mencoba untuk mencairkan kecanggungan.
"Tidak masalah, aku senang bisa membantu orang lain," jawabnya. "Aku Greg Rudolf. Jangan memanggilku Tuan karena kupikir usia kita tidak jauh beda."
"Salam kenal, Greg," sapaku. Dan ketahuilah aku benar-benar canggung. Beruntung ia tidak bisa melihat wajah kikuk milikku di balik kaca mata hitam.
"Well, Nona—"
"Eleanor Pohl." Aku memperkenalkan diriku tanpa diminta, dan itu adalah hal yang aneh bagi diriku sendiri.
"Eleanor? Boleh lepaskan tongkatmu? Biar kubantu bersihkan." Aku mengangguk kemudian menyerahkan benda itu padanya. Tak perlu khawatir sebab itu bukan boton sword, hanya tongkat lipat biasa.
"Kenapa kau pergi sendirian malam-malam begini, Ellie? Apa tidak ada keluargamu yang mengantar?"
Bibirku menyungging senyum kecil ketika ia memanggil nama kecilku. Wajahku menunduk lalu menoleh pada Greg. "Aku tidak punya keluarga. Dan lagi pula, aku sudah terbiasa naik bis sendirian."
"Ini." Greg menaruh kembali tongkat yang sudah bersih ke telapak tanganku. "Aku sering naik bis ini setiap malam, tapi aku baru kali ini melihatmu. Boleh aku tahu kau tinggal di mana?"
Pertanyaan yang sulit kujawab. Aku hanya diam menelan salivaku yang hampir mengering.
"Tidak apa. Maaf, jika pertanyaanku mengganggumu. Seorang wanita memang tidak boleh memberi tahu tempat tinggalnya pada pria asing." Kudengar Greg meringis tawa kecil. Begitu pun denganku, bahkan tawa di bibirku mungkin lebih lebar darinya.
Dan percakapan kami berlanjut. Jangan diterka kalau aku adalah tipe wanita introvert seperti yang orang lain kira saat melihat fisikku. Jangan kalian pikir aku akan begitu saja terjerumus dalam kekuranganku sendiri dan membatasi diri dengan lingkungan. Aku memang punya pekerjaan yang tak lazim. Namun bercengkerama dengan orang lain adalah kesenangan. Aku merasa lebih hidup. Dan itu satu-satunya cara untukku memiliki keluarga.
Ah, bukan. Apa yang kujelaskan barusan rupanya hanya sebagian dari caraku berbaur dengan orang lain. Dalam setahun belakangan ini. Setidaknya, aku berusaha senyaman mungkin untuk bicara dengan mereka. Terkadang. Saat perasaanku tak memburuk.
Perjalanan di dalam bis menjadi lebih singkat. Greg menyalakan lelucon yang membuatku sesekali tertawa. Greg bilang, dia suka mendengar suaraku yang khas saat melengkingkan tawa. Kami begitu cepat akrab, dan pembahasan kami mengenai kota kelahiran Greg berujung pada senda gurau yang harus disudahi.
Halte ke-5 sudah sampai, Greg membantuku turun dari bis dengan genggaman tangannya yang hangat dan keras.
"Senang berkenalan denganmu, Ellie. Aku berharap kita akan bertemu kembali lain kali," ujar Greg di depan pintu bis saat memberi- kan salam perpisahan padaku.
Senyumku mengembang, melambaikan tangan pada Greg tanpa tahu di mana letak posisinya berada, seiring dengan laju bis yang mulai menjauh dari hadapanku. Kemudian senyumku menyusut dua detik kemudian.
Tongkat kembali kugeser di atas permukaan jalan trotoar. Hanya berjarak lima puluh langkah ke depan, maka aku akan tiba di depan pintu masuk gedung apartemen. Kembali menenangkan diri dalam kesepian, dan ketika esok pagi tiba, sebelum fajar menyingsing, aku sudah menemukan sekantung uang kertas Euro di bawah selipan kusen jendela kamarku. Imbalan atas usahaku tadi malam.
______________________


 innda_majid
innda_majid