Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalanan kompleks. Embun menempel di dedaunan, dan langit berwarna biru pucat—tanda matahari belum benar-benar muncul.
“Kak Lara, cepetan! Nanti keburu ada matahari! Gue males pake sunscreen!” teriak Luna dari halaman depan. Ia berdiri dengan satu tangan di pinggang, tali skipping melilit di tangan satunya. Nafasnya terlihat di udara dingin.
Lara berjalan malas keluar rumah. Kaos putihnya kebesaran, hampir menutupi celana tidur panjangnya yang kusut. Rambutnya masih kusut, matanya sembab karena kurang tidur.
“Kamu aja, Lun. Kakak mau bantu Ibu siapin sarapan,” ucapnya pelan, suaranya parau.
Belum sempat Luna membalas, suara berat Ayah mereka menyusul dari dapur.
“Biar Ayah aja yang bantu Ibu. Kamu ikut olahraga kecil sama Luna. Badan kamu itu kayak kurang gerak. Besok aja bantuin Ibu.”
Lara menunduk pasrah, tanpa protes. Ia mengambil tali skipping dari tangan Luna, lalu berdiri sejajar di halaman yang masih sepi. Jalanan kosong, hanya suara burung pagi yang sesekali terdengar.
Luna mulai duluan. Gerakan kakinya cepat, teratur, ringan seperti sudah terbiasa. Tali skipping melambung dan membentur tanah dengan ritme yang pasti.
Lara mencoba mengikuti. Lompatannya canggung. Kakinya menyentuh tali berkali-kali. Nafasnya cepat memburu hanya dalam waktu satu menit.
“Kamu sering olahraga gini, ya? Kakak nggak pernah tahu,” tanya Lara sambil mengatur napas.
Luna menghentikan lompatannya. “Kepo amat sih, sok deket banget,” katanya sambil memutar bola matanya. Tapi membuat Lara tersenyum tipis.
Lima menit… sepuluh menit…
Keringat mulai mengalir dari pelipis mereka. Luna masih terlihat segar, semangatnya tinggi, lompatan stabil. Sebaliknya, Lara mulai terlihat goyah. Tubuhnya mulai gemetar, wajahnya pucat, dan bibirnya mengering. Nafasnya terdengar semakin berat.
Tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia memegangi perutnya dan menunduk, berusaha menahan rasa mual.
"Kak Lara?” Luna melirik, ada keraguan di matanya. Ia ingin bertanya, tapi gengsi menahannya.
“Udah ya, Lun. Kakak nggak kuat,” ucap Lara lirih, meletakkan tali skipping di pinggir tangga teras. Jalannya menuju pintu tampak limbung, seperti kapan saja bisa jatuh.
Luna tetap berdiri di tempat, melihat punggung kakaknya menghilang di balik pintu. Raut wajahnya berubah—ada kekhawatiran yang tak ia ucapkan.
Di dalam rumah, Lara langsung disambut tatapan tajam sang Ibu.
“Kamu kenapa nggak bantu Ibu hari ini?” suaranya tinggi.
Lara menelan ludah, perutnya terasa melilit. “Bu… boleh nggak Lara izin dulu hari ini? Kepala Lara pusing banget… kayaknya masuk angin.”
Ibu mendengus. “Alah, lebay amat! Baru olahraga sebentar udah ngeluh! Ibu bayar mahal sekolah kamu!”
Lara mengangguk pelan. Tak ada amarah, tak ada tangis. Ia hanya melangkah lemah ke kamar, menutup pintu dan menguncinya.
Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Hatinya berat, tubuhnya lebih berat lagi. Dalam keheningan itu, ia meraih buku catatannya dari laci. Di lembar kosong, ia mulai menulis. Bukan puisi, tapi surat.
Untuk Lara, dari Lara
Hai, kamu...
Aku tahu kamu capek. Tapi terima kasih karena hari ini kamu masih kuat berdiri. Masih bisa tersenyum meski rasanya pengen rebahan aja dan ngilang dari dunia sebentar.
Aku tahu kamu berusaha jadi anak yang baik. Bantuin Ibu, nurutin Ayah, sabar sama Luna, diem waktu disalahin. Tapi kamu juga manusia, Ra. Gak apa-apa kok kalau hari ini kamu ngerasa gak sanggup.
Kamu lelah? Gak apa-apa. Itu wajar.
Kamu merasa sendiri? Gak apa-apa juga. Tapi kamu gak sendirian, karena kamu masih punya dirimu sendiri. Aku, yang ada di sini, ngerti kamu banget.
Jadi, istirahat dulu ya, Ra. Hari ini gak usah sempurna. Hari ini cukup bertahan aja. Gak perlu jadi kuat terus-terusan. Kamu udah luar biasa.
Salam hangat dari hati kamu sendiri,
Lara
*****
Lara baru saja melangkah masuk ke gerbang sekolah saat suara bel pertanda masuk berbunyi nyaring. Lorong-lorong masih sepi, hanya beberapa siswa yang tergesa melewati kelas demi kelas. Aroma khas kapur tulis dan debu lantai bercampur dalam udara pagi, menciptakan suasana yang tak asing tapi juga tak pernah sepenuhnya nyaman.
Ia berjalan pelan melewati dinding abu-abu yang mulai memudar warnanya. Tangan kanannya menenteng tas, dan langkahnya sedikit terseret, seperti tubuhnya terlalu berat untuk digerakkan. Bukan karena capek, tapi karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam dada.
Lara mengingat kata-kata Ayahnya tadi pagi.
"Hari ini, biar Ayah yang jemput kamu."
Sederhana. Tapi aneh. Begitu asing sampai membuat Lara berhenti sejenak di lorong, menatap lantai seperti mencari jawaban yang tak bisa ditemukan.
Ayahnya? Menjemput?
Ia ingat betul, beberapa bulan lalu—di tengah pertengkaran hebat yang membuat Luna menangis berhari-hari—Ayahnya pernah membentaknya keras. Suara itu masih terngiang jelas dalam kepala Lara.
"Kalau kamu bukan karena tanggung jawab, udah saya buang kamu!"
Itu kalimat yang tak pernah bisa benar-benar dilupakan. Bahkan ketika Ayahnya bersikap seolah-olah tak pernah mengucapkannya.
Jadi kenapa sekarang tiba-tiba perhatian? Kenapa sekarang bersedia datang ke sekolah menjemput? Lara tak tahu. Dan jujur saja, ia tak yakin ingin tahu.
“Lar?!” Sebuah suara ceria memotong lamunannya. Sera muncul dari arah berlawanan, wajahnya sumringah seperti biasa, langkahnya terlihat ringan.
Entah sejak kapan Sera sudah ada di sebelahnya, berjalan seiringan.
“Hari ini lo cantik banget deh,” ujarnya sambil menatap bibir Lara. “Tapi kok pucet, ya? Kamu pake lip cream yang nude ya?”
Lara menyentuh bibirnya tanpa sadar. “Enggak. Ini yang peach, yang kita beli bareng waktu itu.”
Sera memiringkan kepala. “Kok beda dari biasanya, ya? Keliatannya pucet banget.”
Lara tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan. “Aku lagi gak enak badan. Mungkin masuk angin.”
“HEY LEADIS!"
Suara cempreng khas Zea langsung menyerbu mereka, membuat Lara dan Sera reflek menoleh. Zea datang dengan gaya sok gemas, rambutnya dikuncir tinggi seperti biasa, dan wajahnya tak berubah: penuh drama.
“Oh iya, Lara, beliin gue susu cokelat di kantin dong. Kaki gue sakit,” pintanya dengan gaya manja, seakan Lara adalah asisten pribadinya.
Sera langsung melirik malas. “Eh, Ze…”
“Gak mau,” potong Lara pelan, namun tajam.
Zea mengernyit. “Hah?”
“Ada Kesya, ada Citra. Kenapa kamu nyuruhnya aku terus? Aku bukan pembantu kamu, Ze.”
Zea terdiam sejenak. Lalu—seperti biasa—senyum sinisnya muncul.
“Wah, rumor tentang lo mulai berubah ternyata bener, ya? Gimana ya kalau Bu Meri tahu anak kesayangannya sekarang udah gak nurut lagi?”
Kalimat itu menusuk. Bu Meri… satu-satunya guru yang benar-benar peduli pada Lara, yang selalu bilang bahwa ia anak baik. Lara merasa hatinya mencelos. Kalau Bu Meri tahu… apakah ia juga akan kecewa?
Ia terdiam. Pundaknya sedikit merosot, seolah menanggung sesuatu yang berat. Sera menatapnya dengan iba, seakan tahu apa yang dirasakan sahabatnya itu.
“Ser,” bisik Lara kemudian, suaranya kecil dan nyaris tenggelam di keramaian anak-anak yang mulai berdatangan.
“Yang aku lakuin… salah gak sih?”
Sera mengangguk mantap. “Enggak, Lar. Kamu harus belajar mikirin diri kamu sendiri. Kamu juga berhak marah. Kamu juga punya batas. Kamu bukan boneka siapa pun. Kamu juga manusia Lar... berhak punya emosi, berhak nolak. Wajar banget kok, aku dukung kamu!”
Lara akhirnya tersenyum samar. Tak ada yang tahu, bahwa di balik senyum itu, hatinya masih remuk.
Tapi hari itu, di lorong sekolah yang dingin dan asing, Lara tahu satu hal, Lara tak lagi sendirian.
*****
Langit sore mulai berubah warna. Jingga pucat menyelimuti atap sekolah yang kini nyaris kosong. Suara langkah kaki terakhir para siswa telah lama menghilang, hanya menyisakan desiran angin yang mengusik daun-daun kering di halaman. Di bangku panjang dekat gerbang, Lara duduk sendiri.
Tangannya memeluk tas, sesekali menunduk menatap sepatu. Tatapannya kosong, tapi di dalam dadanya—berisik.
Ayahnya berjanji menjemput.
Dan Lara menunggu.
Sudah hampir satu jam sejak bel pulang berbunyi, dan satu per satu temannya pergi meninggalkan sekolah. Bahkan petugas kantin sudah menutup warungnya. Tapi Lara bertahan. Menanti. Dengan hati setengah cemas—setengah percaya. Setengah takut dikecewakan, tapi setengah lagi berharap... mungkin saja, hari ini berbeda.
Mungkin kali ini Ayahnya benar-benar datang.
Mungkin.
Lara menatap gerbang sekali lagi.
Kosong.
Lalu, ponselnya bergetar pelan. Sebuah notifikasi muncul. Ia buru-buru meraihnya—jantungnya berdegup cepat.
Tapi detik berikutnya, rasanya seperti ada yang menampar hatinya keras-keras.
Lara maaf, Ayah ada meeting mendadak. Gak jadi jemput.
Lara membeku.
Tak ada air mata yang jatuh—hanya diam. Namun diam itu seperti retakan besar yang membelah hatinya dari dalam. Sekolah sudah benar-benar sunyi sekarang. Tak ada siapa-siapa lagi. Bahkan suara motor penjaga sekolah pun sudah lenyap.
Hanya dia, dan perasaan dikhianati oleh harapan.
“Harusnya aku gak suka terlalu berharap…” gumamnya pelan, hampir seperti berbisik pada diri sendiri. “Ayah kan selalu kayak gini…”
Suara itu nyaris tenggelam dalam suara angin yang lewat pelan.
Lara berdiri. Kakinya melangkah perlahan, meninggalkan bangku tempatnya duduk. Ia tak tahu akan ke mana. Tak ada angkutan lewat jam segini. Tak ada yang benar-benar ada dipikirannya. Tapi Lara tetap berjalan, entah menuju arah mana.
Yang pasti, bukan menuju rumah.
Mungkin hanya ingin menjauh.
Dari rasa kecewa.
Dari janji yang tak ditepati.
Dari rasa percaya yang kembali ia beri, dan lagi-lagi dihancurkan.
Langit makin gelap.
Dan Lara masih berjalan.
Sendiri.


 yourassiee
yourassiee
















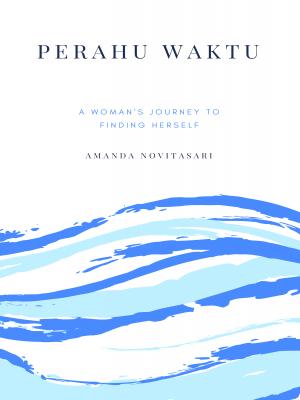


i wish aku punya temen kaya sera:((
Comment on chapter 9 - Luka yang tak diakui