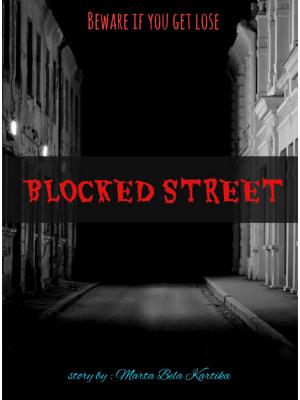Hujan mengguyur deras di luar rumah sakit, menghantam genteng dan jendela seperti rintihan langit yang tahu apa yang sedang terjadi di dalamnya.
Malam menebal dalam pekat dan dingin, menusuk hingga ke tulang. Di balik sekat ruangan itu, seorang gadis bernama Fitri terbujur kaku. Tubuhnya menggigil. Napasnya tak lagi stabil.
“Fit, Fitri, Fitri!”
Teriakan histeris kedua orang tuanya terdengar memilukan. Seorang dokter menerobos masuk, diikuti dua perawat yang bergerak cepat menyibak tirai. “Kami butuh ruangan, silakan keluar sebentar.” ucap salah satu perawat tegas namun lembut.
Dengan enggan, kedua orang tua Fitri melangkah mundur. Tapi mata mereka tetap tertambat pada putri mereka, seakan tatapan itu bisa menjembatani harapan yang nyaris hilang.
Seorang dokter memeriksa cepat rekam medis yang dibawa perawat.
“Kita temukan bekas luka kecil di lehernya, seperti gigitan atau suntikan, kemungkinan besar efek dari kontak langsung dengan serangga, hewan…” Sang dokter menghentikan kalimatnya sesaat. Tenggorokannya seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan. “...gigitan taring manusia…” Dia tidak percaya mengucapkannya. “...Reaksinya lambat, tapi mematikan.”
Waktu seakan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tubuh Fitri yang semula tenang, tiba-tiba kejang. Dari mulutnya, busa putih mengalir, membuat ketakutan yang semula samar kini menjelma nyata. Ketenangan itu hanyalah kedamaian palsu sebelum badai menggulung.
Waktu merambat lambat. Setiap detik seperti palu godam yang menghantam dada. Kemudian, tirai itu terbuka. Dua perawat mendorong ranjang keluar dengan langkah terburu.
“Dok, bagaimana keadaan anak saya?” Ayah Fitri mendekat, suaranya parau.
“Kritis. Kami akan bawa dia ke UGD sekarang. Mohon beri jalan.” Dokter tak sempat menjelaskan lebih jauh. Situasinya terlalu genting.
Tanpa bicara, ayah dan ibu Fitri mengikuti dari belakang. Kecemasan menggerakkan kaki mereka lebih cepat daripada logika.
Adit muncul tak lama setelah itu. Ia berdiri mematung di lorong, tubuhnya membeku oleh kenyataan yang baru saja dilihatnya. Napas tercekat. Langkahnya goyah. Matanya menatap ranjang Fitri yang di dorong menjauh, tubuh gadis itu terus kejang. Busanya belum surut.
Ketika ia mencoba mendekat ke pintu UGD, seorang perawat menghadangnya.
“Maaf, Mas. Hanya tim medis yang boleh masuk.”
Adit menunduk. Ia merasa tidak berdaya. Dunia di sekitarnya seakan runtuh perlahan. Ia menelan kekalutan, lalu memutuskan pergi. Dengan langkah tergesa, ia kembali menuju ruang perawatan Askara.
“Ra.” panggilnya pelan dari ambang tirai yang setengah terbuka.
Askara menoleh dari ranjang. Matanya sayu, tubuhnya masih lemas.
“Fitri, dia nggak apa-apa, kan?” tanyanya penuh harap.
Adit menggeleng, raut wajahnya kusut, suara lirih. “Keadaannya kritis, Ra. Dia kejang-kejang, busa di mulutnya, sama kayak Anita dan Ifal. Sekarang dia di UGD.”
Askara terdiam. Jantungnya mencelos. Tangannya meremas selimut, seolah butuh sesuatu untuk ditahan agar tidak gemetar.
“Ra?” Tanya Adit dengan hati-hati.
“Ini semua, salah aku, Dit” bisiknya tiba-tiba, hampir tak terdengar.
Adit menatapnya, bingung. “Salah kamu?”
“Aku yang ngajak dia ke kuburan Ifal malam itu. Kalau aja aku nggak bawa dia, semua ini nggak bakal kejadian. Aku nggak bisa jagain dia. Aku, lemah, Dit. Aku nggak guna.”
Air mata jatuh dari sudut mata Askara. Peluh mengalir pelan di pelipisnya. Ia menggenggam selimut lebih erat, ingin memukul dan ingin menghukum dirinya sendiri.
“Jangan gitu Ra, jangan salahin diri kamu.” Ucap Adit parau maksud hati ingin menyemangati sahabatnya.
“Kalau Fitri sampai kenapa-kenapa, aku nggak akan tinggal diam, Dit. Aku bakal cari orang itu.”
“Siapa?” tanya Adit dengan dahi berkerut.
“Monster itu, yang menyerupai Anita.”
Adit tertegun. Kalimat itu menghantam pikirannya seperti badai. Monster? Anita?
“Ra, Monster itu kan nggak a”
“Ada Dit, ada.” Askara memotong kalimat Adit. “Aku diserang kemarin malam. Itu bukan mimpi. Mereka nyata. Dan kalau kamu nggak percaya, terserah. Tapi aku bakal balas. Demi Fitri. Aku siap, bahkan kalau harus sendirian.”
Adit menatap sahabatnya lekat-lekat. Napasnya berat. Kemudian ia mengangguk mantap. “Kalau gitu, kamu nggak sendiri. Aku bakal bantuin kamu.”
Mata Askara membulat, terkejut. Dia tak menyangka sahabatnya yang penakut mau membantunya.
“Serius?”
“Serius.” jawab Adit pelan. “Tapi kita bahas itu nanti aja. Sekarang, kita fokus ke Fitri dulu.”
Askara hanya mengangguk. Hening menyelimuti ruangan. Mereka diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing, seolah dunia di sekitar tak lagi ada artinya.
“Oh iya Ra, aku mau lihat kondisi Fitri dulu ya.” Tiba-tiba Adit memecah kesunyian. Dia melangkah pelan menuju pintu. Dia berharap ada kabar baik.
Askara mengangguk pelan, matanya masih menatap langit-langit ruangan. Di balik rasa takut dan amarah yang menumpuk, ada satu hal yang selama ini ia pendam, perasaannya pada Fitri. Ia jatuh cinta sejak pertama melihatnya di depan kelas. Tapi Ifal selalu lebih dekat. Ia hanya bisa mengagumi dari jauh, mencoba mendekat lewat Anita yang akhirnya justru menghancurkan semuanya.
Kini, harapan itu mungkin telah sirna.
Kelopak matanya mulai berat. Kesadarannya melayang seperti ditarik ke dunia lain, jauh dari ruangan rumah sakit. Hening, gelap.
Ketika membuka mata, Askara mendapati dirinya berada di tengah hamparan padang pasir yang luas. Pasir membentang sejauh mata memandang, namun anehnya, ia tidak merasakan panas apa pun.
Ia menoleh ke kanan dan kiri, matanya menyapu sekeliling dengan penuh keheranan. Semua terjadi begitu tiba-tiba dan entah mengapa, terasa sangat familiar, seolah ia pernah mengalami ini sebelumnya.
Di kejauhan, sebuah bangunan besar tampak berdiri megah dengan pintu lebar yang terbuka. Bangunan itu, ya, bangunan yang sama yang pernah ia lihat dalam penglihatan-penglihatannya. Di kanan dan kirinya, kerumunan orang berjalan perlahan memasuki pintu tersebut, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat.
Lalu, tiba-tiba seperti butiran pasir yang menyatu dan membentuk wujud sosok seorang gadis muncul di hadapannya. Tubuhnya memadat dari pusaran debu dan wajahnya mulai tampak jelas.
Dia memanggil namanya.
“Askara.”
Ia menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Gadis berseragam SMA putih bersih dengan rambut tergerai rapi.
“Fitri?” bisiknya, nyaris tak percaya.
Askara melangkah mendekat. Langkahnya ringan, nyaris tak bersuara.
“Kenapa kamu di sini?” tanya Askara lagi, matanya membelalak.
Fitri tidak menjawab. Ia melangkah mendekat, lalu berkata lirih. “Maaf ya, udah ngerepotin kamu. Sekarang aku mau pamit. Aku mau nyusul teman-teman kita yang lain. Makasih banyak, Ra. Makasih banyak buat semuanya.”
“Fitri, kamu ngomong apa sih? Jangan pergi! Tunggu!” seru Askara panik.
Fitri tersenyum. Senyumnya hangat, tapi menyimpan kesedihan dalam diam. “Selamat tinggal, Askara Karsa.”
Dan sosoknya memudar, tertiup angin gurun.
Askara mematung. Napasnya tercekat. Dadanya sesak. Pemandangan itu terlalu nyata untuk disebut mimpi dan terlalu halus untuk dianggap kenyataan. Pemandangan ini seperti saat Ifal muncul berpamitan yang berakhir kematian.
Apakah sekarang giliran Fitri?
Askara yang masih terdiam di tempat, tiba-tiba tersedot ke dalam tanah berpasir. Tubuhnya meluncur turun tanpa kendali dan sekelilingnya berubah menjadi gelap gulita. Ia menjerit, panik, ketika pasir menelan tubuhnya sepenuhnya.
Lalu, dalam sekejap, gelap itu sirna.
Saat matanya kembali terbuka, suara itu langsung terdengar di telinganya, pintu ruangan tempatnya dirawat terbuka tiba-tiba. Dia telah kembali ke dunia nyata, pikirnya.
Adit masuk. Matanya merah. Bahunya gemetar.
“Ra.” suaranya pecah. “Fitri, dia, meninggal.”
Askara terdiam di tempatnya. Dunia seakan berhenti berputar. Mulutnya terbuka, matanya membelalak lebar.
“Dokter udah coba semuanya. Tapi, setelah kejang hebat itu, jantungnya berhenti. Dia kena serangan jantung.”
Air mata Askara mengalir perlahan, menetes satu-persatu ke bantal di bawah kepalanya.
“Serius, Dit?” bisiknya lirih, seperti masih menggantungkan harapan terakhir pada keajaiban.
“Iya.” Ucap Adit sambil mengangguk pelan dengan air mata yang membasahi pipinya.
Saat dia mengucapkan kabar kematian itu, suara dunia lenyap. Semua suara lenyap. Seolah hanya detak jantung Askara yang menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Lalu sunyi. Hampa.
Malam sebelum pemakaman, Askara duduk sendirian di ranjangnya menatap langit gelap tanpa satupun cahaya bintang, seperti menggambarkan pikirannya yang kusut. Ia berucap sendiri pada dirinya.
“Fitri…” suaranya sedikit bergetar, hampir tak terdengar di tengah sunyi ruangan rumah sakit. Matanya mulai berkaca-kaca.
“Aku nggak sempat bilang kalau aku suka kamu.” Tanpa bisa ia tahan, setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Ia menggenggam tangannya erat, menunduk, bibirnya gemetar.
Lalu, dengan suara lirih yang pecah oleh tangis, ia berbisik. “Seharusnya kamu jangan mati dulu, aku belum siap kehilangan kamu.”
Tangisnya pecah perlahan. Ia menutup wajah dengan tangan, mencoba meredam sesak yang menghinggapi dadanya. Semua terasa salah. Andai saja ia tidak meminta Fitri untuk menemaninya melakukan pengintaian, mungkin semuanya tak akan begini.
Ia menarik napas panjang, menatap kosong ke luar jendela, dia berharap Fitri tiba-tiba muncul, tersenyum dan berkata kalau semua hanya mimpi buruk semata.
Keesokan harinya, pemakaman Fitri segera dilangsungkan. Askara memaksa pulang dari rumah sakit agar bisa menyaksikannya. Meskipun memar masih membekas di sekujur tubuhnya. Ia diizinkan pulang dengan syarat banyak istirahat agar luka-lukanya segera pulih. Askara menyanggupi.
Pemakaman dilakukan di tempat yang sama seperti sebelumnya. Di desa Tatar Loka Kumayan, memang hanya ada satu area pemakaman, satu SD, satu SMP dan satu SMA. Semuanya serba satu.
Sanak keluarga Fitri datang dari berbagai daerah. Begitu pula teman-temannya dari masa kecil hingga SMA. Fitri adalah anak seorang abdi negara, jadi selama hidupnya ia sering berpindah-pindah tempat. Tak heran jika pemakamannya jadi ramai. Banyak wajah yang tidak dikenali Askara, hanya beberapa teman sekolah yang ia sapa.
Ia berdiri di samping Adit, yang mengenakan pakaian serba hitam. Mereka menyaksikan jenazah Fitri dimakamkan. Ayahnya sendiri ikut menurunkan jenazah ke liang lahat. Isak tangis terdengar dari keluarga, kerabat dan teman. Askara dan Adit menatap dengan mata yang berkaca-kaca. Air mata mereka mungkin sudah habis sejak semalam, tapi kesedihan masih terasa dalam.
Askara merasa hampa. Perasaan bersalah terus menggerogoti dadanya. Semalam, ia hanya bisa menangis tanpa tidur. Meskipun tubuhnya mulai pulih, penyesalan di hatinya malah semakin parah.
“Ra, semua orang udah ada waktunya.” bisik Adit pelan. “Kamu ajak dia atau nggak, Fitri tetap bakal ninggalin dunia ini. Jangan terus nyalahin diri sendiri.”
Askara melirik Adit, sedikit heran. Jarang sekali temannya bicara sebijak itu.
“Tumben kamu ngomong bener, Dit.”
“Biasanya kenapa?”
“Ngaco. Nyindir mulu.”
“Yee.” Adit cemberut.
Tiba-tiba Askara menatap Adit dengan penuh semangat. “Dit, aku yakin malam ini Fitri bakal hidup lagi.”
Adit langsung bergidik. “Ih, serem. Maksud kamu jadi hantu?”
“Hantu itu nggak ada! Tapi aku yakin, bakal ada yang bongkar makamnya dan ambil Fitri pas dia bangkit.”
Adit masih kebingungan. “Terus?”
“Kita lapor ke polisi. Biar malam ini kuburan dia dijaga. Kalo bener kejadian, kita tangkap mereka. Aku bisa buktiin semua yang aku omongin itu bener. Termasuk soal Anita dan para Vrykolakas.”
“Kalau gitu, kita harus ke kantor polisi dong.”
“Nggak perlu. Soalnya aku lihat pak Dayat di gerbang sana.” Askara menunjuk seseorang yang memakai seragam polisi sedang memperhatikan proses pemakaman. Adit mengenalinya, dia pak Dayat.
Askara langsung berjalan cepat ke gerbang pemakaman. Dia menemui pria berseragam polisi yang mencolok bila dibandingkan dengan pelayat yang lain.
Adit menyusul dari belakang. Ia sempat terkejut melihat polisi yang pernah dijumpai waktu itu datang ke pemakaman.
“Pak, masih ingat saya?” Tanya Askara tiba-tiba.
Pak Dayat menatapnya. “Ingat. Kamu Askara, kan? Sudah sehat rupanya?”
“Iya, Pak. Ngomong-ngomong, kenapa bapak disini? Penyelidikannya belum selesai ya?”
“Bukan. Saya kesini bukan karena tugas. Kebetulan, saya teman lama Pak Setyo, ayah Fitri. Jadi, saya berkunjung melayat.”
“Oh.” jawab Askara dan Adit bersamaan.
“Kalau gitu, hasil penyelidikannya gimana, Pak? Sekarang pasti bapak percaya dong sama cerita saya.” Askara bertanya lagi.
Polisi itu menggeleng, menarik napas panjang.
“Warga bilang saat mereka kejar pelakunya, si pelaku berhasil lolos, nggak ketangkap. Larinya cepat, malah sangat cepat, nggak kayak manusia. Akhirnya mereka yakin kalau itu adalah jin atau demit. Sayang sekali, kepercayaan mistis di desa ini masih kuat. Saya jadi tidak menemukan petunjuk berarti.” Pak Dayat merendahkan suaranya. Ada nada kecewa di kalimatnya.
“Mereka memang bukan manusia, Pak.” Ucap Askara penuh keyakinan.
“Nah, kamu sendiri bilang begitu kan.”
“Eh, maksud saya.”
“Sudahlah. Saya bosan dengar cerita-cerita nggak masuk akal. Saya harus cepat pergi ke laboratorium untuk dapat hasil darah Fitri. Kalau nanti saya dapat petunjuk, saya akan hubungi kamu lagi.”
Polisi itu berbalik, tapi Askara buru-buru menahan.
“Pak, tolong kasih saya satu kesempatan. Malam ini, saya bakal buktiin semuanya. Tolong bantu saya intai makam Fitri.”
Polisi itu menoleh, ragu.
“Kenapa?”
“Karena Fitri bakal hidup lagi malam ini.”
“Hah? Tunggu sebentar.”
Sejenak, wajah Pak Dayat mengeras. Perlahan, kerutan di dahinya dalam dan ia menarik napas panjang.
“Ada apa, Pak?” tanya Askara, menatap curiga.
Pak Dayat menelan ludah, suaranya sedikit bergetar. “Cucu tetangga saya, dulu pernah digosipin udah mati dan hidup lagi, tapi beberapa hari kemudian, neneknya ngaku lihat dia beberapa kali berdiri di depan rumah. Diam aja, matanya kosong. Waktu itu semua orang bilang neneknya cuma halusinasi, ya namanya juga orang tua.”
Ia mengusap tengkuknya, seperti mencoba menepis rasa tidak nyaman.
“Tapi, kalau diingat-ingat lagi, sekarang saya jadi kepikiran. Soalnya anak itu juga pernah pulang dengan kondisi aneh. Kata warga, badan nya pucat, nggak sadar diri dan di lehernya ada dua luka kecil. Dokter bilang itu cuma gigitan hewan liar. Jadi waktu itu saya nggak ambil pusing.” Pak Dayat terdiam sejenak sebelum melanjutkan. “Terlebih nggak ada pelaporan ke Polisi.”
Askara mencondongkan tubuhnya, nadanya mendesak. “Siapa nama cucunya, Pak?”
Pak Dayat menatap Askara dengan ragu, lalu menjawab. “Anggara.”
Deg. Askara membeku. Nama itu menghantam dadanya seperti palu godam.
“Anggara Sidartha? Anak kelas sebelas dari sekolah saya?” tanyanya pelan, tapi dengan tekanan kuat.
Pak Dayat mengangguk pelan. “Nah, iya itu. Kamu kenal?”
“Nggak terlalu sih, Pak. Tapi aku pernah lihat makamnya dibongkar. Dan dia beneran hidup lagi. Malam itu dia nyerang saya, habis-habisan.” Askara menunjuk wajahnya yang masih tampak lebam, bekas peristiwa semalam. “Lihat ini? Ini gara-gara dia.”
Pak Dayat mematung sejenak, lalu mengusap wajahnya sambil mendesah berat. “Ya ampun kok kayak cerita film horor ya.”
“Makanya Pak, Ayolah, bantu saya. Saya janji, saya nggak bohong. Saya masih waras.” Askara memelas, kedua telapak tangannya saling bertaut, memohon dengan tulus.
Pak Dayat terdiam, menimbang-nimbang dalam benaknya. Wajahnya serius.
Adit yang sedari tadi hanya terdiam memperhatikan, akhirnya melangkah maju perlahan. Suaranya lirih namun mantap saat ia berkata kepada Pak Dayat,
“Bapak nggak harus percaya dia sekarang…”
Ia menunjuk ke arah Askara.
“Tapi dia pernah cerita ke saya, kalau dia bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang lain, hantu, pak. Awalnya saya juga mikir dia cuma ngarang. Tapi dia bukan tipe yang suka bohong. Dan waktu itu, dia nunjukin banyak bukti yang bikin saya nggak bisa nyangkal lagi.”
Adit menatap Pak Dayat sungguh-sungguh.
“Makanya sekarang saya percaya. Dan mau bantu dia dalam pengintaian ini.”
Pak Dayat memperhatikan dengan seksama kesaksian Adit. Setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang dan mengangguk pelan.
“Baiklah.” katanya akhirnya.
Karena ia memang masih akan menginap semalam lagi di desa ini dan hasil lab darah Fitri sebenarnya baru keluar besok, ia memutuskan untuk menyanggupi ajakan Askara.
“Tapi ada syaratnya.” Pak Dayat mengacungkan jari telunjuknya. “Kalau kamu bohong atau main-main, saya akan bawa kamu ke kantor polisi pusat untuk dimintai keterangan, Ngerti?” ucapnya tegas.
Askara menelan ludah. Ragu sempat menyelinap, tapi demi kebenaran, ia mengangguk menyetujui.
Mereka pun sepakat untuk bertemu pukul sembilan malam nanti di rumah pak RT. Pak Dayat lalu pergi, masih dengan raut wajah yang jelas-jelas menyimpan ketidakpercayaan.
“Ra, aku ikut ya.” bisik Adit tiba-tiba sambil menyenggol bahu Askara.
“Hah, serius kamu?” Tanya Askara meragukan keinginan sahabatnya. Dia teringat kejadian yang menimpa Fitri. Askara tidak ingin hal yang sama terjadi pada Adit.
Adit tersenyum, seolah bisa membaca pikirannya. “Tenang, sekarang kita nggak sendirian. Ada polisi. Kalau ada apa-apa, kita bisa hadapi bareng.”
Askara tercenung. Lagi-lagi Adit terdengar bijak.
Dia menoleh dengan ekspresi bingung. “Kamu tuh habis transplantasi otak, ya?”
“Nggak, emang kenapa?” Adit mengernyitkan dahi, merasa heran.
“Omongan kamu sekarang bener terus.”
“Haha, makasih.” Adit tertawa kecil.
Pukul enam malam kediaman Willie dan William.
Senja merayap perlahan di balik jendela saat Ifal terbangun dengan tubuh basah oleh peluh dingin. Napasnya terengah, jantungnya masih berdebar keras. Dalam mimpinya, atau mungkin ingatan yang terkubur, seorang wanita menangis tersedu.
Kamu bukan anakku lagi...
Suara itu menyayat, namun wajahnya kabur. Apakah itu ibunya? Atau hanya bayangan? Ifal tidak mengingat siapa wanita itu. Semua ingatannya menjadi samar akibat perubahan yang dialami olehnya.
Sebelum ia sempat mengurai arti mimpi itu, tatapannya menangkap sosok Anita yang berdiri tak jauh dari ranjang. Wajahnya datar, sorot matanya dingin.
“Willie sudah menunggu kita di ruang makan. Cepat turun!” ucapnya tanpa ekspresi, lalu berbalik meninggalkan ruangan.
Ifal bangkit perlahan, matanya menelusuri kamar yang kini ia sadari adalah satu ruangan besar, tempatnya dan Anita tidur dalam sekat berwarna hijau. Langkah kakinya berat mengikuti jejak Anita, seolah masih terjebak antara mimpi dan kenyataan.
Begitu tiba di ruang makan, suasana terasa asing dan sunyi. Di ujung meja, Willie tersenyum hangat, seakan menyambut seorang tamu kehormatan. Tapi senyum itu tak menular pada yang lain.
Vrykolakas lain hanya menatapnya datar, wajah mereka pucat tanpa emosi. Termasuk Anita, yang kini duduk membisu, menatapnya seperti orang asing.
“Ifal, selamat datang. Selamat bergabung menjadi bagian dari Vrykolakas. Ini kehormatan besar bagiku bisa menyambutmu malam ini.”
Sambutan Willie terdengar penuh kebanggaan.
Mereka duduk melingkar di meja makan berbentuk kotak. Jamuan malam itu tampak istimewa, cairan merah kental di dalam gelas kristal yang berkilau lembut diterpa cahaya remang dari lampu dapur dan nyala lilin.
Tujuh sosok berada di ruangan itu: enam Vrykolakas dan satu pelayan berdiri tegak di sudut ruangan, diam, mengenakan jas rapi, kontras dengan penampilan Willie yang berantakan, kemeja kusut, rambut awut-awutan, namun matanya memancarkan wibawa yang tak bisa diabaikan.
Anita duduk di antara mereka. Tatapannya tertuju pada Willie, penuh antusias, meski tanpa senyum. Begitu pula Ifal, wajahnya serius, mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya memantulkan cahaya lilin, pakaian barunya tampak rapi, hasil pemberian Alfred. Kain kafan telah ia tinggalkan.
Kini, dia adalah bagian dari mereka. Seorang Vrykolakas. Sang penghisap darah.
“Pertama-tama, aku ingin kenalin kamu sama keluargaku.” lanjut Willie.
“Di samping kamu, itu Fernando, kakak sepupuku. Di seberang kamu, Abdul Razak, adik sepupuku. Mereka yang ngebantuin kamu bangkit dari kubur.”
Ifal mengikuti arah tangan Willie, menatap wajah-wajah asing di sekelilingnya. Nama-nama mereka terdengar asing di telinganya, jauh dari lingkungan yang ia kenal. Willie, seolah membaca keraguan itu, melanjutkan penjelasannya.
“Kami lahir di tempat yang berbeda-beda. Aku dan William lahir di kota Amsterdam. Fernando di kota Manila. Abdul Razak di kota Sarawak. Kami tersebar bukan tanpa alasan. Ini bagian dari strategi untuk mempertahankan keberadaan kami, agar Vrykolakas nggak punah.”
Ifal mengangguk pelan, tidak banyak menanggapi.
“Kamu udah kenal Anita, Alfred dan Anggara, bukan?”
“Tentu. Tapi Alfred, aku nggak yakin. Apa dia Vrykolakas?”
“Bukan.” jawab Willie sambil tersenyum samar. “Dia manusia. Tapi kakek buyutnya menandatangani kontrak dengan bangsa Vrykolakas. Sejak itu, seluruh keturunannya terikat sebagai pelayan keluarga kami.”
“Kontrak?” Ifal mengangkat alis, heran.
Alfred menyela cepat. “Tuan, sebaiknya jangan…”
“Benar. Maaf, Alfred.” Willie mengangguk pelan, lalu menatap Ifal dalam-dalam. “Itu cerita untuk lain waktu. Ada hal yang lebih penting yang harus kamu tahu.”
Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan.
“Sebagai Vrykolakas, kita nggak bisa hidup di bawah matahari. Sinar itu bakal ngebakar tubuh kita sampai mati. Karena itu, kita hanya aktif di malam hari. Di siang hari, Alfred bakal bantu menjalankan urusan kita.”
Semua menoleh ke arah Alfred yang berdiri diam seperti bayangan.
“Dan sekarang, aku bakal kasih tahu kamu sesuatu yang lebih penting.”
Willie bersandar ke belakang, suaranya berat tapi penuh gairah.
“Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu. Kita akan membangun koloni di desa ini, koloni yang keseratus. Tujuannya? Sederhana.”
Mata Willie membelalak, senyum mengerikan menyeringai di wajahnya.
“Menciptakan pasukan Vrykolakas yang kuat. Dan kalau saatnya sudah tiba, kita akan menggantikan umat manusia.”
Udara di ruangan seketika terasa menebal, sesak oleh aura mencekam. Napas beberapa dari mereka terdengar berat, tertahan.
“Untuk mencapai itu, kita harus terus ciptain koloni di berbagai wilayah. Dan di setiap koloni, akan ada pemimpin seperti aku. Di sini, aku memimpin bersama saudara kembarku, William. Walau dia kadang terlalu naif, tapi kemarin saat ku hajar dia, kupastikan dia mengerti posisinya.”
Willie melirik Alfred.
“Benar, Alfred?”
“Benar, Tuan.” jawab Alfred mantap.
“Kalian dipilih karena memiliki darah murni Vrykolakas. William yang menemukannya dalam diri kalian. Itulah sebabnya kalian bisa bangkit dari kematian.”
Willie berdiri perlahan, pandangannya mengelilingi meja.
“Kalian akan membantuku menciptakan Vrykolakas baru. William akan memilih siapa yang layak. Sisanya…”
Dia tersenyum lebar, dingin.
“...akan jadi makanan. Persediaan darah. Itulah tujuan kalian dibangkitkan. Ada yang ingin bertanya?”
Ifal mengangkat tangan, lalu menurunkannya pelan saat Willie mengangguk, memberi isyarat agar ia bertanya.
“Aku akui, kebangkitanku sebagai Vrykolakas ngasih aku kekuatan luar biasa. Tapi saat pertama kali ngerasain darah, aku berusaha memuntahkannya. Aku ketakutan. Tapi rasa haus itu semakin kuat tiap menit, ditambah, Anita terus memaksa aku untuk meminumnya. Sampai akhirnya, aku menyerah.”
Ifal terdiam sejenak, menelan ludah.
“Rasanya kayak, semua rasa sakit menghilang, tenaga aku meningkat. Aku bisa ngelakuin segalanya. Saat itulah, sisi kemanusiaanku seakan lenyap. Rasanya menakjubkan.”
Ia melirik ke arah Anita, seolah meminta pembenaran. Anita mengangguk pelan, matanya menyiratkan kesepakatan tanpa ekspresi.
“Tapi, ada satu yang aku nggak ngerti, Willie.” lanjut Ifal. “Kenapa kamu ingin menghabisi umat manusia? Bukankah mereka sumber makanan kita? Apa salah mereka sampai harus dimusnahkan?”
Willie tersenyum samar. Ia bangkit dari kursinya, melangkah mengitari meja makan sambil memutar-mutar gelas kristal berisi darah pekat dalam genggamannya.
“Itu pertanyaan bagus, Ifal.” katanya pelan. “Tapi jawabannya akan panjang.”
Ia berhenti sejenak, menatap api lilin yang berpendar di meja, lalu melanjutkan.
“Ribuan tahun lalu, dunia ini bukan milik manusia. Vrykolakas telah lebih dulu ada. Kami nggak makan, nggak minum. Kami hidup dari tidur siang, menyerap energi matahari, seperti tanaman, semacam fotosintesis.”
“Tapi kemudian lahirlah satu anak yang berbeda. Ia nggak tidur di siang hari, justru bermain di bawah terik mentari. Tidurnya malam. Kami menganggapnya cacat. Tapi seiring waktu, dia tumbuh dan anehnya, makin kuat. Ia butuh makan, minum dan bisa berkembang biak.”
Willie berjalan perlahan, seperti membawa semua perhatian padanya. Tak ada suara lain selain langkah kakinya.
“Anak itu adalah awal dari evolusi. Keturunannya menjelma menjadi spesies baru: manusia. Mereka mengambil alih dunia siang hari, membangun peradaban dan perlahan-lahan, melupakan asal-usul mereka.”
“Yang lebih parah, mereka menganggap kita, Vrykolakas, makhluk terkutuk. Mereka memburu kita, membakar kita, menyebut kita iblis dalam legenda. Dan itulah saat peperangan dimulai.”
Willie meneguk darahnya perlahan, suaranya makin dalam.
“Tapi dalam konflik itu, kami menemukan sesuatu yang mengejutkan, darah manusia. Ternyata masih menyimpan fragmen warisan Vrykolakas. Saat kami meminumnya, kekuatan kami bangkit, lebih kuat dari sebelumnya.”
“Dan yang lebih mencengangkan, gigitan kami bisa memicu kebangkitan. Manusia yang digigit, lalu mati, kemudian bangkit sebagai Vrykolakas. Bukan kutukan, Ifal. Itu adalah pemulihan. Kembalinya mereka pada jati diri yang terlupakan.”
Ia terdiam sejenak, menatap langit seolah mengingat luka lama.
“Tapi manusia… mereka mulai takut. Mereka tak paham. Mereka menciptakan cerita demi cerita untuk menutupi kebenaran, menyebut kami kutukan, menyamakan kami dengan iblis.”
“Kita ini bukan iblis. Kita ini leluhur mereka. Tapi lihat apa yang manusia lakukan, mereka buang sejarah, ubah kita jadi cerita horror, hantu dan terror. Aku cuma mau satu hal: membuat dunia mengingat siapa penguasanya.”
Ruangan seketika senyap. Beberapa Vrykolakas menahan napas, seolah menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Willie. Ifal dan Anita saling pandang, terpaku dalam kebingungan dan rasa takjub.
“Itulah sebabnya kita memusnahkan mereka. Lalu, yang bertahan akan kita kembalikan menjadi bangsa kita.” Suara Willie terdengar mantap, bergema di tengah kesunyian ruangan yang dipenuhi aura gelap. “Rencana ini kusebut sebagai Kebangkitan.”
Beberapa Vrykolakas tampak mengangguk setuju, namun Anita justru menatapnya lekat, seolah masih menyimpan tanya. Ia perlahan mengangkat tangannya.
Willie menangkap gerakannya, lalu mengangguk memberi isyarat. “Silakan.”
Anita menarik napas, suaranya pelan namun terdengar jelas. “Apakah Vrykolakas bisa mati, maksud aku... benar-benar mati?”
Ia ragu sejenak. “Selain oleh sinar matahari?”
“Tentu saja.” Willie tersenyum simpul. “Kita memang abadi, tapi jantung kita masih berdetak. Tusuklah hingga berhenti, atau penggal kepalanya. Selain dua hal itu, kita nggak bisa mati.”
Mata Anita membelalak. Abadi, kata itu terasa asing, menakutkan sekaligus menggoda. Ia mengangguk, mencoba mencerna kenyataan barunya.
Willie melanjutkan dengan suara tegas.
“Malam ini, William bakal milih korban pertama. Tugas kalian mudah. Gigit, hisap darah mereka sampai habis. Biarkan mereka mati, lalu tunggu kebangkitan mereka dari kuburnya.”
Di balik pintu dapur, William berdiri membeku. Ia mendengarkan setiap kata saudaranya dengan gelisah, wajahnya muram. Beberapa kali ia menggeleng pelan, menahan napas. Ia tahu pasti, cerita itu hanyalah dongeng. Tidak ada bukti yang mendukung dongeng tentang anak aneh dan evolusi.
Yang pasti hanyalah, Willie menyimpan dendam. Dendam karena manusia telah membantai orang tua mereka.
Willie tidak ingin membangkitkan Vrykolakas. Ia ingin membalas dendam.
William mengepalkan tangan. Ia ingin sekali berteriak, mengungkapkan kebenaran. Tapi ia tahu, Willie bukan orang yang bisa dihadapi begitu saja. Kakaknya licik, kejam dan tak segan menyiksa.
Rasa takut menggerogoti nyalinya. Maka diam-diam ia kembali ke kamarnya. Di sana, ia sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah rencana yang belum waktunya diumumkan.
Sementara itu, Willie masih mengatur strategi dihadapan pasukannya.
“Ifal, kamu pergi sama Fernando ke sekolah. Anita, kamu sama Abdul dan Anggara menyusuri pemukiman. Setelah semua siap, William akan memandu kalian menemukan korban.”
Semua mengangguk patuh, lalu beranjak meninggalkan meja makan.
Dalam diam, Ifal dan Anita berjalan menyusuri lorong gelap menuju kamar mereka yang bergaya Indische Empire tua. Suasana sunyi, hanya langkah kaki yang terdengar menjejak lantai keramik.
“Anita, Aku boleh tanya?” Ifal memecah hening. “Kamu percaya semua yang dibilang Willie?”
Anita menjawab tanpa menoleh. “Aku nggak peduli.”
Ifal mengernyit. “Maksud kamu?”
Anita berhenti, menoleh perlahan. Wajahnya dingin.
“Dengar ya Ifal. Kita udah mati. Kita nggak bisa hidup kayak manusia lagi. Jadi, apa pun tujuan Willie, itu lebih masuk akal dibanding hidup tanpa arah.”
“Tapi gimana kalau orang-orang terdekat kamu ikut berubah? Orang tua kamu, teman-teman kamu, semuanya?”
“Justru, aku berharap mereka bisa berubah seperti aku” jawabnya singkat, matanya menerawang. “Biar kita bisa hidup bareng selamanya, dalam keabadian.”
Ifal terdiam. Ada kecewa yang mencuat di dadanya. Anita yang sekarang bukanlah yang dulu. Matanya tajam, hatinya seperti menghilang. Iming-iming keabadian telah menggoda dirinya.
Langit menggantung muram, awan hitam menutupi bulan. Di balik semak-semak yang tumbuh liar, Askara dan Adit berjongkok, matanya terpaku ke arah tanah kubur yang tak jauh dari posisinya. Di sebelahnya, seorang polisi berseragam lengkap mengusap tengkuknya yang berkeringat, gelisah.
“Askara, ingat, jangan main-main dengan saya.” gumam polisi itu seraya menyipitkan mata. “Ajakan kamu ini, bikin saya ngerasa jadi orang gila. Saya masih nggak percaya ada orang mati bisa hidup lagi?”
Askara hanya menoleh sekilas, wajahnya serius dan penuh keyakinan.
“Tolong percaya, Pak. Saya nggak main-main. Saya tahu ini gila, tapi kita bakalan lihat sendiri nanti.”
Polisi itu mengangguk setengah hati. Kemudian, hening kembali menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang menemani.
Pandangan mereka kini terfokus pada satu titik, makam Fitri. Tumpukan bunga layu dan nisan berdebu menjadi saksi bisu dari gadis yang telah tiada. Tapi bagi Askara, makam itu bukan akhir. Ia adalah kunci. Jika benar seseorang membongkar kuburan itu dan Fitri hidup kembali, maka semua teori gilanya akan terbukti, bahwa penghisap darah bukan cuma nyamuk.
Vrykolakas.
Makhluk yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang, akan muncul ke permukaan.
Setiap menit yang berlalu terasa seperti seumur hidup. Di kepala Askara, suara tawa Fitri, yang seharusnya sudah mati, terus terngiang. Apakah dia gila? Atau apakah semua orang lain yang buta?
Mereka harus muncul. Malam ini. Kalau nggak, semua orang bakal menganggap aku gila. Fitri, buktiin aku nggak salah. Tunjukin kalau kamu memang bakal hidup lagi. Aku butuh kamu… Pikir Askara dengan keringat dingin yang mulai mengguyur lehernya.
Sebenarnya sore tadi, Askara sempat meminta izin kepada orang tua Ifal dan Anita untuk membongkar kuburan mereka, tapi ia ditertawakan, dianggap sudah kehilangan akal sehat. Maka, harapan satu-satunya kini hanya pada makam Fitri.
Waktu terus bergulir.
Menit-menit berjalan seperti silet yang mengiris perlahan. Jam dinding digital di tangan polisi menunjukkan pukul sepuluh lebih lima belas. Tak ada satu pun pergerakan. Tanah tetap hening. Bayangan nisan bergoyang diterpa angin, tapi tak ada galian, tak ada tangan yang menjulur dari bawah tanah.
Pak Dayat mulai tak sabaran. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir seperti menahan amarah yang siap meledak. Dia menatap langit, lalu Askara disampingnya. Untuk sesaat, dia merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Ini bukan hanya perasaan, kan? bisiknya pelan. Tapi dia tak ingin Askara mendengarnya.
“Kamu yakin ini bukan cuma halusinasi anak muda yang kurang kerjaan?” gumamnya, akhirnya.
Askara diam. Keringat membanjiri pelipisnya. Ia tidak tahu lagi harus menanggapi seperti apa. Memaksanya percaya, berharap atau mungkin menyerah. Tapi jauh di dalam dadanya, ia menolak menganggap Fitri telah benar-benar pergi.
Dia harus percaya. Harus.
Karena jika malam ini tidak terjadi apa-apa, maka mungkin, dialah yang perlahan-lahan akan kehilangan kewarasan.
Adit menatap sahabatnya yang tampak semakin gelisah. Ia bisa menebak apa yang sedang bergolak di benaknya. Tapi lidahnya kelu, setiap kali ia mencoba bicara, niat baiknya sering disalahartikan. Jadi ia memilih diam, membiarkan hening yang bicara, lalu mengalihkan pandangannya ke arah deretan kuburan yang diselimuti senja.
Kabut turun makin tebal. Angin menggoyangkan dedaunan. Suara jangkrik pun berhenti, seolah alam pun ikut menahan napas. Tidak ada suara manusia, hanya degup jantung mereka masing-masing yang makin keras di kepala.
Sementara itu, di kediaman Willie, pukul sebelas malam.
Rumah tua itu sunyi, tapi tak pernah benar-benar damai. Di lantai dua, langkah kaki Willie terdengar pelan namun berat, seperti menahan murka yang terus membara di dalam dadanya. Ia berhenti di depan sebuah pintu kayu, kamar William.
Tanpa mengetuk, Willie mendorong pintunya perlahan. Cahaya temaram dari lampu meja menerangi sebagian ruangan. William terlihat meringkuk di atas ranjang, membelakangi pintu. Selimut tebal menutupi hampir seluruh tubuhnya, seolah dunia luar adalah mimpi buruk yang ingin ia hindari.
Willie berdiri tegak di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada. Suara dinginnya menembus keheningan.
“William. Bersiaplah. Kita mulai rencana kita malam ini.”
William sejenak tak menanggapi. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara pelan dari balik selimut.
“Kamu bohong ke mereka, kan?” katanya lirih. “Semua yang kamu bilang itu, cuma dongeng.”
Willie menghela napas, matanya menyipit.
“Nggak semua. Ada bagian yang benar.” jawabnya santai. “Lagipula, kalau mereka tahu yang sebenarnya, mana mungkin mereka mau bantu kita balas dendam ke manusia?”
William perlahan bangkit, duduk di tepi ranjang. Rambutnya berantakan, wajahnya sayu.
“Tapi itu nggak benar, Willie. Itu malah bikin semuanya tambah kacau, sama aja kayak masa lalu. Vrykolakas sama manusia bakalan perang lagi. Kenapa susah banget buat kamu ngerti?”
Willie melangkah masuk, tatapannya tajam.
“Justru aku ngerti. Yang nggak ngerti itu kamu, Wil. Kamu terlalu naif. Terlalu lemah.” gumamnya, menahan emosi. “Ayah sama ibu mati karena kamu! Mereka nyoba lindungin kamu, padahal kamu yang nggak mau ngikutin apa yang mereka perintahin.”
William menunduk.
Bayangan malam mengerikan itu melintas kembali, saat ayah dan ibunya dihujani pasak dan dibakar oleh manusia, tepat di depan matanya. Mereka coba bertahan hidup dengan menghisap darah musuhnya, tapi William, William terus menolak.
Ia tidak mau membunuh siapapun malam itu. Dan keputusan itu jadi akhir dari keluarganya.
Willie menatap adiknya dalam-dalam. Suaranya makin dingin, seperti es yang menggores kulit.
“Sekarang tebus kesalahan kamu. Jangan bikin masalah malam ini. Kalau kamu coba-coba mengacau.”
Dia mendekat, menunduk ke wajah adiknya.
“Aku nggak bakal mikir dua kali buat menghabisi kamu. Saudara kembar kek, adik kandung kek, sama aja. Nggak ada ampun.”
Mata William membesar.
Dadanya sesak, antara marah, takut dan sedih bercampur jadi satu. Ia tahu, kakaknya sudah bukan Willie yang dulu. Sekarang, yang berdiri di depannya adalah monster yang dilahirkan oleh dendam.
Tepat tengah malam.
Langit kelam menggantung tanpa bintang. Di luar rumah bergaya Indische Empire yang kini menjadi markas kegelapan, enam sosok berdiri mematung dalam bayangan, Vrykolakas, makhluk-makhluk haus darah, bersiap meneror malam.
Willie melangkah ke teras depan, matanya menyapu sekeliling.
“Alfred, mana William? Kok belum kumpul?” gumamnya, nada gusar mulai terdengar.
Alfred, pelayan tua yang setia namun kini ikut dalam kegelapan, menunduk cepat.
“Maaf, Tuan. Saya tidak tahu, Saya cek dulu ke kamarnya.”
Tanpa buang waktu, Alfred menaiki tangga dan masuk ke kamar William. Ruangan itu kosong. Sepi. Ia mengecek setiap sudut, lemari, kolong tempat tidur, kamar mandi. Tak ada jejak William. Tapi ada satu hal yang membuat langkah Alfred terhenti.
Pintu belakang rumah, terbuka. Padahal ia yakin tadi sudah menguncinya.
Matanya menyipit.
“Jangan-jangan dia kabur.” bisiknya.
Alfred segera kembali melapor. Di halaman, Willie tampak semakin tidak sabar.
“Gimana?” tanyanya cepat.
“William tidak ada, Tuan. Pintu belakang terbuka. Sepertinya dia pergi lewat sana.”
Willie mendengus keras, rahangnya mengeras.
“Dia kabur?!” bentaknya, nada marahnya menggema malam itu.
Alfred menunduk dalam. “Mau saya cari lagi, Tuan?”
Willie melambaikan tangan kasar. “Nggak usah. Kalau dia milih pergi, biarin. Kita lanjut aja.”
Ia berbalik menghadap pasukan Vrykolakas yang sudah berdiri menunggu perintah. Tatapan mereka kosong, tapi haus. Hanya Anita yang tampak gelisah, tatapannya masih menyapu sekitar, mencari bayangan seseorang yang tak muncul juga.
Willie menarik napas dalam.
“William kabur. Jadi ada sedikit perubahan rencana.”
Mata Anita membesar, tubuhnya seketika melemas. William kabur? Ia menatap Willie, seakan menunggu penjelasan lebih, atau alasan. Perasaan yang ia simpan rapat-rapat untuk William tiba-tiba jadi bara dalam dadanya. Haruskah dia mencarinya?
Willie melanjutkan, suaranya datar, dingin, tegas.
“Karena dia nggak ikut, kalian sekarang cuma bisa ngandelin keberuntungan. Kalian tahu sendiri, nggak semua manusia bisa langsung berubah. Tergantung darahnya, fragmen Vrykolakas mereka.”
Ia menatap satu per satu wajah mereka.
“Jadi, berpencarlah. Serang siapa pun yang kalian temui. Tapi ingat, jangan sampai bikin keributan. Kita masih butuh waktu.”
Pasukan mengangguk serempak, patuh seperti boneka yang digerakkan kehendak tuannya.
“Mungkin perlu dua atau tiga kali hisap buat jadikan mereka Vrykolakas, tandai target kalian. Tapi, salah satu dari kalian mungkin punya kemampuan istimewa. Bisa langsung ngebunuh atau bikin mereka berubah seketika. Kalau kalian punya kekuatan itu, ya sudah, habisin aja sebanyak-banyaknya.”
Willie berjalan maju, menatap tajam ke kejauhan.
“Semakin banyak pasukan, makin cepat dunia ini tunduk pada kita.”
Ia berhenti. Satu kalimat terakhir keluar dari mulutnya, pelan, tapi mengiris seperti sembilu.
“Dan kalau kalian ketemu William, kasih dia pelajaran. Kalau dia melawan, bunuh saja.”
Langkah Anita terhenti. Jantungnya berdegup lebih kencang. Kata-kata itu memukulnya lebih keras dari yang ia kira. Membunuh William? Orang yang justru jadi alasan ia masih bertahan di sisi Willie.
Tatapan matanya goyah. Tapi ia diam. Di dalam hatinya, tekad baru mulai tumbuh. Kalau Willie ingin memburu William, maka dia harus mencarinya lebih dulu darinya.
Sementara itu, Willie berdiri tegak di depan pasukannya. Sorot matanya tajam. Nadanya berat, penuh tekanan. Tak ada yang berani bersuara. Malam itu, Willie benar-benar menunjukkan siapa dirinya.
Seorang pemimpin tanpa belas kasihan.


 risyadfarizi
risyadfarizi