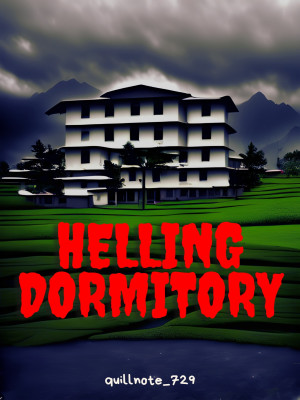Cahaya bulan pucat menggantung di langit, menyinari bukit yang dekat dengan pemakaman yang sepi. Kabut tipis merayap di antara pepohonan, menutupi tanah basah oleh embun.
Askara berdiri di tengah lingkaran yang membuat dadanya sesak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, panik. Bayangan-bayangan gelap semakin mendekat, diam, tapi mengancam. Mereka adalah Vrykolakas, para penghisap darah. Mata mereka merah menyala, napas mereka berat dan menggeram. Mereka lapar.
Dan di antara mereka, ada Anita.
Ia berdiri tegak, rambut yang dikuncir dua berantakan, wajahnya pucat tertimpa sinar bulan. Askara sudah tidak bisa melihat sisa-sisa sosok sahabatnya di sana. Hampir hilang.
“Itu bukan Anita.” batinnya bergemuruh, dia berusaha berkelit. “Itu bukan Anita.” Kalimat itu terus diulangnya seperti mantra.
Keringat membasahi pelipisnya, menetes dari dagunya hingga ke tanah, diiringi detak jantung yang menabuh seperti gendang. Gemetar.
Tak ada celah. Tak ada harapan.
“Biarkan aku pergi!” teriaknya, namun suaranya memantul kembali ke dalam dirinya, hampa. Kata-katanya tak memiliki kekuatan, membeku oleh rasa takut.
Dari balik kabut, Willie muncul.
Langkahnya pelan namun menekan, kepalan tangannya berlumur darah akibat pukulan yang dia lakukan pada William. Tatapannya membakar diiringi senyumnya yang bengis.
“Menyerahlah, Askara.” bisiknya, nada suaranya mendesis. “Serahkan jiwamu dan jadilah bagian dari kami, Vrykolakas.”
Para Vrykolakas yang mengepung Askara, sudah siap menerjang. Tapi Willie melambaikan satu tangan ke udara, gerakan kecil tapi cukup untuk membuat para Vrykolakas berhenti. Mereka menggeram pelan, menahan diri seperti anjing liar yang menunggu aba-aba dari pemimpinnya.
“Belum sekarang.” bisik Willie ke mereka, lalu tatapannya kembali pada Askara. “Aku ingin dia menyerah, dengan kehendaknya sendiri. Itu lebih bagus.”
“Nggak!” Raung Askara, suaranya terdengar seperti jeritan. “Aku nggak akan nyerah, aku nggak akan jadi monster.”
Willie menyeringai lebar, menampakkan taring-taring tajamnya. “Kalau begitu, apa boleh buat. Pasukanku siksa dia dan hisap darahnya sampai habis.” Tangan Willie terulur ke depan, memberi perintah kepada mereka.
Askara mendekap Fitri erat dengan tatapan khawatir. Tubuh gadis itu masih lemas, napasnya terputus-putus. Ia menoleh ke belakang hendak mencari celah, namun harapannya lenyap. Dua Vrykolakas telah berdiri di sana. Mata mereka memantulkan cahaya bulan, penuh nafsu hendak memangsa.
Pandangannya diedarkan ke sekelilingnya, hutan bambu, tanah basah, kuburan, hanya itu yang bisa dia lihat. Tidak ada jalan keluar.
Saat tubuh Fitri masih dipeluknya dan para monster mendekat, Askara menatap bulan di atas. Pucat. Jauh. Tapi, tetap bersinar.
Ia menarik napas panjang. Dalam detik itu, bayangan Fitri tersenyum menari dalam benaknya, saat mereka tertawa bersama, berjalan pulang dari sekolah, saat Fitri bercanda dengannya.
“Kalau aku mati malam ini, biar aku mati untuk sesuatu yang berarti.”
“Nggak ada jalan lain.” desisnya lirih, lalu menatap ke depan. “Aku bakal lawan kalian.”
Dengan hati-hati, ia membaringkan Fitri di tanah. Tangannya gemetar, namun wajahnya teguh. Dia berdiri. Menegakkan tubuh dengan tatapan tajam lurus kedepan. Kaki terbuka selebar bahu, tangan mengepal, napas mulai diselaraskan. Lalu ia melompat-lompat kecil, dia telah siap dengan kuda-kudanya.
“Maju kalian, para monster! Aku nggak takut!”
Seorang Vrykolakas bernama Anggara menerjang pertama. Mulutnya terbuka lebar, menampakkan taring yang gemetar karena gairah memangsa. Tinju kanan, mengarah ke pelipis Askara, disusul tinju kiri, memburu rahang. Tapi Askara menghindar. Gerakannya ringan namun lincah. menghindari ke kanan dan ke kiri.
SAT, SET.
Lalu dia bergeser ke samping perlahan, kemudian,
BUG!
Tendangan tinggi kaki kanannya menghantam telinga Anggara. Sosok itu terhuyung merasakan telinganya yang berdengung, kemudian dia mundur ke belakang dengan menahan rasa sakit.
Vrykolakas lain berlari ke arah Askara dengan brutal. Tendangan lutut diarahkan ke dada Askara, namun dia berhasil menahannya dengan dua telapak tangan. Dia mundur, satu, dua langkah, untuk menepis serangan bertubi-tubi yang datang seperti ombak.
Lalu, secepat kilat, Askara memutar tubuh dan,
BUG!
Tendangan ke ulu hati membuat lawannya terpelanting. Suara erangan mengisi udara.
Willie menyipitkan mata, kagum sekaligus marah. “Apa-apaan dia.”
Anita yang berniat menyerang Askara, tiba-tiba berhenti dan menahan napas. “Gerakan itu, .” Teringat akan sesuatu. Dia terdiam mematung.
Lawan ketiga melangkah maju. Posturnya lebih tegap dan gaya bertarungnya seperti seorang petinju. Ia mendekat, mencoba menyerang. Askara mengayunkan tangannya yang terkepal lebih dulu, tapi meleset, lawan itu menunduk cepat, lalu dia muncul dan memegang kepala Askara untuk mengunci, setelah itu dia menghujamkan lututnya ke muka Askara bertubi-tubi.
DUG! DUG! DUG!
Askara terhuyung. Napasnya tercekat, mukanya luka dan terasa nyeri, nyeri yang hebat. Ada sedikit perasaan yang berbisik padanya untuk menyerah.
Apa gunanya melawan? Aku udah kalah. Bisiknya dalam hati. Mereka lebih kuat. Aku sendirian. Aku,
Tapi suara lain muncul. Lembut, seperti suara Fitri di benaknya. Kamu nggak sendirian. Kamu pernah bertekad buat lindungi aku, ingat?
Seolah tersadar, di detik itu, dengan sisa tenaga, Askara mengayunkan kaki kanan dan kirinya mengarah ke tulang kering lawannya.
BUG! BUG! BUG!
Lawan itu meringis, kesakitan, dia memundurkan tubuhnya beberapa langkah. Saat itulah Askara kembali memutar tubuhnya dan,
BUG!
Tendangan samping memutarnya tepat mengenai sisi kepala Vrykolakas. Membuatnya terjatuh dan spontan memegangi kepala yang terasa pusing akibat rasa sakit yang teramat.
Mata Willie membelalak. “Itu, gerakan Taekwondo.” desisnya.
Anita yang tak jauh disampingnya bergumam. “Kapan dia belajar itu? Jangan-jangan.” Suaranya gemetar, niat untuk menyerang Askara seketika lenyap. Dia mengenal setiap gerakan-gerakan yang dilakukan olehnya. Dulu, hanya satu orang yang bisa melakukannya dengan sempurna, Ifal.
Askara berdiri tegak. Napasnya berat, tapi matanya tajam menatap tiga orang yang kini terguncang dan kesakitan. Dalam hati, ia bersyukur karena sejak SMP sampai SMA, ia sering berlatih Taekwondo secara sembunyi-sembunyi bersama Ifal, sahabatnya. Bukan untuk bertanding, bukan untuk pamer. Tapi karena dalam hatinya, ia yakin, suatu hari nanti bela diri akan menyelamatkannya. Tibalah hari dimana itu terjadi.
Ia mengingat lagi satu persatu gerakan yang telah dipelajari. Ia melompat kecil, mendekat ke salah satu Vrykolakas, Anggara, lalu mengayunkan tendangan beruntun ke pahanya secara bergantian, kanan dan kiri.
DUP! DUP! DUP!
Anggara menjerit pelan, langkahnya mundur. Saat tubuhnya membungkuk karena rasa sakit, Askara tidak menyia-nyiakan peluang.
Kaki kanan Askara naik tinggi, lalu dihujamkannya hingga menghantam tepat di belakang kepala Anggara.
PRAK!
Tendangan terakhir yang menghantam keras membuat suara tulang retak memenuhi udara. Anggara tumbang. Tak sadarkan diri.
Tapi perlawanan belum usai.
Dua Vrykolakas yang lainnya menyergap bersamaan. Satu menghantam kaki kiri dan kanan Askara hingga dia terhuyung, lalu yang lainnya melakukan tinju yang mengarah ke kepalanya dari kanan dan kiri.
BUG! BUG!
Kepala Askara terkulai. Kedua lawan yang ada di hadapannya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mereka menendang tubuh askara dengan tendangan telapak kaki yang kuat, menghantam tubuhnya seperti palu godam. Askara terlempar, lalu jatuh membentur tanah.
Ia menatap Vrykolakas di depannya. Diatas mereka terlihat bulan purnama, pucat, tapi tetap bersinar. Dan di sinarnya, ia menemukan tekad yang tersisa.
Aku nggak bakal jadi monster, gumamnya. Aku bakal tetap jadi manusia, sampai akhir.
Gelap mulai mengisi pandangannya. Seluruh tubuhnya nyeri, dari mulai kepala, wajah dan tubuhnya. Semuanya terasa menyakitkan. Rasa itu seperti dipukuli oleh besi panas berkali-kali. Dia bahkan tak bisa berdiri dibuatnya.
Willie berjalan mendekat sambil terkekeh puas.
“Sudah berakhir, Askara.”
Kemudian Willie mengalihkan pandangannya pada Anita yang sedari tadi masih mematung memperhatikan pertarungan tiga lawan satu. Dia memberi isyarat. “Anita. Giliranmu, hisap darahnya!”
Anita terdiam. Butuh waktu beberapa detik baginya untuk mencerna perintah itu. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena hatinya terpecah.
Satu sisi dipenuhi amarah karena Askara pernah menolaknya. Tapi sisi lain masih menyimpan rasa peduli yang belum padam.
Perasaannya tarik-menarik, membuat setiap langkah terasa berat. Tapi suara Willie memecah kebisuannya.
“Cepat!”
Suara dingin itu membangunkannya dari keraguan. Anita akhirnya mendekat. Tangannya meraih wajah Askara yang lemas, menengadahkannya perlahan hingga mata mereka bertemu. Tatapan Anita menyimpan luka dan kehampaan.
“Ra, saat kamu bangkit nanti, jadilah milikku. Kita akan selalu bersama.” bisiknya.
Mulutnya terbuka, taring mulai terlihat. Ia mendekat ke leher Askara.
Namun tiba-tiba terdengar bisikan samar di udara, seperti desahan ribuan suara yang berlapis dan tak terlihat sumbernya. Para Vrykolakas langsung mendongak, gelisah. Willie menyipitkan mata, menyadari ada sesuatu yang bergerak di malam itu, sesuatu yang tak seharusnya datang.
“Cepat selesaikan!” hardiknya. Tapi sebelum Anita bisa menggigit Askara, cahaya senter menembus kabut, langkah kaki bergemuruh, disusul teriakan nyaring!
“Hei! Kalian ngapain di sana?!”
Suara itu, ayah Fitri, bersama warga desa yang membawa senter. Cahaya menyinari para Vrykolakas yang langsung panik.
Willie berteriak. “Cepat kabuuur!”
Mereka langsung lari ke arah hutan bambu, terbirit-birit. Menghilang dalam sekejap. William pun ikut diseret. Askara dan Fitri dibiarkan tergeletak.
Ayah Fitri segera menghampiri anaknya yang masih bernapas meski lemah. “Fitri!” serunya panik.
“Cepat, panggil ambulans!” teriaknya. Salah satu warga menelepon, lainnya mengejar ke arah hutan.
Askara mulai sadar. Pandangannya kabur, tapi ia melihat Fitri, selamat.
“Syukurlah.” bisiknya.
Seorang warga membantunya berdiri dan membawanya ke tandu.
Namun Askara menahan mereka. “Tunggu, di bawah sana, ada kuburan, kuburan Ifal, dibongkar.” katanya lemah, menunjuk ke arah pemakaman.
Warga melihat ke arah yang dimaksud, tapi semua kuburan terlihat utuh.
“Nggak ada kok.” ujar mereka.
Askara menggeleng pelan. “Nggak mungkin, aku lihat sendiri.”
“Hus, jangan ngayal. kamu aman kok sekarang. Luka kamu banyak, mungkin kamu ngelantur.” ucap salah satu warga.
Askara ingin membantah, tapi tubuhnya terlalu sakit. Ia pun dibawa masuk ke ambulans.
Di tengah rasa sakit itu, satu hal tetap jelas dalam pikirannya, semua yang ia lihat malam ini nyata. Kuburan Ifal memang terbongkar. Ia bangkit, sama seperti Anita waktu itu.
Hatinya tahu, ini bukan sekadar mimpi buruk. Para Vrykolakas telah mengusik ketenangannya. Dan ini bukan lagi soal kebenaran, melainkan perjuangan untuk bertahan hidup.
Rumah Sakit, Kamar Perawatan nomor 203 – Pagi harinya.
Cahaya matahari pagi menyelinap lewat celah tirai kamar rumah sakit, menciptakan garis-garis terang di lantai. Bau antiseptik menyengat di udara, aroma yang selalu membuat Askara merasa tidak nyaman.
Ia terbaring lemah di ranjang, tubuhnya nyaris tak bergerak. Selang infus menempel di tangannya, pelipisnya dibalut perban. Keringat dingin mengalir di dahi, rambutnya berantakan. Perlahan, kelopak matanya bergerak. Ia membuka mata, menatap langit-langit yang asing dan terlalu terang, terlalu nyata setelah malam yang mengerikan.
Di sudut ruangan, kedua orang tuanya duduk berdekatan di sofa kecil. Sang ibu menggenggam tangan ayahnya, mencoba menahan cemas. Sang ayah berusaha menenangkan, meski wajahnya juga tegang.
“Mah, Pah.” suara lirih Askara terdengar. Serak, lemah.
Orang tuanya langsung menoleh. Sang ibu bergegas mendekat, matanya berkaca-kaca. Ia menyentuh wajah Askara dengan tangan gemetar.
“Syukurlah, kamu sadar.” isaknya.
Sang ayah ikut mendekat, suaranya bergetar. “Nak, kamu baik-baik aja kan?”
“Iya” Jawab Askara pelan, kemudian mengalihkan pandangan ke ibunya.
“Fitri, gimana?”
“Ia aman.” jawab sang ibu cepat. “Masih dirawat di rumah sakit ini, tapi belum sadar.”
Askara terdiam. Ingatannya tentang semalam kembali muncul, sosok menyeramkan, darah, jeritan. Napasnya berat. Lalu ia bertanya dengan suara datar. “Mah, Pah, kalian percaya nggak kalau orang mati bisa hidup lagi?”
Mereka saling pandang, bingung dan khawatir.
“Apa maksudmu, Sayang?” tanya ibunya pelan.
“Kalau aku bilang, Anita dan Ifal hidup lagi, kalian percaya?”
Ayahnya tertawa getir, gugup. “Kamu bilang apa sih, masih ngelindur, ya?”
Askara tak menjawab. Ia tahu mereka tak akan percaya. Satu-satunya harapannya adalah Fitri, jika dia bangun dan bicara, semua akan berubah.
Sang ibu membelai rambut Askara. “Istirahat dulu, ya.”
Askara memejamkan mata. Sunyi menyelimuti ruangan, hanya suara jam yang terdengar.
Kamar lain – Ruang perawatan nomor 204
Langit mendung di luar, cahaya kelabu masuk ke ruangan. Fitri terbaring diam di ranjang yang dikelilingi tirai sekat berwarna oranye. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Di sampingnya, kedua orang tuanya berdiri penuh kecemasan. Sang ibu menggenggam tangannya erat, berharap kehangatan kembali. Sang ayah diam, rahangnya mengeras.
Seorang dokter masuk bersama suster, lalu menoleh. “Kami perlu memeriksa kondisinya. Bisa beri kami waktu sebentar?”
Orang tua Fitri keluar dari balik tirai dan tiraipun di tutup. Beberapa menit kemudian, dokter membukanya.
“Bagaimana, Dok?” tanya ayah Fitri saat menghampiri sang dokter, nada suaranya cemas.
“Kondisinya masih kritis.” jawab dokter serius. “Kami melakukan transfusi darah karena ada yang aneh.”
“Aneh gimana?”
“Darah yang hilang sangat banyak untuk satu malam. Dan, kami menemukan luka gigitan di lehernya. Mirip bekas gigitan ular.”
Sang ayah terpaku. “Gigitan?”
Dokter mengangguk. “Kami akan uji darahnya di lab. Kalau ada racun, kami mungkin akan tahu apa penyebabnya. Tapi kalau tidak, kami harus cari kemungkinan lain. Apa kalian tahu apa yang terjadi sebelum dia dibawa kemari?”
Ayah Fitri menjawab pelan. “Kami nggak tahu Dok, Kami nemuin dia di pemakaman kemarin malam. Sama temannya, Askara. Tapi kayaknya, Askara belum bisa ditanyai.”
Dokter mengangguk. “Baik. Kalau begitu, kami akan terus pantau.”
Dokter berpamitan dan keluar ruangan. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Kedua orang tua Fitri duduk menatap putrinya yang masih tak bergerak, hati mereka penuh pertanyaan dan ketakutan yang belum mereka pahami.
Rumah sakit, pukul tiga sore.
Langit mendung menggantung di balik jendela kaca hampir menurunkan air hujan. Askara masih terbaring, setengah duduk di ranjang, dikelilingi kabel infus.
Cahaya biru dari layar ponselnya menyinari wajahnya yang pucat, tatapan matanya tertuju pada gim yang sedang dimainkan, walaupun terlihat ‘sibuk’, tapi pikiran dan jiwanya terus melayang kepada Fitri dan malam kemarin yang mencekam.
Pintu terbuka mendadak.
Adit muncul di ambang, napasnya ngos-ngosan, rambutnya berantakan dan seragam sekolahnya kusut, ia berlari tergesa-gesa.
“Ra! Maaf aku baru datang, baru pulang sekolah.” ucapnya sambil mengatur napas. “Kamu nggak apa-apa, kan?” tanyanya penuh kecemasan.
Askara tak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk menatap gim di layar ponsel. Suaranya datar saat menjawab.
“Aku baik-baik aja. Yang harus kamu khawatirin itu, Fitri.”
Seketika tubuh Adit menegang. “Hah? Fitri? Emang kenapa dia?” suaranya tercekat dan tangan yang masih memegang tasnya mulai gemetar.
Askara mematikan gim dan meletakkan ponsel di samping tubuhnya. Ia menatap langit-langit, seperti mencari jawaban di antara pola-pola tak beraturan.
“Dia belum siuman. Sejak semalam. Dia dirawat di sini.” Hening sejenak. “Terakhir yang aku dengar, kondisinya belum membaik.”
Adit menelan ludah. Matanya melebar. “Emangnya kalian ngapain kemarin malam?”
Askara menarik napas dalam. “Kita ngintai kuburan, Dit.” Ia menoleh perlahan ke arah Adit.
“Hah, Terus.” Ucap Adit, suaranya mengecil, seperti luka yang belum mengering.
“Mungkin kedengarannya gila. Tapi kamu harus percaya.”
“Emang apaan?” Adit mengerutkan kening, tidak sabar.
“Anita sama Ifal, mereka hidup lagi.”
Adit tercekat kaget, tubuhnya berguncang. Wajahnya menegang dan rahangnya mengeras.
“Hah, masa sih?”
“Iya. Tapi yang lebih parah, Anita berubah. Jadi, monster. Ifal, aku nggak tahu, dia ngilang setelah itu.”
“Gila Ra” desisnya. “Jangan bercanda ah, ngomong jangan ngelantur.”
“Kan tadi aku udah bilang, kamu harus percaya! Soalnya itu yang aku sama Fitri alamin. Setelah itu kami diserang sama mereka, sampe babak belur kayak gini.”
Belum sempat Adit menjawab, pintu kamar terbuka lagi. Askara dan Adit seketika menoleh ke arah sumber suara.
Kali ini, seorang polisi masuk. Seragamnya rapi, langkahnya mantap, namun sorot matanya tajam. Topinya ia lepas dan diselipkan ke pinggang, lalu berdiri beberapa meter dari ranjang Askara.
“Halo, Askara kan?” sapanya singkat.
“Iya.” Askara refleks menjawab dan menegakkan tubuh, wajahnya memucat. Adit ikut berdiri di samping ranjang, gelisah, seakan memperlihatkan keheranannya. Ada apa?
“Tidak perlu panik.” lanjut polisi. “Perkenalkan, saya BRIPTU Dayat, panggil saja pak Dayat, saya kesini hanya ingin dengar cerita kamu soal kejadian semalam. Kamu masih ingat kan?”
Askara mengangguk. Nafasnya menjadi berat. Tangannya diam-diam meremas selimut, mencoba menenangkan diri. Di benaknya, kalimat-kalimat berseliweran, ia berusaha merangkai kata yang masuk akal, terdengar logis dan tidak seperti khayalan. Ia teringat reaksi Adit tadi, sinis, tak percaya.
Bagaimana jika polisi yang ada di hadapannya juga berpikir begitu? Beberapa detik sunyi menyelimuti ruangan. Hingga akhirnya, dengan napas pelan, Askara membuka suara.
“Kemarin malam, aku diserang orang jahat, Pak.”
“Lalu?”
“Mereka mukulin aku. Parah. Tapi kabur waktu ada warga datang.”
Polisi mengangguk pelan. “Itu saja?”
Askara menoleh ke Adit, mencari keberanian, tapi Adit hanya membalas dengan anggukan bahu. Dia tidak ingin terlibat dalam cerita Askara. Tak ada bantuan di sana. Seolah Adit menyuruhnya untuk hadapi sendiri.
“Nggak, Pak.” suaranya terdengar berat. “Sebelum mereka kabur. Mereka menghisap darah teman saya pak, Fitri namanya.”
Kening sang polisi berkerut. Tapi tak ada tawa atau cemoohan. Ia justru mengulang dengan satu istilah, perlahan.
“Vampir?”
Askara membelalak, tidak menyangka reaksi polisi tidak menyangkalnya. Nada suaranya berubah antusias dan bersemangat
“Bukan itu sebutannya pak, mereka nyebut diri mereka, Vrykolakas. Mayat hidup yang hisap darah. Di antara mereka, ada Anita. Dan Ifal. Teman-temanku yang hidup lagi setelah mati. Bahkan salah satu dari mereka nyerang Fitri dan hisap darahnya. Sedangkan aku disiksa tiga Vrykolakas yang lain. Lalu se”
Tangan sang polisi terangkat, menghentikannya.
“Cukup, Askara. Sepertinya kamu masih butuh istirahat.”
“Tapi, Bapak nggak percaya ya?” suara Askara lirih, matanya bergetar, seperti anak kecil yang tak didengarkan.
Polisi itu hanya menatap dalam beberapa detik kemudian mulutnya berucap.
“Maaf, saya belum bisa menanggapi. Cerita kamu terdengar mengada-ada. Saya rasa lebih baik saya mendapatkan keterangan dari pihak lain terlebih dahulu, mulai dari warga yang terlibat, kemudian kamu dan mungkin terakhir Fitri. Setelah semua informasi terkumpul, barulah saya bisa menyimpulkan. Terima kasih.”
Pak Dayat membalik badan dan permisi untuk keluar. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara gesekan yang nyaring mengiris lantai. Askara menggigit bibir. Kepalanya tenggelam menatap selimut, tatapannya nanar, kehilangan arah.
Adit berdiri di samping Askara, terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Suasana hening, seolah waktu berhenti memberi ruang pada luka yang belum sempat diungkapkan.
Tiba-tiba, suara langkah tergesa terdengar dari lorong rumah sakit, diikuti teriakan panik dari perawat.
“Kondisi Fitri memburuk! Kejang-kejang, jantungnya melemah, nyawanya terancam!”
Seruan itu memecah keheningan seperti sirine. Askara dan Adit langsung menoleh. Tanpa pikir panjang, Adit menerobos polisi yang masih berdiri di depan pintu dan berlari keluar.
Askara hanya bisa terdiam di ranjang. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Jantungnya berdegup kencang, rasa cemas membuncah. Wajah Fitri yang pucat dan lemah terbayang jelas di benaknya.
Rasa bersalah pun menghantamnya. Ia menyesal telah mengajak Fitri ikut dalam penyelidikan berbahaya kemarin malam.
Di tempat lain, pukul enam sore.
Langit malam gelap, hujan deras mengguyur. Warna jingga senja berganti hitam pekat. Di dalam rumah tua bergaya kolonial Belanda, di balik dinding batu dan jendela berdebu, Willie perlahan membuka mata.
Ia berkedip pelan seperti predator yang baru bangun. Bangkit dari ranjang berkanopi, dengan seprei kusut dan selimut tebal berwarna abu. Lampu redup menggantung, menyinari ukiran kayu tua di dinding.
Sebagai Vrykolakas, Willie tertidur di siang hari dan bangun saat malam tiba.
“Alfred?” panggil Willie lirih. Tak ada pelayan di kamar.
Pintu terbuka. Seorang pria tua dengan rambut putih dan tubuh tegap berdiri di sana. “Iya, Tuan?”
Willie duduk di tepi ranjang. “Kita akan segera mulai rencananya beberapa malam lagi. Apa Ifal sudah dibawa?”
“Sudah, Tuan. Dia ada di ruang bawah tanah, kondisinya stabil.”
“Jejak kuburannya?”
“Sudah saya tutup. Tak ada yang curiga.”
“Bagus.” Willie melangkah ke depan cermin tinggi, tapi tak ada pantulan. Ia hanya tersenyum tipis.
Lalu, ia berbalik. “Oh iya, Bagaimana kondisi William?”
“Masih tak sadarkan diri karena luka parah. Anita menjaganya. Apakah Anda ingin”
“Tidak.” potong Willie cepat. “Aku nggak mau melihatnya, Aku ingin bertemu Ifal. Sekarang.”
Alfred mengangguk mantap, mempersilahkan Willie mengikutinya menuju pintu rahasia yang berada di dapur. Langkah kaki menggema di lantai berubin tua. Alfred berhenti di depan lemari piring, menekan tuas tersembunyi. Pintu rahasia terbuka, menyingkap jalan ke ruang bawah tanah.
Mereka menuruni tangga gelap, diterangi lampu dinding. Bau tanah dan karat menyengat. Botol-botol darah tersusun rapi di rak. Peralatan medis tua berdebu tampak di sudut ruangan.
Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan sempit. Seorang pemuda duduk di tengah, tubuhnya pucat dan gemetar. Lehernya dirantai ke tiang. Kain kafan lusuh menempel di tubuh, penuh tanah dan lumpur. Napasnya cepat, matanya masih terpejam.
“Selamat malam.” kata Willie.
Pemuda itu membuka mata. Begitu melihat wajah di depannya, ia terbelalak.
“William?”
Willie tertawa kecil. “Bukan. Aku Willie. Saudara kembarnya. Kita pernah bertemu, tapi mungkin kamu lupa.”
Alfred menambahkan. “Tuan sempat menghapus ingatannya.”
Willie tersenyum samar. “Oh, iya.”
Ifal mengalihkan pandangannya ke arah Alfred, menatap pria itu dengan sorot mata yang menyala oleh amarah dan ketakutan. “Kamu, kamu yang nyulik aku sore itu, kan?!” serunya, suaranya bergetar antara marah dan ngeri.
Alfred hanya mengangguk pelan namun sopan, dia tidak menjawab apapun.
“Lepaskan aku! Dasar orang-orang sinting!” teriak Ifal, meronta-ronta. Rantai di lehernya berbunyi nyaring, memantul di dinding. Dia memajukan tubuhnya untuk meraih kedua orang dihadapannya, namun terhenti oleh cekikan rantai yang melilit kuat.
Willie melipat tangan, menghembuskan napas berat perlahan. “Untuk apa kami ngelepasin kamu Ifal, kamu itu udah mati, orang-orang akan takut ngelihat kamu. Lebih baik kamu bersama kami disini. Jadi bagian dari kami.”
“Udah mati? Maksud kamu apa?”
“Hmm, aku harus jelasin lagi nih.” Dengus Willie kesal, karena dia sudah dua kali menjelaskan hal yang sama pada orang yang baru dihidupkan, sebelumnya ada Anita yang mengalami hal yang serupa, jadi penjelasan seperti ini membuatnya jengkel.
“Aku udah menggigitmu satu kali, kemudian besoknya pasukan Vryko, maksudku Vampire, menggigitmu lagi secara brutal sampai kamu terkapar dan mati. Kamu pasti nggak ingat kan?”
Ifal menggeleng kuat, tidak mengingat apapun yang diceritakan oleh orang yang selalu memiliki seringai senyum yang menakutkan.
“Lihat tubuhmu, pucat seperti orang mati, bahkan baju kamu adalah kafan kotor. Kamu bodoh kalau nggak sadar.”
Ifal seketika melihat ke bawah menyaksikan sebagian tubuhnya yang masih tertutup kain kafan, kemudian tangannya yang dia lihat seperti tidak memiliki warna coklat sama sekali. “Aku udah mati?” ucapnya parau.
“Iya, tapi jangan khawatir, kamu udah hidup lagi. Menjadi sosok yang bukan manusia, melainkan Vampire, si penghisap darah atau kami menyebutnya Vrykolakas.”
“Sial, nggak mungkin.”
“Mungkin lah, malah dalam hitungan, Lima, Empat, Tiga, Dua” Willie menghitung dengan wajahnya yang datar.
Ifal mengernyit.
“Kamu akan.”
“Aaaargh!!”
Tiba-tiba, jeritan terdengar. Tubuh Ifal membungkuk. Perutnya terasa nyeri seperti dikerat dari dalam. Ia menggeliat, tangan mencakar lantai, napasnya mendesah keras.
“Kenapa sama perutku?” jeritnya memecah keheningan.
“Sudah dimulai.” bisik Willie.
“A-apa yang terjadi, ?!” Ifal berusaha bangkit, namun tak mampu berdiri. “Apa ini?!”
“Kamu lapar.”
“Kalau gitu, kasih aku makanan!”
Willie menatap Alfred sekilas. “Bawa masuk.”
Alfred mengangguk dan berjalan ke lemari besi besar di sudut. Ia membuka kuncinya dan dari balik pintunya, menarik seorang gadis remaja. Tubuhnya lemas. Matanya tertutup kain, mulutnya disumpal. Ia menggeliat, tangannya terikat.
Pakaian seragam SMA-nya masih utuh, tapi kotor.
Ifal menoleh sekilas ke arah gadis remaja itu dan matanya langsung membelalak. Gadis itu adalah Siska, teman satu klub Taekwondo yang pernah ia kunjungi saat ulang tahunnya.
Seketika itu juga, Alfred melontarkan kalimat dingin yang kejam, seolah tanpa rasa bersalah sedikit pun.
“Aku menculiknya tadi siang. Dia gadis yang cocok untuk percobaan makan Ifal yang pertama. Walaupun mungkin tidak bisa bangkit karena dia tidak dipilih oleh William.” ujar Alfred.
Ifal yang mendengarnya kembali meronta dan meraung keras. Rasa nyeri di perutnya tak mampu menahan ledakan emosinya. Tatapannya berubah tajam, penuh dendam. Ia menatap Alfred dan Willie dengan kebencian membara, tak terima karena mereka telah menyeret temannya ke dalam kekacauan ini.
“Kalian, iblis!” serunya penuh amarah, suaranya bergetar tapi tegas.
Willie berlutut di depan Ifal. “Benarkah?” Willie terkekeh. “Kamu harus makan Ifal, biar bisa jadi Vrykolakas seutuhnya.” Tatapan tajam dan seringai jahat terlihat di wajah Willie. Dia tidak memberikan sedikitpun belas kasihan. “Makanlah, hisap darahnya!”
Ifal memandang dengan horor. “Apa? Nggak, dia temanku.”
“Kamu adalah Vrykolakas sekarang. Tanpa darah, kamu bakal membusuk.”
“Nggak!” jerit Ifal sekali lagi, menendang tiang, mengguncangkan rantai.
“Aku bukan monster!”
“Udah aku bilang, kamu udah mati. Kamu bukan manusia lagi. Tanyakan pada tubuhmu.” ujar Willie pelan.
Perut Ifal kembali dicengkram, dia kesakitan, dia berteriak, tubuhnya melengkung. Willie berdiri, mendesah panjang. Kepalanya menggeleng-geleng beberapa kali. “Hmm, Alfred, panggil Anita.”
Di lantai atas, di kamar William, Anita sedang duduk di kursi. Ia menggenggam tangan William yang lemah, membelai jari-jarinya pelan. Wajahnya kosong, tapi matanya menyimpan badai yang belum reda.
Anita menatap wajah William lekat-lekat. Sedikit demi sedikit luka-luka di wajahnya mulai memudar, bekas pukulan dari saudaranya perlahan menghilang.
“Cepat banget.” gumam Anita dalam hati, matanya membulat tak percaya.
“Apa ini kekuatan Vrykolakas?”
Ia terdiam, diliputi rasa takjub sekaligus ngeri.
Semakin cepat wajah itu pulih, semakin kuat pula keyakinan Anita, bahwa ada sesuatu dalam diri William yang tak pernah ia temukan pada seseorang yang namanya enggan ia sebut. Bukan karena lupa, tapi karena luka. Karena benci yang tumbuh dari cinta yang tak pernah berbalas.
Gurat wajah itu, lekukan hidung, garis rahang, bentuk alis dan tatapannya, menurutnya semua itu mirip dengan sosok yang pernah mengisi hidupnya.
Kenangan tentang ungkapan rasa dari William saat keadaan sedang genting kembali menghantui benaknya. Hatinya gundah. Apakah kini ia benar-benar mendapatkan cinta yang terbalaskan? Apakah kata-kata William kala itu diucapkan dengan sepenuh hati?
Tatapan Anita yang penuh tanda tanya itu berubah menjadi ketertarikan yang dalam, keinginan untuk tetap berada di sisi William, setidaknya sampai ia mendengar sendiri jawabannya dari mulut pemuda itu.
Sejak Anita terbangun, matanya tak sekalipun lepas dari William. Ia terus memperhatikan diam-diam, berharap dan bertanya.
Dalam lamunan, Anita mendengar suara berat dan tegas di ambang pintu.
“Willie memanggilmu untuk ke ruang bawah tanah.”
Ucapan Alfred tiba-tiba membuat Anita tercekat. Jantungnya berdegup kencang, kaget bercampur waspada.
Ia berdiri terpaku beberapa detik, ragu untuk menoleh. Namun Alfred mengulang kalimatnya dengan nada menekan, membuat Anita tidak punya pilihan.
Mendengar nama Willie, membuatnya mencerna kembali siapa sosok dia sesungguhnya, kegelisahan selalu berubah menjadi ketakutan. Willie adalah figur yang menakutkan, lebih menakutkan dari siapa pun yang pernah ia kenal.
Dan karena itulah, timbul kekhawatiran kecil dalam dirinya: jika ia tidak menurut, mungkin dia akan disiksa. Sama seperti yang terjadi pada William. Karena tidak punya pilihan, dia akhirnya mengangguk.
Dengan berat hati, Anita mengekor Alfred. Tanpa sepatah kata pun terucap, mengikuti langkah Alfred menuju ruang bawah tanah.
Begitu memasuki lorong, tubuhnya menggigil. Bau darah, tanah dan besi mengingatkannya pada malam pertamanya bangkit sebagai Vrykolakas.
Saat memasuki ruangan tempat Ifal berada, pandangan mereka bertemu.
“Ifal.”
Ifal mengangkat wajah. Napasnya memburu.
“Anita, itu, kamu?”
Anita tak menjawab. Ia hanya berjalan pelan, lututnya sedikit goyah. Setiap langkah seperti pertarungan batin yang menyakitkan.
“Anita, bagus kamu ada disini.” ucap Willie dengan tangan terbuka lebar. Namun Anita hanya terdiam. Tak ada senyum, tak ada balasan. Tatapannya tertunduk ke lantai, seakan keberadaannya di sana adalah beban yang tak bisa ia hindari.
“Bantu aku ngasih contoh ke Ifal, bagaimana caranya makan.”
Anita tercekat sesaat, kepalanya seketika menengadah ke arah Willie, dia berusaha bertanya Serius? Tapi pertanyaan itu tidak keluar, dia seperti tertahan di kerongkongan.
“Cepatlah!” Willie mendesaknya.
Anita menatap gadis yang terduduk memeluk lutut di dekat Ifal. Perlahan, ia mendekat. Tangannya meraih bahu sang gadis dan menekannya ke bawah dengan dingin. Tubuhnya condong ke depan dan mulutnya terbuka, memperlihatkan taring-taring tajam yang siap menembus kulit.
Gadis itu, Siska, menggigil. Terikat dan tak berdaya, ia merasakan hawa dingin menusuk dari bahu hingga ke dadanya. Ketakutan menguasainya. Kakinya menggosok-gosok lantai, mencoba melepaskan diri. Kepalanya bergerak panik, berusaha menghindar.
Namun Alfred melangkah maju. Dengan tangan kuat, ia memegangi kepala Siska, menahannya agar tetap diam. Tak ada lagi ruang untuk melawan.
Ifal membelalak. “Tunggu! Jangan”
Terlambat. Taring Anita sudah menancap. Suara robekan halus kulit dan aliran darah mengisi ruangan dengan nada yang dingin dan menyeramkan.
Setelah beberapa saat, Anita mengangkat kepala. Tetes darah menetes dari bibirnya. Wajahnya merah, matanya menyala. Senyum terlihat di wajahnya. Senyum jahat yang hampir menyerupai Willie.
“Ifal, beginilah cara kamu makan sekarang.” Ucap Anita parau.
“Nggak. nggak. Aku nggak bakal lakuin itu.”
“Jangan bodoh Ifal, kalau kamu nggak lakuin, kamu bakal mati lagi. Mau kamu?” Sekarang nada Anita berubah tegas penuh penekanan.
“Masa bodoh, lebih baik aku mati daripada harus ngebunuh Siska.”
Anita mengerutkan dahi, rahangnya mengeras, tatapannya tajam. Dia merasa ada bara api di dadanya yang ingin di ledakan ketika mendengar ucapan naif dari Ifal. Tanpa pikir panjang, Anita kembali menancapkan taringnya di leher Siska, kemudian cairan darah yang berhasil dia hisap ditampung di mulutnya.
Ia berjalan mendekati Ifal secara perlahan, setelah jarak mereka dekat, Anita mengeluarkan darah yang ada di mulutnya dan di tampung di telapak tangan, seketika itu juga tangan itu di dekapkan ke mulut Ifal dengan paksa, di suapkannya darah tanpa permisi, tanpa aba-aba tanpa persetujuan.
“Makan!” Perintah Anita dengan kekesalan yang memuncak. “Biar kamu bisa balesin rasa sakit aku ke Askara.”
“Hmmm, hmmm” Ifal mengeram.
“Asal kamu tahu saja. Dulu aku kira Askara orang yang tulus, tapi sekarang aku tahu. Dia penuh kebohongan, penuh alasan. Dia cuma manfaatin aku buat deketin Fitri.”
Anita semakin menekan telapak tangannya ke rahang Ifal, sementara tangan satunya mencengkeram erat bagian belakang kepalanya. Dengan mata yang menyala penuh kebencian, ia memaksa Ifal menelan cairan merah pekat itu. Ifal meronta, berusaha memuntahkannya, tapi Anita tak mengendurkan cengkeramannya sedikit pun.
Air mata amarah menggenang di sudut mata Anita saat bayangan Askara muncul di benaknya. Semua luka itu, semua rasa sakit yang menyesakkan, kini ia lampiaskan pada Ifal.
“Sampai akhirnya…” desisnya lirih, gemetar oleh amarah. “…aku berhenti jadi manusia. Karena manusia... cuma tahu cara nyakitin.”
Ifal terus meronta berusaha melepaskan diri namun tangan Anita tidak juga mau terlepas.
“Kamu harus ngebantuin aku ngubah dia. Dengan begitu, aku bisa sama dia selamanya.”
Mata Ifal terbelalak, cairan hangat masuk ke tenggorokan, rasa asing itu seperti membebaskan tubuhnya dari derita. Ia terpaksa menelan. Satu teguk. Dua teguk hingga perutnya terasa terisi. Pikirannya jernih.
Ifal mengerjapkan pandangannya ketika semua tetesan darah di telapak tangan Anita berhasil dia telan sepenuhnya. Kemudian ada perasaan lega menjalar di sekujur tubuhnya, tapi perasaan itu disertai rasa ingin mendapatkan lebih banyak darah. Lebih lapar dan lebih buas ingin memangsa.
Pandangan Ifal bergeser pada Siska yang sekarat di lantai. Lehernya berdarah. Napasnya pelan.
Dorongan itu mengambil alih. Ia merangkak perlahan, seperti serigala yang lapar. Tangannya gemetar. Tapi ketika bibirnya menyentuh kulit gadis itu, mulutnya membuka lebar, taringnya yang tajam kini mencuat. Dia menancap,
Dunia hening.
Tubuh Siska bergetar. Darah yang dihisap terasa manis. Hangat. Mengalir seperti arus kehidupan langsung ke lambung Ifal. Ia minum dan tak ingin berhenti.
Willie dan Anita tersenyum di balik bayangan.
“Bagus, Ifal, akhirnya langkah pertama menuju rencanaku dimulai.” Ucap Willie puas.


 risyadfarizi
risyadfarizi