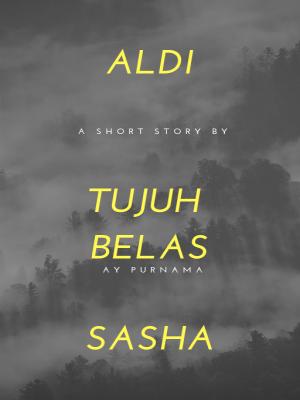Ifal adalah siswa yang paling diunggulkan di sekolah. Ia berprestasi di akademik dan jago Taekwondo. Piala dari lomba sains dan bela diri sering ia bawa pulang. Sosoknya dikenal pintar, tenang dan rendah hati. Tapi tak semua orang menyukainya, ada yang diam-diam iri.
Di sekolah, Ifal bersahabat dekat dengan Askara sejak SMP. Mereka kemudian berteman dengan Adit yang suka bercanda, Anita yang blak-blakan dan Fitri, murid pindahan yang datang diam-diam tapi membawa perubahan besar.
Fitri masuk saat semester dua kelas sepuluh. Awalnya pendiam dan nyaris tak terlihat aktif, tapi justru itu yang menarik perhatian Ifal. Wajah manis dan sikap tenangnya membuatnya berbeda. Ia tidak mudah tergoda, bahkan oleh Ifal. Dan itu membuatnya makin menarik di mata Ifal.
Suatu sore sepulang sekolah, mereka sedang bersiap-siap.
“Fal, weekend ini kamu kemana?” tanya Askara sambil merapikan buku.
Ifal menutup buku Fisika dan menjawab “Fitri mau minta diajarin Fisika Sabtu ini, tapi belum pasti sih. Minggu aku latihan Taekwondo.”
“Mau nongkrong bareng aja nggak? Di kafe baru dekat rumah Anita. Katanya tempatnya enak buat ngobrol. Fitri pasti bakalan suka, kalau belajar disana.” kata Askara.
“Iya juga. Tapi aku tanya dia dulu.” balas Ifal.
Belum sempat dibalas, Adit muncul dari pintu belakang sambil tersenyum lebar.
“Belajar mulu, nggak kebakar tuh otak?” godanya sambil menepuk bahu Ifal.
Ifal tertawa kecil. “Nggak lah, santai aja.”
Mereka bertiga keluar kelas. Tak lama, Anita berteriak dari kejauhan.
“Hei! Tungguin! Tas kita masih di dalam!”
Anita berlari kecil, sementara Fitri menyusul dengan langkah santai.
“Nih, tas kalian. Udah aku bawain.” kata Ifal, menyerahkan tas mereka.
“Perhatian banget sih kamu Fal.” ujar Anita sambil tersenyum.
Adit menyipitkan mata. “Dari mana aja sih? Udah waktunya pulang malah ngilang.”
“Baru dari ruang guru. Bu Tuti suruh ngumpulin tugas sekelas.” jawab Fitri datar. “Makasihnya mana?” Fitri mendekat ke Ifal, membuat Ifal grogi, lalu tertawa kecil. “Iya, iya, makasih nona-nona.”
Ifal memperhatikan Fitri, cara bicara, gerak tubuh, hingga ekspresi gugup saat mata mereka bertemu. Wajah Fitri memerah, lalu ia menunduk dan membetulkan tali tasnya. Waktu terasa berjalan lambat.
Askara sudah berjalan duluan di depan.
“Hei, Ra! Tungguin dong, buru-buru amat.” teriak Anita sambil mengejar.
Yang lain tertawa kecil. Mereka tahu Askara memang cuek, tapi selalu bisa diandalkan saat dibutuhkan.
Mereka berjalan beriringan menyusuri jalan di trotoar, menikmati sore yang mulai gelap. Rumah mereka tak terlalu jauh dari sekolah. Askara tinggal paling dekat, disusul Anita dan Ifal, sementara Adit dan Fitri biasanya naik motor atau mobil. Tapi kali ini mereka sepakat jalan kaki bareng sampai halte, momen langka di tengah kesibukan.
Tawa mereka sesekali pecah, diiringi lelucon ringan. Sasaran utama tetap Ifal dan Askara, dua karakter yang kontras tapi cocok dijadikan bahan bercanda. Ifal selalu menanggapinya dengan senyum, sementara Askara tetap tenang, nyaris tak bereaksi.
“Fal, kenapa sih kamu masih jomblo?” goda Anita sambil menyenggol bahunya. “Ganteng, pinter, atlet lagi. Jangan-jangan kamu.”
Ia melirik ke arah Askara dengan gaya menggoda. Semua langsung paham arah candaannya.
“Apa?” tanya Askara datar.
“Eh, nggak jadi deh.” sahut Anita tertawa.
Adit menyambung. “Jangan-jangan kalian homo-an, ya? Hahaha.”
Tawa pecah. Fitri hanya tersenyum kecil. Ifal tetap tenang seperti biasa, tak terganggu.
“Haha, nggak lah.” jawab Ifal. “Lagi fokus sekolah sama Taekwondo aja. Lagian belum nemu yang cocok.”
Tapi sebelum melanjutkan langkah, mata Ifal sempat melirik Fitri. Tatapan singkat itu tak luput dari Adit yang mengangkat alis dan tersenyum curiga.
Tak lama, mereka tiba di warung kecil dekat halte. Pepohonan menaungi bangku panjang tempat mereka duduk. Seperti biasa, es krim jadi teman santai mereka.
“Eh, Sabtu ini jadi nggak ke kafe deket rumahku? Promonya masih ada lho.” tanya Anita sambil menikmati es krimnya.
“Ayok!” sahut Adit langsung.
Askara hanya mengangguk seperti biasa.
Ifal dan Fitri diam.
Anita melirik mereka. “Kalian gimana? Kok diem?”
Ifal menoleh ke Fitri. “Fit, belajarnya jadi di kafe aja?”
Fitri menatap es krimnya sebentar, lalu beralih ke Ifal. “Ayok aja, kita belajar disana.”
Ifal mengangguk. “Tapi kamu yakin bisa fokus? Bukannya kamu butuh tempat tenang?”
Fitri tersenyum tipis. “Nggak masalah kok. Asik juga kan, jadinya bisa belajar bareng.”
Anita mengamati mereka berdua dengan penasaran. Ia melirik Adit, berharap ada yang punya pikiran sama. Ternyata Adit juga menatapnya, seolah paham. Tatapan mereka bertemu dan tanpa kata-kata, mereka mengerti sesuatu sedang tumbuh di antara Ifal dan Fitri.
Mereka pun menatap ke arah dua orang itu, terlihat tenggelam dalam percakapan sendiri, seakan dunia hanya milik mereka. Sementara Anita dan Adit? Hanya penonton dan pendengar tuli.
Adit sempat ingin meledek, tapi hanya menahan tawa sambil menjilat sisa es krimnya. Ia melirik lagi ke arah Anita dan mengangkat alis, memberi isyarat: mereka pasti ada apa-apa. Tapi keduanya sepakat dalam diam, jangan digoda dulu. Salah-salah, Fitri malah enggan ikut nongkrong di kafe.
“Okay, aku ikut.” ucap Ifal akhirnya, nada suaranya ringan, tapi dalam.
“Aku juga” sambung Fitri pelan.
“Fix ya” sahut Anita sambil mengusap tangan dari sisa lelehan es krim. “Sabtu pagi, jam sepuluh!”
Tak lama kemudian, mereka mulai berpencar. Adit dan Fitri naik ke angkot jurusan barat. Askara berbelok sendirian ke arah gang rumahnya. Tinggal Anita dan Ifal yang berjalan perlahan di trotoar, membiarkan senja mengiringi langkah mereka.
Langit berubah keungu-unguan, angin mulai dingin. Senja itu terasa aneh, terlalu sunyi di sela tawa tadi.
“Fal” suara Anita pelan. “Kamu suka ya sama Fitri?”
Ifal terdiam. Matanya menatap ke depan, lalu ke langit. “Nggak tahu.”
“Tapi aku perhatiin, kamu merhatiin dia mulu dari tadi.”
Ia tersenyum. “Hmm, masa sih.”
Anita menatapnya sebentar, lalu mengangguk. “Ye, pake ngelak lagi.”
Ifal lagi-lagi hanya tersenyum tidak menanggapi. Hingga mereka sampai di rumah masing-masing.
Hari yang ditunggu akhirnya datang. Matahari bersinar terik, tapi semangat kelima sahabat itu tak padam. Meski udara panas dan lengket, mereka tetap antusias seperti yang sudah direncanakan.
Tempat kumpul mereka adalah kafe mungil dekat rumah Anita. Suasananya hangat, dinding bata merah, aroma kopi dan musik indie lembut mengisi ruangan. Tapi seperti biasa, janji pukul sepuluh hanya tinggal janji. Mereka datang satu per satu dan baru lengkap dua jam kemudian.
Anita jadi yang paling duluan datang. Ia duduk di pojok dekat jendela, bermain-main dengan cangkir kopi kosong.
“Lama banget sih kalian. Ini udah jam berapa coba?” keluhnya, mencoba kesal, meski senyum tipisnya menunjukkan rasa rindu.
Adit menimpali. “Siapa suruh tepat waktu?”
Askara ikut menambahkan. “Kalau semua datang tepat waktu, kamu nggak bisa ngomel.” Anita mendengus, tapi akhirnya tertawa juga.
Fitri datang tak lama setelah itu. Ia duduk di samping Anita. “Maaf ya guys aku telat.” ujarnya sambil tersenyum malu-malu.
Anita mengerucutkan bibir, tapi tidak benar-benar marah.
Ifal jadi yang paling terakhir datang. Ia melangkah santai, tersenyum damai.
“Maaf ya” katanya, lalu duduk.
“Padahal rumah kamu paling deket” celetuk Anita.
Ifal hanya tersenyum. “Iya, maaf. Besok-besok nggak telat lagi, deh. Soalnya tadi nganterin baju seragam Taekwondo dulu ke sekolah.”
“Taekwondo terus yang dipikirin. Kita mah nggak pernah jadi prioritas.” celetuk Adit sambil bercanda.
“Hahaha” Ifal tertawa sebagai balasan.
Mereka lalu mengobrol santai. Saat menunggu pesanan, Askara membuka topik baru.
“Kalian tahu rumah tua di pojokan komplek itu nggak? Yang gede dan kayak arsitektur Belanda?”
“Tau dong. Yang gerbangnya selalu nutup itu, kan?” sahut Anita.
“Kayaknya keren ya. Pas tadi lewat, aku jadi kepikiran terus.” kata Askara.
“Katanya kosong udah lama.” tambah Ifal.
“Siapa tahu ada harta karunnya” celetuk Adit.
“Nanti kalau rumah itu aku beli, baru kita cari harta karunnya bareng-bareng.” ujar Askara sambil tertawa.
Mereka ikut tertawa bersama. Suasana hangat, sederhana, tapi terasa istimewa. Di tengah tekanan ujian akhir kelas dua belas, momen seperti ini terasa langka.
Sore menjelang. Cahaya jingga menyusup lewat jendela. Obrolan mulai mereda.
Anita melihat jam. “Guys, kayaknya aku duluan deh.”
Adit menanggapi dengan alis mengkerut. “Hah? Cepet amat. Malam mingguan, ya?”
Anita terkekeh. “Nggak, Dit. Mau belanja. Buat besok.”
Tatapannya sekilas melirik ke arah Askara. Hanya sedetik, namun cukup untuk membentuk teka-teki. Senyum samar bermain di bibirnya.
Adit menangkap isyarat itu. Ia tertawa kecil dan mengangkat alis, seolah berkata. “Aha, ketahuan.”
Askara yang awalnya tak peduli kini melirik balik. Ia menyandarkan tubuh dan menghela napas malas.
“Mau pulang sekarang? Jangan lupa bantuin PR Pak Surya Senin nanti ya. Pelajaran dia tuh, sumpah, ngantuk banget.”
Anita tertawa, matanya menyala percaya diri. “Santai. Kamu bisa andelin aku, kok.” Senyumnya hangat dan entah kenapa, membuat ekspresi Askara melunak.
Anita pamit, lalu pergi. Tapi bukan ke rumah. Ia menyalakan motor dan melaju ke arah yang tak diketahui siapa pun sore itu.
Tak lama, Adit ikut berpamitan. “Udah sore juga. Aku cabut duluan ya.” katanya sambil merenggangkan badan.
Askara menyusul, dengan alasan klasik. “Aku mau lanjut nge-game sambil rebahan. Belum tamat soalnya.”
Tinggallah Ifal dan Fitri. Meja kini sepi. Di tengahnya, hanya secangkir teh yang dingin dan buku Fisika yang terbuka.
Sunyi kembali hadir. Namun kali ini, bukan sunyi yang akrab, melainkan sunyi yang canggung.
Ifal menggeser kursinya, pelan. Gerakannya membuat Fitri mendonggak, sedikit heran.
“Fit, boleh ngomong sesuatu nggak?” Suaranya pelan, namun nadanya serius.
“Ngomong aja” jawab Fitri, senyumnya lembut.
Hening. Detik berdetak lambat.
“Kita kan udah lama temenan, bahkan sahabatan.” Ifal menunduk, lalu melanjutkan dengan suara nyaris berbisik. “Aku mikir, gimana kalau, kita coba hubungan yang lebih dari sekadar sahabat?”
Wajahnya memanas. Ia tak berani menatap langsung mata Fitri. Dadanya bergemuruh hebat, seperti genderang perang di dalam dada.
Fitri diam. Tidak langsung menjawab. Lalu, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia membuka mulut.
“Ifal, aku hargain keberanian kamu. Tapi.”
Kata itu. “Tapi?” Seperti awan mendung yang datang tiba-tiba.
“Aku belum bisa terima hubungan kita jadi lebih dari sahabat.” lanjutnya, tegas.
Ifal tertunduk. “Kenapa?”
Fitri menghela napas, lalu menatap lurus ke jalan di luar jendela kafe, melihat orang-orang berlalu-lalang.
“Aku pingin fokus ke sekolah dulu sampai lulus. Aku pikir kamu juga gitu, kan?”
“Hmm, iya sih. Tapi sekarang-sekarang ini, aku ngerasain sesuatu yang beda ke kamu. Aku pingin ungkapin kalau aku suka sama kamu.”
Sejenak hening. Angin dari pendingin ruangan berdesir lembut, seperti suara bisikan yang ikut meredam perasaan.
“Aku ngerti.” ucap Fitri akhirnya. “Sejujurnya, bukan berarti aku nggak suka sama kamu, Ifal.”
Ucapan itu membuat Ifal mendonggak. Ia menatap wajah Fitri yang kini menunduk sedikit, dengan nada suara lirih di akhir kalimat.
“Aku juga suka sama kamu, cuma aku nggak mau nyia-nyiain waktu yang bisa aku pakai buat belajar. Aku pingin fokus buat lulus. Aku nggak sepintar kamu.”
Nada itu berubah jadi sedih. Mata Fitri sedikit berkaca-kaca, tapi dia tetap mencoba tegar.
“Ayo kita sama-sama berjuang biar bisa lulus. Aku akan bantu kamu kapanpun kamu butuh.” kata Ifal tulus, senyumnya kembali muncul.
Fitri pun tersenyum, kali ini lebih tulus dan hangat. “Terima kasih, Ifal.”
“Sama-sama.” Ifal tersenyum. “Jadi kalau udah lulus, kita bisa jadian kan?” Ifal memastikan, kali ini nada suaranya lebih lembut dan penuh harap.
“Bisa.” Fitri malu-malu mengatakannya. Pipinya merona merah, senyum merekah di wajahnya. Terlihat jelas kalau dia bahagia.
Ifal merasakan kehangatan dan harapan. Penantiannya tidak akan sia-sia. Fitri akan bersama dengannya di waktu yang tepat.
Sesi belajar bersama usai. Ifal sempat menawarkan untuk mengantar Fitri pulang, tapi Fitri menolak dengan halus dan memilih memesan ojek online.
“Nggak apa-apa. Aku pingin sendiri.” katanya.
Ifal tak memaksa. Ia hanya berdiri di depan kafe, menunggu hingga motor ojek itu melaju dan menghilang di tikungan. Hanya aroma samar parfum Fitri yang tersisa, seolah masih menyelimuti udara malam.
Di kepalanya, Ifal membayangkan ribuan kemungkinan. Tentang masa depan. Tentang Fitri. Tentang harapan yang kini harus disimpan dulu, diam-diam.
Namun lamunannya buyar saat sebuah motor melintas.
“Hei!”
Anita, dengan helm dan senyum cerah, melambaikan tangan.
Di boncengan motornya, ada bingkisan kotak besar dengan gambar vas bunga indah di sampulnya. Ifal menatapnya penuh tanya, tapi tak sempat bertanya.
Anita sudah melaju pergi, meninggalkan rasa penasaran yang mengendap di udara malam.
Keesokan harinya. Hari Minggu.
Langit siang terik menyilaukan. Panas menyengat, aspal tampak bergetar. Tapi bagi Ifal, cuaca bukan masalah. Ini hari yang ia tunggu-tunggu tiap minggu: latihan Taekwondo. Saat tubuh bisa bergerak bebas, pikiran lepas dari soal ujian dan semangatnya tersalurkan.
Sejak jam sebelas, ia sudah siap. Seragam putih dan sabuk hitam tergantung rapi, botol minum, handuk kecil dan helm motor tertata lengkap. Semua dicek ulang, bukan karena pelupa, tapi karena ia perfeksionis, apalagi soal hal yang ia cintai.
Orang tuanya sedang pergi ke luar kota, jadi rumah hanya dijaga olehnya. Kunci rumah tergantung di pinggangnya, terikat lanyard hitam usang, kenang-kenangan dari ayah saat ia pertama kali boleh ikut latihan di luar kota.
Setelah siap, ia menyalakan motor miliknya. Suara mesin menggeram pelan, siap menemani. Ia pun melaju perlahan melewati jalanan komplek yang lenggang.
Namun langkahnya terhenti.
Di ujung komplek, sebuah truk besar terparkir di depan rumah tua bergaya Impersche Empire, Belanda, yang biasanya tertutup rapat. Rumah itu selama ini tampak kosong dan tua, cat terkelupas, gerbang selalu ditutup.
Tapi hari ini, gerbangnya terbuka.
Ifal melambatkan motornya, lalu menepi. Dari balik helm, ia memperhatikan truk yang membongkar muatan.
Bukan barang biasa. Ada lampu gantung kristal, piano tua dengan ukiran megah dan pot-pot bunga besar dengan tanaman unik. Semuanya tampak antik, seperti milik orang kaya penyuka sejarah.
Warga mulai berkerumun diam-diam, menonton dari balik gerbang. Rumah itu, yang dulunya sunyi, kini tampak hidup. Tapi bukan itu yang membuat Ifal terheran-heran.
Sebuah mobil tua berhenti di belakang truk. Volkswagen Beetle, tapi sangat mengkilap, terlalu sempurna, seolah tak tersentuh waktu.
Pintunya terbuka perlahan. Seorang pria turun, tinggi, ramping, rapi dengan jas hitam-putih dan dasi kupu-kupu. Wajahnya datar, dingin, seperti patung hidup.
Ia mengeluarkan dua kursi roda, lalu membuka pintu belakang mobil.
Dengan hati-hati, ia mengangkat seseorang yang seluruh tubuhnya dibungkus kain hitam tebal, dari kepala sampai kaki, tak satu pun terlihat. Ia di dudukkan di kursi roda dan di dorong masuk ke rumah. Diam. Tanpa kata.
Lalu, ia kembali dan melakukan hal yang sama dengan orang kedua, tubuhnya lebih berat. Pria itu sempat terhuyung, tapi kain tetap terjaga.
Setelah dua anak itu masuk, pintu besar rumah tua tertutup perlahan. Sunyi. Misterius.
Ifal masih terdiam di atas motornya. Jantungnya berdegup cepat.
“Aneh, kenapa bawanya kayak gitu ya? Apa mungkin mereka sakit, atau mungkin butuh privasi?” gumamnya, meski hatinya tak yakin.
Ia melirik jam. Sudah lewat pukul dua belas.
“Sial.” katanya, sadar latihan sudah dimulai.
Dengan berat hati, ia pergi, tapi pikirannya tertinggal di rumah itu.
Sore nanti, ia akan kembali. Ia harus tahu siapa yang pindah ke sana. Tekadnya dalam hati.
Malam itu, sekitar pukul sembilan lewat. Udara dingin mulai menusuk, meresap ke balik jaket yang masih dipakai Ifal. Ia baru pulang dari latihan Taekwondo, lebih larut dari biasanya. Salah satu temannya yang bernama Siska merayakan ulang tahun dan meski tubuhnya lelah, ia tetap harus ikut. Tak enak menolak soalnya.
Saat melintasi rumah tua itu, ia otomatis menoleh. Siang tadi, rumah itu membuatnya penasaran. Tapi malam ini, rumah itu tampak seperti biasanya, gelap, sunyi dan misterius. Jendelanya tertutup rapat, tak ada cahaya. Tapi entah kenapa, rasanya berbeda. Lebih mencekam. Lebih, tidak nyaman.
“Mungkin besok aja aku kenalan sama tetangga barunya sepulang sekolah.” gumamnya, mencoba menenangkan diri.
Sesampainya di rumah, langkahnya terhenti. Dia melihat di depan rumah Anita, terparkir mobil tua yang sama persis dengan yang ia lihat siang tadi. Volkswagen yang mengkilap, mencolok di bawah lampu jalan. Tak mungkin salah.
Dengan jantung berdebar kencang, Ifal mematikan motornya dan mendorongnya masuk ke garasi rumah. Dari balik pagar, pandangannya terpaku pada mobil yang terparkir di sana.
Lalu, Anita keluar dari mobil.
Tapi Ifal langsung merasa ada yang aneh. Cara Anita berjalan kaku. Ekspresinya datar, matanya kosong, seolah bukan dirinya. Ia menutup pintu mobil pelan, lalu sempat menoleh ke dalam seakan berbicara pada seseorang, tapi tak terdengar apa-apa.
“Anita!” seru Ifal sambil mengangkat tangan, mencoba menarik perhatiannya.
Tapi tak ada reaksi. Gadis itu berjalan masuk ke rumah, disambut keluarganya, lalu menghilang di balik pintu.
Ifal mengernyit. “Anita kenapa ya?”
Mobil yang tadi terparkir itu kini melaju kencang, meninggalkan rumah Anita.
Ifal membuka pintu, masuk ke rumah yang masih kosong. Ayah dan ibunya belum pulang. Setelah mandi dan berganti baju, ia berbaring di kasur, tapi pikirannya tetap gelisah. Memikirkan Anita.
Ia meraih ponsel dan mengirim pesan:
“Nit, baru pulang? Tumben malem hehe.”
Tak dibalas. Ia coba lagi:
“Tadi aku lihat kamu keluar dari mobil antik lho, keren. Boleh tahu nggak, mobil siapa itu? hehe”
Masih tidak ada balasan. Bahkan belum terbaca.
Ifal menghela napas. Ditatapnya langit-langit kamar, lalu meletakkan ponsel. Matanya terpejam, tapi pikirannya masih sibuk. Ada sesuatu yang terasa janggal dan ia tahu, ada yang aneh dengan tetangga baru itu.
Pagi harinya.
Sinar matahari menyusup malu-malu dari celah tirai. Udara pagi sejuk, tapi tak cukup menenangkan gelisah yang sempat ia bawa tidur. Ifal terbangun dan nyaris langsung meraih ponsel di samping bantal.
Satu notifikasi.
Dari Anita.
“Teman baru aku. Nanti aku kenalin, tapi sekarang tolong rahasiain dari anak-anak yang lainnya. Biar aku aja yang bilang ke mereka.”
Alis Ifal terangkat. Matanya membaca ulang pesan itu dua kali, mencoba menangkap nada tersembunyi di balik kalimat yang terdengar biasa.
Ia mengetik cepat:
“Oke 😉”
Tapi bahkan setelah mengirimnya, rasa janggal di dadanya belum benar-benar hilang.
Di sekolah, mereka kembali bertemu.
Anita bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Senyumnya tipis, ucapannya singkat. Setiap kali Ifal bertanya soal pemilik mobil antik, Anita langsung menghindar.
“Aku nggak mau ngomongin itu sekarang. Tolong jangan bilang siapa-siapa dulu.” ucapnya datar.
Ifal mengangguk, meski hatinya gelisah. Ia tahu, memaksa hanya akan membuat Anita makin menjauh.
Tapi rasa penasaran itu tak hilang. Justru makin tumbuh.
Tiga malam berturut-turut, mobil antik itu datang lagi. Selalu di waktu yang hampir sama, sekitar pukul tujuh malam.
Malam pertama, mobil itu pulang pukul sembilan.
Malam kedua, baru pergi pukul satu dini hari.
Ifal tak tahan. Ia coba kirim pesan, menelepon, bahkan berdiri lama di depan rumah. Tapi jawaban Anita sekarang berbeda:
“Mereka keluarga jauh. Jangan bilang siapa-siapa dulu ya.”
Kata-kata itu makin lama terdengar tak ada arti.
Di malam ketiga, Ifal akhirnya memutuskan untuk mengintai. Mengenakan hoodie hitam, ia berdiri di balik pagar, berjinjit pelan sambil menoleh ke segala arah, matanya tak lepas mengamati rumah Anita yang tampak sunyi.”
Ia menunggu.
Pukul delapan.
Sembilan.
Sepuluh.
Sebelas.
Tak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah Anita sepi, seolah tak berpenghuni.
Ia kirim pesan lagi, tetap tak ada balasan.
Akhirnya, rasa kantuk mengalahkannya. Ia masuk rumah, tertidur di sofa dengan hoodie masih melekat.
Keesokan paginya, saat sarapan, ayahnya berkata santai. “Tamu dari rumah Anita pulang sekitar jam satu. Ayah sempat dengar suara mobilnya.”
Ifal hanya mengangguk. Tapi pikirannya terus berputar.
Siapa sebenarnya orang itu? Kenapa Anita makin aneh?
Di sekolah, suasana terasa berbeda. Langit mendung, angin lembap berembus dari jendela.
Di dalam kelas, murid-murid belum siap belajar. Tapi Ifal punya hal lain yang dipikirkan.
Ia ingin bicara dengan Anita hari ini.
Namun niat itu hilang begitu melihat Anita masuk kelas.
Langkahnya pelan, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia terlihat sangat lelah, seperti baru bangun dari mimpi buruk.
Ifal bergumam. “Dia kenapa ya?”
Adit dan Fitri juga memperhatikan.
Mereka bertiga menghampiri Anita yang duduk lemas.
“Nit, kamu kenapa? Sakit?” tanya Fitri pelan.
Anita tersenyum tipis. “Nggak apa-apa kok.” ucapnya, tapi nadanya hampa.
Di sudut kelas, Askara sudah tertidur di mejanya.
Tiba-tiba,
Duk!
Pintu terbuka. Pak Surya masuk dengan langkah cepat.
Matanya langsung ke arah Askara.
“Lagi-lagi kamu tidur di kelas, Askara! Ini sudah ketiga kalinya kamu tertidur di kelas saya! Keluar sekarang! Saya bakal catat kamu sebagai alpa!”
Askara terbangun, menguap dan keluar sambil menggerutu.
Pak Surya menghela napas dan meletakkan kertas di meja.
“Hari ini ulangan dadakan. Siapkan kertas satu lembar.”
Kelas langsung ribut.
“Pak, dadakan banget.”
“Belum belajar.”
Pak Surya diam saja.
“Yang belum siap, siapin sekarang.” ujarnya tegas.
Satu per satu murid mulai menyiapkan kertas.
Kelas pun tenggelam dalam hening, hanya suara pena dan gesekan kertas yang terdengar.
Namun,
Tiba-tiba, sunyi itu pecah.
“AAAHH! Berenti! Jangan! Keluarin aku! Tolong! Sakit!”
Suara Anita menjerit parau, robek, menggetarkan udara kelas.
Semua murid terlonjak.
Ifal nyaris menjatuhkan pulpennya. Fitri membeku, matanya membelalak.
Anita menggigil di kursinya. Tubuhnya menegang, tangannya mencengkeram meja begitu keras hingga buku di depannya bergeser.
“Anita?! Ada apa?!” Pak Surya bergegas menghampiri.
Tapi Anita tak menjawab. Matanya terbelalak lebar. Pandangannya kosong dan liar dalam waktu bersamaan.
Lalu napas panjang tertarik dari paru-parunya. Dan,
DUGH!
Kepalanya menghantam meja dengan suara mengerikan.
Busa putih keluar dari sudut bibirnya.
Tubuhnya bergetar hebat, lalu terkulai, diam.
Panik merambat cepat.
“Anita!!”
“Astaga! Lihat dia!!”
“Tolongin cepat!!”
Suara-suara panik membanjiri ruangan. Beberapa murid berdiri. Yang lain menjauh, ngeri. Fitri menutup mulut, nyaris menangis.
Ifal hanya bisa mematung, jantungnya berdetak cepat.
Sore itu, langit mendung menyelimuti sekolah. Udara lembab dan angin berhembus, membawa aroma tanah basah.
Ifal melangkah pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia masih terguncang oleh kejadian pagi tadi, teriakan Anita, tubuhnya gemetar, mulut berbusa di depan semua orang. Bayangan itu terus menghantuinya.
Saat melewati rumah Anita, Ifal berhenti. Rumah itu gelap, tirainya tertutup rapat, tak ada cahaya atau suara. Seperti ditinggalkan.
“Aku harusnya ngelakuin sesuatu lebih cepat.” gumamnya pelan.
Ia pun melangkah masuk ke rumahnya dan menuju kamar, ia mengganti baju, lalu rebah di kasur. Tapi pikirannya tetap gelisah.
Jam terus berdetak. Pukul tujuh malam, bel rumah berbunyi.
“Ifal, ada yang nyariin!” teriak ibunya dari ruang tamu.
Dengan penasaran, Ifal menuju pintu. Di sana berdiri seorang remaja laki-laki. Rambutnya hitam tebal, kulitnya pucat, wajahnya tampak familiar. Ifal ingat, dia pernah melihat remaja ini datang ke rumah Anita.
“Hai, kamu Ifal, ya?” sapa remaja itu dengan senyum tipis.
“Iya, kamu siapa?” tanya Ifal waspada.
“Namaku William. Aku tetangga baru, tinggal di rumah tua di ujung jalan.”
“Oh, ada perlu apa?”
“Aku cuma mau tanya, Anita ke mana? Dia pernah bilang kalau ada apa-apa, aku bisa hubungi kamu.”
Ifal menatap tajam. “Anita lagi sakit. Sekarang dirawat di rumah sakit.”
“Ya Tuhan.” William terlihat kaget, tapi nadanya datar.
Ifal makin curiga. “Jujur aja, kamu sering ke rumahnya, kan?”
“Kami cuma ngobrol. Kadang sampai malam.”
Ifal menyipitkan mata. “Apa itu yang bikin dia sakit seperti sekarang?”
William sempat terdiam, lalu menjawab. “Aku nggak tahu. Makanya aku nyariin dia.” Kemudian ia bertanya. “Dia dirawat di mana?”
Ifal menggeleng. “Belum tahu pasti.” Jawaban itu sengaja disamarkan.
William mengangguk. “Kalau gitu, aku pamit dulu. Semoga Anita cepat sembuh.” Ia berbalik dan melangkah pergi.
Tapi Ifal termenung memikirkan sesuatu, entah kenapa, meski alarm di pikirannya terus memekikkan bahaya, ada dorongan dalam diri Ifal yang tak bisa ia redam, dorongan untuk menggali lebih dalam.
Ia ingin tahu apa sebenarnya hubungan William dengan Anita. Kenapa pemuda itu bolak-balik ke rumah mendiang sahabatnya? Ada sesuatu yang mencurigakan, tapi juga menggoda rasa ingin tahunya. Ketakutan sempat menghampiri, namun rasa penasarannya jauh lebih kuat.
“Tunggu.” Panggil Ifal.
William menoleh.
“Aku pingin ngobrol lebih jauh sama kamu. Boleh?”
William mengangkat alis, sejenak menimbang. “Aku nggak suka ditanyain hal pribadi.” ujarnya datar, nada suaranya mengandung jarak. Tapi kemudian ia menatap Ifal lebih lama. “Tapi, karena kamu temannya Anita…” Matanya sedikit melembut. “...jadi boleh lah, sebentar aja tapi, soalnya aku ada urusan lain.”
“Okay.” Ucap Ifal.
Sebenarnya di balik tatapan tenang William, tersembunyi perintah yang membebani, ia diminta kakaknya, Willie, untuk mencari korban. Persediaan darah harus terus ada dan korban itu harus bisa dibangkitkan. Karena Willie mempersiapkan sebuah rencana. Tapi jauh di lubuk hatinya, William tidak sepenuhnya setuju. Ada sisi dalam dirinya yang menolak menjadi pemburu seperti Willie. Namun ketakutan akan kakaknya yang kejam membuatnya tak punya banyak pilihan.
Awalnya, Ifal bukan target. Tapi Ifal yang justru mendekat, memberi celah dan kepercayaan. Di titik itu, William mulai goyah. Jika Ifal memang begitu mudah didekati, mungkin ini tak seburuk itu. Lagipula, Anita pasti akan senang jika sahabatnya ikut bangkit bersamanya, itu yang terus ia bisikkan pada dirinya, sebagai alasan untuk membenarkan semuanya.
Ifal membalas dengan senyum tenang. Ia mengajak William untuk mengobrol di kafe. Mereka duduk di kafe kecil di ujung blok. Lampunya hangat, tapi tak cukup meredakan rasa tak nyaman di hati Ifal.
Sesampainya di kafe, Ifal memesan kopi latte. Saat pelayan menoleh ke William, dia hanya menggeleng. “Aku udah kenyang, makasih.”
Sikapnya sopan, tapi terasa dibuat-buat.
Sambil menunggu, Ifal membuka obrolan. “Gimana ceritanya kamu bisa kenal sama Anita?”
William menatap Ifal lamat-lamat. “Dia nggak sengaja mampir waktu aku beresin barang-barang pindahan. Dia tertarik sama bunga langka yang ditanam asisten rumah tangga ku. Namanya Alfred.”
Ifal mengernyitkan alis. “Oh, tipikal Anita banget sih. Selalu penasaran sama bunga. Ngomong-ngomong dia juga yang paling gampang akrab sama semua orang di geng kita lho.”
William mengangguk. “Wah, setuju. Aku yang baru kenal sama dia, udah ngerasa akrab.”
Tak lama kemudian, pesanan kopi latte Ifal tiba. Seorang pelayan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Kali ini tangan Ifal menggenggam gelas kopi yang menghangatkan telapak, tapi bukan hatinya. Detak jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya, pertanyaan selanjutnya akan lebih menantang banginya, seolah tubuhnya tahu ia sedang duduk berseberangan dengan bahaya.
“Kalau aku boleh tanya, apa yang kalian obrolin sampai tengah malam? Aneh juga, soalnya setahuku Anita nggak pernah kayak gitu.”
Ifal bertanya dengan nada serius setelah memperbaiki posisi duduknya.
William duduk tenang di permukaan, tapi jemarinya terus dimainkannya, dia gugup. Di balik tatapan datarnya, pikirannya berkecamuk, batinnya makin sulit menahan dorongan gelap untuk menjadikan Ifal sebagai korban. Rasa bersalah menyelinap, tapi ketakutan akan Willie lebih kuat menekannya.
Tatapannya sesekali menelusuri wajah Ifal, lalu mengawang ke sudut ruangan, seolah mencari jalan keluar dari jebakan yang ia ciptakan sendiri, dan berharap, Ifal tak menangkap gelagat niat jahat yang perlahan menggerogoti dirinya.
“Oh, satu malam aku minta dibuatin Buket bunga mawar sama Anita. Dia kan suka banget sama bunga. Jadi pas aku tawarin kerjaan itu, dia antusias. Tapi emang sih, deadline-nya mepet banget. Jadi aku harus bolak-balik sampai tengah malam buat nyelesaiinya.” Dusta William dengan nada semeyakinkan mungkin.
Sebenarnya, selama tiga malam itu, yang bolak-balik ke rumah Anita adalah Willie dan Alfred. Diam-diam, mereka menyelesaikan ritual mengerikan, menyedot habis darah Anita sedikit demi sedikit, hingga nyawanya benar-benar hilang pada malam ketiga.
Ifal berdehem panjang mendengar cerita William. Dia berusaha untuk meragukan ceritanya. Tapi ekspresi William sungguh meyakinkan, sehingga sulit untuk menebak apakah dia berkata jujur atau berbohong.
“Kenapa kamu perlu Bouket banyak-banyak?” Tanya Ifal.
“Aku dan Alfred sedang berencana untuk berjualan bunga di sebuah toko yang akan kami sewa.” Ucap William, kali ini senyuman ramah mengakhiri kalimatnya.
“Oh.”
Obrolan mereka terus mengalir ringan. Tapi makin lama, suasananya berubah. Lampu di atas mereka berkedip pelan, sekali, dua kali, lalu stabil. Di kejauhan, suara klakson kendaraan terdengar sumbang, dibungkus musik lembut dari speaker kafe yang nyaris tak terdengar. Pelayan yang melayani mereka tadi terlihat masih mengintip dari balik rak bar, seperti ikut mengawasi percakapan mereka.
Disaat itulah Ifal mulai merasa aneh. Tatapan William mengarah ke lehernya. Bukan pada suasana kafe yang menurutnya ganjil, tapi seperti, terobsesi.
Ifal menyadarinya. “Ehm, ada yang aneh di leherku?”
William terlihat kaget, seperti baru tersadar. “Nggak, maaf. Aku cuma, tertarik.”
“Tertarik?” Ifal mengernyit. “Maksudnya?”
William tidak menjawab cukup lama. Ifal menunggu jawabannya, namun tak kunjung terjawab, malah, William seperti kebingungan, dia memutar bola matanya dan berdehem panjang. Akhirnya Ifal cukup terganggu dengan itu, ia pun berdiri.
“Baiklah, aku rasa udah kemaleman, aku pulang duluan. Besok harus siap-siap soalnya.”
Tiba-tiba William berkata. “Tunggu.”
Ia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Ifal. Genggamannya dingin. Sangat dingin.
Ifal mencoba menarik tangannya, tapi William menggenggam makin erat.
“Hei, lepasin! Kamu kenapa, sih?” seru Ifal, mulai panik.
William tetap diam, menatap Ifal tanpa ekspresi. Lalu dengan cepat, ia menarik tangan Ifal dengan kuat, sehingga posisi mereka berdekatan, wajah mereka hampir bersentuhan.
William memiringkan kepalanya dan mengendus leher Ifal.
Napasnya dingin. Menakutkan.
“Anjir! Kamu ini kenapa?!” Ifal seketika marah besar, wajahnya merah padam. Dia tak sengaja mendorong tubuh William keras. William terhuyung, tapi belum melepaskan genggamannya.
“Lepasin! Dasar aneh!”
Suara Ifal menggema. Beberapa pengunjung melihat, tapi tak ada yang membantu.
Ifal kembali mencoba menarik tangannya dengan tenaga yang lebih kuat. Dia mencobanya beberapa kali, hingga akhirnya William melepaskan. Wajahnya berubah, takut dan panik.
“Maaf, maafin aku, Ifal.” katanya pelan.
Ifal menatapnya tajam. Bukan cuma marah, tapi juga heran. Saat Ifal melihat tangannya, ada bekas lebam membiru. Ia berbalik. Tak bicara sepatah kata pun, lalu pergi. Meninggalkan William. Meninggalkan kafe.
Di otaknya masih terbayang-bayang kejadian barusan, hal itu menyisakan pertanyaan yang makin gelap: Siapa sebenarnya William? Dan apa yang dia inginkan dariku?
Saat sampai di rumah, Ifal tampak murung. Langkahnya berat.
Ibunya menyapa dari ruang tamu hendak menuju kamarnya. “Ada apa, Fal?”
Ifal menjawab pelan, tanpa menoleh. “Nggak ada apa-apa.”
Ifal masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Ia duduk di tepi ranjang dan melihat pergelangan tangannya.
Bekas cengkraman William membiru. Bentuknya jelas, seperti bayangan tangan. Ia memutar pergelangannya pelan sambil mengerang pelan.
“Tenaganya kuat banget, padahal dia keliatan lemah.”
Pikiran buruk mulai muncul. Apa dia punya kelainan? Atau, sesuatu yang lebih parah? Cowok homo kah? Ah nggak, nggak, nggak. Aku nggak boleh mikir kayak gitu.
Ia berdiri, keluar kamar dan berniat ke kamar mandi untuk membasuh wajah dan tangannya dengan air dingin, agar pikiran-pikiran buruk bisa menyingkir dari kepalanya. Tapi saat hendak membuka pintu kamar mandi.
Tok. Tok. Tok.
Ifal menghentikan langkahnya. Menoleh ke arah pintu depan.
Tok. Tok. TOK!
Kali ini lebih keras. Kasar. Mengusik.
Jantungnya berdetak cepat. Suara itu seperti memaksa. Jangan-jangan, dia?
Dari kamar, suara ayahnya terdengar.
“Fal? Siapa itu?”
“Aku cek dulu, Yah.” jawab Ifal cepat, menyembunyikan kegelisahan.
Langkahnya pelan, penuh ragu. Bayangan William muncul dalam benaknya. Tapi ada rasa penasaran. Jantungnya berdetak semakin kencang seiring tangannya meraih gagang pintu.
Saat pintu terbuka, tubuhnya membeku.
“William?”
Tapi bukan. Sosok itu pucat, matanya kosong, rambut acak-acakan dan wajah lebih tirus daripada William. Di belakangnya berdiri pria tua berjas rapi, seperti pelayan era kolonial.
“Kenalin. Aku Willie. William itu adikku.” ujar pemuda itu, suaranya datar dan tanpa jiwa. “Dia bilang rasa kamu mirip Anita. Aku mau ngebuktiin itu.”
“Maksud kamu, apa?” Ifal mengernyit, gelisah. Kakinya mundur setapak. Tapi belum sempat menjauh, Willie bergerak cepat, mencoba masuk.
“Hey!” teriak Ifal sambil mendorong pintu.
BRAK!
Tapi tangan Willie, kuat dan dingin, menahan pintu. Dalam sekejap, tubuhnya menyelinap masuk.
Ifal hendak berteriak, namun tangan Willie menutup mulutnya, dingin dan kasar. Yang satu lagi mencekik lehernya, kuku-kukunya tajam, menembus kulit.
“Jangan teriak.” bisiknya. “Sedikit saja, kamu bisa mati.”
Ifal kesulitan bernapas. Rasa sakit menyebar dari leher. Darah hangat mengalir perlahan. Dia mencoba berontak dengan menendang, mendorong dan bahkan menggigit tangan yang membekapnya.
“Mmmgh! Mmmgh!!”
Tapi Willie terlalu kuat, dia seperti tidak bergeming merasa sakit, walau tangannya sudah digigit. Lalu pria tua itu, Alfred, meraih tangan Ifal yang mencoba memukul dan segera mengikatnya cepat dengan tali. Ifal menjerit tertahan, tubuhnya gemetar. Tenaganya kalah kuat bila dibandingkan dengan Alfred dan Willie. Ifal merasa heran dengan kekuatan mereka. Rasanya mereka bukan seperti manusia.
Suara dari dalam kamar terdengar lagi.
“Ifal? Ada apa itu?”
Langkah berat mendekat ke wajah Ifal. Willie mendesis. “Bilang yang tenang. Satu kata saja salah, tenggorokanmu robek.”
Ifal menelan ludah. Napasnya tercekik. Tapi ia tahu, jika ayahnya datang ke ruang tamu dan memeriksanya, dia bisa dibunuh atau bahkan ayahnya juga akan bernasib sama. Dia melihat mata Willie, dingin dan mengancam. Dia merasa kalau masalah ini harus dihadapi seorang diri.
Dengan suara bergetar, Ifal menjawab. “Teman, Yah, ketinggalan barang tadi.”
Beberapa detik hening, tak ada tanggapan, lalu suara itu terdengar menjauh.
“Jangan lupa kunci pintunya kalau sudah” jawab sang ayah dari dalam kamar.
Mulut Ifal kembali dibekap. Kini oleh kain yang sengaja Alfred sumpal ke mulutnya. Tangis tertahan di matanya.
Willie tersenyum. Senyum yang menggambarkan rasa puas dan intimidasi.
Alfred mengeluarkan kain lain dari sakunya. Bau kimia menyengat menampar hidung Ifal saat kain itu menutupi wajahnya. Napasnya makin berat, kesadarannya mulai kabur. Tapi ia masih bisa melihat, namun samar.
“Bagus.” kata Willie datar. “Sekarang, di mana kamar kamu?”
Ifal tak menjawab. Ia hanya menatap kosong. Willie mencengkeram lehernya lebih erat, kuku-kukunya seperti duri.
“Bicara, atau orang tuamu jadi target selanjutnya.”
Ifal bergidik. Air matanya mengalir. Ia menunjuk ujung lorong dengan gerakan kepala lemah. Disana ada sebuah pintu yang tertutup.
Mereka berjalan senyap, nyaris tak terdengar. Ayah Ifal sudah kembali ke ranjang tempat tidur, sedangkan ibunya sudah lama terlelap, mereka tidak tahu kalau diluar kamar ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi.
Ifal, Willie dan Alred masuk ke dalam kamar. Begitu pintu ditutup, dunia Ifal ikut terkunci.
Willie menatap lehernya, masih mengucur pelan darah segar. Napasnya memburu, mata merahnya menyala. Ia mendekat seperti hewan lapar.
Ifal berusaha melawan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengangkat kakinya dan menendang ke arah lutut Willie. Tapi gerakannya terlalu terbaca. Dalam sekejap, Alfred menangkap kaki itu dengan cepat dan kuat, membuat tubuh Ifal kehilangan keseimbangan dan nyaris terjatuh ke belakang.
Belum sempat ia memulihkan posisi, Willie tiba-tiba menekan lehernya dengan brutal, mendorongnya keras hingga tubuh Ifal terhentak ke dinding di belakangnya. Suara benturan menggemuruh dan seluruh tubuhnya bergetar akibat hantaman itu.
DUUGGH!
Kepalanya terbentur keras. Pandangannya langsung mengabur. Dunia di sekitarnya berputar-putar seperti pusaran mimpi buruk yang tak berujung. Tubuhnya jatuh terduduk, lemas tak berdaya.
Willie tak memberi jeda. Tanpa ragu, ia mendekat. Mulutnya terbuka perlahan dan dari balik gusinya, taring-taring panjang dan tajam menjulur keluar, seolah seekor makhluk buas yang kelaparan tengah bangkit dari dalam dirinya.
CETAK!
Taring itu menancap ganas ke leher Ifal.
Rasa sakitnya menjalar cepat, menusuk hingga ke sumsum. Dingin menjalar seperti racun beku, menggantikan setiap denyut hangat dalam tubuhnya. Napasnya tercekat. Tangannya mengejang. Pandangannya semakin gelap.
Sakit.
Dingin.
Menyiksa.
Dalam pikirannya, terlintas wajah orang tuanya, Askara dan Fitri.
Maafkan aku,
Kesadarannya memudar.
Willie mendesah puas. “Aku ingin minum lebih banyak darahnya. Tidak masalah bukan?” Tanyanya kepada Alfred yang sedari tadi berdiri di sebelahnya.
Sebelum dia menjawab, Alfred segera mengeluarkan botol kaca hitam dari dalam jas. Di dalamnya, suntikan kecil berkilat. “Tentu tuan, sisakan saja untuk adik Anda” jawabnya datar.
Willie menyedot darah dari luka di leher Ifal dengan ganas. Sedangkan Alfred menghisap darah Ifal menggunakan suntikan dan menampungnya di dalam Botol. Lalu botol kedua. Dan satu lagi yang terisi cairan kuning.
Willie memiringkan kepala. “Itu penawar kan?”
Alfred mengangguk. “Ya. Tapi yang ini tak sesempurna yang dulu.”
Ia menyuntikan cairan kuning itu ke urat nadi Ifal. “Efeknya hanya menutupi luka luar. Tapi tubuhnya akan tetap bereaksi untuk mengubahnya jadi Vrykolakas, walau lambat, tapi pasti. Mungkin setelah ini dia akan terlihat baik-baik saja, tapi mimpi buruk, hilang arah, atau bahkan kematian. Mungkin saja terjadi.”
Willie tersenyum. “Bagus. Jadi tidak akan ada yang curiga untuk sementara.”
Alfred mengangguk lagi.
Tubuh Ifal perlahan kembali hangat. Luka di leher mengering. Wajahnya tampak seperti orang tertidur, normal. Tapi jiwa di dalamnya rusak.
Alfred membaringkannya di ranjang. Menyelimuti tubuhnya seperti anak yang tertidur lelap.
Lalu Willie berbisik di telinga Ifal, lirih dan tajam. Membisikan mantra.
“Saat kamu bangun nanti, lupakan semuanya. Tunggu sampai aku datang lagi.”
Tubuh Ifal tampak tak sadar. Tapi kepalanya mengangguk pelan. Mantranya berhasil.
Willie dan Alfred keluar tanpa suara. Seolah mereka tak pernah datang.


 risyadfarizi
risyadfarizi