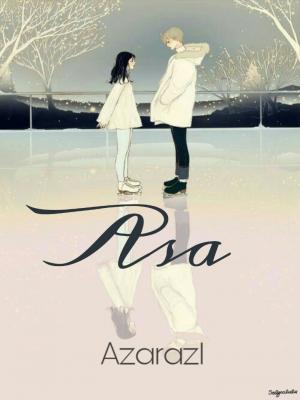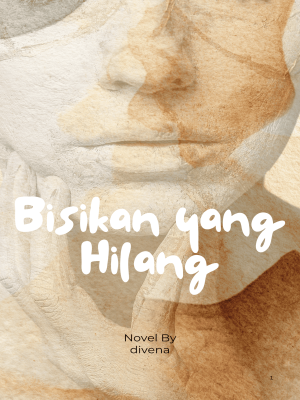Saat Zian semakin menjauh, Nara masih terpaku di tempatnya. Kata-kata yang baru saja ia ucapkan menggema di kepalanya. "Aku milih buat pergi."
Kenapa rasanya begitu sakit? Bukankah ini yang seharusnya membuat semuanya lebih mudah?
Ia menghela napas panjang, mencoba mengabaikan rasa sesak yang mengganjal di dadanya. Namun, saat ia menunduk, ia bisa melihat tangannya sedikit gemetar.
Di sisi lain, Zian melangkah keluar dari kantin dengan langkah lebar. Rahangnya mengeras, dan dadanya terasa penuh dengan amarah yang tak bisa ia luapkan.
Begitu sampai di luar, ia bersandar di tembok terdekat, menarik napas panjang sebelum menghembuskannya kasar.
"Brengsek," gumamnya sendiri.
Ia tak menyangka akan sesakit ini mendengar Nara memilih untuk menjauh darinya.
"Zian."
Suara Reza membuatnya mendongak. Sahabatnya itu berdiri di depannya dengan ekspresi penuh tanya.
"Lo ketemu Nara?"
Zian tertawa kecil, tapi nadanya penuh kepahitan. "Ketemu. Dan dia beneran milih buat pergi."
Reza menatapnya dengan prihatin. "Lo baik-baik aja?"
Zian menyeringai, meskipun tidak ada keceriaan di sana. "Menurut lo?"
Reza diam sejenak, sebelum akhirnya menepuk bahu Zian dengan pelan. "Kalau lo mau marah, kecewa, atau apapun, nggak apa-apa. Tapi jangan hancurin diri lo sendiri cuma gara-gara ini."
Zian mendengus. "Gue nggak selemah itu, Za."
Reza hanya menghela napas, tahu kalau Zian sedang mencoba menutupi perasaannya.
"Lo mau kemana sekarang?" tanya Reza akhirnya.
Zian melirik ke arah lapangan basket yang sepi. "Kemana aja, asal jauh dari sini."
Tanpa menunggu jawaban Reza, Zian melangkah pergi, mencoba mengusir semua perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya.
Sementara itu, Nara masih duduk di kantin dengan pandangan kosong. Ia bahkan tak menyadari ketika Amel kembali dan duduk di sampingnya.
"Ra?"
Nara tersentak, menoleh ke arah Amel dengan mata yang masih menerawang.
"Kamu nggak apa-apa?"
Nara mencoba tersenyum, tapi hasilnya malah terlihat menyedihkan. "Aku baik-baik aja."
Amel mendesah. "Kalau ini yang terbaik menurut kamu, aku nggak akan maksa. Tapi, Ra... aku cuma mau bilang satu hal."
Nara menatapnya, menunggu kelanjutan kata-kata Amel.
"Kamu bisa bohongin orang lain, tapi kamu nggak bisa bohongin hati kamu sendiri."
Kalimat itu membuat Nara terdiam.
Amel menepuk tangan Nara pelan sebelum kembali berbicara. "Coba tanya lagi ke diri kamu sendiri, Ra. Beneran nggak ada bagian kecil dalam hati kamu yang nyesel?"
Nara menggigit bibirnya, mencoba menyangkal. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu jawabannya.
Ada.
Dan bagian itu semakin besar setiap kali ia mengingat tatapan terakhir Zian sebelum pergi.
***
Hari-hari berlalu, dan Zian benar-benar membuktikan kata-katanya.
Ia tak lagi mencari Nara, tak lagi menanyakan kabarnya pada Amel, tak lagi memperlihatkan sedikit pun kepedulian seperti sebelumnya. Jika mereka kebetulan bertemu di koridor, Zian akan melewatinya seolah ia tak pernah mengenal Nara.
Tidak ada tatapan tajam penuh protes, tidak ada pertanyaan yang menuntut jawaban. Hanya diam.
Dan diam itu justru membuat dada Nara terasa semakin sesak.
"Ra, aku lihat daftar peserta lomba cerdas cermat tadi. Nama kamu masuk!" seru Amel dengan semangat begitu mereka duduk di kantin.
Nara tersenyum kecil. "Iya, tadi Pak Rudi bilang kalau aku salah satu yang kepilih."
"Kamu keren banget! Ini kan lomba tingkat nasional! Siapa lagi yang keipilih selain kamu Ra?"
"Ada Dion, Shafa, sama Satria."
Amel mengangguk-angguk. "Wah, tim lo solid banget sih. Harusnya bisa juara nih!"
Nara hanya mengangguk pelan. Seharusnya ia merasa lebih bersemangat, lebih bangga. Tapi entah kenapa, ada perasaan kosong di hatinya.
"Eh, kak Zian udah tahu belum yah?" Amel tiba-tiba bertanya.
Jantung Nara mencelos.
"Aku nggak tahu," jawabnya singkat, lalu buru-buru menyeruput jusnya.
Amel mengernyit. "Tapi dia pasti udah denger sih? Ini kan kabar besar, mustahil dia nggak dengar."
Nara hanya mengangkat bahu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia bertanya-tanya juga.
Dan benar saja, Zian tahu.
Ia mendengar kabar itu dari salah satu juniornya di tim basket.
"Kak Zian, udah denger belum, kalau Nara jadi salah satu perwakilan sekolah kita untuk ikut lomba tingkat nasional?"
Zian menghentikan langkahnya di lorong menuju lapangan. "Bukan urusanku." jawabnya cepat.
Juniornya terlihat bingung, dia hanya takut salah bicara. Tapi dia tidak mungkin salah, karena setahu dirinya, Nara dan Zian cukup dekat. Dan kabar ini seharusnya membuat Zian bangga. Tapi respon yang dia dengar, tidak sesuai ekspektasinya.
Sementara itu, Zian tak mengerti kenapa hatinya terasa berat saat mendengar nama Nara. Kenapa meskipun ia sudah berusaha mengabaikan, setiap kali mendengar sesuatu tentang gadis itu, dadanya tetap berdenyut aneh.
Tapi, bukankah ini yang Nara mau?
Bukankah gadis itu yang memilih menjauh?
Ia menguatkan hatinya. Jika Nara bisa bersikap seolah tak ada yang terjadi, maka ia juga bisa.
Hari pengumuman peserta lomba tiba, dan pihak sekolah mengadakan acara kecil di aula untuk memperkenalkan tim yang akan bertanding.
Nara berdiri di atas panggung bersama tiga peserta lain, sementara kepala sekolah memberi sambutan. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat para siswa duduk di kursi mereka, beberapa berbisik-bisik, beberapa bertepuk tangan.
Lalu matanya menangkap sosok Zian.
Ia duduk di barisan belakang bersama Reza dan beberapa anak basket lainnya. Tatapannya datar, sama sekali tidak menunjukkan ekspresi bangga atau peduli.
Bahkan saat nama Nara disebut oleh kepala sekolah dan para siswa mulai bertepuk tangan, Zian tidak melakukan apa-apa.
Tidak tersenyum. Tidak menepuk tangan. Tidak menatapnya lebih lama dari satu detik.
Dan itu… lebih menyakitkan daripada jika Zian marah padanya.
Ketika acara selesai dan Nara turun dari panggung, Amel langsung menghampirinya dengan penuh semangat.
"Ra! Gila, ini keren banget! Lo bakal tanding di tingkat nasional!"
Nara tersenyum tipis. "Iya, Mel."
Tapi Amel segera menyadari sesuatu. "Lo kenapa? kayak gak seneng gitu sih?"
Nara tertawa kecil. "Nggak, aku baik-baik aja kok. Ayo kita ke kelas Mel."
Bersambung


 riska_awalliah
riska_awalliah