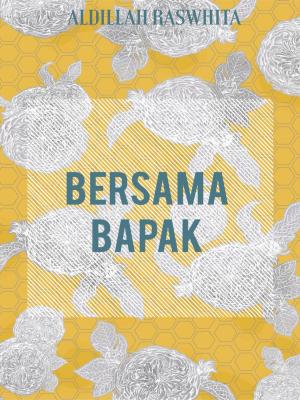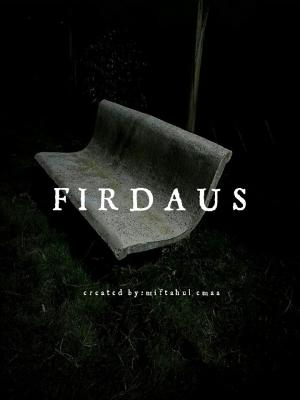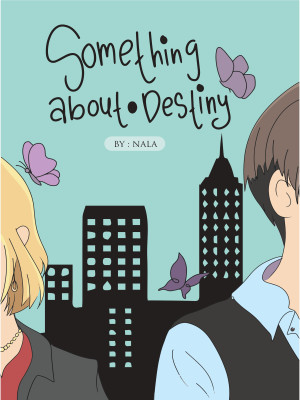Sepulangnya ke rumah, Samara mencoba menghubungi nomer handphone ibunya kembali. Pada dering kelima, panggilan telepon akhirnya diterima. Ia lega sekali bisa mendengar suara ibunya lagi.
“Samara, apa kabar kamu di sana?” tanya ibunya, suaranya khas wanita Solo yang lembut dan anggun.
“Di sini baik, Bu, alhamdulillah,” ujar Samara. “Ibu bagaimana di sana?”
Suara motor dan mobil terdengar bising di latar, ibunya lanjut berbicara, “Ibu lagi dalam perjalanan ketemu orang yang mau nyambung bisnis dengan Sendang Laras.”
“Oh, orang yang jualan lukisan di Bali, ya, Bu?” tanyanya, sekedar mau memastikan.
“Iya, dia punya toko di Bali. Ibu ditawari beli per paket, harganya lebih murah dari pada beli satuan. Nantinya Ibu berencana pajang semua lukisannya di toko Sendang Laras,” ujarnya. “Sebenarnya dia masih bersaudara jauh sama Ibu.”
Lantas ia menggerutu, “Samara saja belum pernah Ibu bawa ke Sendang Laras. Padahal sudah setahun tinggal di Solo. Apalagi dikenalin sama saudara-saudara Ibu langsung.”
“Nanti setelah Ibu pulang, kita bisa jalan-jalan bersama,” gumam ibunya, memberikan harapan.
Samara tersenyum lebar. Saat itulah ia teringat surat misterius yang diterimanya pagi ini. Secepatnya ia ingin menanyakan, “Oh, iya, Bu, tadi pagi ada—”
“Sudah dulu ya, Sam,” potong ibunya, terdengar buru-buru. “Ibu sudah mau sampai di lokasi pertemuan, nanti kita bisa telponan lagi.”
“Oh, ya sudah—” gumamnya pasrah. “Hati-hati di jalan ya, Bu.”
Padahal ia sangat ingin mengonfirmasi; apakah sang ibunda mengenal Pak Soeprapto? Sayang, ibunya terburu-buru menutup telepon. Rasa penasarannya pun harus ditunda sampai nanti bisa menghubungi ibunya lagi.
Menjelang langit gelap, sambil menunggu adzan maghrib, Samara berselonjor di atas kasur kamarnya. Ia membuka buku yang baru dibelinya tadi di acara book signing.
Sebelum ia merobek plastik buku, sejenak ia mengamati cover buku biru tersebut. Ada gambar pegunungan dan bola dunia. Nama sang penulis terpampang jelas di bagian bawah cover, sekali lagi dibacanya, “Nathan Woroyo—”
Setelah membuka bungkusan plastiknya, ia langsung membuka lembaran paling akhir. Ia ingin mengintip sedikit latar belakang si penulis. Nathan lulusan diploma Sejarah di Australia. Ternyata masih seumuran dengannya. Tahun lulus kuliahnya pun sama. Sekilas info pada halaman si penulis membeberkan; Nathan sering melakukan pendakian dan penulusuran ke berbagai wilayah di Indonesia. Dalam buku yang ditulisnya pertama kali itu, ia lebih banyak mengisahkan pengalaman manis pahitnya di kawasan Mistis Rimak. Samara belum pernah mendengar nama tempat tersebut. Dari info di bukunya, tempat di Kalimantan Barat itu banyak menyimpan misteri.
Samara segera membuka acak lembaran bukunya. Ia menemukan beberapa footnote yang menyematkan nama ayahnya. Salah satu buku ayahnya yang sering dijadikan acuan si penulis berjudul; Sejarah Budaya yang Terlupakan. Bukan judul yang menarik, bahkan mungkin banyak orang yang tak mengenal buku sang ayah. Cover bukunya saja nampak amat jadul untuk selera orang jaman sekarang. Mungkin bagi para sesepuh sejarawan dan budayawan di Solo, tulisan Bung Pierre Utomo masih banyak dikenang. Ia tak menyangka, pemuda seusia dirinya seperti Nathan berminat dengan karya ayahnya.
Belum selesai membaca buku, Samara sudah menguap beberapa kali. Karena keburu mengantuk, ia menutup bukunya.
Tiba-tiba suara ketukan di pintu kamarnya terdengar. Si Mbok setengah mengintip di ambang pintu seraya menyeru, “Ndoro, jangan tidur kalau menjelang maghrib! Ndak bagus!”
“Aduh, Mbok, lima menit doang kok,” gerutunya seraya bersembunyi dibawah bantal.
“Mbok sudah panaskan semur ayamnya untuk makan malam, nggih,” sahutnya.
Ketika adzan sudah terdengar, Samara akhirnya beranjak dari kasur. Walau rasa ngantuk masih kuat menganggunya, ia tetap sembahyang tepat waktu.
Sejam kemudian, Samara lanjut makan malam. Saat itu ia mendapat pesan singkat.
Ibu:
Sam, Ibu rencana menginap 2 hari saja di Bali. Paling hari senin malam pulangnya.
Sudut bibirnya terangkat. Ia amat senang membaca pesan dari ibunya. Itu berarti rencana jalan-jalan bersama sang ibunda akan segera terlaksana. Ia hanya harus bersabar menunggu waktu kepulangan ibunya ke Solo.
***
Esoknya, hari Minggu pagi, Samara mendapat kiriman foto dari ibunya. Karena baru bangun, ia mengucek matanya beberapa kali. Barulah ia mencermati foto di layar handphone miliknya itu. Ia terkekeh mendapati ibunya nampak bahagia berfoto sendirian di tepi pantai.
Sepanjang hari itu mereka saling berkirim foto. Samara terkadang iseng mengambil foto keringetan Mbok Miyem yang sedang bersih-bersih di rumah. Kadang ia memamerkan foto selfie dirinya, begitu juga dengan ibunya. Mereka tak bosan saling merindu.
Usai kenyang, ia berjalan-jalan mencari udara segar di teras. Ia melihat sisa-sisa sesajen di meja teras masih belum dibersihkan oleh si Mbok. Bunga-bunga tabur di piring sudah nampak layu. Dupa-dupa di dalam kendi juga masih ada. Seketika itu ia mengernyit kesal melihat pemandangan di seberangnya.
Sejenak ia bersender di ambang tembok pintu teras. Ia menengadah memandang langit malam. Bulan hampir membentuk purnama di atas sana. Sesekali dalam benaknya terbesit mau melanjutkan hidup bagaimana tinggal di kota Solo. Ibunya bahkan sudah mempertanyakan apa yang akan dilakukannya setelah lulus kuliah. Sudah setahun menjadi pengangguran, Samara belum berniat mau mencari kerja. Lagi pula ibunya berharap ia akan meneruskan bisnis batik dan jajanan lokal di Sendang Laras.
Tiap malam, udara di rumah terasa dingin tanpa harus menyalakan AC. Udara malam yang semakin dingin membuatnya memeluk erat bahunya. Seharusnya ia memakai cardigan untuk menghangatkan tubuhnya. Namun ia terlalu malas untuk bolak-balik ke kamar. Ia masih ingin melamun di ambang pintu teras. Samara hampir tiap hari suka memakai atasan tank top dan rok kain tumpuk. Malam itu ia memakai atasan polos berwarna hitam.
Kala merasa seperti ada yang wara-wiri di belakang punggungnya, ia menengok.
“Mbok?!” sahutnya, heran. Sekali lagi ia berteriak, “MBOK MIYEM?”
Ia menengok ke kanan dan ke kiri di ruang meja makan. Tidak ada siapa pun di sana. Ia coba memeriksa ke dapur. Ternyata hanya ada denging bunyi teko yang dipanaskan di atas kompor.
Hampir saja air teko luber jika ia tak segera mematikan nyala apinya. Lantas ia menggerutu kesal, “Ih, si Mbok ke mana, sih?”
Beberapa kali serasa ada angin dingin berhembus di belakangnya. Sontak ia menengok kaget. Lampu menyala terang di dapur dan ruang makan. Namun tak didapatinya ada siapa pun. Sudut matanya kerap mendapati bayang-bayang hitam menyalip di ruangan. Rasanya bagai ada yang sedang wara-wiri di sekitarnya.
Padahal masih jam delapan. Namun nuansanya terasa bagai tengah malam. Ketika mendadak suasana di rumah sangat sepi, bulu kuduknya berlahan merinding. Pikirannya pun melayang ke mana-mana. Mungkin acara ritual dan semedi yang suka dilakukan ibunya menyebabkan suasana jadi agak mistis di rumah. Ingin rasanya ia menuduh sisa-sisa sesajen yang belum dibersihkan di teras sebagai dalangnya.
Sekali lagi ia menyeru kesal, “MBOK!”
Si Mbok baru terlihat keluar dari kamar mandi di ujung koridor dapur.
Sambil terburu-buru mendatanginya, si Mbok berujar, “Wonten menopo, Ndoro? Saya tadi di kamar mandi—”
Sejenak ia mengusap tengkuk lehernya. Ternyata memang tak ada orang di dapur dan ruang makan. Lantas bayang-bayang hitam itu dari mana asalnya?
Samara menatapnya kesal seraya melayangkan gerutu, “Mbok, lain kali jangan ditinggal kalau kompor nyala. Tadi air tekonya hampir luber.”
Si Mbok terkejut mendengarnya. Segera saja si Mbok memeriksa keadaan teko. Sambil tersenyum-senyum, si Mbok berkata, “Oalah, si Mbok mau buatkan teh hangat buat Ndoro. Ternyata si Mbok lupa ngecilin apinya—”
“Ya sudah, aku mau tidur dulu. Tehnya nanti langsung kirim ke kamarku, Mbok,” ujar Samara. Lalu melipir pergi ke kamar tidurnya.
Si Mbok mengangguk-angguk patuh sambil menyiapkan cangkirnya.
***
Hari yang ditunggu tiba, Samara menyeringai saat melihat tulisan Senin pada layar handphone. Kemarin ibunya sudah memberitahu akan pulang malam. Namun Samara tetap ingin memastikan bahwa ibunya tak akan merubah rencananya. Ia menelponnya pagi-pagi.
Beberapa kali ia coba hubungi, panggilan telepon belum diterima ibunya. Segera ia menulis pesan singkat.
Samara:
Bu, jadi pulang hari ini, kan?
Usai pesan terkirim, ia lanjut menjalani hari Senin seperti biasa. Sambil menunggu-nunggu ibunya membalas pesan, Samara menonton siaran televisi. Namun pikirannya tak bisa fokus. Dalam benaknya ia terus membayangkan kesibukan hari terakhir ibunya di Bali.
Saat siang tiba, Samara mencoba menghubunginya lagi. Kali ini ia memincingkan mata ketika pesan singkatnya tak terkirim. Bahkan nomer ibunya mendadak tak bisa dihubungi. Mendadak ibunya serasa menghilang dari radarnya.
Samara terus menggigit jari jemarinya dengan resah. Ia sangat cemas memikirkan mengapa panggilan telepon ke ibunya tidak bisa terhubung. Pikirannya meracau lagi, takut membayangkan sesuatu terjadi pada ibunya. Apalagi ia tak kenal siapa pun yang tengah menemui ibunya di Pulau Dewata. Tidak ada kontak lain yang bisa dihubunginya jika terjadi apa-apa dengan ibunda.
“Leh weleh, Ndoro—” si Mbok mencoba menenangkannya, “Mungkin Gusti Laras mendadak ada urusan, makanya belum sempat menerima telponnya Ndoro Ayu.”
Samara mendongak padanya dan menyahut, “Tapi HP Ibu mati, makanya aku cemas.”
Usai menyajikan kopi susu padanya, si Mbok menghembuskan nafas panjang. “Mungkin nanti sore Ndoro bisa telpon lagi. Bisa jadi Gusti Laras lagi sibuk banget. Mbok tinggal dulu ya, mau masak serundeng.”
Samara hanya menatap kepergiannya sambil sesekali menggigit jari telunjuknya.
Sampai malam tiba, Samara menunggu di kasur kamarnya. Ia menatap gelisah pada layar handphone yang digenggamnya. Pesan-pesan terakhirnya masih belum terkirim. Nomer kontak ibunya juga masih belum bisa dihubungi.
Apa saja bisa terjadi, di mana saja, kapan pun. Namun ia mencoba menahan pikirannya untuk tidak meracau gila. Ia tak mau berpikir aneh-aneh tentang keadaan ibunya. Ia sekedar berharap ibunya lupa mengisi baterai handphone. Seketika itu akal sehatnya berlogika; bagaimana mungkin hal penting dilupakan ibunya? Bukankah ibunya butuh untuk menghubungi orang yang ada di Bali?
Samara sontak mengacak-acak rambut gelapnya. Ia berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran yang membuatnya gundah. Mungkin saja ibunya berubah pikiran, rencana mundur untuk pulang hari Senin.
Usai berdo’a semua baik-baik saja pada ibunya, Samara pergi tidur. Ia mencoba menenangkan pikiran berkecamuknya.
Di kala sudah terlelap, bayang-bayang rasa gundah gelisah malah semakin menghantuinya. Alam bawah sadarnya bagai bermain intrik padanya. Ia serasa terjebak dalam alam tidur yang tak dapat dikuasainya.
Tiba-tiba saja ia sudah menginjakkan kaki di atas lantai kayu. Ia merasa tidak asing dengan keberadaan ruang di sekitarnya. Sejenak ia mengerjap dan mengucek matanya.
Bagai benar-benar sedang terjaga. Ia tak dapat membedakan apakah ia sedang berada di alam nyata atau mimpi. Ia tiba-tiba sudah berada di rumah tua yang pernah sekali dilihatnya dalam mimpi yang amat buruk. Nuansanya pun serupa dengan mimpi tersebut.
Ketika membalikkan badan, ia melihat siluet ibunya duduk di antara banyak sesajen di lantai. Dirinya pun resah kepikiran ibunya yang masih terobsesi melakukan ritual. Bahkan di tempat yang terasa angker di sini baginya.
Samara akhirnya berseru, “Bu! Ibu ngapain sih di sini?!”
Wanita bersanggul dan berkebaya itu tetap duduk bersimpuh. Samara mengamati heran apa yang sedang dilakukan ibunya.
“Bu! Ayo kita pulang!” tegur Samara.
Namun wanita itu tak bergerak sama sekali. Beliau tetap duduk tegap menghadap meja kayu berisi banyak lilin bercawan perak yang mencair demi waktu.
Samara geram dengan sikap tak acuh ibunya. Ia merasa ada yang tak beres dengan tempat ini. Apalagi sikap aneh ibunya semakin membuatnya was-was.
Segera ia mendatangi dan menggoyangkan bahu ibunya. Seketika itu ia mengernyit heran. Bahu ibunya terasa amat keras dan dingin ketika disentuh. Bagai jasad mayat yang sudah mengeras. Samara semakin merasa gelisah.
Ia tetap merasa harus memaksa ibunya pergi dari sini, “Bu—”
Berlahan ibunya menengok ke arahnya. Seketika itu Samara panik terjatuh ke lantai, tergopoh-gopoh menjauhinya. Ia terkejut luar biasa mendapati wajah ibunya berlumuran darah. Saat menyadari raut wajah lara ibunya, Samara kembali mendatanginya, cemas.
Ia menyahut resah, “Bu! Ibu, kenapa?!”
“Samara—” bisik ibunya, lemah.
Ia tak sabar mendengar lanjutan ucapannya.
“Ada hal-hal yang kita yakini, tidak selalu urusannya dengan duniawi.”
Jantungnya terasa berhenti berdegup. Ia langsung mengernyit bingung. Ia tak asing dengan ucapan ibunya itu.
Seketika itu suara-suara gaduh terdengar. Ketika ia memalingkan wajah untuk melihat, ia syok bukan main. Bagai teror malam yang menerkam jiwa. Dengan sangat nyata ia melihat wujud-wujud menyeramkan di luar rumah. Makhluk-makhluk setan itu nampak kelaparan sambil menggeliat di kaca jendela.
Ketika kembali menengok, mendadak ibunya membungkuk padanya dan berteriak kencang, “BUKALAH MATAMU!”


 keefe_rd
keefe_rd