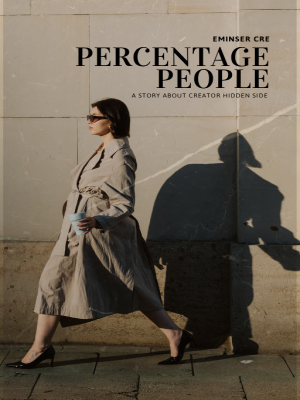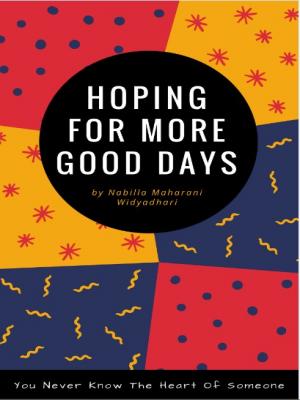Semakin larut, acara semakin seru. Namun, Ara tidak bisa sepenuhnya menikmati, pun dengan kedua sahabatnya yang ketir-ketir karena melihat Ara yang lebih banyak bengong.
“Gue kebelet pipis,” beri tahu Ara.
“Gue temenin?” Monic menawarkan diri.
“Lo pikir gue anak TK? Atau lo sekalian mau cebokin gue?” Ara berseloroh demi menghibur diri.
Vika menjitak kepala Ara. “Udah, buruan sana.”
Secepat kilat Ara lari menuju kamar mandi untuk mengosongkan kandung kemihnya. Setelahnya, dia mencuci tangan di wastafel sembari mengamati pantulan dirinya sendiri di cermin.
Ara menarik masing-masing sudut bibirnya ke atas dan dia tampak tersenyum. Sayangnya itu tak bertahan lama karena beberapa saat kemudian tangisnya pecah. Tak seorang pun tahu betapa takutnya dia sekarang ini. Tubuh Ara gemetaran. Sel-sel otaknya serasa mati karena tidak bisa digunakan untuk berpikir.
Ara berani bersumpah demi apa pun jika dirinya belum siap meninggalkan dunia ini beserta isinya. Dia masih ingin makan masakan Mama, dia masih menanti Papa membelikannya mobil, dan dia juga masih ingin bersama-sama dengan kedua herdernya. Vika dan Monic pasti akan menangis jika dia mati. Lalu Hendra, cowok itu pasti akan menyesal seumur hidupnya karena merasa merampas waktu yang seharusnya digunakan untuk mencari si ‘cowok kekurangan cinta’.
Ara menarik tisu dan menghapus air mata yang membasahi wajahnya, mencoba untuk membesarkan hati jika ramalan itu hanyalah isapan jempol belaka. Tepat saat itulah sebuah suara menyusup ke dalam indra pendengarannya.
“Ra....”
Ara membalikkan badan, celingukan sendiri. “Ini masih jam sepuluh, kenapa udah dateng aja sih malaikat pencabut nyawa?”
Ara bergegas keluar dari kamar mandi dan dia mendapati sosok itu. Cowok berpenampilan serbaputih, rambut acak-acakan, dan wajah kucel.
Prince.
“Lo gila!!! Sumpah lo—”
Ara belum menyelesaikan umpatannya saat Iago memeluknya tanpa izin. “Berhenti! Berhenti nyumpahin gue, Ra. Karena gue nggak bakalan pergi sekalipun lo nendang gue.”
“Lo kenapa bisa ada di sini?”
“Hendra minta tolong sama gue buat bantu lo cari cowok itu,” jawab Iago. “Dia khawatir banget, tapi dia juga nggak ngerti harus gimana.”
Ara melepaskan diri dari Iago, kemudian mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Dia tersenyum miring. “Dan emangnya lo ngerti?”
Iago menggeleng.
“Terus kenapa lo di sini?!”
“Kalau emang hari ini hari terakhir lo, gue bakalan ada di sisi lo buat ngelawan malaikat pencabut nyawa.”
“Oh....” Ada sesuatu yang bergetar di dada Ara. Bukan perasaan takut, tapi entah apa. Jauh di dalam diri Ara, dia senang bisa kembali melihat Iago.
Tubuh Ara yang semula bersandar di dinding merosot, terduduk di lantai. “Gimana kabar lo?”
Iago ikut-ikutan duduk di lantai, persis di sebelah Ara. “Lo mau jawaban jujur atau bohong?”
Ara mendengus. “Terserah lo.”
“Kabar gue nggak baik.”
“Lo ribut lagi sama bokap lo?” Kini Ara menoleh pada lawan bicaranya. Ada segumpal rasa penasaran yang menggelayuti benaknya.
“Bokap gue selalu marah-marah dan gue nggak ambil pusing.” Iago mendesah pelan. “Gue tahu masalah itu pasti ada selama gue masih bernapas, tapi setidaknya gue udah berusaha semampu gue buat hadapi semuanya.” Lalu Iago menoleh pada Ara, menatap cewek itu lekat-lekat. “Sekarang itu yang jadi masalah bukan gue. Melainkan lo, Ra.”
Ara diam seakan kehabisan kata.
Iago meraih tangan Ara. “Gue nggak mau lo mati, Ra. Gue bakal lakuin apa pun biar lo nggak mati.”
Kecemasan mendominasi wajah Ara. “Gue bingung sama perasaan gue sendiri, Go.” Dia berpaling untuk menghindari tatapan Iago. “Jujur gue kangen sama lo.”
Iago menarik sebelah sudut bibirnya.
“Jangan ge-er lo.” Ara meninju pelan bahu Iago. “Gue pikir semua bakalan kembali seperti semula waktu kita jalan sendiri-sendiri. Tapi nyatanya gue ngerasa ada yang nggak pas. Gue bahagia jalan sama Hendra, cuma....” Ara menggigit sudut bibirnya.
“Cuma...?”
“Di dalam sini,” Ara memegang dadanya, “terasa ada yang kosong. Seolah ada yang bawa lari hati gue.” Ara masih memegang dadanya, merasakan bila sesuatu di balik rongga dadanya berdegup semakin cepat.
Ara meremas bagian depan kausnya, berharap debar-debar di balik rongga dadanya mereda. Namun yang ada malah semakin menggila.
“Kalau gitu berhenti,” desis Iago.
Ara menatap Iago penuh tanda tanya.
“Berhenti cari cowok itu,” lanjut Iago.
“Dan gue bakal mati.”
Iago menggeleng cepat, menepis kalimat Ara. “Lihat gue.” Iago memegang masing-masing lengan Ara dan menghadapkannya padanya. “Jatuh cinta sama gue, Ra,” pinta Iago. “Bisa, kan?”
Untuk sesaat dunia di sekelilingnya terasa berhenti berputar. Ara membeku tanpa tahu apa yang terjadi. Ketika sadar, dia spontan mendorong cowok di dekatnya tersebut.
“Tadi waktu di rumah gue emang sempat berpikir kalau gue jatuh cinta sama lo, tapi nggak mungkin, kan?”
Iago memegang bahu Ara lagi, memaksa cewek itu untuk menatapnya. “Selama kita berjauhan, lo ngerasa kehilangan nggak?” tanya Iago. “Selama kita berjauhan, gue ngerasa kehilangan lo. Hati gue kosong karena lo udah nggak ada di hari-hari gue. Jujur sama diri lo sendiri, lo ngerasa kayak gitu juga, kan?”
Ara tercenung. Tidak membantah, tidak juga mengiyakan. Cinta yang selama ini dia kira selalu indah dan menyenangkan, rupanya tidak sesederhana itu. Setiap pertengkarannya dengan Iago, kejengkelannya pada Iago, juga rasa ingin menolong yang tak lagi dapat dibendung ... itu hanya sedikit dari banyak rupa cinta.
“Selama ini gue kira gue benci sama lo,” bisik Ara.
“Batas antara benci dan cinta itu tipis, Ra, yang kadang bikin lo sendiri nggak sadar lo ada di mana,” beri tahu Iago. “Kalau lo nggak jatuh cinta sama gue, lo nggak mungkin sampai bangun rumah di hati gue.” Iago nyengir. “Terus rumah yang terlanjur lo bangun, lo tinggal pergi gitu aja. Sekarang hati gue rasanya kosong.”
Ara tak merespons apa-apa.
“Sebenernya gue pengin ngomong soal ini waktu kita di rumah sakit, tapi gue mau lo sendiri juga sadar tentang perasaan yang lo punya buat gue.”
“Kenapa lo bisa yakin kalau gue bisa jatuh cinta sama lo? Sedangkan gue sendiri nggak yakin.”
“Saat lo lebih milih datang ke rumah sakit buat gue dan bilang kalau lo nggak bisa jatuh cinta sama Hendra, saat itulah gue yakin kalau lo punya perasaan yang sama kayak gue. Lo itu bukannya nggak yakin, melainkan nggak mau mengakui perasaan yang lo punya buat gue.”
Lama, mereka diam tanpa kata, melewatkan begitu saja setiap detik berharga yang harusnya mereka gunakan untuk saling berterus terang.
Ara bungkam, sedangkan Iago menunggu.
Ara beringsut, memberi jarak agar dia bisa berpikir dengan lurus. Ara mengingat-ingat kembali perkataan Madam Maris, bahwa cowok itu beriringan dengannya, tapi tidak bersinggungan. Mirip dengan dirinya dan Iago. Mereka berdekatan, saling tahu, akan tetapi tidak pernah saling menyapa.
Lalu, soal cowok yang kekurangan cinta....
Ara tersentak di tempatnya. Baru memahami jika maksudnya bukanlah cowok yang mengharapkan cinta darinya, melainkan cowok yang hampir-hampir tidak menerima cinta dari orang-orang di sekelilingnya. Hidupnya selalu tertekan dan butuh ditolong.
“Lo bener, Go,” kata Ara setelah kembali menemukan suaranya. “Lo yang diam-diam bawa lari hati gue. Bikin gue kelimpungan setengah mati sampai gue nggak ngerti sama perasaan gue sendiri.”
Iago tertegun.
“Tapi lo itu terlalu jauh buat gue jangkau,” lirih Ara dengan bibir gemetar. “Mungkin itu yang ngebuat gue sama sekali nggak kepikiran kalau gue jatuh cinta sama lo.”
“Ra....”
“Kenapa harus lo sih? Lo kenapa jahat banget sama gue?!” Ara mendorong Iago, memukuli dada cowok itu dengan membabi buta. “Kenapa lo maling hati gue tanpa izin? Lo tega banget bikin gue kelimpungan.”
Iago mematung, sama sekali tak beranjak dari tempatnya. “Karena dari awal gue nggak bermaksud maling hati lo. Gue juga nggak menyangka kalau bakal jatuh cinta sama lo.”
Kalimat itu menghentikan Ara, dia berhenti memukuli Iago dan terisak. “Terus gue harus gimana?”
“Lo tinggal jadi pacar gue.”
“Cih!” Ara berpaling, masih berusaha menepis. “Gue masih nggak yakin.”
Iago menarik masing-masing sudut bibirnya, membentuk senyuman datar tanpa ekspresi. Sebelah tangannya terulur untuk menyeka lelehan air mata di pipi Ara.
Sentuhan Iago membuat dada Ara yang sudah tenang kembali memberontak, berdebar tanpa ampun. Ini bukan kali pertama dia berada dalam jarak sedekat ini dengan Iago, hanya saja mendadak semua terasa berbeda.
“Oke,” kata Iago kalem. “Kita tunggu sampai jam dua belas. Kalau lo nggak mati,” Iago menelengkan kepala, “berarti lo emang jatuh cinta sama gue.”
“Kalau gue mati?”
“Gue yakin lo nggak mati,” tukas Iago cepat.
Ara menepikan tangan Iago. “Dan gue harus jadi pacar lo? Pacar sungguhan?” tanyanya, menekankan kata sungguhan.
Iago tersenyum. Cowok itu berpaling sebentar ke arah lain sebelum kembali menatapnya. “Gue nggak maksa,” katanya. “Bagi gue, yang penting lo nggak mati.”
“Go—”
“Lo mau cabut nggak?” serobot Iago. “Gue laper.”
“Gue pengin, tapi gue nggak bisa.”
“Lo bisa,” tegas Iago. Cowok itu menyambar tangan Ara, menggandengnya paksa, membawanya kabur dari sekolah.
“Go, gue harus jaga—”
Iago tak peduli. “Kan ada Vika sama Monic.”
“Tapi—”
“Jangan bantah lagi atau mau gue cium?”
“Iago!”
Ara membuang napas, mengeluarkan sesak di dadanya. Dalam genggaman Iago, Ara percaya jika semuanya akan baik-baik saja. Soal perasaannya pada Iago, jujur dia sendiri masih belum sepenuhnya yakin. Sumpah, semua ini begitu tiba-tiba. Ara butuh waktu untuk mengakui semuanya.
“Kalau emang gue nggak mati. Gue mau jadi pacar lo.”
Iago mempererat genggamannya pada Ara. “Lo pasti bakal jadi pacar gue.”
*
Iago mengajak Ara makan di sebuah warung nasi goreng yang letaknya tak jauh dari sekolah. Ara sempat menyipit berkali-kali, heran pada Iago yang ternyata mau makan di warung pinggir jalan seperti ini. Malahan Iago dengan santainya duduk di trotoar sembari menanti nasi goreng pesanannya matang.
“Aduh, panas,” kata Ara saat Abang nasi goreng menyerahkan piring padanya.
“Mau pindah ke dalam aja?” tawar Iago. “Tapi di dalam tenda hawanya panas. Kalau di sini masih ada angin yang lewat.”
“Di sini aja deh kalau gitu.”
Iago melepas hoodie-nya, melipatnya dan meletakkannya di pangkuan Ara. “Taruh piringnya di atas situ biar tangan lo nggak kepanasan.”
“Ntar baju kesayangan lo kotor.”
“Kan bisa dicuci.”
“Gue ogah cuciin baju lo.”
“Kan ada si Mbok.”
“Kalau kotorannya nggak bisa hilang gimana?”
“Tinggal beli lagi yang baru.”
Ara mendecak. “Dasar anak Sultan!”
“Ck, mau makan aja pakai ngajakin debat,” gerutu Iago, kemudian langsung menyantap nasi gorengnya.
Ara makan dengan pelan, sesekali memperhatikan cara makan cowok di sebelahnya. Iago makan dengan lahap seperti orang yang seharian tidak makan. Dalam sekejap nasi goreng di piringnya sudah tandas. Dan yang membuat Ara terperanjat adalah ketika Iago meminta Abang nasi goreng membuatkannya satu porsi lagi.
“Lo laper apa kesurupan?” tanya Ara. Sebab menurutnya satu porsi piring saja sudah banyak. Dia bahkan tidak yakin bisa menghabiskan miliknya sendiri.
“Gue miara naga di dalam perut,” jawab Iago sekenanya.
Ara mencubit lengan Iago.
“Aduh-duh,” rintih Iago. “Gue belum makan dari pagi.”
“Kenapa?”
“Gue kepikiran lo terus, sampai nggak nafsu ngapa-ngapain.” Iago meneguk es tehnya. “Waktu Hendra telepon gue tadi, gue langsung ke sekolah. Buat informasi aja, gue belum mandi dari pagi.”
Ara yang sedang mengunyah seketika tersedak. “Njirrr! Lo jadi orang jorok banget sih?! Heran gue.”
Iago nyengir. “Ck, nggak mandi di hari libur itu sah-sah aja kok.”
Malas berdebat, Ara hanya menggumam pelan dan melanjutkan makan.
Jam hampir menunjukkan pukul dua belas malam. Ara betul-betul tidak sanggup menghabiskan nasi gorengnya, sementara Iago yang sudah melahap dua porsi tampak baik-baik saja, sama sekali tidak mengeluh kekenyangan atau semacamnya.
Mereka berdua masih duduk-duduk di trotoar meski sudah selesai makan dan membayarnya. Ara menyambar tangan kanan Iago untuk melihat jam tangan cowok itu. “Pukul 11.58,” desahnya. Pasrah. “Nanti pas kurang semenit gue tutup mata aja ya.”
Iago mengangguk.
Tepat enam puluh detik sebelum pukul dua belas, Ara memejamkan mata dan mulai menghitung mundur dalam diam. Dia menarik napas, menyusupkan oksigen sebanyak-banyaknya untuk meredam ketakutannya.
Enam puluh.
...
Empat puluh.
...
Dua puluh.
...
Sepuluh.
...
Lima.
Empat.
Tiga.
Dua.
Satu.
Tidak terjadi apa-apa.
Jantungnya masih berdetak. Nadinya masih berdenyut. Napasnya masih berembus.
Ara masih enggan membuka mata. Dia takut kalau-kalau saat dia membuka mata, malaikat maut sudah siap menyambutnya.
“Lo mau tutup mata sampai kapan?” tegur Iago.
Sontak Ara membuka mata.
Iago mendesah lega. “Gue pikir lo ketiduran.”
“G-gue masih hidup?!” Ara histeris, mencengkeram erat pergelangan tangan Iago.
“Emang di akhirat ada cowok seganteng gue?!”
Tanpa sadar Ara memeluk Iago dan berteriak kegirangan. “Gue masih hidup! Gue masih hidup! Go, gue masih hidup!!!”
Iago yang tahu mereka jadi pusat perhatian Abang nasi goreng dan dua orang yang sedang makan di situ hanya bisa mengedikkan bahu. Iago sama sekali tak keberatan dengan tingkah Ara.
Baru setelah beberapa saat Iago menegur Ara, “Ra, kita dilihatin orang tuh.”
“Eh, sori.” Ara melepaskan pelukannya dan mengedarkan pandangan ke sekitar, dia mengangguk kecil sebagai permintaan maaf. “Gue nggak mati, Go,” katanya, entah sudah yang keberapa kali.
“Selamat ulang tahun, Ara.”
Ara tersipu. “Makasih ya, Go.”
Iago tersenyum, terlihat amat lega. “Ra, lo mau jadi pacar gue?”
Pertanyaan itu menghentikan sejenak kegirangan Ara, membuatnya terdiam cukup lama. Setelah satu tarikan napas panjang barulah Ara menjawab, “Gue mau.”
“Serius?” Iago terbelalak tak percaya. “Lo beneran mau jadi pacar gue?”
Ara melengos. “Nggak. Gue bercanda doang,” katanya. “Baru kali ini gue ditembak sama cowok yang belum mandi seharian. Mana nembaknya di warung nasi goreng padahal dia anak Sultan,” cibirnya, lalu terbahak.
Iago meraih kedua tangan Ara dan menyatukannya dalam dekapannya. “Sori, gue udah maling hati lo.”
Ara menggigit bagian dalam pipinya. “Go, tapi gue nggak janji kita bisa pacaran yang manis-manis gitu. Gue—”
“Nggak masalah,” serobot Iago. “Gue nggak keberatan kalau kita tetep kayak gini. Adu mulut, saling nyumpahin, atau apalah. Kita pacaran dengan gaya kita sendiri.”
Ara mengangguk.
“Dan yang paling penting....”
Ara mengerjap.
“Lo sekarang pacar gue.”
*


 sandrabianca
sandrabianca