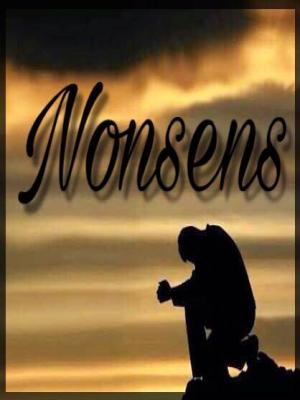I'd never given much thought to how I would die. But dying in the place of someone I love seems like a good way to go.
Kutipan kalimat pembuka yang diucapkan Bella Swan dalam film Twilight itu tiba-tiba saja mampir di benak Ara. Sebelum ramalan itu, dia tidak pernah memikirkan bagaimana caranya mati dan tidak pernah memedulikannya. Bedanya, jika Bella Swan berpikir berada dalam pelukan orang yang dicintai pada saat menjelang ajal adalah jalan terbaik untuk mati, Ara tidak memiliki cowok yang dicintai untuk menangisi kematiannya.
Jam terus berputar ke kanan dan tak ada cara untuk menghentikannya. Seharian ini Ara terus mengurung diri di kamar, membayangkan bagaimana ajal akan menjemputnya.
Apakah jiwanya akan melayang begitu saja ketika dia terlelap? Atau, apakah jantungnya tiba-tiba saja berhenti berdetak ketika teman-temannya sedang menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya?
Jika boleh memilih, Ara akan memilih opsi yang pertama. Mati di hadapan banyak orang bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan.
Hingga detik ini, Ara masih tidak tahu siapa ‘cowok kekurangan cinta’ yang dicarinya. Bagaimana ciri-cirinya, seperti apa rupanya, dan di mana dia. Secuil pun Ara tidak menemukan potongan dari puzzle yang sudah mengacak-acak hidupnya.
Ara duduk di atas tempat tidur, menekuk kaki dan memeluknya, lalu meletakkan dagu di atas lutut. Seperti saran Iago, dia sudah mencoba untuk jujur pada dirinya sendiri, mengingat-ingat semua perasaan yang pernah dirasakannya pada lawan jenis. Namun, Ara merasa tidak menemukan apa-apa.
“Mungkin benar yang dibilang Iago, gue selama ini udah terbiasa dikelilingi cinta, jadi seseuatu yang dianggap orang lain sebagai cinta, buat gue terasa biasa aja,” gumam Ara pada dirinya sendiri.
Sejak kejadian di rumah sakit itu, Ara belum mengobrol lagi dengan Iago. Mereka sering berpapasan di sekolah, akan tetapi tak satu pun dari keduanya yang memiliki inisiatif untuk memulai pembicaraan. Jika dulu semua yang berkaitan dengan Iago selalu menjengkelkan, kini rasanya menjadi aneh. Tanpa disadari, Ara mulai berandai-andai bila saja Iago merupakan cowok yang dicarinya.
Semua yang dilewatinya bersama Iago menjadi sesuatu yang baru dalam hidup Ara. Untuk pertama kalinya, Ara bertemu dengan seseorang yang begitu menjengkelkan, yang dengan gigih mengusik ketenangan hari-harinya. Namun, sebetulnya semua itu memberikan warna baru pada hidup Ara.
Lantas, seperti apa perasaanya pada Iago?
Ara mendengus. Dia tidak merasa seperti jatuh cinta pada cowok itu, tapi saat berjauhan seperti ini ... terus terang Ara merindukannya.
Ara merindukan Iago.
“Ck, mikir apa sih gue?!” Ara menempeleng kepalanya sendiri. “Sadar dong, gue nggak mungkinlah jatuh cinta sama Iago!”
Sesaat setelah mengatakan itu, Ara mulai berpikir ulang. Selama ini mungkin dirinya terlalu abai dan selalu bersikeras menolak apa yang dirasakannya pada Iago. Ara merenung, mencoba sedikit membuka hatinya, jujur sejujur-jujurnya pada dirinya sendiri. Semuanya terasa berbeda ketika bersama Iago.
Ponsel Ara terus-menerus bergetar. Nama Vika, Monic, dan Hendra bergantian muncul di layarnya. Kedua sahabatnya belum tahu bila Ara sudah berterus terang pada Hendra mengenai apa yang terjadi dan seperti apa perasaannya.
Ara sengaja mendiamkan ponselnya. Sebentar saja, Ara ingin berada di dunianya sendiri. Ara tidak ingin ada orang lain yang membuat pikirannya bertambah kacau. Seringnya pikiran dari banyak kepala memang membantu, tapi terkadang itu malah membuat segalanya menjadi jauh lebih ruwet. Jadi menjelang ulang tahunnya—atau sekarang dia lebih suka menyebut hari kematiannya, Ara memilih untuk menghabiskan hari-harinya dengan tenang.
Suara pintu yang dibuka memecah fokus pikiran Ara. Mama masuk ke kamarnya. “Kamu kenapa bengong aja di kamar?”
Ara menggeleng. “Nggak apa-apa, Ma. Lagi males keluar, mending mantengin demo minyak goreng.”
Mama mencebik. “Sok jadi emak-emak kamu ya.”
“Nantinya Ara juga bakal jadi emak-emak kayak Mama.”
Mama mendekati Ara, mengelus kepalanya dengan sayang. “Mama tahu kamu sedang ada masalah. Kalau kamu nggak keberatan, Mama mau kok dengerin.”
“Kok Mama tahu kalau Ara lagi ada masalah?”
“Ya tahu dong. Mama kan kenal anak Mama.”
Ara diam dan menimbang-nimbang, antara menyimpan atau membagikannya pada Mama.
“Ma, kalau Ara mati gimana?”
Mendegar itu, sontak Mama melotot. “Kamu punya masalah sama preman?”
“Bukan, Maaa....” Ara bingung harus memulainya dari mana. “Ara cuma ... aduh, Ma, kematian kan bisa datang kapan aja.”
“Huss! Kamu itu bilangnya kok yang jelek-jelek. Mau ulang tahun itu harusnya berdoa yang baik-baik, bukan malah bayangin yang jelek.”
Ara diam lagi. Mau dijelaskan sampai berbusa-busa Mama juga tak akan paham, terlebih Mama termasuk golongan orang yang anti dengan ramalan dan sebangsanya.
“Dek, itu dicari si Hendra.” Kak Marcel melongokkan separuh badannya ke dalam kamar. “Katanya mau jemput lo ke sekolah. Ada acara apa sih? Bukannya Sabtu ini sekolah libur?”
Ara menepuk dahi. “Astagon dragon! Hari ini kan ada acara keakraban bareng anak kelas 10. Kok gue bisa blank gini sih? Gue kan panitia.”
Kak Marcel mendecak. “Ya dari tadi ente mikirin apa aja, Maemunah?!”
“Mikirin June Oppa.” Kemudian Ara berlari menyongsong poster yang ditempel di dinding dekat pintu kamar. “Oppa, kapan ke Jakarta lagi? Aku tuh capek LDR-an terus,” katanya pada sosok yang ada di poster.
“Ma, tuh anak mending diloakin deh. Ogah banget punya adek kayak gitu.”
Mama terbahak melihat kelakuan kedua anaknya. “Kamu cepetan siap-siap sana,” suruu Mama pada Ara.
“Hendra-nya suruh tungguin bentar ya, Ma. Ara mandinya kilat kok.”
Lagi, wanita itu tersenyum. “Iyaaa.”
“Ma, nanti Ara nginep di sekolah. Acaranya mulai nanti jam lima sore sampai besok sore.”
“Ya udah, Mama bantu siapin barang-barang kamu.”
“Makasih, Ma.”
Masuk ke kamar mandi, Ara menyalakan shower dan menangis. Semua tawa dan kegirangannya tadi hanyalah kedok untuk menutupi kesedihannya. Siapa yang tahu jika tadi adalah terakhir kalinya dia tertawa bersama Mama dan kakaknya?
Mengingat bila semua tawa itu besok akan lenyap dan berganti dengan air mata, hati Ara terasa berdenyut-denyut.
Sakit.
Tak mau berlarut-larut, Ara segera mengguyur wajahnya dan mandi. Jika Bella Swan berpikir berada dalam pelukan orang yang dicintainya pada saat menjelang ajal adalah jalan terbaik untuk mati, maka Ara berpikir berpura-pura jika hari esok masih ada adalah jalan terbaik untuk mati.
*
Hendra yang biasanya mencerocos kali ini lebih banyak diam, pun dengan Ara yang terkesan tidak berbicara jika tidak ditanya. Baru setelah mereka sampai di sekolah, cowok itu membuka suaranya.
“Ra, lo beneran percaya sama ramalan itu?” tanya Hendra sembari mengambil alih ransel Ara.
“Gue juga ogah banget percaya kalau gue belum buktiin sendiri,” balas Ara. “Masalahnya peramal itu tahu semua isi kepala gue, padahal waktu itu gue sama sekali nggak ngomong apa-apa.”
“Bisa aja kebetulan.”
“Nggak ada kebetulan yang angkanya sampai seratus persen,” tukas Ara, membungkam Hendra.
Mereka berjalan menuju ruang OSIS tanpa secuil pun percakapan. Hendra diam. Ara diam. Hanya suara langkah kaki yang memecah atmosfer sunyi mereka.
Sebagian besar anggota OSIS sudah datang, termasuk Vika dan Monic. Ara duduk di sebelah Vika. Monic yang curiga dengan ekspresi Ara langsung tahu jika ada sesuatu yang tidak beres, cewek yang kali ini memilih memakai lensa kontak itu tanpa basa-basi bertanya, “Lo marahan sama Pak Ketua?”
Ara menggeleng lemah.
Vika mengarahkan pandangannya pada Hendra yang sedang mempersiapkan materi rapat di depan, lalu beralih pada Ara. “Lo nggak bisa bohongin kami berdua, Ra. Lo sama Hendra kenapa?”
“Gue udah cerita semuanya sama Hendra, termasuk soal ramalan dan perasaan gue ke dia,” sahut Ara ringkas, tak mau bertele-tele.
Monic langsung panik, sementara Vika membeku.
“Gue nggak bisa jatuh cinta sama Hendra,” pungkas Ara.
“Terus gimana dong? Besok ulang tahun lo yang ke-17.” Monic menggigit sudut bibirnya. “Jangan bilang lo pasrah gitu aja.”
Ara mengangkat bahu. “Terus gue harus gimana? Seberapa keras gue mencoba buat jatuh cinta sama Hendra, gue nggak bisa.” Dia sudah benar-benar pasrah.
“Terus lo bisanya jatuh cinta sama siapa? Iago?” tanya Vika.
Tak ada jawaban dari Ara. Terus terang hatinya meragu.
“Lo jatuh cinta sama siapa aja boleh, Ra. Setelah gue pikir-pikir, Iago lumayan juga.” Vika berusaha membesarkan hati Ara. “Pokoknya lo nggak boleh mati, Ra. Jangan sampai lo mati.” Kedengarannya begitu ketus dan memaksa, tapi sebetulnya Vika tulus.
Ara menarik napas dalam, mengumpulkan udara sebanyak mungkin di paru-parunya. “Udahlah, kita lihat aja apa yang terjadi nanti.”
Sekarang ini apa yang dirasakan Ara seperti tidak nyata. Apa benar dirinya akan mati jika tidak bisa menemukan cowok itu? Entahlah. Ara tidak bisa menjawabnya. Namun, jika memang semua ini hanya mimpi, Ara merasa enggan untuk bangun dan mengakhiri semuanya. Sebab dalam mimpinya, ada sosok Iago. Ara tidak rela jika harus menghapus semua ceritanya dengan Iago.
“Semua sudah datang?” Suara lantang Hendra langsung menarik perhatian semua yang ada di ruangan itu.
Serentak semua menjawab, “Sudah.”
“Oke, kalau begitu bisa saya mulai sekarang, ya?”
Setelahnya, Hendra secara singkat meninjau kembali masing-masing anggota beserta dengan segala persiapannya. Ara, Vika, dan Monic nantinya tidak membaur langsung bersama anak-anak kelas 10 karena mereka ditugaskan di bagian medis. Mulanya Hendra hendak menggandeng anggota PMR, tapi sayangnya anak-anak itu sedang berhalangan, jadilah dia memilih mereka bertiga yang dirasa mampu dalam memberikan pertolongan pertama.
“Ada pertanyaan?” tanya Hendra sebelum menyudahi rapat singkatnya.
Ara mengangkat tangannya. “Gue, Vika, sama Monic harus stand by di tenda medis atau boleh lihat-lihat acara?”
“Kalian atur aja sendiri. Yang penting, waktu ada yang butuh pertolongan, kalian harus siap.”
“Oke.”
“Ada lagi yang perlu ditanyakan?”
Semua menggeleng.
“Baik. Kita bubar sekarang dan langsung masuk ke kelompok masing-masing. Acara dimulai tepat jam lima.”
Usai menuntaskan kalimatnya, Hendra menghampiri Ara yang tampak lesu. “Ra, lo—”
“Gue baik-baik aja.” Ara mengangkat bahu dan mencoba untuk tersenyum. “Kalau emang gue harus mati besok, gue akan jalanin hari terakhir gue dengan sebaik-baiknya.”
“Lo kenapa bisa sesantai itu sih?” tanya Hendra, setengah membentak.
“Kalau gue tegang, ntar badan gue kaku semua pas mati. Kasihan yang mandiin gue.”
“Ara!!!” Kali ini Hendra benar-benar membentak, meski siapa pun tahu dia tidak bermaksud begitu.
Ara mendongak, berusaha keras menghalau air matanya yang nyaris tumpah. Hendra atau siapa saja tidak akan mengerti apa yang dia rasakan. Melihat kematian sudah berada di depan mata, siapa yang bisa santai?
Jauh di dalam dirinya, Ara juga ketakutan setengah mati.
“Udahlah,” lirih Ara sembari menyeka butiran air mata di sudut matanya. “Anggap aja ramalan itu hoax. Cuma itu yang bisa gue lakukan saat ini biar gue nggak takut-takut banget.”
Hendra menarik tubuh Ara, mendekapnya erat dalam pelukannya. “Lo harus percaya kalau lo bisa menemukan cowok itu. Meski di detik-detik terakhir.”
“Gue akan berusaha.”
Bibir Ara berucap seperti itu, tapi hatinya ciut. Ulang tahunnya akan tiba dalam hitungan jam dan sampai sekarang dia tidak tahu keberadaan cowok yang konon katanya sudah mencuri hatinya itu.
Seperti baru saja tersadar, Ara bertanya-tanya, bagaimana bisa dia tidak mengenali pencuri hatinya sendiri?
*


 sandrabianca
sandrabianca