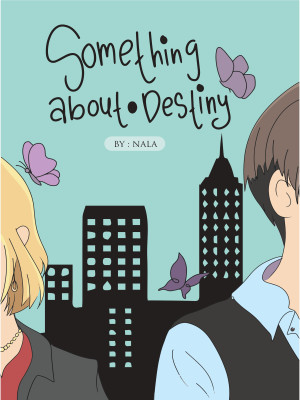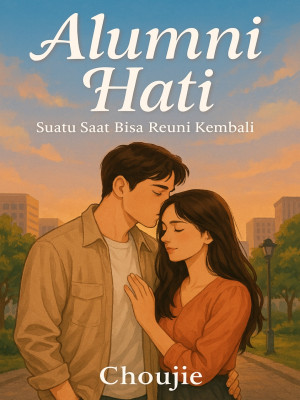Cukup lama Iago menatap pagar berwarna putih yang beberapa saat lalu ditutup oleh Ara. Sosok Ara telah menghilang ke dalamnya, menyisakan bayangannya masih berputar-putar di benak Iago.
Setelah merasa cukup, Iago akhirnya menginjak pedal gas dan perlahan meninggalkan area rumah Ara. Sembari mengemudi, Iago melirik jam di dasbor. Hari ini tidak ada les, juga tidak ada tugas kelompok atau PR berarti yang membuatnya harus sibuk seharian. Seringai tipis perlahan timbul di wajah Iago, belakangan ini dirinya terlalu sibuk memikirkan cara agar Ara bersedia membantunya, kini ketika Ara sudah setuju, Iago malah merasa sedikit bosan.
Tak dapat dimungkiri jika setiap argumennya dengan Ara membuat Iago merasa lebih ‘hidup’. Hari-harinya tak lagi sepi dan monoton. Tak selalu ada tawa, malahan porsi pertengkaran mereka lebih banyak. Sesekali ada air mata, juga sakit hati. Namun semuanya terlihat begitu berwarna. Jadi ketika saat ini Iago membayangkan hari-hari tanpa ada Ara di dalamnya, dia merasa hampa.
Iago takut melewati hari-hari tanpa Ara.
Di sela pikiran Iago yang terbelah antara fokus pada jalanan di depan dan bayangan hari-harinya tanpa Ara, Iago melihat sesuatu yang seketika menyita seluruh fokus pikirannya.
Tak jauh di depan sana adalah mobil milik Papi. Kening Iago mengerut penasaran. Sebagai pebisnis, berada di mana pun, bahkan di tempat yang bukan merupakan wilayahnya sekalipun, memang bukan hal yang aneh. Namun kali ini pikiran Iago menuntut untuk mengetahui lebih lanjut. Sesuatu yang biasanya berlabel ‘masa bodoh’ itu kini telah berubah menjadi ‘ingin tahu’.
Sedan hitam berlogo huruf T tersebut menyalakan lampu sein kirinya, kecepatannya perlahan berkurang sampai akhirnya berbelok ke sebuah hotel bintang lima. Tepat di depan lobi, mobil yang diikuti Iago itu berhenti. Papi keluar bersama dua orang gadis muda. Sontak pemandangan itu membuat Iago menyeringai, rasa bencinya pada Papi kian menjadi. Lebih-lebih setelah diamati, Iago juga mengenali siapa gadis-gadis yang kini menggandeng masing-masing tangan Papi. Agar tidak mencolok, Iago tidak berhenti di lobi, lagi pula masih ada tiga mobil di depannya, jadi Iago rasa kecil kemungkinan untuk ketahuan. Iago keluar dari mobil dan menggunakan jasa valet.
Dengan hati-hati Iago mengikuti Papi dan kedua gadis tersebut. Menangkap samar-samar obrolan mereka, Iago tahu jika ketiganya hendak makan di restoran hotel tersebut saat tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk keras bahunya.
Iago tersentak. Seluruh badannya terasa kaku, kakinya tak lagi dapat digerakkan. Pikir Iago, sopir Papi berhasil memergokinya. Siapa sangka, setelah Iago menoleh, sosok yang membuatnya kaget setengah mati barusan bukanlah sopir Papi, melainkan Daniel.
“Sialan lo!” umpat Iago, masih belum benar-benar pulih dari rasa terkejutnya.
“Lo ngapain di sini? Jadi panggilan tante-tante?” tanya Daniel sarkastik.
“Kalau iya kenapa? Lo mau gabung juga?” balas Iago meladeni Daniel.
Daniel tak merespons.
“Gue ada perlu,” kata Iago seraya kembali melangkah.
Namun lagi-lagi langkah Iago diadang oleh Daniel yang mencengkeram erat bahunya. “Lo kalau mau masuk hotel ganti baju dulu kek. Gue nggak tahu apa tujuan lo kemari, yang pasti penampilan lo mencolok banget,” terang Daniel, memindai Iago dari ujung kepala hingga ujung kaki. “Bro, lo itu masih pakai seragam sekolah!”
Iago membuang napas kasar. Meski tidak diucapkan, Iago mengakui jika Daniel benar.
“Ikut gue!”
Daniel berjalan mendahului Iago, menuju ke lift. Iago sempat ragu, tetapi akhirnya memilih untuk mengikuti Daniel.
“Lo kenapa bisa di sini?” tanya Iago.
“Nggak usah banyak tanya soal itu. Yang terpenting maksud gue baik kok. Anggap aja ini sebagai permintaan maaf karena gue udah bikin cewek lo dalam masalah.”
“Cewek gue?”
“Arabella.”
Ingatan Iago otomatis bergerak mundur dan berhenti di hari itu. Hari di mana Ara dilecehkan oleh orang-orang suruhan Lisa.
“Kalau mau minta maaf jangan sama gue,” ketus Iago. Kemarahannya masih tersisa, walau di sisi lain Iago juga berusaha untuk memahami posisi Daniel saat itu. Lagi pula hari itu Daniel juga sudah melakukan hal yang tepat dengan memberi tahunya.
“Nanti kalau ada kesempatan gue pasti minta maaf sama Ara. Soalnya WA gue diblokir sama dia.”
“Kalau gue jadi Ara juga bakal ngelakuin hal yang sama.”
“Dulu Ara adalah temen chatting-an gue yang paling seru. Jadinya gue agak-agak ngerasa kehilangan.”
Sebelah alis Iago terangkat. “Kalian berdua sering chat WA?”
Daniel mengangguk. “Dulu. Mulanya cuma buat cari perhatian Ara, tapi lama-lama obrolan kami berdua jadi seru.”
“Dan ujung-ujungnya Ara nolak lo,” sambung Iago sinis.
Daniel hanya mengedikkan bahu.
Pintu lift terbuka dan keduanya keluar dari lift. Daniel berjalan terlebih dahulu, sementara Iago mengikuti. Tepat di depan kamar 808 Daniel berhenti, dia mengeluarkan kartu dari saku untuk membuka pintunya.
Masuk ke dalam kamar, Iago mengedarkan pandangannya, memindai ruangan. Sebuah suite room yang jauh dari kata rapi. Baju—yang entah kotor atau bersih—berserakan di lantai, sebagian lagi di atas tempat tidur. Sepasang sepatu terletak di depan kulkas, plastik bekas snack bertumpuk, menggunung di tempat sampah dekat meja televisi.
“Lo hebat banget bisa ngubah kamar hotel jadi sarang demit,” sinis Iago. Dia menoleh pada Daniel yang sedang berkacak pinggang dengan wajah tanpa dosa. “Udah berapa lama lo tinggal di sini?”
“Hampir dua bulan.”
“Kenapa? Lo akhirnya ketahuan sama bokap lo?”
Daniel menggeleng. “Hampir. Lagian gue nggak nyaman di rumah. Ya udah, gue tinggal di hotel aja.”
Iago meringis. Dirinya tak sepenuhnya mengenal Daniel. Namun Iago seperti mengerti apa yang dirasakan Daniel. Biasanya manusia-manusia yang memiliki privilege seperti mereka memiliki alur kehidupan yang tak jauh berbeda.
Serupa dengan Iago yang menyukai musik, akan tetapi ditentang habis-habisan oleh Papi. Daniel yang menyukai futsal ditentang oleh kedua orangtuanya. Yah, rata-rata memang seperti itu. Anak hanya dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan dan meneruskan bisnis mereka. Dari segi materi mereka memang lebih dari cukup, tapi sedikit yang tahu jika hati dan jiwa mereka miskin perhatian dan kasih sayang.
“Nih, lo pakai baju gue!” Daniel melemparkan kemeja flanel merah yang warnanya sudah pudar serta celana jeans pada Iago. “Gue rasa ukuran kita nggak jauh berbeda.”
Iago memandangi baju di tangannya sejenak, kemudian tanpa berpikir panjang, dia mengganti bajunya dengan baju milik Daniel.
“Gue cabut dulu,” ujar Iago.
“Eh, gue ikutan dong!”
“Nggak perlu!”
“Gue nggak berniat ikut campur. Gue cuma kepo aja. Dan ... gue penasaran dengan bokap lo yang sering banget datang ke sini sama Laura.”
Iago nyengir. Batinnya, apa selama ini dirinya terlalu lambat? Sampai-sampai malah Daniel yang terkesan lebih tahu mengenai hal yang tengah diselidikinya ini.
“Gue beneran nggak ada niat apa-apa. Cuma yah, karena gue tinggal di sini dan beberapa kali ngelihat bokap lo—”
“Banyak omong lo! Nanti mereka keburu pergi,” serobot Iago kesal.
Daniel mengangkat kedua tangannya, menyerah—atau mengalah?
Iago dan Daniel keluar dari kamar dan langsung menuju ke restoran. Menurut Daniel yang memang sudah cukup lama tinggal di hotel ini, dalam seminggu Papi bisa dua atau tiga kali datang bersama Laura untuk makan. Biasanya sekira pukul tiga atau empat sore. Kadang-kadang Lisa juga ikut serta.
Saat keduanya memasuki restoran, Daniel langsung celingukan dan menyikut Iago tatkala mendapati jika orang yang mereka cari masih berada di sana.
“Menurut lo, kita harus duduk di mana supaya kita bisa denger apa yang mereka omogin?” tanya Iago, merasa jika keberadaan Daniel rupanya cukup membantu.
Daniel tersenyum lebar. “Kali ini gue merasa dihargai banget sama lo.”
Iago membalas ocehan Daniel dengan sorot mata setajam belati.
“Di sana.” Daniel menunjuk sebuah meja dengan dua kursi yang terletak di balik tiang penyangga. “Kalau buat ngedengerin obrolan mereka bakalan susah, tapi kalau lo mau ngelihat aja, gue rasa udah cukup jelas.”
“Gue nurut aja.”
Daniel memesan americano, sementara Iago memesan espresso. Iago masih fokus mencuri-curi pandang ke meja Papi saat waiter mengantarkan pesanan. Namun tidak dengan Daniel. Cowok itu menyambar ponsel Iago yang tergeletak di atas meja dan menyodorkannya pada Iago, “Fingerprint.”
“Buat apaan?”
“Udah, nurut aja sama gue.”
Iago menempelkan ibu jarinya pada layar ponsel untuk membuka akses. Setelah itu ponsel Iago dengan cepat berpindah ke tangan Daniel.
“Mas,” panggil Daniel pada waiter yang baru saja meninggalkan meja mereka.
Waiter bertubuh pendek tersebut buru-buru kembali. “Ada yang mau dipesan lagi?”
“Lo taruh ponsel ini di sana,” Daniel menunjuk sebuah vas besar yang berada tak jauh dari meja papi Iago, “terus lo arahin ke meja itu ya.”
“Baik, Mas.”
Daniel mengeluarkan beberapa lembar uang seratus ribuan dan menyelipkannya ke saku celana waiter tersebut.
Iago memelototi Daniel. “Lo serampangan banget jadi orang!”
Dengan santai Daniel menyesap americano-nya, terlihat sama sekali tidak terganggu dengan kalimat skeptis Iago. “Lo lupa gue pernah jadi babunya Lisa? Tuh cewek beneran ular! Otaknya cerdik, tapi hatinya busuk. Dulu-dulu gue sering disuruh Lisa buat ngelakuin ini dan itu. Gue nggak bisa apa-apa karena dia selalu ngancam gue.”
“Gimana ceritanya dia bisa tahu lo kecanduan?”
“Kan udah gue bilang kalau dia itu ular. Dia punya seribu cara untuk tahu dan ngancam gue. Dia tahu gue bakalan tamat kalau sampai bokap sama nyokap gue tahu soal itu.” Daniel mengambil jeda. “Dan ... gue menyesal pernah suka sama Lisa.”
“Lo dulu suka beneran sama dia?” dengus Iago.
“Menurut lo?”
“Gue bisa ngerti.”
“Nggak Lisa, nggak Laura, dua-duanya hobi banget bikin masalah sama perasaan orang.”
Iago meringis, mengiyakan kalimat Daniel. Dulu-dulu Iago tidak pernah peduli dengan gadis-gadis muda yang ‘dipelihara’ atau sekadar disewa oleh Papi, sampai suatu hari dia melihat Papi jalan berdua dengan kakak perempuan Lisa tersebut. Tangan Papi melingkar di pinggang Laura. Antara jijik dan bahagia, Iago seperti menemukan permata di kubangan lumpur. Sayang waktu itu dia belum sempat mengambil bukti apa-apa.
“Dan, menurut lo, perjodohan gue sama Lisa ada kaitannya dengan Papi dan Laura nggak?” tanya Iago pada Daniel yang saat ini tengah sibuk sendiri dengan ponselnya.
“Gue sama lo jelas tahu kalau perusahaan bokapnya Lisa sedang ada masalah keuangan. Ditambah lagi bokap gue cabut, udah nggak mau investasi di sana.” Daniel menggaruk kepala hingga membuat rambutnya acak-acakan. “Gue nggak tahu ada masalah apa sih, gue juga nggak kepengin tahu. Cuma menurut gue, saat ini Lisa dan Laura sedang berusaha keras untuk menahan bokap lo agar tetap berinvestasi di perusahaan bokap mereka.”
“Hmmm.”
“Kalau lo kawin sama Lisa, otomatis hubungan bisnis bokap kalian bisa saling mendukung.” Daniel tiba-tiba terkekeh. “Dan bokap lo bisa dengan leluasa selingkuh sama Laura.”
Iago tak merespons. Kepalanya terasa penuh.
“Intinya, apa yang dilakukan Lisa dan Laura semata-mata demi uang. Kalau perusahaan bokap mereka bangkrut, mereka nggak bisa foya-foya lagi, kan? Mereka nggak mau hidup susah. Jadi—”
“Yang mereka lakukan adalah selalu menginjak perahu yang lebih besar,” potong Iago, mengulangi kalimat yang dulu pernah diucapkan oleh Daniel.
“Yup! Saat ini orang yang benar-benar bisa menyelamatkan bisnis bokap mereka cuma bokap lo. Kayaknya sih gitu, makanya mereka menghalalkan segala cara.”
“Oh....” Seringai sinis terbit di wajah Iago. “Sayangnya mereka lupa satu hal....”
Daniel menyimak dengan serius.
“Kalau nggak cuma mereka yang bisa menghalalkan segala cara. Ketika mereka menghalalkan segala cara agar tujuan mereka berhasil, maka gue akan menghalalkan segala cara untuk menggagalkan upaya mereka.”
Daniel ternganga, kedua matanya berbinar penuh kekaguman. “Wah! Kalau sampai lo bisa ngendaliin Lisa, bilang sama dia jangan sampai bokap gue tahu gue kecanduan.”
“Soal itu, lo yang harusnya berusaha buat berhenti.” Iago menganggapinya datar. “Lo bisa cari pelampiasan yang positif.”
“Gampang banget lo ngomongnya?!”
Iago mengangkat bahu. “Terserah lo aja. Tapi gue mau bilang makasih buat apa yang lo lakuin hari ini.”
“Ara cewek baik,” kata Daniel memulai. “Dan gue lihat lo naksir beneran sama dia. Jadi gue pikir, yah ... anggap aja sebagai permintaan maaf gue buat hari itu. Gue akan jadi orang pertama yang ngucapin selamat katika kalian jadian nanti.”
“Jadian?” Iago tersenyum kecut. “Gue sama Ara nggak mungkin jadian.”
Daniel melempar pandangan dengan sebuah tanda tanya besar.
“Anggap aja semesta nggak merestui,” lanjut Iago. “Gue rasa cukup buat hari ini.” Iago melihat Papi, Laura, dan Lisa berjalan meninggalkan restoran. “Thanks buat bantuannya. Gue sekarang udah pegang kartu AS kedua.” Iago berdiri dan bersiap untuk pergi.
“Eh, lo juga harus bawa kartu yang ini,” Daniel menyodorkan kartu kamar pada Iago, “soalnya lo nanti kan perlu balik ke kamar gue buat ambil baju lo lagi.”
Iago menerima kartu tersebut.
“Besok-besok, lo harus bantuin gue juga kalau gue sedang butuh. Bantuan gue nggak sepenuhnya berwujud sebagai permintaan maaf. Tapi gue tulus kok.”
Iago mengangguk. “Gue pasti bantu lo.”
Ponsel yang berisi rekaman pertemuan Papi dengan Lisa dan Laura sudah kembali ke tangan. Iago menyeringai tajam, kartu AS kedua sudah terpegang, membuat posisinya kini berada di atas angin.
*


 sandrabianca
sandrabianca