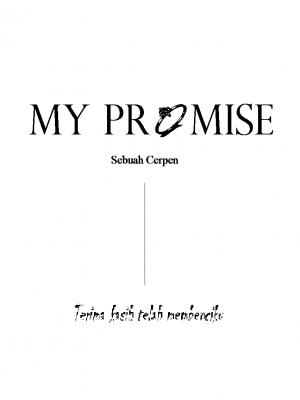Beberapa hari belakangan ini hubungan Iago dengan Hendra tidak terlalu baik. Tidak sampai pada tahap saling mendiamkan atau saling melempar kalimat sarkas, hanya saja interaksi Iago dan Hendra sudah tidak seluwes dulu. Dulu-dulu mereka tidak dekat, tapi juga tidak secanggung ini. Hendra terkesan terlalu memperhatikan tindak tanduk Iago. Apa yang Iago lakukan, siapa yang Iago ajak bicara, serta topik apa yang dibicarakan seakan menjadi prioritas Hendra. Sedikit pun, Hendra tidak ingin kecolongan. Sedangkan Iago yang tidak merasa memiliki salah pada Hendra memilih bersikap tak acuh. Bagi Iago semuanya sudah jelas, setelah ulang tahunnya, sesuatu antara dirinya dan Ara akan usai. Iago sudah membantu Ara menemukan cowok yang dicari, Ara juga sudah bersedia membantu Iago. Mereka sudah sepakat dan kesepakatan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Hendra.
Iago bersedekap, menjatuhkan punggungnya pada sandaran kursi. Di depan sana Hendra tengah serius menuliskan jawaban nomor lima dari PR matematika yang diberikan oleh Pak Ali minggu lalu.
“Jadi 2x+2y-5z=8,” ucap Pak Ali lantang, membaca jawaban akhir yang baru saja dituliskan Hendra di whiteboard. Tiba-tiba pandangan guru senior berkacamata tebal tersebut mengarah pada Iago. “Iago, jawaban Hendra ini benar atau salah?”
Iago menghela napas, lantas membetulkan posisi duduknya. Tangannya bergerak cepat, membalik lembar demi lembar buku tugasnya. “Jawaban saya -7, Pak.”
“Hm, coba kamu tulis jawaban kamu di depan,” perintah Pak Ali.
Iago melirik bukunya sebentar sebelum berdiri dan berjalan ke depan. Beberapa anak, termasuk Hendra, fokus pada Iago yang terkesan santai tanpa membawa buku yang berisi jawabannya.
Dengan lancar Iago menuliskan jawabannya di whiteboard, tanpa sedikit pun peduli pada Hendra yang memperhatikannya dengan sorot mata tajam. Hendra sama sekali tidak peduli dengan jawabannya, benar atau salah itu tidak jadi masalah, yang Hendra pedulikan hanyalah Iago. Melihat Iago yang menuliskan jawaban dengan lancar—bahkan tanpa melihat buku—membuat segumpal rasa iri singgah di hati Hendra. Sekalipun dirinya merupakan ketua OSIS dan memiliki prestasi cemerlang, tetap saja mengalahkan Iago adalah angan-angan belaka. Padahal jika dibandingkan, mereka berdua tidak jauh berbeda. Satu-satunya perbedaan yang mendasar adalah Iago memiliki segalanya dari lahir.
Benar, Iago memiliki privilege.
Pak Ali mengamati jawaban milik Hendra dan Iago, kedua matanya menyipit, tangan kanannya yang memegang antena bekas menunjuk-nunjuk whiteboard.
“-7,” ucap Pak Ali singkat. “Iago, jawaban kamu benar.”
Hendra mendengus pelan, berlapang dada menerima kekalahannya. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada perasaan semacam ini, tidak pernah sekali pun Hendra merasa iri ataupun merasa sebagai saingan Iago. Kini semuanya tidak lagi sama. Hendra memandang Iago sebagai saingan terberatnya.
“Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk,” perintah Pak Ali. “Untuk semuanya, biasakan tetap mengerjakan PR. Saya lebih menghargai jawaban yang salah daripada tidak mengerjakan PR.”
Iago dan Hendra meletakkan spidol ke tempatnya, pandangan keduanya kontak melalui sudut mata. “Nggak masalah gue kalah dalam pelajaran matematika, tapi gue nggak akan mengalah untuk menangin hati Ara,” desis Hendra pelan sesaat sebelum kembali ke tempat duduknya.
*
Iago bersedekap di ujung koridor, menanti seseorang yang sebenarnya sejak beberapa hari lalu ingin diajaknya bicara. Tak berselang lama, doanya dijawab oleh semesta. Hendra muncul bersama Dion dan Brian. Enggan membuang waktu, Iago langsung mencegat ketiga temannya tersebut.
“Hen, gue minta waktu lo sebentar,” pinta Iago.
Hendra menyipit, setelahnya dia mengangguk. “Oke. Lo mau ngomong di mana?”
“Di sini aja.”
Kemudian Hendra menoleh pada Dion dan Brian. “Lo berdua duluan deh, gue ada sedikit urusan sama dia,” tunjuk Hendra pada Iago.
Dion kersah-kersuh. “Kenapa kalau Iago yang mau ngomong selalu gue sih yang diusir,” gerutunya.
Iago menarik masing-masing sudut bibirnya. “Udah, terima aja nasib lo.”
“Lo nggak berniat nyogok gue pakai apa gitu?” lanjut Dion.
Iago menggeleng pelan.
“Udah, sanaaa.... Kenapa lo kepo amat kayak cewek sih?!” Hendra menendang pelan betis Dion.
“Udah, kita makan mi ayam dulu di dekat halte,” ajak Brian yang langsung tanggap bila Iago dan Hendra memerlukan privasi. “Kita ajakin Vika sama Monic sekalian.”
“Tapi lo yang traktir gue, ya?”
Brian menggeleng tak telaten. “Mental traktiran lo! Gini nih calon-calon aparat negara yang gampang disogok. Mentalnya bobrok!”
“Yang penting hidup gue makmur!”
“Udah. Ayo!” Brian merangkul paksa Dion dan membawanya menjauh.
Sepeninggal Dion dan Brian, barulah Hendra membuka suara untuk memulai pembicaraan, “Apa yang mau lo omongin sama gue?”
“Gue boleh pinjam Ara?”
Pertanyaan Iago yang to the point jelas membuat Hendra tersentak.
“Cuma sehari, pas ulang tahun gue,” lanjut Iago.
Otomatis Hendra memberi Iago pandangan keberatan. Permintaan Iago itu jelas-jelas terasa ‘tidak enak’ di hati Hendra.
“Gue bilang gini, minta izin sama lo karena gue nggak mau lo nyangka gue nikung lo,” lanjut Iago lagi. “Gue nggak ada niatan ke arah sana.”
“Ara bukan buku di perpustakaan yang bisa dipinjam terus dikembalikan sesuai tenggat waktu yang ditentukan,” anggap Hendra.
“Gue tahu. Setelah urusan gue kelar, gue janji nggak bakal berhubungan sama Ara lagi kalau lo keberatan.”
“Emangnya lo mau apain Ara?” tanya Hendra setengah menyerobot.
“Gue butuh dia jadi pacar gue.”
Kedua tangan Hendra sontak mengepal, akan tetapi cowok itu berusaha keras mengendalikan emosinya.
“Gue butuh banget bantuan dia,” kata Iago lagi, sama sekali tak terpengaruh dengan emosi Hendra yang nyaris meledak.
Hendra menghela napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. “Sebelum gue jawab boleh atau nggak, gue pengin tanya sesuatu sama lo. Gue minta lo jawab dengan jujur.”
Iago mengangguk.
“Lo sebenernya ada hubungan apa sama Ara?”
“Nggak ada.”
“Perasaan lo ke Ara—”
“Gue suka sama Ara.”
Hendra bungkam.
“Tapi gue tahu diri dan nggak berniat melanjutkan rasa suka ini. Lo lebih pantas buat Ara,” Iago menyeringai samar, “gue cuma bisa kasih Ara masalah. Sementara lo, gue yakin lo adalah orang yang tepat buat dia.”
Hendra menyipit. “Maksud lo?”
“Gue menyerah. Lagian Ara itu nggak mungkin suka sama gue, yang ada dia itu benci setengah mati sama gue.”
Cukup lama Hendra terdiam. Berpikir.
“Lo nggak usah takut gue ingkar janji. Kita berdua emang nggak deket, tapi gue yakin kalau lo tahu siapa gue. Lo bisa pegang omongan gue,” ucap Iago, berusaha meyakinkan Hendra.
“Oke,” putus Hendra pada akhirnya. “Sehari. Cuma sehari dan setelah itu lo jangan deket-deket Ara lagi.”
Iago mengulurkan tangan. “Deal.”
Hendra menjabat tangan Iago. “Deal.”
*
Ara tengah duduk sendirian di halte depan sekolah, hari ini dirinya tidak pulang bersama Vika dan Monic karena dua sahabatnya itu memiliki acara bersama pacarnya masing-masing.
Pacar, ya?
“Ra!” Dari kejauhan Iago memanggil-manggil. Ingin rasanya menghindar, saat ini Ara sedang tidak ingin membicarakan topik yang menguras pikiran dengan Iago. Sayangnya Ara juga tahu jika Iago tidak akan pernah membiarkannya menghindar, jadi mau tak mau Ara tetap duduk di tempatnya hingga sosok Iago berdiri menjulang di hadapannya.
Ara menggeser posisi duduknya. “Duduk sini, gih!”
Iago mengangguk dan duduk di sebelah kiri Ara. “Gue udah minta izin sama Hendra,” beri tahunya.
“Hah?”
“Iya, gue udah minta izin sama Hendra buat pinjam lo. Cuma sehari buat jadi pacar gue.”
“Bisa lo ceritain detailnya nggak?”
Dan Ara hanya bisa bengong mendengarkan Iago bercerita. Sungguh, Ara tidak pernah berpikir jika Iago akan benar-benar melakukan hal itu.
“Hendra bener, Go, gue kan bukan buku di perpustakaan yang bisa dipinjam dan dikembalikan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan,” cerocos Ara.
“Gue tahu. Lo itu lebih berharga dari koleksi buku di ruang kerjanya Dumbledore.”
Ara mendesah panjang mendengar respons Iago, sama sekali tak menangkap sinyal humor yang diberikan oleh cowok di sampingnya tersebut.
“Gue juga bukan punya Hendra, jadi kenapa lo harus izin ke dia segala?”
“Terus, lo ini punya siapa?”
“Nyokap dan bokap gue lah!”
Iago terkekeh pelan. Detik berikutnya raut wajahnya berubah serius. “Ra, percaya sama gue, setelah ulang tahun gue, hidup lo akan tenang karena gue nggak akan gangguin lo lagi. Lo bisa jatuh cinta sama Hendra, lo nggak mati, dan kalian bisa bahagia.”
Itu benar. Lantas kenapa Ara masih saja merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya?
Hati Ara berkecamuk. Rasanya begitu tidak nyaman. Ada suatu hal yang menuntut untuk dijelaskan, akan tetapi Ara tak tahu apa itu dan bagaimana menjelaskannya.
“Go,” lirih Ara tercekat.
Iago menoleh, menatap Ara yang binar matanya meredup. “Ya?”
“Lo keberatan pisah sama gue?”
Pertanyaan Ara yang tidak biasa itu hanya mendapatkan respons senyum pahit dari Iago.
“Jawab, Go!”
“Nggak. Karena gue tahu kalau gue bukan cowok yang lo cari. Gue bukan cowok yang bisa bikin lo jatuh cinta. Gue ini cuma cowok yang bikin kacau hidup lo.” Iago berpaling dari Ara, memandang ke arah lain. “Kalau gue udah angkat kaki dari kehidupan lo, gue yakin lo pasti akan bahagia.”
Ara menggeleng-geleng. Perasaannya bertambah kacau. Akal sehatnya sudah tak lagi dapat diandalkan. Detik ini Ara merasa ... buta!
“Kalau gitu, setelah ulang tahun lo, tolong jangan pernah muncul di hadapan gue lagi,” pinta Ara dengan suara serak.
Iago mengulurkan tangannya. “Deal.”
Ragu-ragu, namun akhirnya tangan Ara menyambut tangan Iago. “Deal.”
“Gue anter lo pulang.”
“Oke.”
*


 sandrabianca
sandrabianca