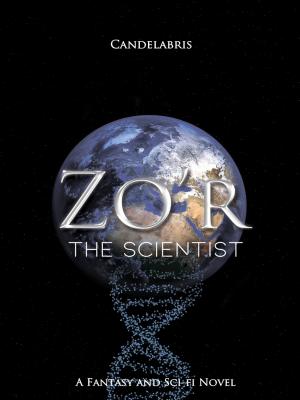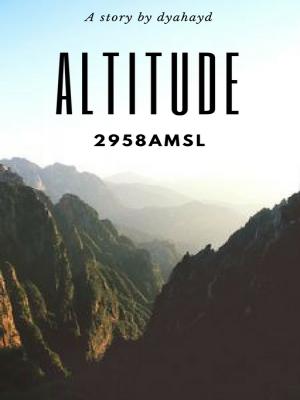Pulang sekolah Ara, Vika, dan Monic berencana untuk nongkrong di salah satu kafe. Pilihan jatuh pada kafe milik tante Vika. Selain suasananya yang nyaman dan menunya yang enak, setiap kali nongkrong di sana mereka hanya perlu membayar setengah harga. Namun yang terpenting dari semua itu adalah Ara membutuhkan waktu untuk ‘istirahat’. Belakangan ini hari-harinya terasa begitu melelahkan.
Mereka bertiga masuk ke mobil dan mengambil posisi seperti biasa. Vika di belakang kemudi, Monic di bangku penumpang, sementara Ara menempati bangku belakang seorang diri.
“Agak ngebut dikit, Vi. Gue udah haus banget,” pinta Monic.
“Nih,” Ara menyodorkan air mineral, “lo minum ini dulu daripada mati kehausan. Mau balik ke kantin juga udah tutup.”
“Gue pengin yang dingin-dingin.”
Ara mencebik. “Virgin mojito kayaknya enak banget, Mon. Seger.”
“Araaa, kenapa lo bikin gue tambah haus sih?!”
Vika menghidupkan mesin sembari mengomel, “Kalian berdua berisik amat! Kafenya nggak jauh, tahan bentar.” Namun ketika Vika sudah nyaris menginjak pedal gas, seseorang mengetuk kaca mobilnya. “Njrit! Kaget gue!” umpat Vika keras-keras.
Vika menurunkan kaca mobilnya dan langsung bertatap muka dengan sosok Iago.
“Gue mau ngomong bentar sama Ara,” kata Iago. “Sama kalian juga sih.”
“Soal apa?” tanya Vika.
“Cowok yang dicari Ara.”
Ara yang tadinya duduk malas-malasan di kursi belakang langsung terjingkat. “Lo udah tahu siapa dia?” tanyanya antusias.
“Makanya biarin gue ngomong dulu.”
“Sini. Masuk!” perintah Ara sambil membuka pintu belakang.
Iago masuk dengan gerakan canggung. Cowok itu mengedarkan pandangan, memperhatikan interior mobil Vika.
“Sori, mobil gue nggak sebagus mobil lo,” kata Vika.
Iago mendecih. “Lo kenapa mikirnya cetek amat sih? Gue cuma penasaran, mobil cewek itu dalemnya kayak apa.”
“Eh, kenapa malah ngomongin soal mobil sih?” protes Monic. “Langsung aja ke bahasan utama.”
Ara mengangguk. “Iya, gue nggak sabar denger info dari lo.”
“Jadi gini,” Iago berdeham, “gue udah dapet info lengkap soal cowok-cowok yang pernah nembak lo. Alan, seperti yang udah lo tahu, dia udah nggak suka-suka banget sama lo dan milih buat temenan aja. Terus si cowok drama—”
“Namanya Jefrey,” koreksi Ara.
“Iya pokoknya cowok itu, rasa suka dia ke lo cuma sekadar rasa kagum aja.”
“Kagum sama gue kenapa?”
“Muka lo mirip Caitlin Halderman katanya.”
Monic menggaruk pelipisnya. “Siapa itu Caitlin.... Duh, susah amat namanya.”
“Artis favoritnya si cowok drama,” jawab Iago.
Ara memutar mata, ingin sekali menegaskan jika si cowok drama itu bernama Jefrey. Dan setelah dipikir-pikir lagi sepertinya percuma. Iago sama sekali tidak punya niatan untuk mengubah panggilannya terhadap Jefrey.
“Semirip apa gue sama dia?” tanya Ara.
“Mana gue tahu. Gue nggak pernah nonton TV,” sahut Iago.
Sebelah alis Vika terangkat. “Terus tontonan lo apa? Jangan-jangan HP lo isinya video 3gp semua.”
Iago mendecih. “Gue anak IPA, nggak perlu bantuan video gituan buat tahu cara bereproduksi.”
Lagi-lagi Monic kebingungan. “Video apaan sih, Vi?”
“Bokep,” desis Ara tidak telaten. Monic masih hendak membuka mulutnya, tapi Ara buru-buru melanjutkan, “Bahas si Caitlin sama video 3gp-nya nanti aja. Sekarang lanjut ke Richard, Daniel, Kak Ardan.”
“Richard, cowok yang kacamatanya setebal botol susu sapi itu cuma naksir lo gara-gara lo suka baca Percy Jackson, sama kayak dia,” beri tahu Iago. “Lalu Daniel, kapten tim futsal kebanggaan sekolah kita....”
“Nggak perlu dijelasin,” ketus Ara. “Daniel bukan cowok yang gue cari.”
Untuk beberapa saat tak ada yang merespons. Vika dan Monic membatu, paham, Ara sudah pernah menegaskan jika dirinya dan Daniel tidak cocok. Sementara Iago tanpa sadar mengepalkan tangan, kejadian malam itu tidak mungkin bisa dia lupakan. Walau dalang di balik kejadian itu bukanlah Daniel, Iago tetap saja marah. Harusnya meski terpaksa, Daniel bisa mengambil keputusan yang tepat.
“Dan yang terakhir Kak Ardan,” ucap Iago pelan. Cowok itu mengatur napas, meredam emosinya. “Kak Ardan udah jadian sama anak kelas 10, jadi itu artinya cowok yang tersisa cuma....”
“Hendra.” Ara melanjutkan.
Iago manggut-manggut. “Lo dan dia cocok dengan clue yang diberikan peramal itu. Kalian beriringan, tapi nggak pernah bersinggungan. Karena lo selalu menjauh saat dia mendekat,” jelasnya.
Ara diam saja. Pikirannya mulai keruh. Perasaannya kembali terombang-ambing.
“Gue rasa itu lebih gampang, Ra. Perasaan Hendra ke lo udah jelas banget. Lo tinggal buka hati buat dia dan jatuh cinta,” imbuh Iago.
“Segampang itu?” sinis Ara.
Iago menjawabnya dengan anggukan.
Ara merenung, merangkai semuanya satu per satu. Sejak awal Hendra adalah teman baik untuknya, tak sekali pun terpikirkan oleh Ara bila dia akan memiliki hubungan lebih dari sekadar teman dengan Hendra. Karena jika suatu hari nanti hubungan mereka bermasalah, pertemanan mereka bisa dipastikan tak lagi terasa sama.
“Makasih ya, Go,” ucap Ara tak bersemangat.
“Sama-sama. Good luck ya, Ra,” balas Iago, sama tak bersemangatnya dengan Ara. Iago meremas bahu Ara. “Kalau lo butuh sesuatu, bilang aja ke gue.”
Ara mengangguk. “Terus soal ulang tahun lo—”
“Gue perlu bicara sama Hendra soal ini. Gue nggak mau dikira nikung dia. Gue nggak suka menyandang status ‘makan teman sendiri’.”
Ara meringis. “Friend-vora?”
Mendengar itu, semuanya terbahak—tak terkecuali dengan Iago. Aura mendung pada cowok itu lenyap seketika, digantikan dengan sebuah ekspresi lepas yang jarang sekali terlihat.
Iago menyentil kening Ara. “Harusnya lo masuk jurusan IPA, siapa tahu lo akan menemukan istilah ilmiah baru. Dan friend-vora ... sounds familiar, gampang banget diingatnya.”
“Ngaco!” Ara merengut. Padahal istilah itu hanya buah dari pikiran isengnya saja.
“Ya udah, gue cabut dulu ya,” pamit Iago, setelahnya dia keluar dari mobil dan berjalan menuju ke mobilnya sendiri.
Ara mengembus napas panjang. Mestinya Ara senang karena pencariannya terhadap ‘cowok kekurangan cinta’ itu sudah menemui titik terang, tapi tak tahu kenapa hatinya malah gelisah. Rasa-rasanya Ara memang tidak memiliki pilihan selain jatuh cinta pada Hendra, teman baiknya sendiri.
“Tuh kan dugaan gue bener, lo itu jodohnya Hendra,” seru Vika merasa menang. “Selamat jatuh cinta, Araaa.”
Monic menggeleng. “Kok gue ngelihatnya nggak gitu, Vi? Lo lihat Ara sama Iago tadi nggak? Mereka kelihatan kayak sepasang kekasih yang dipaksa buat pisah.”
“Kebanyakan nonton drama lo!”
“Udah. Udah,” ujar Ara menengahi. “Kalau memang gue harus jatuh cinta sama Hendra, gue bakal coba. Meski itu mempertaruhkan status gue sama dia yang merupakan teman baik.”
Kalau memang cowok itu adalah Hendra, Ara bisa apa?
Lagi-lagi Ara merasa jika takdir memang selalu bertindak semaunya sendiri. Dan, ya, Ara-lah yang selalu menjadi bulan-bulanan sang takdir.
*


 sandrabianca
sandrabianca