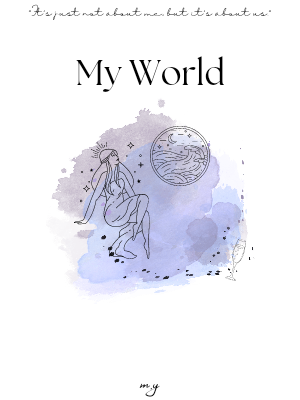Ara mengajak Iago makan di warung bakso Bang Usup. Tempat itu hanya sebuah kios kecil dengan gerobak bakso di depannya, serta meja dan kursi untuk pelanggan yang terletak di dalam dan di luar kios. Meja yang terletak di luar hanya beratapkan terpal untuk menghalau sinar matahari dan hujan rintik-rintik. Sementara meja yang di dalam jumlahnya lebih sedikit dan agak lebih nyaman karena ada kipas angin yang berputar di langit-langit.
Karena ini bukan jam makan siang, warung itu sepi. Hanya ada tiga pria yang sepertinya pekerja kantoran duduk di meja luar, mereka semua sedang merokok. Ara menghampiri Bang Usup yang tengah mengelap meja di dalam. “Bang, gue mau bakso yang biasanya ya, pakai bihun sama lontong. Minumnya es jeruk ya, Bang. Inget, esnya dikit aja.”
“Oke siap, Non.” Pria kurus berkumis itu berpaling pada Iago. “Masnya?”
“Samain aja deh,” jawab Iago. “Eh, Ra, di sini makan bakso pakai lontong?”
Ara mengangguk. “Kenapa? Bakso semangkuk sama lontong nggak haram kok.”
“Bukan gitu. Gue baru tahu aja.”
“Kalau lo main ke Jawa Timur, bakso semangkuk sama lontong bukan hal yang aneh.”
“Oh, oke.”
Mereka memilih tempat duduk tepat di bawah kipas angin agar tidak terlalu gerah. Iago mencopot hoodie-nya dan menaruhnya pada tempat duduk kosong di sampingnya. Tak sampai lima menit kemudian, Bang Usup membawakan pesanan mereka. Ara yang lapar langsung menuangkan sambal, saus, dan kecap ke dalam mangkuk baksonya. Kemudian mengaduknya sebentar sebelum mulai makan.
Iago tertawa geli melihat ekspresi Ara. “Lo itu rakus atau laper?”
“Dua-duanya,” jawab Ara sambil terus mengunyah.
“Ra, gue penasaran. Lo kenapa selalu bilang kalau nggak punya waktu? Hidup lo sebenernya kenapa?”
Seketika Ara berhenti mengunyah. Pertanyaan yang menjurus pada perkara hidup dan matinya itu membuat nafsu makannya lenyap. Perut Ara mendadak terasa penuh hingga timbul sensasi mual. Buru-buru Ara menyeruput es jeruknya. “Gue nggak kenapa-kenapa,” jawab Ara setelah berhasil menenangkan dirinya sendiri.
“Ra, kalau lo ada masalah, lo boleh kok minta bantuan gue. Gue pasti bakal bantu lo,” balas Iago mencoba meyakinkan.
Sejenak Ara menimbang-nimbang, haruskah dia menceritakannya juga pada Iago? Hm, mungkin jika Iago mengetahui masalahnya, Iago akan berhenti merengek minta tolong padanya.
Ara nyengir. “Lo nggak bakal bisa nolongin gue.”
“Prince can do anything.”
“Really? Terus kenapa lo nggak nolongin diri lo sendiri? Kalau lo bisa ngelakuin segalanya, kenapa lo malah minta tolong sama gue?”
Jelas, itu membuat Iago tertohok. Bumerang yang dilemparkanya sukses menancap kembali di dadanya. Iago menggeleng, tak mengerti kenapa Ara susah sekali ditaklukkan. Padahal dia hanya ingin minta tolong, serta menolong Ara menyelesaikan apa pun itu masalah yang dihadapinya.
“Ra ... gue ini serius. Apa pun itu masalah lo, pasti gue bantu.” Iago mencoba memancing Ara untuk bercerita.
“Gue butuh jantung lo, gimana?”
“Ra, gue serius.” Iago terus mencoba meski sebenarnya ingin menyerah. Kepalanya sampai berdenyut saking frustrasinya. “Lo ada masalah apa? Keluarga lo punya utang dan nggak bisa bayar? Sampai lo dikejar-kejar, diancam mau dibunuh? Gitu?”
Ara membuang muka, mengarahkan pandangannya pada ketiga pria di luar yang tengah bersiap-siap pergi. “Kebanyakan nonton sinetron lo.”
“Makanya lo cerita dong, biar gue tahu, biar gue ngerti, biar gue bisa bantuin lo.”
Dikejar terus seperti ini, Ara mulai gelisah. Terlebih tatapan Iago seakan enggan melepasnya. Setiap gerakan kecil yang dibuat oleh Ara, direkam baik-baik oleh Iago.
“Waktu festival musik itu, ada peramal yang bilang ke gue kalau hidup gue ini nggak balance,” Ara memberanikan diri menatap mata Iago, “gue terlalu banyak menerima cinta. Jadi biar seimbang, gue harus mati.”
Cowok di depannya memasang ekspresi sangsi.
“Iya, gue tahu kok itu konyol. Tapi percaya nggak percaya, peramal itu tahu segalanya, bahkan gue belum sempat tanya, dia udah jawab duluan.”
“Jadi lo beneran bakal mati?”
“Nggak. Asalkan gue bisa jatuh cinta sama seorang cowok yang kekurangan cinta. Dan yang paling penting waktu gue cuma sembilan puluh hari,” jelas Ara.
“Cowok kekurangan cinta?” Iago agak merasa lucu dengan istilah tersebut.
Ara mengedikkan bahu. “Cowok yang suka sama gue dengan tulus dan layak menerima cinta gue,” terangnya. “Yah ... kurang lebih gitu deh.”
Semua itu meluncur begitu saja dari mulut Ara. Bahkan setelahnya Ara sendiri tak tahu kenapa akhirnya bercerita pada Iago. Mungkinkah ini akibat batu karang kebencian di hatinya sudah semakin terkikis?
“Lo udah coba cari cowok itu?” tanya Iago. Tak seperti tadi yang terlihat sangsi, kini ada gurat-gurat kecemasan di wajah tampannya.
Ara mengangguk. “Gue udah PDKT sama Alan, tapi yah ... seperti yang lo tahu, ujung-ujungnya Alan cuma mau temenan.”
“Kenapa Alan? Kenapa nggak cowok lain? Misalnya Hendra. Ketua OSIS kita itu jelas-jelas suka sama lo.”
“Gue mulai pencarian dari cowok-cowok yang pernah nembak gue.”
“Jangan bilang kalau lo nyamperin cowok drama itu—”
“Namanya Jefrey,” koreksi Ara. “Gue juga udah PDKT ke dia, tapi,” Ara mengangkat bahu, “Daniel keburu dateng, terus ajaibnya lo juga muncul.”
Iago hanya diam, menanti Ara melanjutkan kalimatnya.
“Dan satu hal yang lo perlu tahu, Daniel masuk dalam salah satu cowok yang bakal gue deketin.”
Sontak Iago melotot. “Daniel?!”
Ara tidak menjawab apa-apa, melainkan menatap Iago lurus-lurus sebagai tanda jika dirinya serius.
“Nggak, lo nggak boleh deket-deket sama Daniel,” perintah Iago, ekspresi wajahnya tak kalah serius.
Seperti yang sudah Ara perkirakan, Iago pasti melarangnya. Hal itu membuat Ara kian penasaran. “Lo nggak berhak ngelarang gue buat deket sama siapa pun, termasuk Daniel,” pancing Ara, berharap Iago buka mulut, mengatakan alasannya.
“Ya pokoknya jangan. Soalnya—”
“Soalnya...?” Ara tak sabaran.
“Gue....” Iago menggeleng cepat seolah menepis sesuatu. “Gue mau lo itu jadi pacar gue, bukan Daniel.”
Ara meringis. Telinga dan hatinya sudah tawar mendengar Iago berkata seperti itu. “Go, gue nggak bakal mau pacaran sama cowok yang nggak suka sama gue, yang notabene cuma minta tolong sama gue.”
Iago diam. Pandangannya tertuju pada bibir Ara yang tengah sibuk mengucapkan kalimat penolakan.
“Gue nggak mau buang-buang waktu sama lo sementara hidup gue semakin singkat,” lanjut Ara.
“Kalau gue beneran suka sama lo, lo mau jadi pacar gue?”
“What?” Ara terperangah. “L-lo beneran udah nggak waras, ya?!”
“Coba lo pikir, kalau gue beneran suka sama lo dan lo beneran suka sama gue ... itu bakal menyelamatkan kita berdua. Gue bisa jalanin rencana gue dan lo nggak bakal mati.”
Kepala Ara berdenyut. Logikanya dipaksa untuk tetap waras. “Kenapa lo sampai segininya demi ngelawan bokap lo? Kenapa lo—”
“Gue nggak mau lo mati,” potong Iago. “Terlepas dari lo bakalan mau nolong gue atau nggak, gue nggak mau lo mati.”
Ara menatap ke dalam mata Iago yang saat ini tengah menatapnya. Binar di mata cokelat gelap itu tajam, menandakan bila Iago tidak main-main dengan ucapannya. Ini membuat Ara bimbang, ide Iago tadi masuk akal walau terdengar terlalu dipaksakan.
Iago mengulurkan tangan kanannya, hendak menyentuh bahu Ara. Namun beberapa senti sebelum mereka bersentuhan, Iago menarik kembali tangannya. “Ra, dengerin gue,” Iago berdeham, “gue bakal ngelakuin apa pun, apa pun itu buat nolongin lo. Gue serius.”
Ara tak membalas. Tatapannya terkunci oleh tatapan Iago, yang bahkan pikiran terwarasnya pun kesulitan untuk melepaskan diri. Berani sumpah, ini semakin rumit.
*
Iago memutar-mutar stik drumnya dengan gelisah. Berulang kali dia mengecek ponselnya, berharap Ara membalas pesan yang dikirimkannya melalui Instagram. “Harusnya gue tadi minta nomor WA-nya,” rutuk Iago, lalu meletakkan stik drumnya di meja belajar.
Iago menyambar ponselnya dengan gerakan kasar, membuka aplikasi Instagram untuk melihat akun @arabell_a yang merupakan milik Ara. Foto yang diunggah Ara cukup banyak, entah itu selfie, candid, atau sedang bersama teman-temannya. Iago menggesernya ke bawah, ada sebuah foto keluarga dengan anggotanya yang lengkap. Dalam foto itu jelas terlihat betapa bahagianya mereka, senyum mereka tidak dibuat-buat.
Kedua kakak kembar Ara tidak mirip meski memiliki bentuk wajah sama. Pemuda berambut jabrik dengan tatapan mata yang menyelidik lebih mirip dengan ibunya. Sementara pemuda yang satunya lagi, yang lebih tembam dan garang, mirip sekali dengan ayahnya. Lalu Ara, cewek itu adalah perpaduan dari kedua orangtuanya. Memiliki wajah kalem seperti ibunya, akan tetapi aura dan sorot matanya ketus seperti sang ayah.
Mendadak dada Iago terasa nyeri.
Iago mengabaikannya dan beralih ke foto lain, yaitu ketika Ara masih tergabung dalam tim cheer. Dalam foto itu Ara berdua dengan Lisa, mengenakan seragam cheer yang didominasi warna merah dan putih. Pada caption-nya tertulis: It’s just goodbye, not a farewell.
Iago berlama-lama menatap foto itu, mengamati wajah cewek itu sekali lagi. Mata Ara sedikit lebih lebar jika dibandingkan dengan kebanyakan mata orang lain, lantas mata itu akan menyipit ketika pemiliknya tersenyum. Wajah Ara tirus, dibingkai dengan rambut hitam lurus sepunggung. Iago mengingat-ingat, sepertinya belakangan ini Ara sudah tidak pernah mengurai rambutnya, cewek itu lebih suka menguncirnya.
Belum juga puas mengamati Ara, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Tak lama, sosok yang dibenci Iago muncul. “Papi denger hari Minggu kamu bakalan manggung di mal.”
“Kalau iya emangnya kenapa?” balas Iago menantang.
“Papi nggak suka kamu buang-buang waktu.”
Iago menyeringai. “Mending buang-buang waktu daripada buang-buang duit buat nidurin pecun.”
Tangan pria yang merupakan versi dewasa dari sosoknya itu terangkat. “Iago!”
“Kenapa? Nggak terima?” Emosi Iago tersulut. “Lo mau pukul gue?”
Papi menggeram dan menurunkan tangannya. “Terserah kamu,” dengusnya tak acuh sembari berjalan keluar dari kamar. “Oh ya, untuk ulang tahun kamu, semuanya sudah diatur. Jangan melawan, juga jangan mangkir kalau kamu masih mau dapat semua akses itu,” lanjutnya sebelum menutup kembali pintu kamar Iago.
“Brengsek!” cowok itu mengumpat keras-keras dan spontan menendang kursi di dekat meja belajarnya hingga benda itu mencelat ke sudut ruangan.
Mengancam. Itulah yang selalu dilakukan Papi. Orang tua itu memiliki kartu AS-nya, sayang Iago tidak memiliki apa-apa untuk membalas. Harapannya hanya Ara. Namun memgingat jika cewek itu hanya membaca pesan yang dikirimkannya, Iago tersenyum pahit.
“Lo seriusan nggak ada rencana buat jatuh cinta sama gue gitu?” tanyanya, entah pada siapa.
*


 sandrabianca
sandrabianca