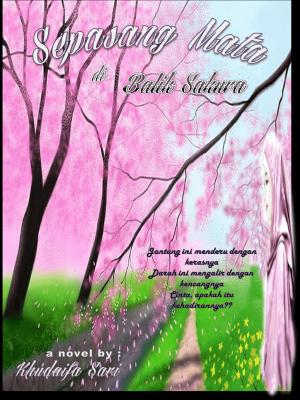Beberapa orang naik ke panggung, salah satu dari mereka mengambil mikrofon dan mengetuk-ngetuknya dengan telunjuk. “Check.... Check.... Ehem, selamat petang menjelang malam semuanya. Perkenalkan nama gue Ardi, vokalis band TYPO dari SMA Nusantara. Sebagai tuan rumah, gue ucapin selamat tahun baru buat kalian semua yang hadir, juga banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah berpartisipasi dalam festival musik ini. Sebagai pembukaan, kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang pastinya sudah sangat familier di telinga kalian.” Cowok berambut mangkuk itu memberikan kode kepada anggota lainnya. “So, listen it, The Reason by Hoobastank.”
Lagu yang benar-benar familier. Hampir semua yang menonton ikut bernyanyi, tak terkecuali dengan tiga cewek yang masih belum bergabung dengan kerumunan di depan panggung. Mereka antusias bernyanyi dengan kualitas suara yang seadanya.
“Kirain pembukaan udah mau diajak jingkrak-jingkrak,” celetuk Monic sesaat setelah lagu berakhir.
“TYPO. Nama band-nya kenapa gitu amat?” timpal Vika, lalu cekikikan sendiri.
Ara menyedot bubble milk tea-nya. “Gue malah ke-distract sama model rambutnya Ardi.”
“Iya juga ya. Kok gue sampai nggak sadar?” Vika tambah cekikikan.
Monic mengangguk setuju. “Habis suaranya kelewat bagus sih, kita jadi nggak perhatian sama yang lainnya.”
Ara hendak menimpali saat tiba-tiba sebuah benda memukul kepalanya. “Anjrittt! Apaan sih lo?!” Ara menoleh dan mendapati Dion berdiri di belakangnya, memasang ekspresi cengengesan. Tangan kanan Dion memegang lightstick Blackpink yang menyerupai palu. Kedua sisi sampingnya yang berbentuk hati berkelap-kelip. Tanpa berkata apa-apa, Ara merebut benda itu dan balas memukul kepala Dion keras-keras. “Sakit, tauk!” Nyaris saja Ara melemparkan gelas bubble milk tea-nya ke muka Dion saking sebalnya.
Namun bukannya marah, Dion malah terbahak. Maklum, cowok itu memang terkenal jail pada siapa saja, kecuali pada Vika—pacarnya sendiri. Tak lama kemudian Hendra dan Brian muncul di belakang Dion.
“Lo dari tadi ke mana aja sih?” sembur Vika pada Dion yang masih memasang ekspresi tanpa dosa. “Satu lagu udah habis baru nongol.”
“Di belakang panggung, Beb. Soalnya Hendra harus memastikan kalau Prince kita dateng,” jawab Dion.
Vika melirik Hendra. “Emang harus ya pakai ditemenin segala?”
“Nggak juga sih. Gue sama Brian aja udah cukup. Dion aja yang ngintilin kami. Ya, nggak?” Hendra menyikut lengan Brian.
Brian, cowok yang penampilannya super kalem itu tersenyum. “Yup!”
Hendra dan Brian itu seperti satu paket. Ketua OSIS dan wakilnya. Kepala dan badan. Sementara Dion, dia lebih seperti kutu loncat yang bisa bergabung dengan siapa saja. Tak ayal jika cowok itu memiliki banyak teman.
“Eh, kenapa ada Prince segala?” tanya Ara. “Dia kan bukan bagian dari band sekolah kita.”
“Teguh, drummer kita, mendadak nggak bisa dateng. Nyokapnya masuk rumah sakit lagi, jadi kita minta tolong Prince buat gantiin,” jawab Hendra.
“Oh...” respons Ara mengambang, dia baru tahu jika ternyata Prince adalah seorang pemain drum.
Prince.
Semua orang pasti tahu siapa itu Prince. Prestasinya yang gemilang membuat cowok itu terkenal di kalangan para pendidik. Wajah tampannya secara otomatis membuatnya populer di kalangan cewek-cewek. Namun yang paling membuatnya dikenal adalah status sosialnya. Dia adalah anak dari salah satu orang terkaya di Indonesia. Anak bungsu dan satu-satunya anak laki-laki dari keempat saudara kandungnya yang semuanya perempuan.
Yah, informasi yang sudah basi sebetulnya. Kalau dihiperbolakan ibaratnya seperti: siapa sih penduduk Indonesia yang tidak mengenal Prince? Semua pasti tahu profilnya meski belum tentu mengenali wajahnya yang memang jauh dari publikasi.
Suara tepuk tangan yang riuh menarik Ara kembali dari lamunan singkatnya. Dilihatnya dua sahabatnya sudah sibuk sendiri-sendiri. Vika tertawa-tawa dengan Dion, sedangkan Monic mengobrol dengan Brian.
Samar-samar seulas senyum terbit di wajah Ara. Jika kebanyakan orang merasa iri ketika melihat orang lain jatuh cinta, Ara malah sebaliknya. Melihat orang yang tengah jatuh cinta membawa aura positif yang membuatnya bahagia.
Yah, cinta memang selalu terasa menyenangkan.
Namun, ketika perkataan Madam Maris tadi menyusup ke dalam ingatannya, senyum Ara langsung memudar. Ara menggigit bagian dalam pipinya, membayangkan seandainya saja dia tidak berhasil menemukan cowok itu....
Kira-kira, mati itu gimana rasanya? Sakit nggak, ya?
“Ra, ngelamun aja dari tadi,” tegur Hendra. Cowok itu menepuk pelan pundak Ara.
Ara gelagapan. “E-eh, nggak kok.”
“Itu mereka udah pada gabung ke tengah, kamu nggak mau ikutan?” Cowok berperawakan tegap itu mengarahkan dagunya pada keempat teman mereka yang sudah terlebih dulu menghambur ke arah kerumunan di depan panggung.
Kamu. Ara selalu merasa tidak nyaman jika Hendra sudah menggunakan panggilan aku-kamu ketika mereka mengobrol. “Ikutan dong, tapi sekarang gue kebelet nih. Kamar mandinya di mana sih, lo tahu nggak?” Ini hanyalah alasan Ara untuk melarikan diri dari Hendra.
“Itu lewat sana.” Hendra menunjuk koridor yang terletak di sisi kanan panggung. “Mau aku anterin?”
“Nggak usah. Lo duluan aja, nanti gue susul. Dadaaah....” Ara berjalan mundur, buru-buru menjauhkan diri dari Hendra.
Setiap kali berada di dekat Hendra, Ara selalu merasakan sinyal-sinyal yang cowok itu kirimkan untuknya. Harusnya Ara bangga ditaksir oleh cowok seperti Hendra. Ketua OSIS, anak IPA, tampan, lumayan tajir, sopan, asyik untuk diajak mengobrol, selalu on time.... Singkatnya, Hendra itu boyfriend material banget. Sayang seribu sayang, Ara sama sekali tidak merasakan getaran apa-apa dari sinyal yang dikirimkan oleh Hendra. Bagi Ara, Hendra adalah teman yang baik.
Ya, hanya sekadar itu.
Ara melesat menuju koridor yang dimaksud. Sesuai papan penunjuk yang digantung di langit-langit, kamar mandi terletak di ujung koridor. Tidak ada orang, tapi ini jauh dari kata seram. Sungguh, ini tidak seperti di sinetron yang kebanyakan menggambarkan kamar mandi sekolah sebagai tempat yang angker.
Sembari mencuci tangan di wastafel, Ara memperhatikan dirinya sendiri di cermin. Wajahnya memang sedikit pucat, tapi sepertinya tidak apa-apa. Toh siapa juga yang akan memperhatikannya. Setelah mengeringkan tangan dengan tisu, Ara merapikan poninya dengan jari dan mengikat rambut panjangnya menjadi satu, kemudian menyampirkannya di bahu kiri.
Ara bersenandung kecil untuk mengusir sepi. Bahunya sudah setengah mendorong pintu kamar mandi ketika lamat-lamat dia mendengar suara seseorang. Tidak terlalu jelas karena suaranya membaur dengan ingar-bingar musik. Merasa bukan urusannya, Ara pun keluar dari kamar mandi.
Tak jauh dari situ, sesosok cowok bersandar di dinding sembari marah-marah pada lawan bicaranya di telepon. Ara hanya mendengar sepotong-sepotong. Seperti musik, media massa, bisnis, sekolah, dan banyak lagi.
Ara mencoba merangkai secara acak kata yang didengarnya, sayangnya tak satu pun yang berhasil menjadi sebuah kalimat. “Bodo ah!” tukasnya tak mau ambil pusing.
Saat melewati cowok itu, Ara berusaha keras untuk tidak menoleh—walau sejujurnya ekor matanya melirik ke arah sana. Masih beberapa langkah, Ara merasakan lengannya dicekal oleh seseorang.
Dan tatapan mereka pun berserobok....
PRINCE?!
*


 sandrabianca
sandrabianca