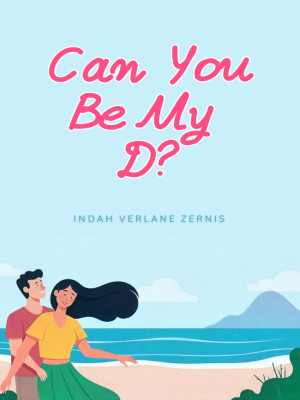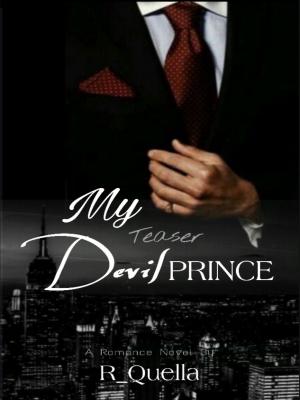Dear seseorang di tahun 2001
Merinding, jujur, aku semakin takut dengan gaya bicara Tian yang semakin datar dan dingin. Kami biarkan ia dengan coretan di tembok sebagai pelampiasan emosinya. Kami tidak bertanya atau menyinggung tentang barang-barang Ayah yang ia sembunyikan di bawah bantal, bahkan berpura-pura tidak tahu. Sengaja, agar ia tidak semakin terluka.
Ketika sore hari, kami temukan deretan balok yang tersusun rapi dengan warna senada lurus membentuk rel kereta. Ia menyusunnya sendiri diletakkan di depan pintu. Sengaja katanya, agar tahu siapa yang datang membuka pintu. Saat seseorang tersandung dan kesakitan, ia hanya akan menatap tanpa ekspresi.
Ibu yang sering terjaga tengah malam untuk menatap langit malam hari dan respon wajah Tian yang semakin datar membuat dadaku semakin sesak.
Kalau sudah begitu aku akan berlari ke dapur, menyumpalkan nasi ke dalam mulutku, menghantam dadaku dengan kepalan tangan. Aku hanya bisa menguatkan diriku sendiri, bahkan nasi dan air mata menjadi satu kesatuan.
Jika aku dapat berbicara pada ibu dan adikku, aku akan berkata―
Aku tahu ada rindu yang tidak terucap. Ibu, Tian … apa kalian tahu? Aku membenci ini. Benci karena rindu, rindu kebersamaan kita dulu bersama Ayah. Benci karena tetap menyayangi walaupun terluka. Sadarkah kalian kini semua telah menjadi kenangan, telah berakhir―usai.
Namun kita memang boleh membenci perbuatannya tapi tidak dengan orangnya, dia tetap ayah bagi kami. Dalam hari-hari kami, ia tak sepenuhnya kejam, ada bagian di mana kami menikmati tawa dan menyantap makanan bersama dalam satu meja, sebelum meja itu menjadi dingin.
Lantas jika boleh aku berkata pada ayah, aku akan tanyakan ..
Andai waktu itu aku menahanmu, menghentikanmu pergi ..
Apakah semua akan berubah, Ayah?
Kawan, kurasa semuanya akan sia-sia bukan? Jelas, ayahku yang sekarang bukanlah ayahku yang dahulu. Ia banyak berubah, entah siapa yang telah mengubahnya.
Pertemuan terakhirku dengannya, menjelaskan segalanya, bahwa ayah lebih memilih wanita itu daripada keluarganya, dan itu membuatku sakit.
Salli, 2023
***
Tidak ada gerhana, tidak gerimis, juga tak ada kucing hitam. Aku tetap memasukkan surat yang semalam kutulis ke dalam kotak pos merah. Tidak ada bunyi apapun, baru saja aku akan mengintip dari celahnya, namun seseorang memanggil.
“Salli, apa yang kau lakukan?” suaranya lantang.
Serta merta aku menoleh lalu menemukan bos yang mengerutkan kening dan menatapku tajam. Aku yakin, ia tidak pernah senang melihatku mendekati kotak pos merah.
“A-apa Bos?” tanyaku tergagap.
“Kemarilah!” Bos memberi perintah.
Aku mendekat padanya ragu. Di sisi lain masih ingin mengintip bagaimana nasib surat terakhirku.
Bos memutar badan tanpa mendengar dulu sanggahanku, kemudian ia berbalik dan menyuruhku mengikutinya. Aku hanya menurutinya. Entahlah, mungkin karena dia bosku. Aku sama sekali tak bisa menolak perintahnya.
Sesampai di ruangan kafe, tidak ada senior dan Tuan Neil ataupun pelanggan saat itu, terlalu sepi hanya terdengar alunan musik The Beatles yang bos sukai.
Menelan ludah, untuk sesaat merasa canggung. Lagi-lagi berdua saja dengan bos membuat rasa yang sulit untuk di gambarkan. Kami duduk dekat meja bar. Menghadap pintu masuk agar mudah melihat siapa saja yang datang.
Sepertinya bos cukup serius. Ia mengambil sikap duduk berhadapan denganku, sikap tangan melipat memangku dagu.
“Sebenarnya apa yang kau lakukan, Salli?” tanya bos tanpa basa-basi.
“A-aku tidak e-“ aku tak bisa meneruskan kata-kataku, aku tak ingin bos tahu aku mengirim surat.
“Jangan mendekatinya, Salli. Kotak pos merah itu!”
“Mengapa Bos? Apa ada yang kau sembunyikan?”
Bos sedikit jengah dengan pertanyaanku yang lugas.
“Aku tidak menampik bila ada yang kusembunyikan, tapi kau tak perlu tahu!”
Aku terkejut dengan ucapan bos, tegas dan jelas. Itu artinya bisa jadi buruk untukku, esok dan seterusnya akan menjadi sulit bagiku mengirim surat kembali, apalagi mendapatkan balasan surat. Membuktikan bahwa surat-surat tersebut benar-benar tertelan pada pusaran mesin waktu saja, masih belum dapat kubuktikan. Hanya intuisi kuat sajalah membuatku masih bertahan mempercayainya, dalam hatipun aku berdoa, semoga ini bukanlah suatu kebodohan.
Aku yakin bos akan lebih mengawasiku, aku juga yakin Tuan Neil adalah mata-mata bos untuk mengawasi siapa saja yang mendekati kotak pos merah.
“Kurasa ada yang aneh dengan ayahmu, Salli.” Bos mengganti topik pembicaraan.
“Hah?”
Bos mengembuskan napas, sempat merenung sebentar sebelum meneruskan bicara.
“Kemarin, saat ayahmu berpamitan, ia seolah telah lama mengenalku.”
“Apa yang dikatakannya?”
“Entahlah, sesuatu yang terdengar seperti masa lalu dalam kenangannya.” Bos memiringkan kepalanya, ciri khasnya ketika berpikir.
“Apa maksudmu? Bukankah kalian tak saling mengenal sebelumnya?” tanyaku penasaran.
“Hmm, ayahmu mengatakan, ‘lama tak berjumpa Moon, kau tumbuh dengan baik. Tinggi badanmu melebihi aku sekarang.’ Seperti itulah kata-katanya.”
“Dari arti kata-kata itu, kalian pernah bertemu di masa lampau.”
Bos mengangguk tanda setuju dengan kesimpulanku, lalu ia menambahkan.
“Apalagi ayahmu memanggilku ‘Moon’. Aku baru kembali ke kota ini sekitar dua tahun lalu dan tak banyak yang memanggilku Moon, pelanggan kafe pun kebanyakan memanggil ‘Bos’.”
Aku pernah mendengar dari senior, bos tinggal lama di Jepang, negeri dari mana ayah bos berasal. Keputusannya untuk tinggal lama di negeri sakura, bermula dari kepergian kakek yang teramat dicintainya. Pada upacara pemakaman Kakek Gerimis, bos langsung mengumumkan rencana menetap di jepang dan hanya setahun sekali pada peringatan hari meninggalnya kakek, bos datang berkunjung. Sementara itu pengoperasian kafe diserahkan pada Tuan Neil yang memang telah menjadi tangan kanan dari pemilik kafe sebelumnya. Aku tahu bos adalah yatim piatu, namun cerita bagaimana kedua orang tua bos meninggal belum sempat diceritakan senior, air muka senior langsung berubah ketika pembahasan kami mengungkit kisah orang tua bos. Tidak ada yang pernah berani membahas, Tuan Neil pun tidak, padahal ia yang paling lama berada di Kafe Gerimis ini. Aku pun tak ingin mengorek luka lama, kubiarkan berlalu begitu saja.
Sebenarnya asyik bicara santai dengan bos, hanya bos lebih sering menutup diri. Obrolan kami harus berhenti ketika raut muka senior yang terlihat merah padam muncul dari balik pintu. Senyum matahari yang menaunginya lenyap. Aku dan bos menoleh padanya, untuk sekian detik kami mematung. Aku menarik kesimpulan, senior marah melihat kami berdua, mungkin cemburu. Kadang aku merasa ngeri dengan marahnya orang ceria. Tak terduga.
Aku lebih dulu mengambil sikap, mengundurkan diri dengan alasan masih ada pekerjaan yang harus kulakukan. Bos mengangguk, sebuah senyum bijak kutangkap dari bibirnya.
Bos dan senior masih berada di meja bar, setelah satu jam berlalu. Kupikir senior akan menyusulku, ternyata tidak. Kini ia dan bos asyik berkelakar berdua, terkadang saling memercikan bubuk kopi satu sama lain, mereka memang tengah menggiling biji kopi pilihan senior yang baru saja dipamerkan pada bos. Senior kembali ceria seperti biasanya. Senior juga selalu bisa mencairkan hati bos yang membeku, dengan senior … bos banyak tertawa, bahkan menjadi cerewet juga melontarkan lelucon garing. Hanya jika ada senior di samping bos.
Sekarang … aku yang cemburu.


 missera
missera