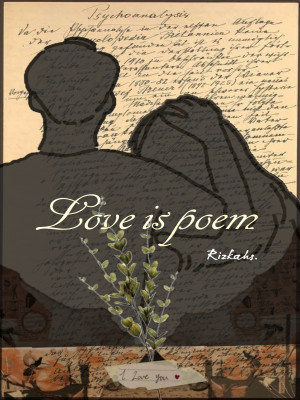Langit kelam sembunyikan bintangnya. Malam terasa amat panjang. Sedikit pun aku belum berhasil memejamkan mata. Ada rasa yang bergejolak, dadaku merasa panas, hatiku masih perih. Benar saja, sungguh, ikhlas tak semudah itu.
Huh, gerah semakin menjadi. Ini sih bukan gerah karena masih kepikiran soal pertemuan dengan ayah. Tapi memang betul gerah karena cuaca. Mendung tetapi tidak hujan.
Huft, menyebalkan! gerutuku dalam hati.
Sebuah suara sayup terdengar. Memastikan sekali lagi sumber suara itu berasal. Petikan gitar terdengar sendu sekaligus menyayat hati.
Hmm, tumben ibu memainkan gitarnya kembali.
Alunan melodi harmoni menuntun langkahku mendekat. Mengintip dari balik tirai, kulihat ibu memainkan melodi yang lama terpendam. Suara petikan gitar yang biasanya teronggok di pojok ruang menimbulkan gairah tersendiri bagi ibu yang selama ini telah membisukan harmoninya sendiri.
Satu-satunya lelaki dalam hidupnya adalah ayahku yang ia kenal sejak usia delapan belas tahun. Ibu memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya untuk sebuah keluarga, suami dan anaknya. Sayangnya, ayahku menginjak-injak ketulusannya tanpa bersisa.
Jemarinya berhenti mencipta nada, ia menunduk, air mata meleleh di pipinya. Ketika menyadari aku berada di sampingnya, ia langsung buru-buru menyekanya.
Aku tersenyum, membelai rambut ibu lembut. Aku mengambil tempat duduk di sisinya, bermaksud memberikan bahuku jika ibu mau. Ibu tertawa, mungkin malu karena tepergok menangis olehku, bulir air matanya tepercik sampai ke pipiku. Mengusap dengan kedua tangan, aku berjanji sendiri di dalam hati.
Tak akan kubiarkan air mata penderitaan ini mengalir lagi ibu, aku bersumpah akan mencari jalan keluar agar kau tak perlu lagi membisukan harmonimu sendiri, lebih baik aku tak dilahirkan ke dunia ini daripada harus melihatmu merasakan ketidak adilan seperti ini.
Pikiranku mengembara pada surat untuk tahun 2001, akankah seseorang menjalankan misi yang kuminta, lalu kapan aku mendapatkan balasan surat-surat itu?
“Jangan berpikir macam-macam Salli,” ujarnya lembut. Kini ia yang membelai pipiku. Seakan ia tahu yang terlintas di kepalaku.
“Ibu ..!” Aku memegang tangannya.
“Hm ..?” Ia menatapku seakan bertanya.
“Bila ibu mau, kembalilah mengejar cita-citamu, tak perlu bekerja di toko bunga lagi, biar aku mengurus segalanya untuk keperluan kita.” Aku menarik napas dan melanjutkan lagi kata-kata yang lama ingin kuungkapkan padanya.
“Ibu boleh seperti ayah, jatuh cinta kembali, jangan pernah merasa terbebani karena aku dan adik.” Mata ibu merespon terkejut, namun tak lama ia meletakkan gitarnya pada sebuah meja dan menarik kepalaku lembut untuk tidur di pangkuannya. Aku menurutinya. Ibu mengelus helaian rambut di kepalaku dengan penuh kasih sayang.
“Jika sepasang suami istri melahirkan anak-anaknya ke dunia, mereka harus bertanggung jawab hinga akhir, dan bila salah satunya tidak memiliki kedewasaan untuk bersikap demikian, maka satu orangnya lagi harus tetap tinggal bersama anak-anak mereka yang tidak bersalah itu―itulah yang harus dilakukan orang tua―aku tak mau anakku tidak memiliki ‘rumah’ untuk pulang. Saat mereka terbentur realita pada kejamnya dunia, aku akan menjadi ‘rumah’ bagi mereka.”
Kalimat yang ibu ucapkan membuatku terharu, sungguh ayahku merugi meninggalkan wanita yang tulus seperti ini.
“Apa kau tidak merasa ini tidak adil, Bu?” celetukku tiba-tiba.
“Dunia memang tidak adil, Salli… tetapi, Tuhan pasti adil!” jawab ibu tenang.
Seandainya saja, aku memiliki separuh saja dari ketenangan hatinya.
“Kau tahu, Salli? Kadang aku juga kekanakan, merasa jiwaku ini seperti gadis remaja, menyukai segala hal layaknya remaja. Aku tidak mengerti mengapa aku tak bersikap layaknya wanita usia empat puluh tahun?”
Kebingungannya membuatku berpikir, lalu tersenyum menanggapinya.
“Apa yang kau maksud karena selera musikmu sama sepertiku, Bu? K-Pop?” Aku memandangnya jenaka.
“Ah ya, itu juga.” Ibu tertawa.
“K-Pop mengalihkan duniaku dari keterpurukan,” ujarnya lagi.
Aku mengangguk tanda setuju. Terkadang kepenatan kita pada dunia butuh hiburan yang membuat kita tersenyum dan membuat luka mengering, dan aku menemukan BTS dalam pencarianku menyembuhkan diri.
“Siapa biasmu di K-Pop, Bu?” tanyaku iseng, sebenarnya aku tahu.
“Ah ya, waktu Salli kecil aku sering mendengar lagu G-Dragon dari Big Bang, sepertinya nular ke kamu ya, karena dari kecil terbiasa jadi suka K-Pop.” ucapnya terkekeh. Aku cuma nyengir membenarkan.
Benar, kecintaanku pada K-Pop pasti sudah dimulai sejak kecil, namun setelah dewasa baru benar-benar lagu BTS yang mengena di hatiku.
Lalu mata ibu menerawang, menggali masa lalu.
“Sejak dulu aku menyukai musik band, bahkan bergabung di dalamnya saat remaja, entahlah Salli, aku merasa jiwaku kembali pada masa-masa itu. Hanya usiaku saja yang menua.”
“Tidak, kau masih muda, Ibu! Baru saja empat puluh tahun.” Aku duduk tegak dan menyangkal penuh jika ibu merasa tua. Bahkan penampilannya sama sekali tidak terlihat berkepala empat. Ibu hanya tertawa.
“Kau hanya mencoba menghiburku, Salli!” ujarnya sambil terus tersipu.
“Ish, benar Ibu.” Kami tertawa berpelukan. Seolah melupakan kenyataan pahit yang mendera. Juga mengabaikan kerinduan kami pada sosok ayah yang pernah hadir di antara kami. Masa-masa itu telah berlalu, dan kami harus siap menerimanya.
“Bu, kau tak membenci Ayah?” Aku penasaran hingga menanyakan pertanyaan konyol itu. Ibu menggeleng kuat.
“Bagaimanapun ia ayahmu, memiliki tempat tersendiri di hatiku, lagipula membenci seseorang hanya akan membuat racun pada tubuhmu.”
“Persis yang dikatakan Min Yoongi,” jawabku bersemangat.
“Suga?” mata ibu membelalak. Lalu kami tertawa bersama.
Ah, senangnya karena aku memiliki ibu yang sefrekuensi, bahkan ibu justru fangirl senior, sebab itu obrolan kami langsung nyambung membahas seputar K-Pop. Menghapus air matanya dan membuatnya bahagia kini adalah tujuanku.
Sengaja aku tak ingin menambah luka ibu dengan menceritakan niat ayah menemuiku tadi siang. Sebenarnya aku masih berharap mesin waktu akan menolongku, sehingga masa lalu ibu dapat berubah, dan di masa kini ibu tak perlu membuka amplop surat cerai dari orang yang ia cintai.
Bagiku, pemikiran ibu sudah sangat dewasa, ibu tumbuh dengan penuh trauma. Kutahu, masa kecilnya dulu bahagia. Namun, semua itu berubah semenjak ia tumbuh remaja. Ketika ia remaja orang tuanya berpisah. Sebagai anak satu-satunya, ibu dititipkan di sebuah panti, sejak itu ia tak pernah bertemu orang tuanya kembali.
Ibu berpikir menikahi ayah adalah jalan keluarnya dari kesepian, membentuk keluarga harmonis seperti yang diidamkan. Namun ibu salah, menikah bukanlah jalan keluar dari masalah, justru menikah dengan orang yang salah memunculkan masalah baru dalam hidupnya.
Jiwa ibu menetap sebagai remaja, kurasa karena hati dan jiwanya berhenti di masa terakhir ia merasakan kebahagiaan bersama orang tuanya.
“Pastinya kau pernah merasakan lelah ‘kan ibu―dalam merawat kami―terutama huum … sikap Tian yang luar biasa istimewa akhir-akhir ini.”
“Akh ya, sebagai manusia biasa aku juga jengkel dan emosi, tetapi yeah .. mengasuh anak tak seberat mengasuh ayahmu, Salli!” Ia lantas tertawa.
Mungkin ibu telah berhasil berdamai dengan semua luka yang tertinggal di memorinya. Namun, bagiku ini tak mudah―karena berkaitan dengan ayah kandungku. Di mana dulu, saat aku kecil pernah begitu mendewakannya―menganggap ia cinta pertama di kehidupan ini―lantas tertampar kenyataan bahwa figur ayah yang terbentuk di masa lampau hanya sebuah bualan membuat hatiku patah untuk pertama kalinya.
Aku mulai melihat perubahan sikap ayah yang semula penyabar jadi sering ngambek dan lebih tantrum daripada Tian. Segala hal yang tak sesuai kehendaknya memicu emosinya yang meledak-ledak. Perasaan ibu semakin hari menjadi mati rasa, walau merawat ayah dengan segenap jiwa, namun tetap saja, ibu pada akhirnya dicampakkan.
***
Berkutat dengan konflik dalam keluarga, materi kuliah yang sama sekali tak bisa santai, ditambah pekerjaan di Kafe Gerimis yang menyita waktu. Aku hanya mengambil libur kerja di hari minggu dengan maksud agar ada satu hari dalam sepekan dapat kumanfaatkan untuk beristirahat. Lagi pula tidak setiap hari aku berangkat ke kampus. Jadwal kuliah memang telah diatur sedemikian rupa oleh para dosen jurusan Sastra Jepang, sehingga mahasiswa hanya akan mendapat jadwal kuliah dari hari Senin sampai Jumat. Kampus tempatku berkuliah adalah kota J yang menempuh waktu kurang lebih sekitar satu jam-an dari tempat tinggalku di kota S. Kafe Gerimis pun berada di kota S, hanya saja terletak di pinggiran kota yang membuatku menempuh perjalanan 20 menit menuju rumah dengan menggunakan bus kota.
Walaupun sering merasa kesulitan, aku tetap senang menjalaninya.
Terkadang, aku justru lebih bahagia seperti sekarang ini. Hidup tanpa ayah, membuatku tak perlu was-was, cemas apabila ayah pulang ke rumah dengan marah-marah pada ibu. Tidak perlu lagi melihat ibu menelan rasa pahit akibat perbuatan ayah yang jelas-jelas melukai harga dirinya. Namun, di sisi lain … aku sangat sedih bila melihat Tian tengah menunggu sosok ayah pulang untuk makan malam bersama seperti kebersamaan kami dulu. Tian semakin terobsesi dengan kata ‘keluarga’. Isi kepalanya seolah menolak kenyataan bahwa telah lama ayah tak pulang ke rumah. Otaknya merangkai cerita sendiri dan hanya ia yang memahami.
Huuft, ada banyak hal terjadi akibat dari satu orang yang berperan antagonis dalam sebuah keluarga. Lalu, sebenarnya … apakah peranku ini? Apakah dengan misiku mengubah masa lalu lewat surat menembus waktu akan mengubah keadaan keluargaku menjadi lebih baik? Apakah jika ayah dan ibuku tidak bertemu dan tidak saling jatuh cinta di masa lalu … masing-masing dari mereka akan bahagia di masa kini? Tanpa aku dan Tian? Tanpa keluarga seperti kami ada di bumi?


 missera
missera